Seorang kawan dekat yang menetap di luar Pulau Jawa mengeluhkan mahalnya harga pembalut yang tersedia di kotanya. Memang, tak hanya pembalut, harga barang-barang kebutuhan lain pun umumnya lebih mahal. Namun, harga pembalut di kotanya bisa 2-3 kali lipat daripada harga di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pilihan merek juga terbatas. Ia mesti menyisihkan uang lebih untuk memperoleh pembalut pilihannya, bahkan kadang lewat jasa titip (jastip).
Padahal, bebas memilih pembalut yang aman, nyaman, dan murah adalah hak semua perempuan. Sayang dalam kenyataannya, banyak perempuan tidak bisa memilih, dan atau tidak mampu membeli pembalut.
Baca juga: Siapa yang Berhak Bicara Soal Kesehatan Menstruasi?
Krisis Pembalut di Banyak Negara
Persoalan terbatasnya akses atas pembalut ini disebut period poverty, yang bisa kita terjemahkan sebagai krisis pembalut. Di beberapa negara, ada serangkaian prakarsa untuk mengatasi krisis tersebut. Di Skotlandia, sejak 2017 pemerintah mengadakan program pembalut gratis di sekolah (tersedia di toilet putri). Begitu juga di Selandia Baru. Di Perancis, pembalut gratis juga tersedia di sejumlah kampus universitas negeri. Di Kenya, Uganda, dan Botswana juga sudah ada program pembalut gratis bagi remaja putri, meski baru terbatas di kota besar.
Memang, menyediakan pembalut gratis adalah satu langkah utama. Sayangnya, kebanyakan pembalut gratis yang disediakan pemerintah tersebut adalah pembalut yang tidak ramah lingkungan. Masih sangat jarang tersedia pembalut (atau alternatif pembalut) yang ramah lingkungan, dan yang mudah diakses oleh remaja putri dan perempuan muda umumnya.
Sayangnya, program pembalut gratis belum direncanakan oleh pemerintah Indonesia (apalagi, dilaksanakan). Boleh jadi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak atau belum menganggap ini penting atau menganggapnya sebagai persoalan individual, alih-alih struktural.
Beberapa organisasi swasta dan lembaga non-pemerintah (ornop) turun tangan. Mereka menyelenggarakan program pembalut gratis di beberapa daerah, terutama di daerah yang jauh dari kota, dan bagi perempuan yang tidak punya/ minim akses atas pembalut. Di beberapa daerah, bahkan ada program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja putri di sekolah. Ada juga organisasi yang menyediakan pembalut ramah lingkungan.
Sayangnya, kebanyakan program ini hanya bersifat sementara dan menghadapi persoalan minimnya dukungan. Masih banyak perempuan Indonesia yang tidak memiliki akses untuk memilih pembalut yang aman, nyaman dan murah. Persoalan dasar ini tetap tidak terpecahkan.
Baca juga: Menstruasi Terganggu Saat Pandemi? Kamu Tidak Sendiri
Mangkir Sekolah Saat Haid, Persoalan Lain
Salah satu akibat dari krisis pembalut di Indonesia adalah banyak remaja putri yang mangkir sekolah saat haid. Karena tidak adanya program pendidikan kesehatan seksual, mereka merasa malu saat haid. Pun, karena ada anggapan budaya setempat atas perempuan haid. Haid disamakan dengan aib.
Kebanyakan remaja putri yang mangkir sekolah saat haid adalah mereka yang berusia 15-17 tahun (kelas 10-12). Di sekolah mereka, umumnya pintu toilet tidak dapat dikunci dan tidak ada air bersih di toilet sehingga mereka lebih memilih berada di rumah. Mereka tinggal di daerah pedesaan karena tidak adanya/ minim akses atas pembalut.
Angka mangkir sekolah saat haid di Indonesia memang relatif lebih rendah daripada di negara-negara berkembang lainnya. Namun begitu, tetap masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga.
Baca juga: Laki-laki dan Menstruasi: Pengalaman Transpria
Hilangnya Pembalut dari Komponen Upah
Krisis pembalut di Indonesia tidak hanya merundung remaja putri dan perempuan muda. Ini bisa dianggap sebagai persoalan nasional. Mengapa begitu?
Pada masa Orde Ba(r)u, penentuan upah minimum didasarkan atas kebutuhan buruh lajang pria. Akibatnya, barang-barang kebutuhan buruh perempuan (baik sebagai lajang, janda, atau orang tua tunggal) tidak diperhitungkan sama sekali.
Akibat tuntutan gerakan buruh dan gerakan perempuan, perubahan mulai terjadi usai Reformasi 1998. Beberapa barang kebutuhan buruh perempuan (lajang) mulai diperhitungkan dan masuk menjadi komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan penentuan upah minimum. Salah satunya adalah pembalut. Meski nilainya masih kecil, hal ini adalah satu bukti keberhasilan perjuangan gerakan buruh dan gerakan perempuan dalam membela kepentingan buruh perempuan kita. Apalagi, di beberapa industri, buruh perempuan adalah mayoritas.
Sayangnya, sejak 2020, pembalut dihapuskan dari komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dalam penentuan upah minimum di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020, tidak ada lagi komponen pembalut, dan malah sebagai gantinya adalah “korek kuping (cotton bud) sebanyak 1 kotak isi 50.”
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini berlaku sejak 9 Oktober 2020, dan ditandatangani oleh Ida Fauziyah. Meski Menteri Ketenagakerjaan kita adalah perempuan, terbukti ia tidak punya keberpihakan terhadap perempuan. Alih-alih mempermudah akses perempuan akan pembalut atau menawarkan pembalut (atau alternatif pembalut) yang ramah lingkungan, ia menghapus pembalut. Malah, beliau mengingkari kebutuhan perempuan akan pembalut, yang sudah diperjuangkan oleh gerakan buruh dan gerakan perempuan kita selama ini.
Terlebih, perubahan ini terjadi saat masa pandemi, ketika banyak buruh perempuan di-PHK dan dipaksa berhenti dari pekerjaan mereka. Banyak buruh perempuan semakin kesulitan memilih pembalut yang aman, nyaman, dan murah. Mereka lebih mementingkan kebutuhan pangan keluarga mereka dengan mengorbankan kebutuhan mereka sendiri akan pembalut.
Dengan melihat kenyataan ini, boleh dibilang krisis pembalut di Indonesia masih jauh dari selesai, dan akan tetap menjadi masalah struktural. Remaja putri dan perempuan muda di pedesaan, dan buruh perempuan kita menjadi kelompok yang paling rentan. Akibat akses yang terbatas dan ketiadaan dukungan dari pemerintah, kebutuhan mereka akan pembalut menjadi tersisihkan. Sementara itu, harga pembalut di pasar akan terus melambung di luar jangkauan mereka.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.



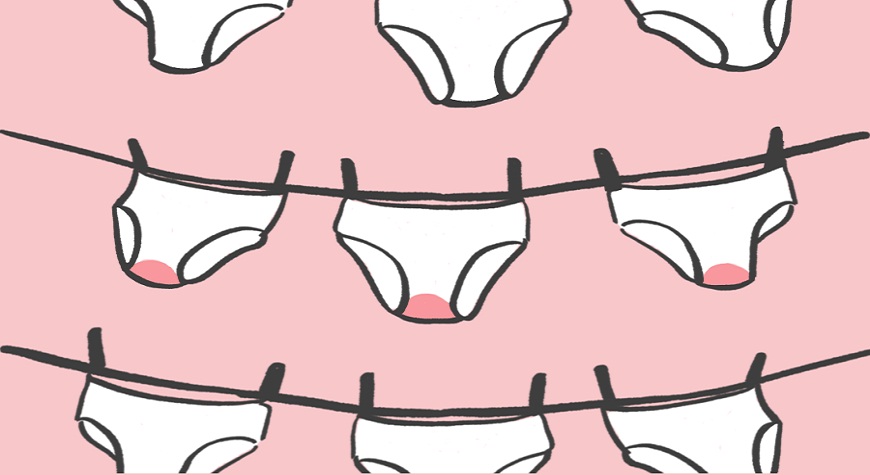



Comments