Kemunculan akun satir calon presiden dan wakil presiden alternatif Nurhadi-Aldo, disingkat Dildo, menyemarakkan proses Pemilihan Umum 2019 di Indonesia yang sedang berada di titik jenuh. Sejak diluncurkan pada Desember 2018, akun ini terus dibanjiri pengikut yang turut menyebarkan meme mereka. Sampai tulisan ini diunggah, akun Nurhadi-Aldo telah memiliki 455 ribu pengikut di Instagram dan 104 ribu di Twitter.
Popularitas Dildo memancing banyak pro-kontra. Ada pihak yang menganggap lelucon mereka mendukung pasangan calon (paslon) tertentu, ada yang menganggapnya candaan seksis, sementara yang lain memujinya sebagai alternatif terhadap Pemilu yang jumud, terbatas pada pertempuran kelompok elite yang hasilnya tidak akan memberikan perubahan yang berarti. Tulisan ini sendiri mengkaji fenomena #Dildo4Presiden sebagai bagian dari budaya pop dan kritik terhadap elite politik, termasuk para aktivis dan partai politik baru yang katanya mendorong anak muda untuk lebih banyak terjun ke politik.
Kampanye Dildo menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan khalayak menggunakan meme sampai video lagu kampanye yang dinyanyikan oleh bot Google. Terlihat simpel dan menghibur, tapi sesungguhnya tidak sesederhana itu. Ilmuwan komunikasi dari Kanada, Marshall McLuhan, dalam bukunya Understanding Media: The Extension of Man (1964) menjelaskan bahwa medium memengaruhi masyarakat lebih daripada konten atau pesan itu sendiri. Meme adalah sebuah budaya komunikasi politik sekaligus medium dan pesan itu sendiri, demikian juga dalam fenomena kritik politik Dildo. Meme sebagai medium humor itu sesungguhnya sangat eksklusif, karena untuk mengerti sebuah meme diperlukan kesamaan latar belakang yang melandasi kemampuan literasi digital, pemahaman budaya populer, kelas sosial, dan gaya bahasa. Meme Dildo memang berasal dan ditujukan kepada anak muda dari kelas menengah ke bawah dan berideologi kiri, tiga kelompok yang sama sekali absen dalam wacana perdebatan politik elite di Indonesia.
Akun-akun meme bersifat sporadis tapi memiliki karakteristik budaya yang hampir mirip: gaya bahasa sarkasme, satir, dan ironi. Seseorang tidak bisa mengaku mengerti meme Dildo tanpa memahami gaya bercanda akun sejenis seperti Penahan Rasa Berak, Bude Sumiati, Pengalaman Virtual Remaja Edgy, Rokok nan Sebatang, Mengapa Temanku Begini, Komik Ms Paint Demi Kehidupan Beragama yang Tentram, dan sebagainya. Para pembaca akun-akun ini umumnya lahir dan besar tahun 90an, ketika budaya JPop atau KPop berjaya. Meme sebagai medium lelucon dengan gaya bahasa satir, ironi dan sarkastis menjadi medium pengejawantahan kegelisahan kelompok remaja dan dewasa muda atas kehidupan yang mapan tanpa harapan bagi mereka. 
Bila tidak mengerti asal-usul dan penggunaan sebuah meme, maka yang terjadi adalah bias. Sebuah meme punya gaya bahasa sendiri yang berlandaskan materi dari budaya populer seperti jejepangan atau koreaan dan mempunyai konteks sejarah kemunculannya. Ada pesan “know your meme” untuk memahami mengapa sebuah simbol menjadi ikonis dan layak untuk dijadikan bahan meme. Dan selayaknya lelucon juga punya batas kadaluwarsa, meme adalah bagian dari humor yang merupakan perpaduan antara tragedi dan waktu. Tragedi di sini adalah kegagalan elite menyuarakan anak muda dan kelompok miskin dan waktu adalah tahun politik.
Milenial dan rakyat miskin sebagai bahan kampanye
Dalam sebuah episode serial kartun Daria (ditayangkan MTV pada 1999 hingga 2000 awal), ada sebuah kritik terhadap budaya “edgy”. Edgy didefinisikan sebagai dewasa tua yang berusaha memahami dan menjadi seorang remaja berdasarkan riset pasar. Generasi X, Y, Milenial, dan Z adalah bukti dari riset pasar dan bahwa setiap generasi dianggap memiliki kultur yang berbeda-beda. Kata Milenial adalah istilah yang dirujuk pada anak muda di Indonesia yang kini menjadi pelaku aktif dalam konsumsi dan juga calon pemilih dalam Pemilu 2019 ini.
Istilah Milenial dianggap seksi dan menunjuk secara gamblang populasi anak muda Indonesia berusia 20-35 tahun. Sayangnya jika diperhatikan, semua orang yang menggunakan kata Milenial tersebut adalah media, bukan anak muda dalam rentang usia tersebut. Tidak ada anak muda yang mengklaim dirinya Milenial, karena itu adalah sebuah label yang diberikan oleh media supaya anak muda menjadi target pasar, objek untuk terus didorong melakukan konsumsi. Istilah Milenial adalah objektivikasi terhadap kelompok muda.
Kelompok elite politik juga melihat Milenial sebagai target pasar, seperti sebagaimana mereka selalu melihat kelompok miskin dan rakyat kecil sebagai objek dagangan. Hal ini yang dikritik dalam fenomena meme Nurhadi-Aldo, bahwa rakyat miskin dan budayanya dianggap vulgar dan rendah tapi di sisi lain selalu dijadikan komoditas. Dengan anak-anak muda yang menjadi administratornya, Nurhadi-Aldo lebih merepresentasikan anak muda dan budayanya melalui meme dan sarkasme yang menyoroti masalah-masalah yang serius. Menganalisis meme Nurhadi-Aldo menggunakan upaya dekonstruksi lebih masuk akan ketimbang memuja political correctness.
Dalam penggunaan simbol-simbol seks yang nyaris menyerempet seksisme, misalnya, mereka berusaha melakukan dekonstruksi melalui akronim-akronim porno. Akronim tahta, harta dan granita misalnya diambil dari frase tahta, harta dan wanita. Apakah candaan itu seksis? Ya, kalau kita tidak tahu apa itu granita karena kita cuma paham bentuk awal perumpamaan seksis tersebut. Tapi siapa yang tahu tentang Granita? Granita adalah minuman kopi susu seharga Rp500-an yang diminum oleh sopir, kuli galian, atau tukang bangunan. Atau bagaimana kata Pelakor yang sebelumnya bermakna peyoratif menjadi “penyanyi lagu korea”. Kata-kata yang vulgar dan simbol seks dan gaya bahasa sarkastis adalah upaya dekonstruksi untuk menantang masyarakat yang munafik, memuja moral konservatif, tetapi di sisi lain menyukai esek-esek. Di sini, simbol seks menjadi sajian utama untuk mengangkat wacana konflik agraria, masalah upah dan jam kerja yang tidak layak, bencana dan kekerasan seksual.
Untuk apa anak muda menonton debat capres perdana tanggal 17 Januari kemarin? Jawabannya adalah untuk mencari bahan meme untuk hiburan. Anak muda tahu bahwa apa yang dikatakan para empat lelaki di podium itu tidak lebih dari menjual jargon-jargon tentang hak asasi manusia, terorisme, dan korupsi tanpa penyelesaian. Setiap isu yang diperdebatkan tidak membicarakan masalah sesungguhnya seperti keterwakilan gender perempuan, hak waria untuk tidak dipersekusi, atau penyelesaian kasus-kasus HAM pada hari yang sama aksi rutin Kamisan di depan Istana Presiden berlangsung. Meme dan sarkasme menjadi kritik sekaligus ekspresi dari fenomena komodifikasi anak muda “add millenials and stir” tanpa merombak struktur dan budaya politik itu sendiri.
Keluarga harmonis seperti yang dicitrakan Jokowi adalah warisan kolonialisme dan Orde Baru.





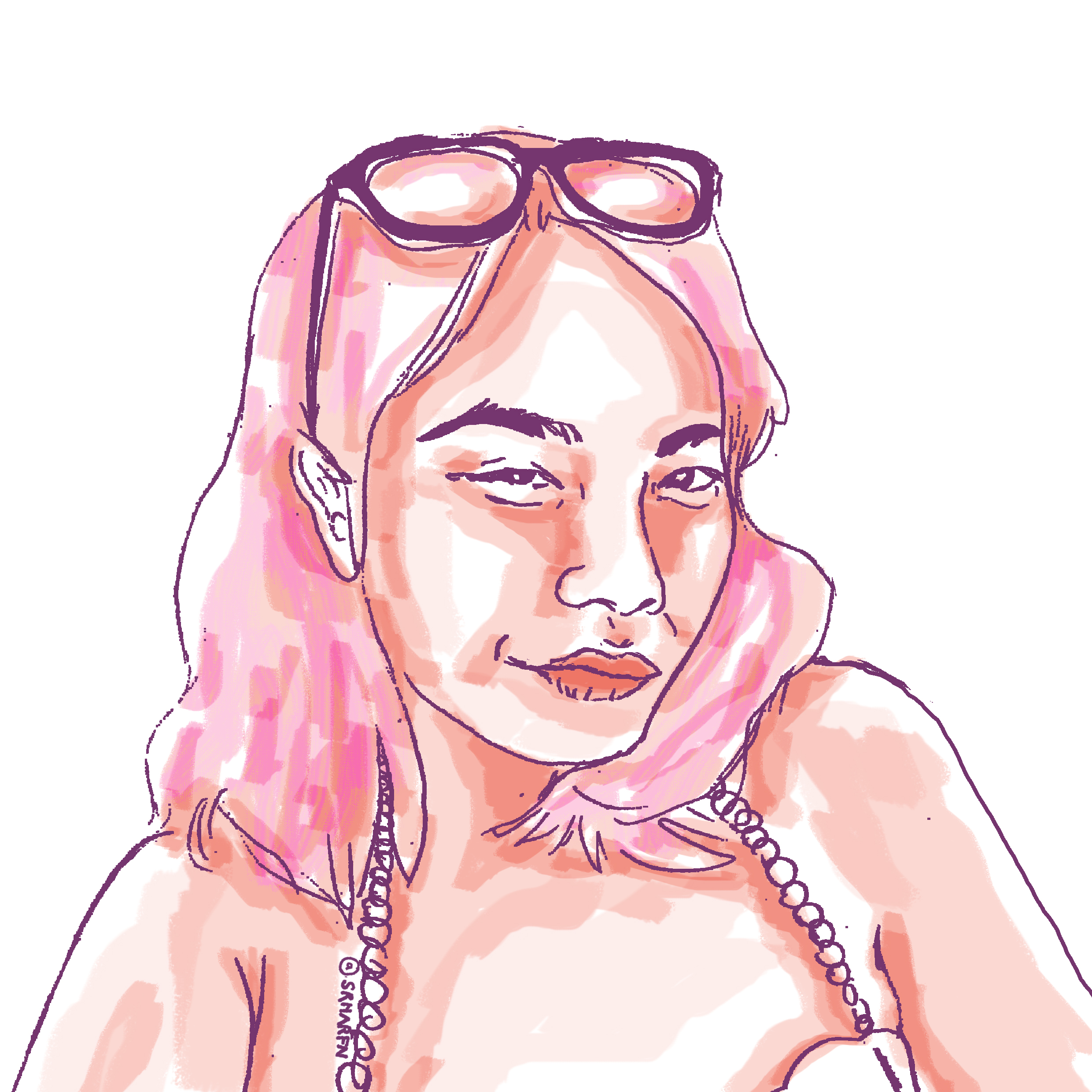



Comments