Di usia yang baru menginjak 16, “Desi” harus menerima kekerasan berlapis dari seorang laki-laki yang diperkenalkan temannya. Mulanya, Desi dijebak temannya tersebut dengan dibawa ke kamar hotel tempat dua orang laki-laki paruh baya telah menunggunya. Rupanya, teman Desi “menjualnya” kepada mereka.
Waktu berlalu sampai akhirnya Desi diperkenalkan kepada “Hadi”, seorang laki-laki yang lantas kerap memaksanya berhubungan seks, dengan ancaman akan melapor ke orang tua Desi bahwa putrinya sudah tidak perawan bila Desi menolak. Tidak hanya paksaan dan ancaman itu, Desi pun pernah dipukul ketika kemudian hamil, dipaksa aborsi, divideokan saat sedang bersenggama tanpa diketahuinya.
Cerita Desi adalah salah satu aduan yang diterima oleh Iqraa Runi Aprilia, salah seorang relawan unit pengaduan untuk rujukan Komnas Perempuan. Ia menyampaikan, video intim Desi itu dikirimkan pelaku ke teman-teman kerjanya (saat melapor, Desi sudah putus sekolah dan akhirnya bekerja).
“Biasanya, kalo orang nunjukin video telanjangnya ke orang kan malu, tapi Desi biasa aja dan bilang, ‘itu kak, itu aku’. Kayak mati rasa dan enggak tahu lagi mau ngapain,” ujar Iqraa.
Jumlah kasus KBGO meroket
Baik di dalam maupun di luar masa pandemi, kekerasan berbasis gender online seperti yang dialami Desi pun kerap terjadi. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 menunjukkan peningkatan KBGO sebesar 300 persen, dari 97 kasus selama 2018 menjadi 281 kasus pada 2019. Dari 281 kasus tersebut, 91 di antaranya merupakan kasus penyebaran foto intim.
Sementara itu, Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi Digital At-Risks Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)—lembaga yang mengadvokasi hak digital dan kebebasan berekspresi warga, mengatakan bahwa penyebaran konten intim mendominasi aduan yang masuk ke lembaganya.
“Datanya sendiri baru akan kami rilis pada 27 Juni nanti,” ujar Ellen.
Baca juga: Kiriman 'Dick Pic' dan Video Porno Tak Konsensual Naik Selama Pandemi
Mengenai definisi tindakan yang termasuk KBGO, Ellen menjabarkan bahwa hal tersebut merupakan kekerasan atau tindakan yang membuat seseorang merasa tidak aman. Pada dasarnya, KBGO melibatkan pelanggaran privasi dan ketiadaan persetujuan (consent), menyerang dan/atau berdampak lebih besar karena gender atau seksualitas seseorang, serta terjadi di dunia daring dan difasilitasi oleh teknologi digital.
Maraknya pengaduan kasus KBGO belakangan ini menurut Ellen disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, bisa jadi KBGO meningkat karena intensitas penggunaan platform digital yang juga meningkat, terlebih pada masa pandemi. Kebijakan swakarantina pada akhirnya menyebabkan orang memiliki lebih banyak waktu luang dan membuka lebih banyak kesempatan bagi seseorang untuk melakukan KBGO.
“Kedua, banyak orang melihat bahwa menjadi pelaku KBGO itu tidak ada konsekuensinya. Belum ada contoh kuat di publik bahwa pelaku KBGO mendapat hukuman setimpal. Yang ada malah korban dengan mudah mereka kriminalisasi. Sementara pelaku makin jemawa, korban merasa makin tidak ada harapan,” jelas Ellen.
Berikutnya, ia menilai bahwa pengaduan KBGO meningkat akibat makin banyak pihak yang mengangkat isu ini dan efeknya, makin banyak pula pengguna internet mengetahui bahwa yang mereka alami termasuk KBGO. Informasi akses aduan pun telah mulai disebarkan ke publik secara luas sehingga membantu para korban untuk melaporkan kasusnya.
Beragam kendala mengadang korban
Sering kali para korban tidak kunjung melaporkan kejadian KBGO lantaran mereka belum paham bahwa dirinya mengalami kekerasan. Minimnya pengetahuan dasar mengenai privasi, persetujuan, gender dan seksualitas, serta akses ke lembaga penyedia bantuan membuat kasus KBGO masih terus bertambah hingga kini.
“Dari sisi pendampingan sendiri, juga belum banyak yang memahami, mendalami KBGO, padahal sudah sering kali menerima aduannya. Sedangkan dari aspek hukum, belum ada perangkat hukum yang memadai untuk mengadvokasi kasus-kasus KBGO,” papar Ellen.
Penegak hukum suka beralasan ‘SDM kami terbatas’ dan ‘Kami tidak memiliki alatnya’ terkait dengan digital forensik atau pelacakan oleh polisi.
Ketika membawa kasus KBGO ke kepolisian, Ellen mengamati masih ada pihak penegak hukum yang memakai alasan-alasan seperti “SDM kami terbatas” dan “Kami tidak memiliki alatnya” bila terkait dengan digital forensik atau pelacakan oleh polisi.
“Ada lagi tantangan yang mereka sebutkan, bahwa susah untuk mendapatkan informasi tentang pelaku kalau minta ke platform digital,” ujarnya.
Di sisi lain, Ellen melihat juga bagaimana sistem di berbagai penyedia platform digital, seperti raksasa media sosial Facebook, Instagram, Google, dan Twitter, memfasilitasi pelaku untuk bisa dengan mudah menyebarkan konten apa pun atau membuat belasan sampai puluhan akun palsu baru.
Ia mencontohkan, dalam kasus penyebaran konten intim, korbannya bisa mendapati bahwa konten tersebut diunggah berulang kali oleh pelaku yang misalnya adalah mantan pacar. Tetapi, bisa juga ada pelaku baru yang merupakan orang asing dan turut menyebarkan konten intimnya. Bahkan orang tersebut bisa ikut memanfaatkan konten intim itu untuk mengancam korban yang sebenarnya dikenalnya, tapi mungkin ia mempunyai informasi akun media sosial korban atau informasi lain yang memungkinkan dia untuk mencari data pribadi korban dan mengontaknya.
Walaupun di berbagai platform digital ada sistem pelaporan konten bermasalah, terkadang pihak mereka tidak menanggapi laporan korban dengan baik. Misalnya, laporan korban direspons dengan jawaban seperti “Kami tidak melihat ini sebagai hal yang melanggar standar komunitas platform kami”.
Di samping itu, masih ada korban yang tidak mau melapor dengan alasan mulai dari takut ketahuan orang tua, permasalahan biaya mengurus kasus, proses hukum yang panjang, sampai kekhawatiran akan disalahkan.
Penyalahan korban
Penyalahan korban tidak hanya kerap ditemukan di masyarakat atas dasar nilai moralitas. Menurut Ellen, masih banyak juga aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban dan malah melakukan victim blaming.
Baca juga: Hati-hati Di Internet dan Hal-hal yang Perlu Diketahui Soal KBGO
“UU ITE (Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik) Pasal 27 Ayat 1 malah sering kali digunakan untuk mengkriminalisasi korban-korban KBGO yang terkait dengan keberadaan konten seksual, termasuk juga UU Anti-Pornografi,” kata Ellen.
Padahal, dalam penyebaran konten intim, bisa saja korban dipaksa untuk mendokumentasikan aktivitas seksualnya oleh pelaku. Atau dalam kasus Desi, tanpa sepengetahuan dan persetujuannya dalam pembuatan video intim.
Penyalahan korban dan kekhawatiran akan dikriminalisasi membuat sebagian korban berat untuk melangkahkan kaki mencari keadilan. Akhirnya mereka lebih memilih untuk diam atau berpasrah dengan situasi dirinya.
Jika pun langkah hukum tidak diambil, sebagian korban, baik sendiri maupun dengan bantuan pihak tertentu, memilih untuk melakukan call-out pelaku di media sosial. Menurut Ellen, ini bisa saja menjadi upaya mencari keadilan, tetapi di lain sisi berpotensi memunculkan kasus KBGO baru.
“Misalnya, korban yang melakukan call-out mengalami doxing [penyebaran informasi pribadi], ancaman, teror, dan seterusnya,” ucap Ellen.
Sementara dalam menyikapi korban yang mengadukan kasusnya, Ellen mengatakan bahwa SAFEnet berposisi mendukung korban, apa pun keputusan yang ia ambil.
“Bila korban memilih melaporkan ke pihak polisi, tentu kami akan tetap mendampingi agar tidak terjadi potensi kriminalisasi, dan tidak sendirian tentunya. Kami bergerak bersama teman-teman komunitas lainnya. Kami pun selalu menyarankan korban untuk tidak melapor sendirian, tetapi mencari bantuan dari lembaga bantuan hukum terlebih dulu jika korban memutuskan untuk melapor,” terang Ellen.
Artikel ini didukung oleh hibah Splice Lights On Fund dari Splice Media.
Jika memerlukan bantuan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, silakan hubungi Komnas Perempuan (021-3903963, [email protected]); Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/LBH APIK (021-87797289, WA: 0813-8882-2669, [email protected]). Klik daftar lengkap lembaga penyedia layanan di sini.







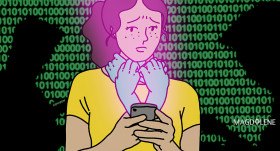
Comments