Aksi teror yang menyasar beberapa gereja di Surabaya pada Mei 2018 mengejutkan banyak orang. Untuk pertama kalinya, perempuan dan anak-anak terlibat dalam aksi bom bunuh diri. Dua tahun sebelumnya, Dian Yulia Novi ditangkap sehari sebelum rencana aksi peledakan bom di depan Istana Negara.
Perempuan sering kali dicitrakan sebagai aktor yang pasif dalam terorisme dan kekerasan ekstrem. Namun, Irine Hiraswari Gayatri, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekaligus kandidat doktor di bidang Gender, Perdamaian, dan Keamanan dari Monash University mengatakan, keterlibatan aktif perempuan dalam aksi kekerasan bukanlah hal baru.
“Pada penelitian yang pernah saya lakukan dengan Akiko [Akiko Horiba, Program Director dan Senior Program Officer Asia Peace Initiatives Department di Sasakawa Peace Foundation], kami menemukan bahwa perempuan bukan hanya aktor pasif dalam konflik bersenjata di Indonesia, yang menandai transisi dari Orde Baru ke Reformasi,” kata Irine dalam diskusi berjudul “The New ‘Jihadist’ Landscape in Sub Regional: Are Women and Children More Vulnerable?”.
Diskusi ini merupakan bagian dari acara 3rd Sub-Regional CSO Forum yang diselenggarakan The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (11/11).
“Dalam beberapa konflik yang diwarnai oleh sentimen etnis dan agama, perempuan merupakan aktor yang mampu melakukan kekerasan,” tambahnya.
Baca juga: Perspektif Gender Penting Namun Absen dalam Penanganan Terorisme
Pelibatan perempuan dalam proses perdamaian
Sejak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) mengeluarkan resolusi No. 1325 Tahun 2000 mengenai Women, Peace, and Security (WPS), pemahaman yang berkembang adalah bahwa perempuan dapat berkontribusi terhadap upaya perdamaian.
Seiring dengan perkembangan politik global, terutama pasca-serangan terhadap gedung World Trade Center (9/11), definisi “ancaman keamanan” tak hanya dipahami dalam bentuk perang dan konflik, tetapi juga terorisme dan kekerasan ekstrem.
Kemunculan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Timur Tengah berdampak terhadap banyak negara sehingga lahirlah resolusi DK-PBB No. 2242/2015.
Resolusi ini menghubungkan situasi perempuan dengan perubahan konteks global, yaitu dampak terorisme dan kekerasan ekstrem pada kekerasan berbasis gender. PBB juga menyerukan negara anggotanya untuk mengintegrasikan agenda WPS dalam penanganan terorisme dan kekerasan ekstrem.
Dengan pendekatan WPS, perempuan tak hanya dilihat sebagai juru damai dan korban, tetapi juga sebagai orang yang dapat terlibat aktif dalam kelompok teroris, ujar Irine.
Baca juga: Jangan Diam, Lawan Teroris!
“Dalam konteks agensi perempuan dalam terorisme, kita melihat kenyataan di lapangan mengenai perempuan sebagai korban propaganda sekaligus pelaku,” ujarnya.
Rekrutmen dan propaganda tak hanya dilakukan perempuan di kelompok teroris, tetapi juga di kelompok radikal yang tidak menempuh jalan kekerasan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Para perempuan ini percaya, mereka adalah agen yang aktif dalam pendirian kekhalifahan, sama halnya dengan laki-laki. Mereka berpendapat bahwa dirinya harus aktif di publik, tak hanya domestik,” jelas Inayah Rohmaniyah, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang pernah melakukan penelitian mengenai eksistensi muslimah HTI di Gorontalo pasca-pembubaran organisasi ini.
Meskipun saat ini tak terlihat di publik, muslimah HTI bergerak di “bawah tanah” dan memiliki ikatan yang sangat kuat. Dalam propagandanya, mereka menggunakan diksi “pemberdayaan” dan “kesetaraan” kendati mereka menolak feminisme. Itulah alasan mengapa mereka tampil di publik, membawa anak-anak ke aksi protes, dan punya ide untuk bangkit melawan pemerintah.
“Bagi mereka, penderitaan dan perendahan martabat perempuan adalah dampak demokrasi dan kapitalisme. Mereka percaya bahwa khilafah adalah solusi karena akan menjaga kehormatan perempuan, dan sebaliknya, feminisme mencabut fitrah perempuan,” katanya.
“Bagi Muslimah HTI, penderitaan dan perendahan martabat perempuan adalah dampak demokrasi dan kapitalisme. Mereka percaya bahwa khilafah adalah solusi karena akan menjaga kehormatan perempuan, dan feminisme mencabut fitrah perempuan.”
Anggota HTI, menurut Inayah, mengalami proses depersonalisasi (kehilangan individualitas dan hak untuk memilih). Proses ini berlanjut dari generasi ke generasi karena, salah satunya, adanya konsep takdir.
“Misalnya, ketika saya bertanya mengenai poligami, mereka berkata, ‘Ini adalah takdir kami’. Ketika saya menanyakan apakah mereka punya harapan, mereka menjawab, ‘Saya tidak punya harapan, karena harapan adalah milik Tuhan. Tuhan akan menentukan segalanya untuk kita’,” ujarnya.
“Konsep takdir membatasi harapan individu. Mereka kehilangan hak memilih, pemikiran kritis, dan impian,” tambah Inayah.
Seiring berjalannya waktu, ada anggota-anggota perempuan HTI yang memutuskan untuk keluar dari organisasi ini. Keberagaman sumber, suasana, dan interaksi sosial berpengaruh terhadap transformasi cara berpikir mereka.
“Mereka akhirnya berubah karena memiliki beragam teman, berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka, membaca buku dari sumber-sumber lain, atau pindah ke tempat lain untuk melanjutkan studi,” kata Inayah.
Mendengarkan suara perempuan korban
Peran perempuan dalam pencegahan terorisme maupun kekerasan ekstrem adalah hal penting, tetapi suara korban sering kali terlupakan. Padahal, mereka adalah orang yang paling terdampak.
Baca juga: Persaingan Rebut Otoritas Agama Suburkan Kelompok Militan Islam di Jawa
Di Patani, Thailand Selatan, perempuan menjadi korban konflik antara pemberontak Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan pemerintah Thailand. Akibat konflik itu, banyak laki-laki ditangkap atau melarikan diri ke Malaysia. Dengan demikian, perempuanlah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
“Perempuan berpendidikan tinggi biasanya berprofesi sebagai perawat atau guru. Ada juga perempuan yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Jadi, perempuanlah yang bertanggung jawab mengurus keluarga,” kata Akiko Horiba dari Sasakawa Peace Foundation.
Sasakawa Peace Foundation memiliki program untuk memberdayakan perempuan-perempuan Patani agar mereka berpikir kritis. Menurut Akiko, mereka adalah sosok yang sangat kuat.
“Meskipun mereka memiliki trauma karena suaminya ditangkap atau tewas, banyak organisasi masyarakat sipil yang membantu. Mereka saling berinteraksi dan memiliki peran semakin besar. Ini juga adalah bagian dari pencegahan kekerasan ekstrem,” katanya.
Akiko menekankan, proses perdamaian memerlukan perspektif holistik dan melibatkan semua aktor.
“Kelompok militan harus terlibat dalam perundingan perdamaian. Suara perempuan penting dan harus didengar. [Pembahasan] Isu-isu hard power seperti keamanan dan perlucutan senjata saja tidak cukup, jadi perspektif perempuan penting untuk disertakan,” jelasnya.







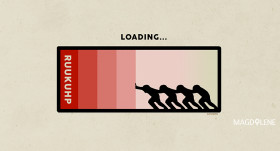
Comments