Berpanas ria saat puasa, dan bukan untuk ibadah yang menyangkut Ramadan tapi justru untuk agama lain, tentu terasa janggal, pasti dianggap “riya”. Tapi sebetulnya yang lebih menyakitkan dan harusnya menimbulkan empati siapapun adalah kenyataan bahwa suatu komunitas harus beribadah di tepi jalan, sudah hampir 100 kali dalam lima tahun terakhir. Mereka terpapar panas terik atau hujan deras karena terusir dari tempat ibadahnya sendiri. Bahkan untuk menuju tepi jalan itu pun, sejatinya jauh dari rumah mereka sendiri.
Sebagai orang yang ikut berpanas ria dengan jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia (karena kebetulan puasa tahun ini hampir tak pernah hujan di Jakarta) pada tiap ibadah Minggu di depan Istana, saya bersyukur bahwa setidaknya tiga jam seusai ibadah Minggu tersebut, saya masih bisa memilih masjid manapun di Jakarta. Bahkan, tak perlu khawatir dengan hidangan berbuka puasa, karena pengurus masjid di manapun di Jakarta (pasti) menyediakan penganan berbuka puasa secara lengkap.
Saya masih beruntung. Yasmin dan Filadelfia sesampainya di Bogor atau Bekasi belum akan secara ajaib bisa beribadah di gerejanya. Mungkin, (utamanya Yasmin) merasa lebih sakit hati karena dengan mudahnya Walikota setempat bisa menggambarkan (pencitraan) toleransi antaragama dengan pemeluk Budha di Bogor (Vihara Danagun) saat Ramadan baru-baru ini, tapi gagal menjadi “pihak yang bijak” memulihkan akses mereka ke Gereja.
Babak baru tentang konflik agama di Indonesia mungkin bisa diungkit melalui contoh anomali saat suatu masjid (komunitas) Ahmadiyah di Jakarta disegel paksa oleh Satpol PP. Gubernur Ahok, yang oleh (utamanya) pendukungnya dianggap orang yang amat pluralis, toleran, bahkan mungkin “nyeleneh” untuk membantu agama yang bukan dianutnya (kasus parsial seperti Ahok berzakat; Ahok memastikan memberangkatkan haji untuk banyak anggota takmir Masjid di Jakarta; bergerak sunyi tapi cepat dalam kasus “Gaza in Jakarta”), menjadi target cibiran saat kasus Masjid Ahmadiyah.
“Bagaimana mungkin orang yang selama ini sok dicitrakan pluralis, ternyata menyegel Ahmadiyah,” cibiran dari sisi konservatif (yang sejatinya mungkin gembira atas penyegelan semacam ini). Hingga tulisan ini ditulis, belum ada konfirmasi memadai apakah ini murni teknis hukum (penyalahgunaan rumah tinggal dibuah sebagai tempat ibadah) atau tendensi intoleransi-menghambat secara sengaja akses beribadah.
Yang terjadi pada Yasmin, Filadelfia, hingga kasus terbaru terkait Ahmadiyah (selain kasus yang dialami Ahmadiyah lainnya), menimbulkan pertanda bahwa masyarakat kita makin mengkhawatirkan dalam hal penerimaan terhadap “yang berbeda dengan yang mayoritas”. Saya selalu khawatir bahwa ini menjadi bom waktu. Kita mungkin salah memaknai perbedaan SARA di antara kita, dan justru menjadi bahan baku bersikap antipati. Meski saya tak yakin bisa disebut pluralis, saya berusaha sekali untuk tak antipati pada nasib “yang minoritas”. Bagi saya, peduli terhadap Yasmin dan Filadelfia pun masih kurang karena seharusnya saya bisa berbuat lebih banyak.
Saya melihat saat Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin di suatu acara talkshow populer yang ditayangkan menjelang tengah malam, berani menyampaikan posisinya dalam isu-isu sensitif dengan artikulasi menarik. Bahkan merespon dengan benar-benar cerdas tentang kemungkinan jika suatu saat Menteri Agama di Indonesia bukan seorang Muslim. Linimasa media sosial riuh atas sikap Menag. Jangankan di talkshow itu. Saya mungkin sudah belasan kali harus meliput dan mencatat tiap ucapan Menag saat rapat di DPR (Komisi VIII, Komisi Agama).
Saya harus akui bahwa seumur hidup saya, inilah Menag yang benar-benar terbuka, equal, progresif dibanding Menteri Agama 25 tahun terakhir. Mungkin juga karena (termasuk menteri) termuda, simpatik, supel, humoris tinggi, kadang menyapa tentang lelucon ringan di media sosial untuk mencairkan suasana. Tapi saya bukan orang yang gampang silap atas nama besar.
Saya tak cukup terhanyut atas linimasa riuh memuji progresivitas Menteri Agama. Tapi ke-tidak antusias-an saya bukan semata karena Menteri Agama tak cukup progresif dalam isu Yasmin dan Filadelfia. Bahkan dalam talkshow itu, Yasmin dan Filadelfia tak disinggung oleh Menteri Agama dan ia tak cukup berani untuk berkomentar tentang Yasmin dan Filadelfia sebelum benar-benar ditanya. Nihil inisiatif nurani atau semacamnya dari Menteri Agama atas isu dua komunitas ini, meski dalam hal komunitas minoritas lain, harus diakui Pak Lukman lebih progresif membela.
Saya berusaha tak silap dan tak antusias, karena masih banyak catatan merah. Radikalisme masih belum surut ditengah kalangan muda. Tak perlu ISIS sebagai acuan. Tindakan “Tawur on the road” yang cenderung meningkat dibanding tahun lalu (di Jakarta saja) membuktikan masih gagalnya penyampaian pendidikan agama untuk diejawantahkan secara horizontal melalui budi pekerti seutuhnya.
Saya tinggal di daerah permukiman padat di Jakarta, yang mungkin bisa saya sebut “masyarakatnya amat konservatif dalam beragama”. Saya bisa berkata, bahwa muda-muda yang datang ke pengajian akbar yang sering diselenggarakan di (utamanya) Jakarta, sebagian kecil diantaranya ikut pula terlibat dalam kekerasan sepele semacam tawuran.
Saya khawatir, seolah “pengajian akbar” atau ibadah masif secara kuantitas seolah menjadi simbol “bahwa seseorang lebih beriman, lebih berpahala, lebih minim dosa”, sehingga kemudian mendiskreditkan yang lain. Ini berlaku bukan semata untuk agama saya, bisa jadi. Tentu kondisi ini menjadi PR bagi Menteri Agama pula untuk memformulasi bagaimana penyampaian pendidikan agama bisa secara simetris menimbulkan riil sepadan pekerti yang baik secara horizontal.
Terkadang, para peserta pengajian memposisikan diri sebagai “pihak yang lebih beriman, lebih taat secara vertikal pada Allah, Tuhan”. Saya harus akui bahwa saya tak cukup agamis, tak cukup Islamis, tak cukup religius. Bahkan kadang saya secara personal mendapat hardikan seolah ibadah saya kurang taat, kurang benar, semacamnya. Misalnya ibadah tak wajib, jumlah rakaat (dalam shalat di Islam) Shalat tak wajib, dan sebagainya, saya pernah menghadapi cibiran bahkan pernah mendapat “sentuhan fisik” amat mengganggu. Saya bukan Ahmadiyah. Tapi, saat secara personal proses ibadah saya dicibir oleh “yang mungkin lebih minim dosanya”, saya bisa memahami susahnya menjadi Ahmadiyah. Lebih-lebih yang non-Muslim.
Terlepas progresivitas kebijakan Menteri Agama, nyatanya itu tak menghasilkan “progresivitas” serupa secara riil dan meluas. Mungkin, bagi kalangan terbatas yang sama-sama menyukai ide-ide progresif, Pak Lukman dipuji setinggi langit. Tapi nyatanya, kasus-kasus hubungan antarseagama dan atau antaraagama tetap banyak, bisa menjadi meningkat.
Ini aneh, di saat Menteri Agama bisa dengan mudah merangkul banyak pihak, lebih-lebih karena beliau aktif di media sosial. Sementara di sisi lain, media sosial pula yang menjadi alat bagi “kubu intoleran” untuk secara leluasa menyampaikan isu-isu sensitif yang cenderung mendiskreditkan pihak lain. Bahkan saya tak bicara tentang ISIS, dan saya tidak sedang berusaha mengulas itu. Saya khawatir bahwa progresivitas untuk lebih peduli lintas agama hanya bergerak pada jargon, tapi hampir nihil dalam realitas.
Problem klasik “beda Lebaran” hampir pasti terulang, dan orang (lagi-lagi) lebih sibuk akan hal itu. Ketimbang memastikan akses yang lebih adil untuk yang minoritas. Lelucon “Bang toyib” secara sarkas lagi-lagi harus dialami Yasmin dan Filadelfia. Entah sudah lima atau enam kali lebaran, tapi tak kunjung diperbolehkan beribadah di gerejanya. Saya sedih bahwa masyarakat meributkan hal yang sepele, tapi justru membiarkan kondisi intoleran.
Saya tak mau bermimpi bahwa menjelang atau setelah Lebaran, Menteri Agama tiba-tiba memulihkan akses ibadah Yasmin dan Filadelfia misalnya. Saya sulit berharap pada Menteri Agama. Dan tentu, tak ingin berharap lebih banyak pada Presiden yang hanya berada 400 meter dari jamaah Yasmin dan Filadelfia saat beribadah di depan Istana. Sedekat itu, tapi Yasmin dan Filadelfia tetap terpaksa beribadah bukan di gerejanya, dan tak kunjung diperhatikan. Ramadan tahun ini masih penuh dengan intoleransi.



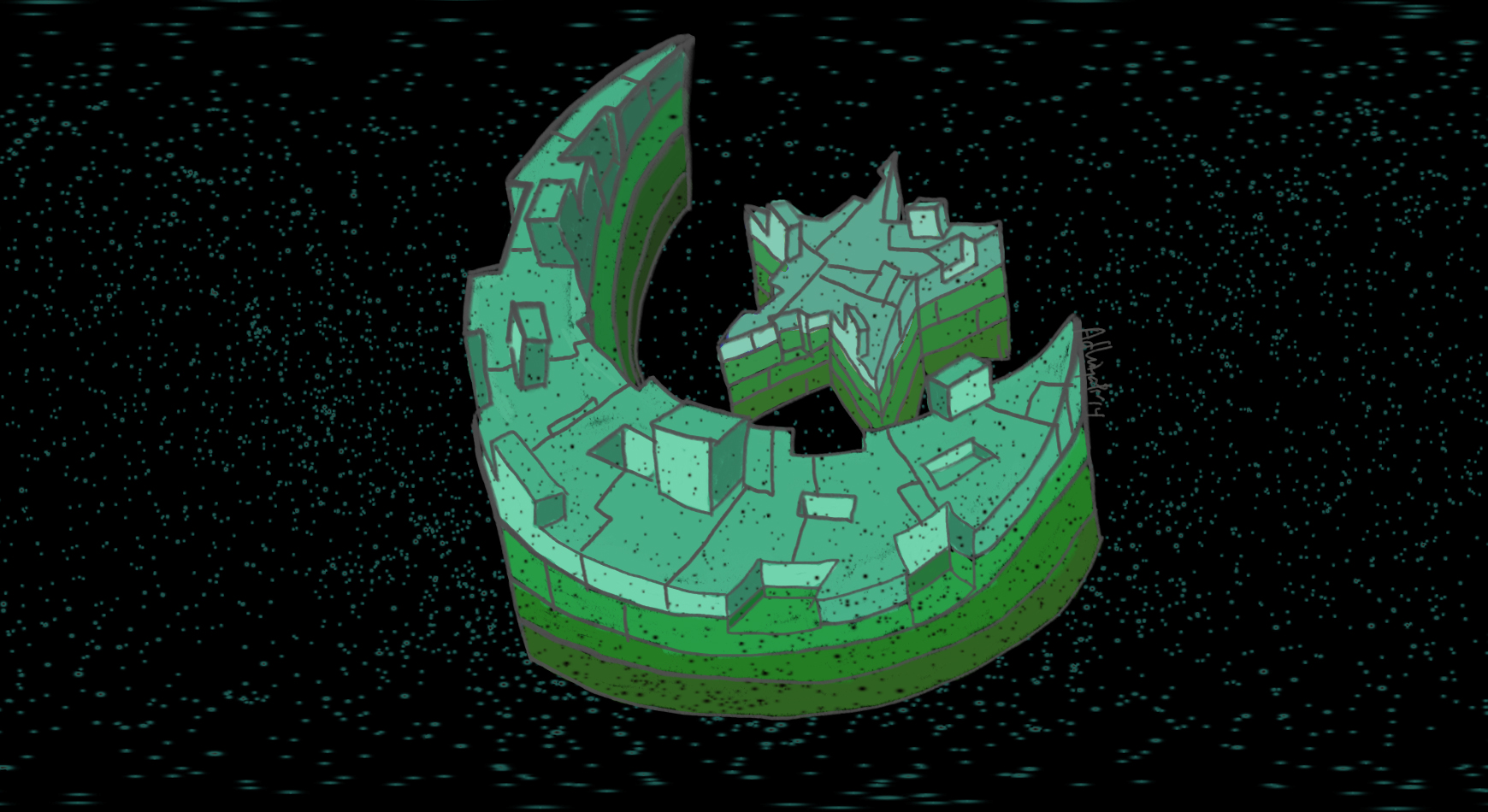



Comments