“Macet” dan “banyak polusi” adalah dua dari sekian banyak kata yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan Jakarta. “Romantis” biasanya tidak termasuk di antaranya.
Sebagai salah satu kawasan mega urban (sebuah kota inti dengan beberapa area metropolitan di sekitarnya) di Asia, Jakarta memang tidak mempunyai reputasi sebagai kota yang romantis. Padahal, sejak lama, Jakarta adalah melting pot (kuali peleburan) terbesar di Indonesia: Pusat bertemunya banyak ragam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Walau kerap didera dengan sederet masalah perkotaan, Jakarta sejatinya adalah sebuah tempat istimewa yang melatari kisah kasih antar penduduknya yang amat beragam ini.
Keanekaragaman suku bangsa di Jakarta terkait erat dengan posisinya sebagai salah satu provinsi tujuan migrasi utama di Indonesia. Menurut data Sensus Penduduk 2010, Jakarta berada di peringkat kedua—setelah Kepulauan Riau—sebagai provinsi dengan proporsi migran internal tertinggi. Sekitar 42 persen penduduk Jakarta lahir di luar Jakarta.
Dalam konteks migrasi dan keberagaman di ibu kota, pola perkawinan antarsuku menjadi suatu jendela yang unik untuk menelisik lebih jauh tentang seberapa besar faktor suku bangsa berperan dalam kehidupan romantika penduduk muda di Jakarta, dan selanjutnya, dalam proses pembentukan rumah tangga mereka.
Pola perkawinan antarsuku di Jakarta
Lima tahun belakangan ini, saya meneliti pola perkawinan antarsuku di Indonesia. Saya menggunakan beberapa sumber data. Selain data dari Sensus Penduduk 2010, saya juga menggali data kualitatif dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah di Jakarta, Yogyakarta, dan Malang, Jawa Timur.
Di Indonesia, perkawinan antarsuku lazim kita jumpai, namun bukan yang paling banyak terjadi. Data dari Sensus Penduduk 2010 mengindikasikan bahwa hanya satu dari sembilan perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan antarsuku.
Baca juga: Bagaimana Rasialisme Terbentuk dan Bertahan di Masyarakat?
Selain faktor campur tangan pihak ketiga seperti orang tua dan keluarga, pilihan individu itu sendiri—misalnya untuk menikah dengan seseorang berlatar belakang keluarga dan budaya yang serupa—juga bisa menjelaskan rendahnya angka perkawinan antarsuku.
Patut dicatat bahwa dengan keterbatasan data sensus yang hanya memperbolehkan satu orang untuk memilih satu suku bangsa yang mewakili dirinya, besar kemungkinan perkiraan dalam sensus jauh lebih kecil dari angka perkawinan antar-etnis sebenarnya. Di samping itu, ada indikasi bahwa tingkat perkawinan antarsuku semakin tinggi di antara pasangan yang usianya lebih muda.
Jakarta mempunyai tingkat perkawinan antar-etnis tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia. Sekitar satu dari tiga pasangan menikah di Jakarta terdiri dari pasangan suami-istri berbeda suku (menurut catatan sensus). Bandingkan misalnya dengan persentase pasangan beda suku di Jawa Tengah yang hanya 2 persen dari total jumlah pasangan.

Hasil analisis saya terhadap sampel penduduk dewasa muda (20-39 tahun) Jakarta yang menikah menghasilkan beberapa kesimpulan.
Pertama, individu dari suku bangsa yang populasinya relatif besar mempunyai kemungkinan perkawinan antarsuku yang lebih kecil dibanding individu yang berasal dari suku bangsa minoritas di Jakarta. Contohnya, suku Jawa. Karena banyaknya suku Jawa di Jakarta (sekitar 36 persen dari populasi), secara matematika, seorang laki-laki Jawa memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertemu dan jatuh cinta dengan perempuan Jawa juga walaupun tidak ada preferensi pribadi atau wejangan orang tua yang mengharuskannya menikah dengan sesama Jawa.
Kedua, tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kemungkinan perkawinan antarsuku. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan dia untuk menikahi orang dari suku yang berbeda.
Dalam hal ini, menarik untuk diteliti lebih jauh apakah pendidikan memengaruhi sikap dan pandangan seseorang dalam melihat perbedaan; atau apakah ruang pendidikan menyediakan tempat pertemuan dan interaksi antar individu yang beragam.
Ketiga, para migran baru (mereka yang baru tinggal di Jakarta kurang dari lima tahun) memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menikah antarsuku dibanding non-migran atau migran yang sudah lebih lama tinggal di Jakarta.
Sayangnya, kita tidak dapat menelusuri kapan dan di mana seseorang bertemu dengan jodohnya. Jadi, kita tidak dapat menyimpulkan apakah para migran baru ini cenderung menikah sebelum atau setelah bermigrasi ke Jakarta.
Di Indonesia, perkawinan antarsuku bukan yang paling banyak terjadi. Selain faktor campur tangan pihak ketiga seperti orang tua dan keluarga, pilihan individu itu sendiri juga bisa menjelaskan rendahnya angka perkawinan antarsuku.
Hasil wawancara mendalam dengan penduduk dewasa muda di Jakarta menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dalam praktik perjodohan oleh keluarga, pengaruh pihak ketiga dan struktur sosial yang lebih luas terus memengaruhi pola berpasangan dan perkawinan.
Menurut responden, selain suku bangsa, identitas sosial yang lebih berperan dalam proses membentuk rumah tangga adalah agama dan kelas sosial.
Dalam konteks masyarakat urban masa kini, perkawinan masih lumrah dilihat sebagai tanda bersatunya dua keluarga. Artinya, walau responden merasa bahwa mereka memiliki jauh lebih banyak kebebasan untuk memilih pasangannya daripada generasi sebelumnya, peran orang tua dan jaringan kekerabatan tetap dilihat penting dalam keputusan menikah.
Patut dicatat bahwa banyak responden menilai bahwa sikap keluarga dan masyarakat yang menentang perkawinan antarsuku sebagian besar berkaitan dengan agama. Namun, terkadang sulit untuk memisahkan identitas etnis dan agama di Indonesia.
Yang bisa dipelajari
Sekilas, mempelajari tentang pola siapa yang menikah dengan siapa terlihat sebagai suatu topik penelitian yang tidak penting. Namun, banyak yang kita bisa pelajari dari situ. Bagaimana pola ini berubah dari masa ke masa? Bagaimana pola ini bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, dan dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lainnya?
Baca juga: Ruang (Ny)Aman: Dilema Pernikahan Beda Agama
Meneliti pola bagaimana individu berpasangan dalam perkawinan adalah salah satu awalan untuk memahami kerumitan karakter hubungan antar-kelompok sosial—baik itu antarsuku bangsa, ras, maupun agama—dan kaitannya dengan proses pembangunan dan perubahan sosial di Indonesia.
Dalam hal ini, proses perubahan sosial mencakup banyak dimensi, termasuk tren migrasi, urbanisasi, dan globalisasi yang berimbas terhadap pergeseran pola perkawinan.
Batas-batas antar-kelompok sosial yang memengaruhi ruang gerak setiap individu tidak bersifat statis. Batas-batas ini kerap mengeras dalam waktu-waktu tertentu.
Dalam pendidikan formal, sejak bangku TK, kita kerap mengelu-elukan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika. Tapi, dalam urusan perkawinanlah pagar-pagar yang membatasi berbagai kelompok masyarakat benar-benar diuji: apakah jika memang berbeda tetap bisa menjadi satu?
Pada kenyataannya, kita masih sering menjumpai kisah kasih tak sampai karena faktor perbedaan agama, suku bangsa, ataupun karena kombinasi keduanya. Tak terkecuali di Jakarta; kota metropolitan yang menjadi simbol modernisasi dan melting pot penduduk di Indonesia.
Dua keluarga dengan suku dan/atau agama yang berbeda bisa hidup rukun bertetangga. Namun, belum tentu perkawinan antar anak-anak mereka akan disambut dengan suka cita dan lapang dada oleh orang tua, kerabat, tetua adat, maupun—dalam hal agama—oleh negara.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.



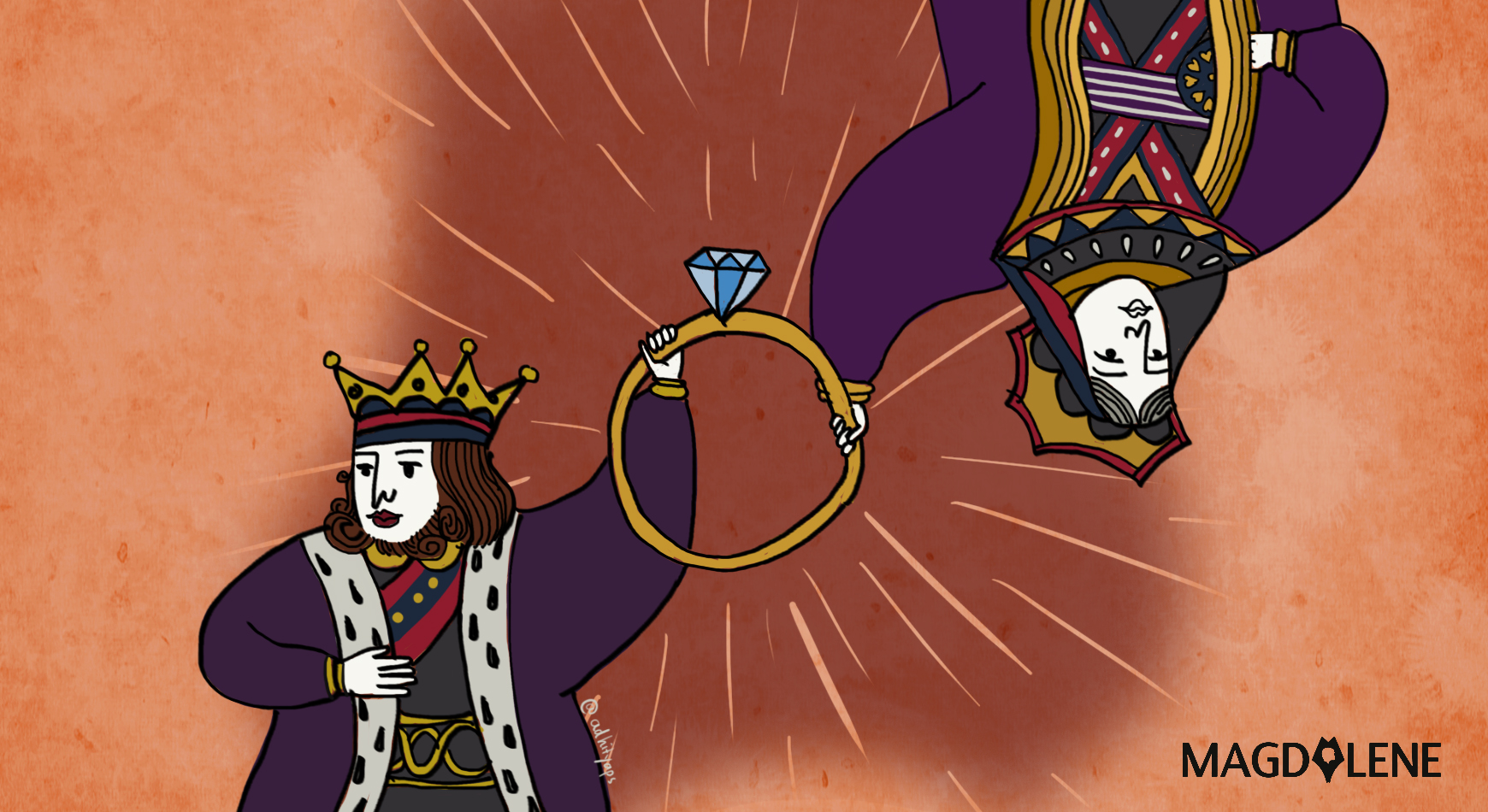



Comments