“Kulit putih bersinar hanya dalam tujuh hari. Dapatkan manfaatnya setelah menggunakan produk ini.”
Hidup di tengah masyarakat modern berarti tak asing dengan jargon-jargon seperti ini tiap kali menyaksikan iklan dan tayangan lain di televisi, radio, media sosial, dan berbagai platform berbasis internet. Sama halnya dengan berbagai produk penurun berat badan, hal ini melahirkan dan turut melanggengkan standar kecantikan yang menuntut perempuan untuk memiliki penampilan tertentu dan membenci penampilan aslinya. Mungkin, jamak kita saksikan atau bahkan alami, ejekan-ejekan dari teman-teman, keluarga, dan masyarakat yang menyerang penampilan kita.
“Kulit apa ban mobil, tuh? Item banget!”
“Eh, tambah cantik, deh! Putihan, ya?”
Bahkan sejak kita kecil, kita sudah disodori keyakinan, memiliki kulit putih akan meningkatkan nilai diri di kehidupan sosial. Sementara, kulit gelap mendorong kita menerima ejekan juga nasihat-nasihat yang tidak perlu mengenai kiat-kiat memutihkan kulit. Namun tahukah kamu, standar kecantikan kulit putih ini memiliki sejarah yang mendasar dalam hal warnaisme (colorism) di dunia?
Associate professor of Women's Studies di University of Hawaii, Manoa dan penulis buku Seeing Beauty, Sensing Race in Transnational Indonesia (2013) Luh Ayu Saraswati menjelaskan, melihat sejarah warna putih tak bisa dilepaskan dari kajian sejarah Indonesia puluhan hingga ratusan tahun silam, terutama pada masa kolonialisme.
Pada zaman pra-penjajahan Belanda, putih tidak dilekatkan dengan ras, tetapi hanya sebagai warna atau warnaisme di mana hal-hal yang berwarna putih memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada warna hitam. Putih kemudian dipercaya bukan sebagai sekadar warna, melainkan terminologi yang mengandung hierarki berbasis rasialisme, warnaisme, dan gender. Sesuatu yang memiliki warna putih dianggap lebih baik karena dianggap lebih bersih. Sementara itu, warna hitam dianggap sebagai hal yang kotor dan tidak diinginkan.
“Secara tidak sadar, kita berpartisipasi melanggengkan gagasan-gagasan mengenai superioritas putih itu. Proses pemaknaan itu berlangsung secara tidak sadar melalui tatanan emosi kita. Misalnya, dalam berbagai film, karakter yang baik biasanya memiliki warna putih atau warna terang. Sementara tokoh yang jahat, menakutkan, dan horor, ditandai dengan warna hitam, seperti jubah hitam,” ujar Ayu dalam diskusi panel ‘Bongkar Kata’ Etalase Pemikiran Perempuan 2021 pada (24/7).
“Yang menarik, di Indonesia, rasialisme dan warnaisme tidak selalu tumpang tindih. Kalau di Amerika Serikat, orang kulit putih dianggap lebih baik. The lighter the better. Namun di Indonesia, berdasarkan riset saya, ketika seseorang berkulit putih tapi dia berasal dari suku atau ras yang tidak populer, misalnya Cina, orang itu belum tentu dianggap cantik dan desirable.”
Baca juga: Bagaimana Standar Kecantikan Menghancurkan Perempuan?
Berlanjut hingga masa kolonialisme Belanda, para penjajah memunculkan gagasan-gagasan kecantikan bahwa bukan hanya berkulit putih, perempuan yang cantik juga adalah perempuan yang berasal dari bangsa kulit putih (Eropa), ujar Ayu. Pada saat itulah, warnaisme dan rasisme tumpang tindih dan mulai dimaknai sebagai satu sama lain.
Begitu pula ketika zaman penjajahan Jepang, para penjajah Jepang memunculkan gagasan cantik yang baru, bahwa yang cantik adalah orang-orang berkulit lebih terang dan berkebangsaan Jepang.
Standar Kecantikan Bergeser, Putih Tetap Nomor Satu
Ayu melanjutkan, ketika Indonesia sudah merdeka, standar kecantikan terus bergeser. Tapi, tetap saja putih yang jadi standar utama.
“Setelah 1998, muncul gagasan putih kosmopolitan atau cosmopolitan whiteness, yaitu standar kecantikan berupa kulit putih, tapi tidak mengacu pada bangsa tertentu. Bangsa apa aja bisa jadi putih. Sebelumnya, perempuan Jepang mengiklankan produk-produk kecantikan Jepang. Nah, ketika masuk reformasi, perempuan Jepang bisa mengiklankan produk-produk Perancis atau negara lain, selama dia berkulit putih,” kata Ayu.
Ia menambahkan, produk pemutih kulit banyak ada di Indonesia, tapi model iklannya pun berasal dari berbagai negara. Pada masa ini, konsep putih menjadi semu, tapi juga berbahaya karena putih seolah bisa dicapai siapa saja dengan mudah dengan berbagai produk kecantikan.
“Pada saat yang bersamaan, putih menjadi elusif atau semakin sulit digapai karena dimaknai secara luas dan tidak jelas,”ujar Ayu.
Keinginan untuk memiliki kulit putih itu ada di berbagai kalangan dan kelas sosial. Hal ini adalah bukti bahwa baik kolonialisme maupun kehidupan masyarakat modern menjebak perempuan dalam angan-angan yang sebenarnya tidak signifikan.
Ayu juga menilai, hierarki warna putih menunjukkan bias kelas atau status sosial. Orang-orang yang berkulit putih dianggap berstatus sosial lebih tinggi karena mereka lebih terawat, jarang bepergian di bawah terik matahari, dan tidak melakukan kerja-kerja kasar yang banyak dilakukan orang-orang dari kelas pekerja.
Baca juga: Stop Pandang Kulit Putih Lebih Superior
Namun di sisi lain, Ayu menemukan keinginan untuk memiliki kulit putih itu ada di berbagai kalangan dan kelas sosial. Hal ini adalah bukti, baik kolonialisme maupun kehidupan masyarakat modern menjebak perempuan dalam angan-angan yang sebenarnya tidak signifikan.
“Kalau mau bicara body positivity, yang harus ditekankan adalah yang bermasalah bukan diri kita, besar kecilnya ukuran tubuh, kulit hitam atau putih. Yang salah adalah ideologi kecantikan yang mengharuskan perempuan menjadi seperti standar ini-itu,” terang Ayu.
Bagaimana Kolonialisme Merugikan Perempuan
Selain membentuk standar kecantikan yang tidak masuk akal, berbagai aspek dalam kehidupan perempuan juga turut berubah dan dirugikan oleh kolonialisme. Menurut akademisi dari Universitas Papua dan aktivis perempuan Els Tieneke Rieke, kolonialisme mengubah struktur sosial masyarakat adat Papua, seperti suku Kamoro di Mimika, yang semula seimbang antara laki-laki dan perempuan, menjadi tidak seimbang. Hal itu juga diperparah dengan sifat kolonialisme yang berdasar pada pemikiran dan perlakuan yang eksploitatif dan kental akan kekerasan.
“Secara tradisional, perempuan adalah pencari nafkah utama. Makanya perempuan diberi kapasitas sebagai pemilik unsur-unsur tanah, sungai sebagai sumber kehidupan. Ketika Belanda datang, peran perempuan diturunkan, diubah menjadi laki-laki sebagai kepala keluarga sebagai ciri masyarakat modern. Mulai diperkenalkan hierarki, yang paling atas laki-laki kulit putih, lalu laki-laki Kamoro, dan perempuan Kamoro,” ujar Els dalam panel yang sama.
“Yang paling bawah itu adalah alam. Masyarakat adat itu sangat menghargai alam, menganggapnya sebagai ibu dan sumber kehidupan. Tapi, Belanda mengubahnya menjadi hubungan eksploitatif. Sebagaimana perempuan, alam juga harus dieksploitasi laki-laki agar bisa menjadi sumber daya bagi laki-laki kulit putih dan perkembangan budaya mereka.”
Baca juga: Operasi Plastik: Antara Otoritas Tubuh dan Tuntutan Masyarakat
Menurut Els, kolonialisme juga merusak konsep seksualitas perempuan. Ia mencontohkan, semula, orang-orang Kamoro, terutama perempuan, sangat menghargai seksualitas. Mereka merayakannya dalam berbagai ritual. Misalnya, ketika perempuan memasuki masa menstruasi, itu dirayakan dalam ritual dan pesta.
Meski begitu, para penjajah menilai, upacara adat dan ritual masyarakat Papua itu menunjukkan kemalasan dan sifat tidak beradab sehingga harus diubah. Menurut Els, para penjajah memaksa masyarakat bekerja, menggiring mereka ke dalam mesin ekonomi kapitalis. Makna seksualitas kemudian digeser menjadi sekadar hubungan seksual yang eksotis, kotor, hanya menguntungkan laki-laki, dan menantang karena penuh petualangan.
“Misalnya, ada buku harian para geologis Belanda. Mereka berkata, melihat puncak gunung yang ditutupi salju itu menggairahkan karena mengingatkan akan tubuh perempuan. Padahal, dalam konteks masyarakat adat, baik alam maupun seksualitas adalah sesuatu yang sakral.” kata Els.
Ilustrasi oleh Karina Tungari



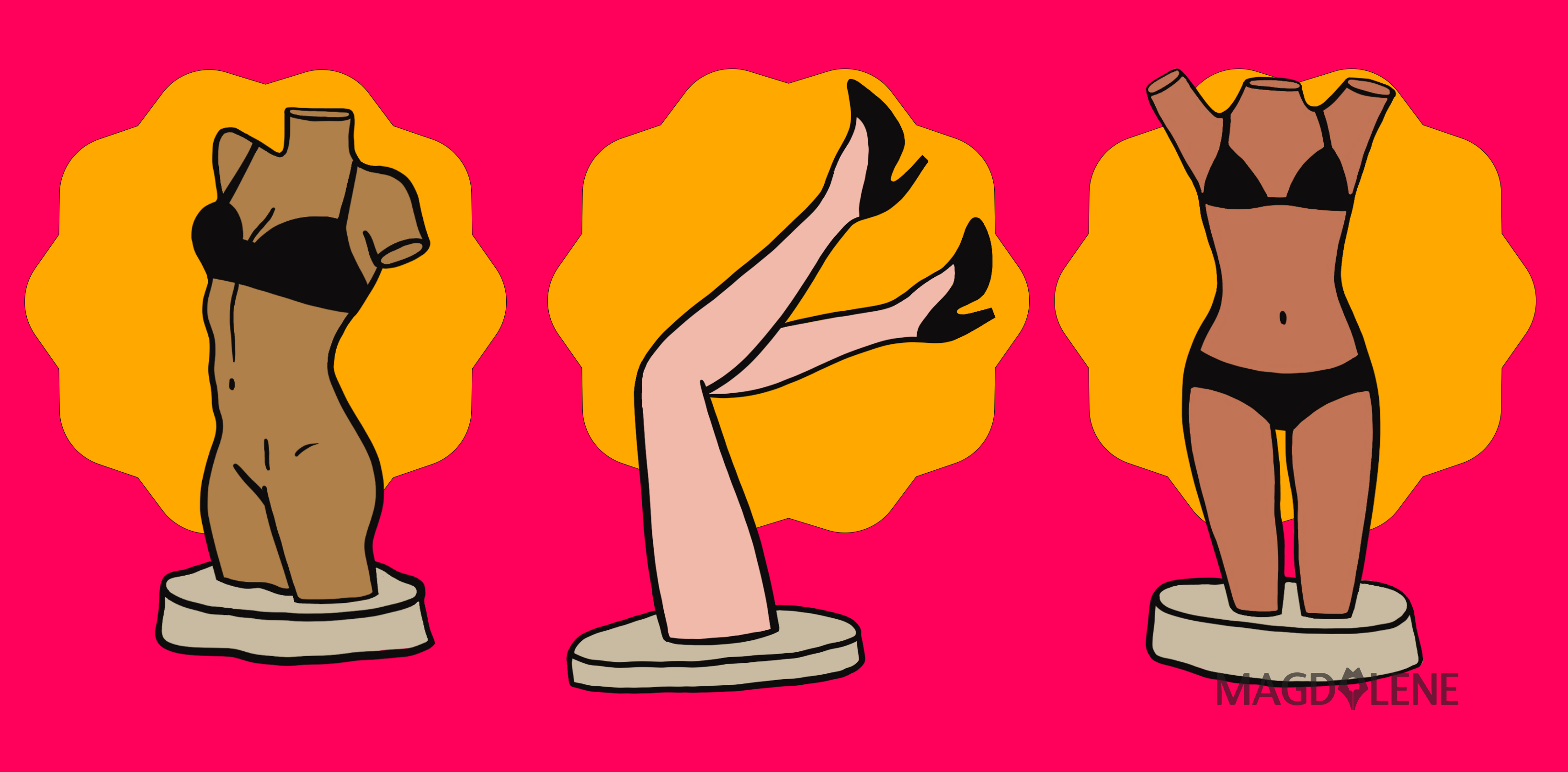




Comments