Belakangan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dialami selebriti LK oleh suaminya sendiri, RB menyedot perhatian kita. Kasus ini sendiri telah memantik kesadaran publik akan pentingnya melawan KDRT sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender.
Banyak perempuan lain di seluruh penjuru Indonesia juga mengalami KDRT – hanya saja pengalaman mereka kerap tak tersorot kamera media.
Pada 2020 saja, Komnas Perempuan melaporkan adanya 2.389 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 1.404 (65 persen) di antaranya merupakan KDRT.
Jumlah tersebut merupakan fenomena gunung es yang hanya terlihat puncaknya saja. Masih banyak kasus yang tidak terlaporkan dan laten di bawah permukaan.
Walaupun Indonesia sudah memiliki produk hukum untuk memerangi KDRT, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan domestik masih kerap terjadi karena adanya hambatan sosiokultural. Ini termasuk kentalnya anggapan dalam masyarakat Indonesia KDRT merupakan ‘aib’ bagi perempuan.
Padahal, dengan adanya kemajuan teknologi, salah satunya media sosial, kita sebenarnya punya peluang lebih besar untuk menyuarakan hak-hak korban KDRT dan membantu mereka mendapatkan akses keadilan.
Baca juga: Nyaring dan Sunyi KDRT: Suramnya Budaya Kepemilikan dalam Keluarga
KDRT adalah Kriminal, Bukan Urusan Privat
Budaya patriarki – yang menempatkan perempuan pada posisi kelas dua – di Indonesia telah membentuk ekspektasi sosial tentang standar seorang perempuan yang “baik”. Selama ini, secara sosial dan kultural, perempuan dikonstruksi sebagai makhluk yang harus bersifat lembut, emosional, dan keibuan.
Langgengnya konstruksi inilah yang memperburuk kondisi ketidakadilan gender di Indonesia.
Dalam kasus KDRT, misalnya, masyarakat menganggap perempuan atau istri, bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jika perempuan menuntut perceraian sebagai upaya untuk lepas dari tindak KDRT, mereka kerap disalahkan dan dianggap gagal mengemban tugasnya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.
Stigma sosial kekerasan domestik adalah aib bagi keluarga selalu membuat masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan privat yang tidak seharusnya diintervensi, cenderung ditutup-tutupi, dan sebisa mungkin jangan sampai diketahui oleh publik.
Hal ini membuat penanganan kasus KDRT menjadi terhambat, baik karena korban enggan untuk melapor atau karena masyarakat enggan mengintervensi.
Konstruksi sosiokultural ini menyebabkan lahirnya dikotomi (pemisahan) antara ruang privat dan publik dalam merespons KDRT. Banyak pemikir feminis telah mengkritik hal ini. Mereka berpendapat bahwa dikotomi tersebut kerap menjadi dalih untuk mempertahankan penindasan terhadap perempuan.
Riset menunjukkan bahwa dikotomi ruang tersebut berdampak negatif terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asas manusia (HAM), khususnya bagi perempuan korban KDRT. Dampak ini lebih besar pada bagi perempuan miskin yang memiliki keterbatasan uang, waktu, dan rasa percaya diri. Peluang mereka untuk mengakses layanan publik, termasuk layanan pelaporan dan perlindungan dari kekerasan, sangat terbatas.
UU PKDRT sebenarnya telah tegas menyebutkan bahwa KDRT adalah pelanggaran HAM. UU ini menjadi bentuk jaminan dari negara untuk mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT.
Sayangnya, sejak UU ini melalui ratifikasi 16 tahun lalu, penanganan masalah KDRT di Indonesia belum juga membaik. Artinya, perangkat UU saja belum cukup efektif apabila tidak diimbangi dengan upaya penanaman nilai tentang pentingnya kesetaraan gender untuk merespon hambatan sosiokultural tersebut.
Amanat UU PKDRT kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai KDRT kepada masyarakat juga belum berdampak signifikan. Ini karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih menafsirkan KDRT hanya sebagai kekerasan fisik. Padahal, UU PKDRT telah menjabarkan, KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga yang berakar pada berbedaan berbasis gender.
Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pelaporan kasus KDRT non-fisik.
Berdasarkan penjelasan di atas, penting bagi publik di Indonesia untuk membantu mendekonstruksi (membongkar) stigma sosikultural tersebut dan menyuarakan bahwa KDRT bukan lagi permasalahan privat, melainkan pelanggaran HAM yang perlu diintervensi oleh publik dan negara.
Dengan melakukan hal itu, perempuan, laki-laki, dan kelompok non-biner yang menjadi korban KDRT tidak perlu lagi ragu atau enggan untuk mencari perlindungan. Otoritas berwajib pun semakin mudah untuk melakukan intervensi.
Baca juga: Beranilah untuk Berpisah
Partisipasi Publik melalui Teknologi
Perkembangan teknologi digital kini semakin mengaburkan batas antara ruang privat dan publik. Hadirnya media baru menyediakan akses bagi publik untuk melihat apa yang terjadi di ranah privat.
Dalam konteks KDRT, kaburnya batas antara ruang privat dan publik ini justru menjadi peluang untuk menciptakan ruang pencegahan dan penanganan KDRT melalui intervensi negara. Dalam kasus dugaan KDRT oleh RB kepada LK, misalnya, publik dapat cepat mengetahuinya karena tersebar melalui media sosial. Adanya tekanan dari masyarakat yang ramai mengecam pelaku kasus ini pun mendorong intervensi yang lebih cepat dari pihak kepolisian.
Publik juga turut berpartisipasi memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Salah satunya, misalnya, berdampak pada pemutusan hubungan kerja antara terduga pelaku dengan salah satu stasiun televisi.
Contoh lain adalah yang dialami oleh seorang kreator video (vlogger) dari Tibet yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya setelah mengalami KDRT. Selang beberapa bulan, ketika ia melakukan siaran langsung (livestreaming) pada September 2020, sang mantan suami tiba-tiba datang dan membakarnya hidup-hidup.
Publik yang menyaksikan peristiwa itu melalui kanal media sosial pun langsung mengecam dan mendorong negara untuk bertindak tegas. Akhirnya, pemerintah menjatuhi pelaku dengan hukuman mati. Sementara, di antara masyarakat Tibet berkembang diskursus mengenai kegagalan negara dalam melindungi korban KDRT.
Kita perlu memahami juga bahwa tekanan publik semacam ini, yang sering disebut viral-based policy, bukanlah bentuk partisipasi warga yang ideal. Namun, di sisi lain, pemanfaatan media sosial menjadi peluang yang besar bagi penanganan KDRT karena aksesibilitasnya yang luas dan mampu menyuarakan kepentingan korban.
Baca juga: KDRT dalam Kebijakan Imigrasi dan Diplomasi
Bijak Menggunakan Media Baru
Meskipun media baru berpotensi menyediakan ruang untuk memenuhi hak-hak korban KDRT, tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi ini belum sepenuhnya bisa menjadi ruang yang aman.
Praktik kekerasan berbasis gender juga banyak terjadi di media sosial seiring berkembangnya teknologi digital. Pada 2020, laporan Komnas Perempuan mencatat 281 kasus kejahatan siber (cybercrime) berbasis gender.
Menyuarakan pengalaman KDRT melalui kanal media sosial juga sangat mungkin menempatkan korban pada posisi rentan terhadap kekerasan verbal di ranah digital. Ini karena, kembali lagi, masih kuatnya keyakinan bahwa KDRT adalah kesalahan perempuan.
Pada akhirnya, kita perlu menggunakan media baru dengan lebih cermat dan bijak. Sebisa mungkin, kita perlu mengupayakan penggunaannya untuk memenuhi hak-hak korban KDRT, bukan justru berkontribusi menimbulkan kekerasan verbal pada korban dan menyalahkan mereka.
Kuncinya, anggapan KDRT merupakan masalah privat perlu kita runtuhkan terlebih dahulu agar tidak menjadi batu sandungan bagi korban dan otoritas berwenang untuk menciptakan ruang aman dari segala bentuk kekerasan.![]()
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.





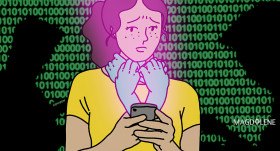

Comments