“Sedih banget. Aku ngerasa kaya satu support system di hidup berkurang. Aku biasanya kalau capek kerja nontonin video mereka. Nanti dua tahun lebih enggak lihat mereka, aku bakal gimana ya?”
Begitulah ucap Aca, 26, pengacara perempuan yang juga seorang ARMY–fans idol BTS. Ucapan itu terlontar saat Aca mendengar pengumuman BTS bakal hiatus untuk mengikuti wajib militer (wamil).
Dalam pengumuman publik, (17/10), label yang menaungi BTS, Bighit Music menyampaikan rencana hiatus idol ini hingga 2025. Hiatus itu dilakukan dalam rentang kurang lebih dua tahun secara bergantian, dimulai oleh anggota tertua Kim Seokjin, 29. Keputusan BTS tersebut mengakhiri perdebatan intens bertahun-tahun tentang kemungkinan pembebasan mereka atas wajib militer.
Dilansir dari BBC, beberapa amandemen undang-undang wajib militer yang akan membuka jalan bagi para anggota BTS untuk dibebaskan, bahkan sempat diperkenalkan di Majelis
Nasional. Namun, Parlemen tidak bisa mengambil keputusan karena anggotanya terbelah tajam.
Sebagai ARMY yang tumbuh secara emosional bersama BTS, pengumuman wajib militer bikin perasaan Aca campur aduk. Ia merasa senang karena BTS punya kontrol terhadap hidup mereka di tengah perdebatan politik yang tak ada habis-habisnya. Namun, ia juga takut hiatusnya BTS pasti sedikit banyak akan berdampak pada hidupnya.
Aca pun tidak sendiri. Sinta, 36, merasakan hal yang sama.
“Sebenarnya soal wamil ini konsepnya ‘tinggal tunggu waktu aja' ya. Meskipun udah terlatih buat siap, pas dikasih pengumuman kemarin aku tetap nangis. Sedihnya lebih ke 'wah dua tahun enggak bakal ketemu atau lihat mereka. Mereka baik-baik aja kan?'”
Baca Juga: Di Balik Rehatnya BTS: Politis, Bisnis, Wajib Militer, sampai Ketahanan Nasional
Kewajiban yang Eksis Sejak Zaman Kerajaan
Berbeda dari negara-negara seperti Swedia, Singapura, atau Swiss yang baru memberlakukan wamil sejak abad ke-21, pemberlakuan kebijakan itu di Korea Selatan sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan.
Dikutip dari Military Manpower Administration of South Korea dan wawancara Yang Seung Yoon, Profesor Emeritus Hankuk University of Foreign Studie bersama CNN, skema wajib militer berakar dari ajaran konfusianisme di Korea Selatan. Melalui ajaran ini, masyarakat Korea mengalami perubahan sosial budaya lewat segregasi peran gender. Laki-laki pada dinasti ini memikul tanggung jawab dalam urusan perdagangan dan pertahanan negara.
Secara spesifik dalam pertahanan negara, jika pada dinasti Goryeo (918 – 1392) mengadopsi sistem ganda tentara reguler profesional dan pasukan cadangan tak memandang jenis kelamin dan usia, maka pada saat dinasti Joseon (1392 – 1897) sistem ini diubah.
Untuk pertama kalinya pada Dinasti Joseon, wamil berlaku jamak bagi laki-laki berusia 16-60 tahun, bahkan dalam kondisi damai sekali pun. Sistem ini bertahan sampai adanya usaha reformasi wajib militer modern yang muncul pada 1894. Hong Beom-shik (komandan Tentara Kemerdekaan Korea selama pemerintahan kolonial Jepang) secara khusus menawarkan visinya untuk mereformasi sistem wajib militer sebagai bagian dari reformasi urusan negara. Pada Juli 1907, Undang-Undang Perekrutan diumumkan dan pada Agustus 1908, Peraturan Pendaftaran Militer ditetapkan.
Aturan-aturan ini adalah kerangka kerja untuk sistem wajib militer modern yang merinci usia, peran, batas waktu layanan, dan rencana rekrutmen di masa damai dan perang. Jong Cheol Kim, guru besar hukum di Fakultas Hukum Universitas Yonsei menjelaskan dasar wajib militer di Korea Selatan yang dikuatkan oleh Konstitusi Republik Korea (대한민국), dan diundangkan pada 17 Juli 1948. Hal ini menyusul urgensi pertahanan nasional Korea Selatan dari serangan Korea Utara setelah pecahnya Perang Korea pada 1950 hingga 1953.
Hingga kini, Korea Selatan pun masih menganggap wamil diperlukan. Alasan perlunya wajib militer tak lain karena situasi di Semenanjung Korea yang masih dalam gelombang Perang Dingin. Hal ini ditambah dengan situasi yang semakin memanas akibat uji nuklir yang dilakukan Korea Utara.
Dengan rentang ratusan tahun, wajib militer secara tidak langsung menjadi unsur integral dalam lanskap sosial budaya masyarakat Korea Selatan. Ia tak hanya jadi penanda nasionalisme laki-laki Korea Selatan tetapi bagi sebagian masyarakat Korea Selatan, punya keuntungan ekonomi.
Setelah penjajahan dan perang saudara yang terjadi di Korea Selatan, perekonomian Korea mengalami pasang surut. Perang mengakibatkan Korea Selatan jatuh dalam jurang kemiskinan. Dilansir dari Forbes pada 1950-an misalnya, sebanyak 80 persen penduduk perkotaan berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita kurang dari US$100. Dengan adanya wamil, pemerintah Korea Selatan dapat menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang melalui skema pertahanan negara.
Baca Juga: Rambut Pendek An San dan Feminisme yang Ditabukan Korea Selatan
Masalah yang Timbul dari Wajib Militer
Kewajiban militer boleh saja dibenarkan lewat situasi politik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Akan tetapi selama pelaksanaannya wajib militer kerap mendapatkan banyak kritikan. Chad de Guzman melaporkan dalam Time, telah terjadi berbagai pelanggaran HAM selama wajib militer diberlakukan di Korea Selatan.
Setidaknya ada sekitar 19.000 orang dijebloskan ke balik jeruji selama bertahun-tahun sejak 1950. Mayoritas dari mereka adalah Saksi-Saksi Yehuwa. Kelompok agama yang secara historis menolak wajib militer atas dasar moral dan agama. Selama tahun-tahun darurat militer pada 1970-an, beberapa disiksa, dipukuli, atau bahkan dibunuh.
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan atas wajib militer ini kemudian jadi sorotan utama dalam revisi undang-undang militer mereka. Tercatat mulai 2018, Korea Selatan memberlakukan alternatif wajib militer. Sebagai pengganti wajib militer, conscientious objector (mereka yang menolak wajib militer atas dasar keyakinan atau hati Nurani) diharuskan bekerja di sistem penjara Korea Selatan.
Mereka ditugaskan di binatu dan dapur penjara dengan waktu tugas selama 36 bulan—dua kali lebih lama dari wajib militer. Meski diberi cuti beberapa minggu, mereka harus tinggal di penjara dengan pergerakan mereka diatur dan diawasi secara ketat. Karena itu, menurut Ajeng Larasati, Human Rights Lead di Harm Reduction International dalam wawancaranya bersama Magdalene diberlakukannya alternatif wajib militer ini bisa diperdebatkan. Ini bisa jadi celah pelanggaran HAM dan menambah stigma sosial bagi conscientious objector yang nanti kembali ke masyarakat.
“Kita harus paham suatu alternatif itu harus melalui pertimbangan bahwa it will be less restrictive dan less damaging bagi individu bersangkutan. Jika alternatif yang diberikan ternyata tidak proporsional, maka jatuhnya bukan alternatif tetapi justru hukuman”
Menentukan proporsionalitas sendiri menurut Ajeng dalam konteks HAM, juga harus didasari perspektif non-diskriminatif. Pemegang kuasa harus menyadari setiap orang punya keadaan berbeda-beda sehingga bisa disesuaikan. Tak lupa, tujuan yang ingin dicapai dalam alternatif itu harus pertimbangan urgensi dan kebutuhannya.
“Kalau misalnya alternatif wajib militer 18 bulan sudah menjawab urgensi dan kebutuhan negara, rentang ‘pengabdian’ selama 3 tahun jadi unnecessary”
Selain dari perspektif HAM, wajib militer juga dianggap problematik karena menggarisbawahi privilese yang dimiliki kelompok masyarakat ekonomi menengah dan atas. Dalam survei yang dilakukan surat kabar Chuso Ilbo kepada 39.096 responden laki-laki misalnya ditemukan semakin banyak penghasilan orang tua, semakin kecil kemungkinan anak laki-laki mereka melakukan tugas militer aktif. Sekitar 7,5 persen laki-laki dengan ayah berpendidikan perguruan tinggi melakukan beberapa jenis wajib militer alternatif, dibandingkan dengan 5,5 persen dari mereka yang memiliki ayah berpendidikan rendah.
Baca Juga: Presiden Baru Korsel Anti-Feminis, Kesetaraan Gender Terancam
Lebih lanjut, anak-anak dokter adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan dinas militer mereka sebesar 81,6 persen. Berikutnya adalah putra pendeta dan tokoh agama lainnya (82,7 persen), penyiar atau seniman (82,9 persen), akademisi (83,8 persen) dan, perwira militer (85 persen).
Dengan adanya privilese ini, ketimpangan ekonomi semakin terlihat nyata. Di saat laki-laki muda dari keluarga miskin dan menengah bawah harus terputus dari masyarakat dan kehilangan pekerjaan atau memutus waktu studi mereka, laki-laki muda berada bisa dengan mudah keluar dari sistem yang tidak menguntungkan ini.
Beberapa narasumber dalam penelitian Johan Cornelis Schoonhoven dari Universitas Lund, Swedia bahkan mengatakan wajib militer hanya memperparah kompetisi di dunia kerja. Dalam rentang dua tahun laki-laki muda menjadi“tidak produktif” dan ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri. Hal yang tentu jadi momok bagi banyak generasi muda Korea Selatan yang harus berhadapan dengan kompetisi di dunia kerja yang semakin ketat dengan angka pengangguran di Korea Selatan semakin tinggi.



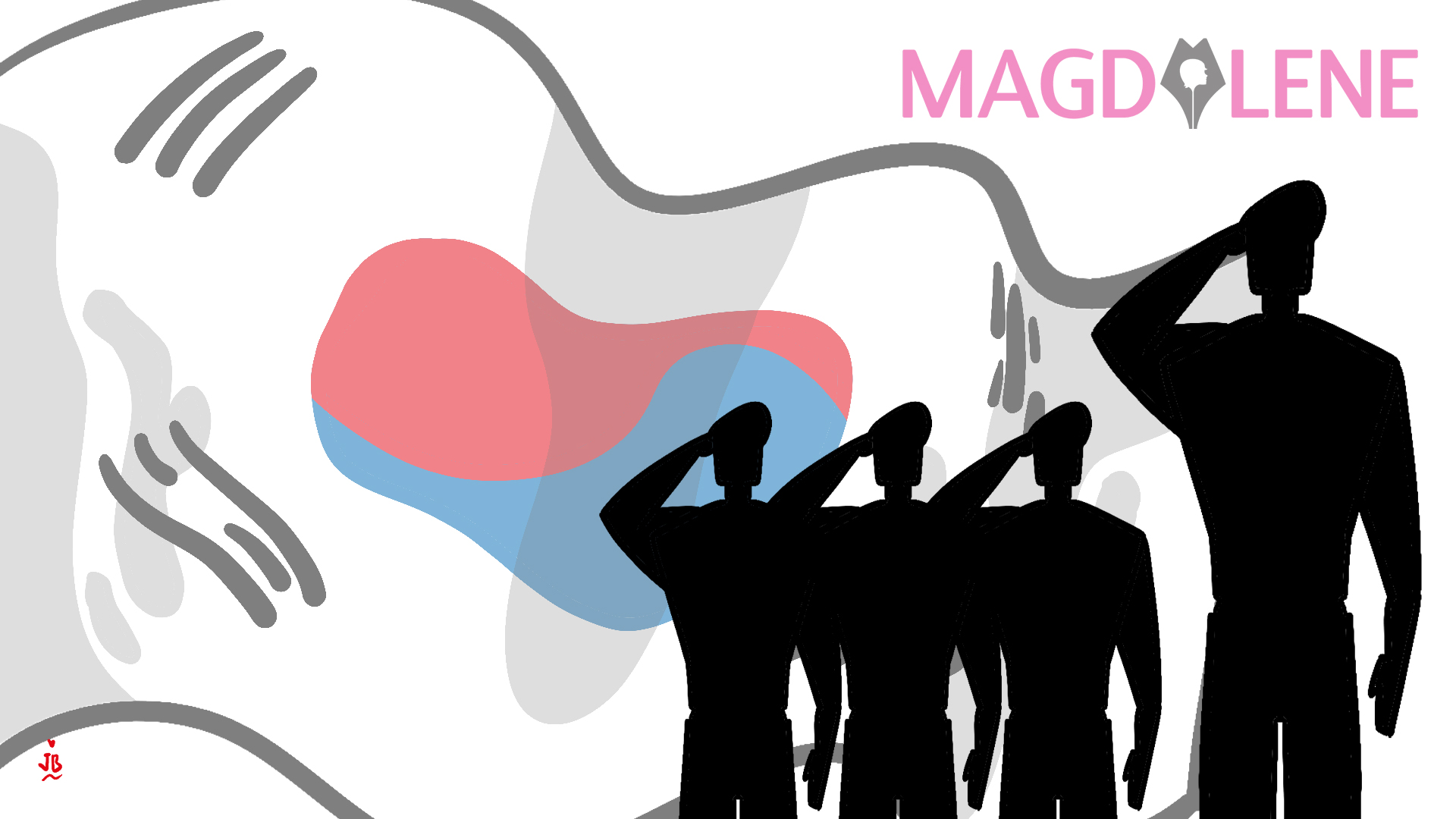




Comments