Organisasi Girl Up di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, yang berfokus pada advokasi kesetaraan gender dan perubahan sosial, pada 2020 bekerja sama dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari sejumlah fakultas di kampus tersebut untuk melakukan survei tentang kekerasan seksual.
Hasilnya, 223 responden dari total 616 responden mengatakan pernah menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di kampus. Sebanyak 452 responden juga mengaku pernah melihat atau mengetahui kasus kekerasan seksual terjadi.
Presiden Girl Up Unpad, Putri I. Shafarina mengatakan, angka tersebut sangat memprihatinkan, tapi banyak pihak yang abai soal ini dan belum ada mekanisme di dalam kampus untuk merespons situasi ini.
Baca juga: Perguruan Tinggi Didesak Punya Aturan Soal Kekerasan Seksual
“Akibatnya, 67,5 persen responden kami mengatakan merasa terancam dan tidak aman saat belajar di Unpad. Ini seharusnya jadi alarm yang besar banget untuk menyadarkan banyak pihak, terutama rektorat untuk fokus pada kasus kekerasan seksual di kampus,” ujar Putri dalam acara Campus Online Talkshow bertajuk “Gerak Bersama Civitas Academica: Lawan Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan Magdalene, bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia (26/2).
Awal 2021 ini, BEM Fakultas Psikologi dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, juga mengadakan survei bertajuk “Apakah Undip Sudah Aman Kekerasan Seksual?’ yang menjaring 286 responden. Hasilnya, 6,3 persen responden mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Ketua BEM Fakultas Psikologi Undip, Yanuarisca N. C. Pratiwi. mengatakan, angka ini sudah besar dan menunjukkan bahwa Undip tidak aman dari kekerasan seksual. Ditambah lagi, pada 2019 lalu ada satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan tenaga pendidik kepada mahasiswa Undip, tambahnya.
Menurut Yanuarisca, banyak korban yang belum bisa berbicara karena belum ada prosedur penanganan yang jelas dan maraknya budaya menyalahkan korban.
“Ada ketidaktahuan ke mana harus melapor bila dia menjadi korban. Jangankan untuk melapor, peraturan pun belum ada yang mengatur secara jelas,” ujarnya.
Relasi Kuasa Hambat Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus
Ketika mendampingi seorang perempuan dosen yang mengalami pelecehan seksual dari profesor di kampusnya, penulis dan aktivis perempuan Kalis Mardiasih menyaksikan sendiri bagaimana pihak kampus justru menyangkal korban karena khawatir akan nama baik kampus.
Setiap hari, dosen tersebut dikirimi pesan-pesan berbau seksual tanpa persetujuan. Namun ketika ia dan beberapa dosen lain akan mengangkat kasus tersebut, pihak kampus dan dosen-dosen lain justru menyangkal dan menganggap pengalaman mereka tidak valid karena berbagai hal.
Baca juga: Kontribusi Laki-laki Penting Agar Kampus Aman dari Kekerasan Seksual
“Kata dosen-dosen lain, ‘Masa sih, si Bapak itu begitu? Dia rajin ibadah loh.’ Penanganannya juga jadi berlapis karena kampus atau fakultas hanya memiliki dua profesor dan satu guru besar. Jadi, korban-korban disuruh diam aja, enggak usah ngapa-ngapain, karena nanti nyusahin fakultas,” kata Kalis.
Kalis mengatakan, hambatan utama penanganan kasus kekerasan seksual di kampus berpusat pada ketimpangan relasi kuasa antara korban dengan pelaku. Selain itu, ada banyak modus kekerasan seksual yang tidak dikenali sebagai kekerasan atau pemerkosaan.
Padahal, dari pengalamannya mendampingi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, hal itu justru berlangsung dengan cara-cara yang halus, tapi memaksa korban dan membuat tidak nyaman, ujar Kalis.
“Para pelaku, misalnya, memuji berkali-kali, ‘Saya ini udah nganggep kamu anak saya sendiri loh. Udah cantik, cerdas lagi.’ Mereka lalu ngajak berangkat ke kampus bareng, tau-tau udah ada di depan kos. Ada juga yang membuat fake account buat minta foto mahasiswanya saat tidak pakai kerudung. Itu digunakan untuk mengancam korban menuju kekerasan seksual yang levelnya meningkat,” kata Kalis.
“Itu sesuatu yang halus yang kita terima sebagai pujian. Kita tahu kita enggak merasa nyaman, tapi kita enggak mengerti cara melawannya bagaimana. Di sinilah manipulasi bekerja.”
Psikolog dari Yayasan Pulih, Nirmala Ika Kusumaningrum mengatakan, ada cara pandang masyarakat yang baru menganggap sebuah pelecehan itu serius apabila berbentuk kekerasan fisik, seperti pemerkosaan. Seolah-olah, dampak yang ditimbulkan dari kekerasan verbal atau gestur tidak sebesar dampak dari kekerasan fisik, ujarnya.
“Padahal, dampak psikologisnya enggak berhubungan (dengan bentuk kekerasan seksualnya apa). Ketika kita bicara pelecehan seksual, dampaknya kepada korban pasti besar. Kita tidak bisa mengecilkan dampak hanya karena bentuk kekerasan seksualnya,” kata Ika.
Ia mencontohkan hasil survei Girl Up dan BEM di Unpad yang menunjukkan sampai hampir 70 persen mahasiswa merasa tidak nyaman di kampus sendiri akibat situasi kekerasan seksual.
Baca juga: Cerita Agni Membantuku Menghadapi Trauma
“Ketika mahasiswa merasa tidak aman, itu akan mempengaruhi performa mereka. Ketika performa akademik turun, itu akan mempengaruhi nilai kampus itu sendiri. Dampaknya memang panjang. Enggak cuma person to person, tapi seluruh komunitas,” ujarnya.
Pentingnya SOP Kekerasan Seksual di Kampus
Wakil Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP Universitas Indonesia, Zeni Tri Lestari, mengatakan, kampusnya memang sudah memiliki regulasi mengenai kekerasan seksual. Tapi mekanismenya rumit dan lama, sehingga ada kekhawatiran para pelaku bisa terlanjur lolos, ujarnya.
“Akhirnya, kami membentuk tim khusus penanganan kekerasan seksual karena tidak mau menunggu respons dari petinggi kampus yang lama. Enam-delapan bulan pertama sudah ada puluhan laporan yang masuk,” kata Zeni.
Ketika mahasiswa merasa tidak aman, itu akan mempengaruhi performa mereka. Ketika performa akademik turun, itu akan mempengaruhi nilai kampus itu sendiri.
Dosen Kajian Gender dari Universitas Indonesia, Gabriella Devi, membenarkan adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku dalam banyak kasus kekerasan seksual menghambat penghapusan kasus kekerasan seksual di kampus.
"Ketika pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi, seperti dosen atau senior, itu menyulitkan korban untuk speak up karena ada intimidasi dari pelaku dan konsekuensi yang diterima kalau mereka melapor,” ujarnya.
"Di UI sendiri, dosen itu terpolarisasi ke dalam dua kubu. Kubu yang progresif dan mendukung isu ini dan kubu yang cenderung konservatif dan menganggap kasus ini tidak perlu dibuka lebar. Kami sudah punya SOP, tapi belum punya peraturan rektor,” ia menambahkan.
Ika dari Yayasan Pulih menyarankan adanya edukasi tentang kekerasan seksual kepada semua pihak di kampus. Bukan hanya korban, tapi juga kepada kalangan yang berpotensi menjadi pelaku, karena kekerasan seksual berdampak kepada semua pihak, termasuk terhadap kampus secara keseluruhan, ujarnya.
Ia juga menekankan, regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga penting untuk dibuat dengan melibatkan seluruh pihak kampus.
“Enggak bisa tim pencari faktanya dosen semua. Nanti enggak objektif kalau pelakunya dosen. Atau jangan juga hanya anak-anak BEM. Nanti enggak objektif kalau pelakunya anak BEM,” ujarnya.
Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia, Ratu Ommaya, menilai kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es di setiap kampus karena berbagai tekanan yang diberikan kampus dan masyarakat kepada korban.
“Korban jadi berpikir, belum tentu mereka mendapatkan keadilan dan keamanan setelah speak up tentang apa yang mereka alami. Inisiatif riset-riset seperti ini bisa mendorong kampus-kampus lain untuk membuat regulasinya masing-masing tentang kekerasan seksual,” katanya.
Dukung kampanye “Semua Peduli, Semua Terlindungi #TBSFightForSisterhood” untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dengan menandatangani petisi di sini.






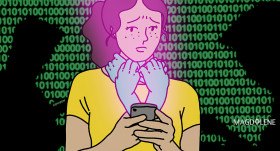
Comments