Perjuangan sepanjang 10 tahun itu tak berhasil mengesahkan amendemen tersebut. Tak lama setelah aku lahir , Amandemen Kesetaraan Hak dikuburk. Meskipun tinggi badanku jauh melebihi ibuku yang hanya 154 centimeter, di usia 12 tahun aku melihat ibuku sebagai raksasa tak terkalahkan dan tak kenal lelah memperjuangkan perempuan, mereka yang miskin, sakit mental, kehilangan anak, dan semua orang yang putus asa dan tertindas. Ibu menyebut dirinya seorang feminis, maka akupun dengan bangga mengenakan lencana itu, melawan segala ketidakadilan.
Suatu hari di sekolah pada jam istirahat, dengan gelang ERA melingkari pergelangan tangan, aku mendekati sekelompok siswa yang dianggap keren – anak-anak cowok dengan rambut panjang berantakan dan anak-anak cewek dengan eyeliner hitam tebal. Mereka berdiri melingkar di tengah lapangan. Beberapa anak laki-laki sedang bermain bola pasir hacky sack di tengah lingkaran. Satu dari mereka meninggalkan lingkaran itu dan duduk di sampingku dengan wajah berkeringat dan memerah. Ia melihat pergelangan tanganku dan bertanya apa kepanjangan ERA. Aku menjelaskan dengan semangat, tetapi kemudian ia tertawa terbahak-bahak dan bertanya apakah aku lesbian atau semacamnya.
Aku tak ingat bagaimana aku merespon anak itu, sebab yang teringat hanya rasa malu yang menenggelamkanku karena lagi-lagi aku menjadi target olokan di lapangan sekolah, dan rasa takut apabila anak itu tahu memang banyak anggota keluargaku dan kerabat kami yang gay dan lesbian. Itu tahun 1992, dan kebanyakan orang Amerika masih tak punya toleransi terhadap orientasi seksual yang mereka anggap sebagai pilihan gaya hidup.
Aku tak pernah memakai gelang itu lagi, dan kata “feminis” tak pernah terucap dari mulutku hingga dua dekade ke depan. Gerakan Riot Grrrl datang dan pergi, dan meskipun aku menggemari musik mereka dan mengikuti etos punk dari band-band seperti Bikini Kill dan Sleater-Kinney, aku menutup mataku terhadap feminisme gelombang ketiga yang mereka usung. Aku berduka ketika Kurt Cobain meninggal, tapi tak pernah tahu bahwa Cobain seorang feminis.
Ketika aku mulai kuliah, aku mencibir pada gagasan bahwa perempuan Amerika berkulit putih dan berpendidikan tinggi masih punya kekhawatiran-kekhawatiran di dunia yang nampaknya memberikan kami berbagai keistimewaan yang memang sepatutnya kami dapatkan. Feminisme, kutegaskan, adalah sebuah kemewahan milik perempuan yang mampu kuliah, yang tak pernah diperlakukan buruk atau dituduh tanpa alasan hanya karena warna kulitnya, dan tak pernah kelaparan.
Tahun lalu, 16,000 kilometer dari tempatku dibesarkan, dan setelah meraih dua gelar pendidikan, kutemukan diriku dalam situasi putus asa dan tertindas. Lima tahun sebelumnya, aku datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian doktoral tentang musik rock lokal, dan aku menetap di sini untuk bekerja.
Aku jatuh cinta dengan seorang seniman yang sangat bergairah pada seninya. Ia juga bergelut dalam dunia seni dan musik yang kutekuni untuk riset akademisku dan kehidupan profesionalku. Aku bertahan dua tahun dengan laki-laki ini, yang kesetiaannya lama-lama menjadi sifat posesif, dan penganiayaan fisiknya terhadapku kadang terasa seperti angin segar setelah teror psikologis yang dilemparkannya padaku setiap hari dan setiap jam.
Rasa takutku padanya kadang hanya sedikit lebih berat di hatiku dibanding rasa takutku bila ada orang lain yang tahu tentang apa yang kualami. Apakah ini akan merusak reputasi profesionalku? Apakah teman-teman dekatku akan menganggapku pembohong? Apakah orang-orang yang sepikiran denganku akan mempertanyakan kenapa aku begitu naif dan menyalahkanku karena tidak meninggalkan dia? Sepertinya sederhana bagi seseorang yang tak terikat secara legal dan punya kemandirian finansial untuk meninggalkan sebuah hubungan. Kita tak menikah. Tak punya anak. Aku sebenarnya tak punya alasan.
Tapi aku tetap bersama dia. Batas waktu untuk menyerahkan disertasiku dan meraih gelar PhD-ku akan berakhir di akhir tahun. Tapi aku tak sanggup menenggelamkan suara laki-laki itu dari kepalaku dan kritikan-kritikan dari diriku sendiri, sehingga aku tak mampu menulis satu kalimatpun, apalagi satu paragraf.
Aku tak ingat semua fragmen-fragmen momen yang pada akhirnya membukakan jalan bagiku untuk membebaskan diri dari hubungan itu. Dosenku memberikan saran-saran yang sangat mendukung untuk risetku. Atasanku memberikanku waktu cuti untuk fokus pada disertasiku. Sebuah hotline di Amerika untuk korban kekerasan menjadi penyelamatku di masa-masa tergelap. Dan selalu ada musik. Lagu wajibku tahun itu adalah “Shake It Out” dari Florence and the Machine.
And it’s hard to dance with a devil on your back
So shake him off
Ketika akhir tahun tiba, aku berhasil menyelesaikan disertasiku dan menyeberang samudera untuk sidang di hadapan dosen dan rekan-rekanku. Aku telah mengenyahkan sang iblis dari punggungku. Tapi aku belum terbebas. Pengkondisian sosial membutakan aku hingga hak perempuan terlihat tak seberapa penting di mataku dibanding persoalan-persoalan lain. Membuatku mati rasa terhadap kekerasan-kekerasan kecil sehari-hari hingga aku tak mampu mengenali bahwa ada seorang pelaku kekerasan di ranjangku sendiri yang masih mencengkram pergelangan kakiku.
Indonesia menjadikan aku seorang feminis karena negara ini menjadi latar perjuanganku yang paling berat sebagai perempuan, dan kemenangan pribadiku yang paling besar melawan kekerasan.
Aku terkejut dengan kelalaianku sendiri. Mengapa aku bisa berasumsi bahwa kurangnya perempuan dalam skena musik adalah karena faktor ketidaktertarikan dan bukan karena mereka tidak dilibatkan? Mengapa aku tidak mendengar humor-humor seksis yang dilontarkan di panggung, atau merasa risih dengan eksploitasi seksual terhadap perempuan di poster-poster acara musik, video, maupun unggahan di media sosial?
Bulan April. Aku duduk bersama Kartika Jahja, seorang musisi yang dikenal, aktivis kekerasan terhadap perempuan, dan juga teman lama. Kami bersemangat merencanakan kampanye yang menyasar kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melalui medium yang paling kami pahami: musik dan seni.
Kami menyadari bahwa kami membawa sejarah personal masing-masing ke dalam upaya ini. Kami juga membawa bakat kami dalam musik dan kritik sosial ke dalam pekerjaan penting ini. Kami setuju bahwa Indonesia membutuhkan perubahan paradigma soal perempuan. Pengarusutamaan gender hanya akan menjadi mimpi tak sampai di sebuah negara di mana kebanyakan perempuan – dan setiap orang gay, lesbian, biseksual, dan transgender- tak mendapatkan hak asasi manusia di level adat istiadat maupun hukum.
Kami prihatin dengan banyaknya advokasi yang menyoroti akibat dari persoalan – pelecehan di jalanan, ketimpangan upah, kekerasan dalam rumah tangga – tanpa menggali penyebabnya. Dan kami ingin menyasar faktor penyebab; yaitu pengkondisian sosial yang selama ini hanya menempatkan laki-laki heteroseksual sebagai penentu moralitas, kebijakan hukum, dan ekonomi untuk “yang lainnya”. Maka kami mengumpulkan seluruh kekuatan yang kami punya, semua kemampuan profesional kami, dan menggalang komunitas pendukung – perempuan dan laki-laki – untuk menyuarakan kesetaraan melalui warisan terbaik dalam sejarah kemanusiaan: lagu, lukisan, dan puisi. Lahirlah Bersama Project
Inilah cerita bagaimana Indonesia menjadikanku seorang feminis. Bukan karena aku pertama kali melihat kekerasan berbasis gender di Indonesia. Pelecehan, ketimpangan upah, dan kekerasan dalam rumah tangga di negara asalku pun tak lebih baik. Bukan karena Indonesia satu-satunya negara yang melanggengkan hiper-maskulinitas dalam industri hiburan yang tidak memandang perempuan sebagai mitra kreatif yang setara – atau melihat perempuan hanya sebagai penghias yang cantik atau objek seksual. Itu juga terjadi di Amerika Serikat, dan tentanya dalam industri musik pop arus utama yang punya pengaruh besar bagi banyak artis, promotor, dan label rekaman di Indonesia. Tidak, aku tidak tertarik membanding-bandingkan satu negara dengan yang lainnya.
Indonesia menjadikan aku seorang feminis karena negara ini menjadi latar perjuanganku yang paling berat sebagai perempuan, dan kemenangan pribadiku yang paling besar melawan kekerasan. Di Indonesia aku merebut kembali kebebasanku dari kontrol seorang laki-laki. Aku menegaskan suaraku sebagai seorang pemimpin di bidang yang kutekuni. Aku mengaplikasikan bakatku untuk memastikan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di masa mendatang semakin berkurang.
Aku menuliskan ceritaku sekarang untuk mengambil langkah menuju kebebasan: untuk melepaskan rasa takut. Rasa takut disalahkan. Rasa takut terhadap orang-orang yang mempertanyakan kenapa aku tak cukup kuat untuk melawan atau meninggalkan dia lebih cepat. Rasa takut terhadap masa lalu yang membayangi potensi-potensiku.
Meskipun idealnya perempuan tak perlu menanggung kewajiban untuk melawan pasangan yang menyiksanya, norma-norma budaya, pengkondisian sosial, atau undang-undang yang tak menggubris kesetaraan gender, namun hanya dengan bersuara, satu demi satu, kita bisa membangun kesadaran kolektif. Dengan membagi kisah kita, kita dapat memberi harapan kepada orang lain yang sedang berjuang menuju kebebasannya.
Indonesia menjadikanku seorang feminis karena ia megantar aku kembali kepada ibuku, yang pertama kali menanamkan kepadaku keyakinan bahwa perempuan layak mendapatkan hak-hak yang setara. Meskipun ia tak dapat menyelamatkan dunia dari semua kepicikan yang ada di dalamnya, ia telah menurunkan darah seorang pejuang kepadaku, dan hati seorang aktivis. Dan hari ini, ia adalah ibu dari seorang feminis.
Rebekah E. Moore adalah seorang etnomusikolog yang lahir di Amerika Serikat. Ia adalah pendiri Bersama Project, sebuah yayasan yang mendukung kesetaraan gender dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan melalui musik dan seni.



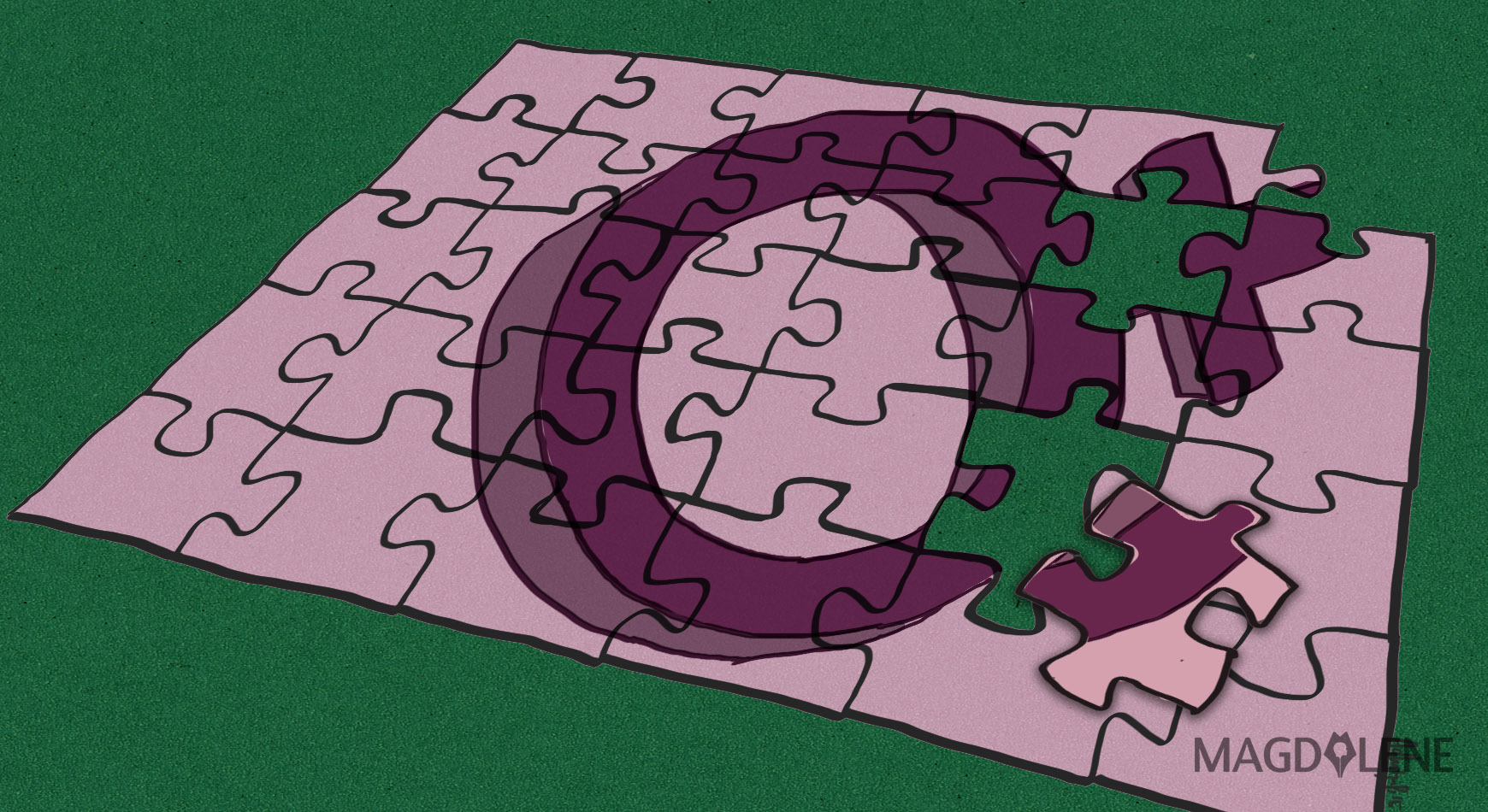




Comments