Sebagai seorang akademisi maupun pelajar sering kali kita melakukan penelitian di Indonesia dengan metode-metode yang diadaptasi dari para pembuat teori yang berasal dari orang-orang kulit putih seperti Eropa maupun Amerika. Tapi apakah pernah kita mempertanyakan hal-hal mendasar tentang untuk siapa ilmu pengetahuan itu dibuat? Mengapa kita harus mengadaptasi metode-metode yang dibuat oleh orang-orang yang dulunya melakukan koloni terhadap kita? Padahal jelas-jelas kita punya sejarah, latar belakang dan privilese yang berbeda dengan mereka, apakah mungkin ada ketimpangan kuasa dalam ilmu pengetahuan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan dasar dari lahirnya teori dekolonial yang awalnya diinisiasi oleh para pemikir di Amerika Latin. Mereka mengkritik tentang struktur kuasa dalam sistem dan produksi ilmu pengetahuan yang didominasi oleh orang-orang kulit putih. Dominasi tersebut secara tidak sadar sudah mengkolonisasi kita. Dekolonialisme mengajak para akademisi untuk berpikir, meneliti, dan menulis bukan lagi dari kacamata negara-negara kolonial tersebut.
Hal tersebut menjadi topik pembahasan webinar Isyarat Feminisme Dekolonial, yang diadakan pada 25 Juli lalu oleh Cipta Media Ekspresi, sebuah lembaga yang memberikan hibah untuk perempuan pelaku kebudayaan di segala bidang seni.
Penulis Intan Paramaditha mengatakan, kritik dekolonialisme juga berlaku untuk melihat spektrum feminisme yang sering diasumsikan sebagai paham yang berasal dari gerakan perempuan liberal di Barat. Wacana dominan orang-orang kulit putih akan feminisme itu telah lama dikritik feminis kulit hitam, gerakan feminis di Amerika Latin dan feminis dunia ketiga seperti Indonesia, ujarnya. Melalui feminisme dekolonial ini, jawaban dari banyak pernyataan kelompok kontra-feminisme karena dianggap produk Barat bisa terjawab, ia menambahkan.
“Argumennya adalah, struktur dominasi yang dialami oleh perempuan tidak sama. Secara umum proyek feminisme dan dekolonialisasi menggaris bawahi hubungan antara seksisme, rasisme, kapitalisme global dan kolonialisme sebagai entitas-entitas yang berkelindan, berlanjut dan belum terselesaikan,” ujar Intan, yang juga merupakan dosen di Department of Media, Music, Communication and Cultural Studies di Macquarie University, Sydney.
“Sebagian negara jajahan sudah merdeka tapi imbas dari kolonialisme sampai sekarang masih ada. Nah, bisa enggak kita membongkar feminisme di Indonesia tanpa spektrum kolonial. Feminisme dekolonial pada dasarnya mengajukan kritik itu,” tambahnya.
Baca juga: Apa yang Perlu Diketahui tentang Dasar-Dasar Feminisme
Meski feminisme dekolonial ini masih awam terdengar di Indonesia, namun menurut Intan, isyarat atau ciri kemungkinan penelitian feminisme dekolonial ini terjadi, dan secara perlahan sudah mulai tampak dilakukan oleh beberapa peneliti. Walaupun mereka tidak mengklaim penelitiannya sebagai produk feminisme dekolonial, namun substansi yang mereka hadirkan cukup menggambarkan bahwa penelitian semacam itu sangat mungkin dilakukan di Indonesia, ujarnya.
Antropolog Rhidian Yasminta Wasaraka misalnya, ia tidak lagi menggunakan kacamata kolonial ketika meneliti tentang masyarakat suku Korowai, Papua, yang sempat “booming” menyusul peliputan oleh tim National Geographic beberapa tahun silam.
“Sesudah meliput ke sana, mereka menulis bahwa orang-orang Korowai adalah manusia terbelakang, kanibal dan bermimpi makan nasi. Mereka datang untuk meliput ke Korowai sudah dibarengi dengan persepsi sendiri (kacamata kolonial). Tapi mereka enggak tahu kalau suku Korowai ini bagi saya yang telah enam bulan tinggal di sana adalah orang-orang yang paling menjunjung kesetaraan. Tidak hanya dengan perempuan, tapi juga dengan alam,” kata Rhidian dalam webinar yang sama.
Menurut Rhidian, relasi kuasa, prasangka dan wacana dominan yang berkembang di luar merusak kebudayaan asli dan struktur sosial-politik masyarakat Korowai yang bersifat demokratis dan tidak mendiskriminasi atau merendahkan posisi dan peran perempuan.
“Jangan salah, perempuan Korowai itu sangat berdaya, mereka bisa minta cerai atau memilih tidak punya anak. Laki-laki di sana enggak malu untuk memasak dan menjaga anak ketika ibunya sedang ada pekerjaan. Semuanya kembali ke alam, enggak ada peran-peran gender sebagaimana aturan normatif orang-orang Indonesia di daerah lain,” ujar Rhidian.
Dampak dari terjadinya “pemiskinan” dari luar karena menyamakan standar kehidupan orang “modern” kepada masyarakat Korowai justru melemahkan dan menghilangkan posisi serta nilai perempuan Korowai di lingkungan masyarakatnya sendiri, ujarnya. Hal ini menyebabkan kemunduran dari masyarakat yang egaliter dan demokratis menjadi hierarkis, Rhidian menambahkan.
Baca juga: Feminisme Interseksional Setelah Perjuangan Kemerdekaan
“Kesetaraan yang orang-orang sering suarakan malah sudah terjadi di Korowai. Salah satu mamak di sana saat saya tanya, mereka bilang kalau bikin anak itu kan berdua, jadinya tanggung jawab bersama-sama. Tapi hal itu enggak akan dilihat kalau sudah ada tuduhan terlebih dahulu mereka hidup terbelakang,” ujar Rhidian.
Dengarkan cerita-cerita perempuan
Akademisi Argentina, María Lugones, mengatakan feminisme harus melawan kolonialitas, tidak hanya terkait dengan warisan sejarah kolonialisme, tapi juga dampak relasi kuasa dalam skala dunia, di mana kolonialisme, kapitalisme, dan globalisasi barat tidak terpisahkan dalam proyek modernitas. Feminisme dekolonial mengkritik false universalism, menantang sistem biner, dan berpihak pada penciptaan agenda lokal.
Pendekatan ini dilakukan oleh penulis dan aktivis Martha Hebi, saat meneliti tentang peran perempuan di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Martha menggunakan pendekatan berbasis aset dengan jalan menelusuri praktik perempuan berpengaruh di Sumba, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ia tidak mau membatasi diri dengan hanya berpaku pada metode-metode yang sudah ada, karena baginya yang terpenting adalah mendengarkan cerita perempuan Sumba secara utuh. Ada sekitar 15 tokoh perempuan Sumba yang ia angkat dengan pendekatan pengalaman.
“Hasil temuan saya adalah gerakan perempuan di Sumba masih terhadang oleh berbagai isu, antara lain dominasi patriarki, feodalisme, stigma terhadap perempuan disabilitas, dan stigma yang juga berhubungan dengan tragedi 1965. Padahal di Sumba pendeta perempuan sudah ada sejak 1980-an. Di tahun tersebut gereja Kristen hadir sebagai lembaga pemicu perubahan,” ujar Martha.
Di Sumba, perlawanan terhadap budaya-budaya yang melemahkan posisi perempuan seperti kawin tangkap, aturan untuk menikahi saudaranya ketika menjadi janda, ataupun perjuangan mempertahankan agama asli Sumba, yaitu Merapu, patut dilihat sebagai sebuah bentuk feminisme lokal.
“Bentuk feminisme di Sumba sangat beragam, tiap-tiap daerah menawarkan struktur sosial yang berlapis. Urusan kekerabatan karena perkawinan, dan kekerabatan lain masih belum tuntas dibahas. Di Sumba ada juga garis matrilineal yang masih jarang diangkat sebagai salah satu bagian dari sistem kekerabatan yang ada di Sumba. Penting mendengarkan suara perempuan sebagai bagian dai sejarah,” ujar Martha.
Baca juga: Ekofeminisme: Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
Lain halnya dengan penulis Erni Aladjai, yang meneliti tentang budaya Bakalesang Lapu Mongsung pada suku Banggai, Sulawesi Tengah. Bakalesang Lapu Mongsung sendiri merupakan sebuah cara masyarakat suku Banggai merawat tubuh perempuan setelah melahirkan dengan obat-obatan tradisional dari tanaman.
“Bakalesang yang masih dilestarikan oleh ibu-ibu di Sulawesi Tengah sering ditertawakan oleh orang-orang yang pergi ke kota dan sekolah medis. Padahal jika dilihat, Bakalesang ini justru adalah proses saling dukung antar perempuan dan alam. Mereka menciptakan ruang untuk perempuan setelah bersalin dengan merawat menggunakan bahan-bahan alami,” ujar Erni.
Sikap-sikap dari mereka yang sudah belajar medis di kota kemudian mengolok-olok pengetahuan tradisional suku Banggai malah bisa memarginalisasi pengetahuan perempuan itu sendiri. Dalam jurnal-jurnal ilmiah yang dibuat oleh peneliti kesimpulan yang selalu disampaikan adalah bahwa obat-obatan tersebut belum diuji secara klinis.
“Sikap seperti itu meminggirkan pengetahuan yang sudah ada. Padahal bisa jadi pengobatan yang mereka lakukan merupakan hasil dari percobaan yang tidak terhitung. Sehingga terbukti efektif dan tanpa bahan kimia yang berbahaya,” ujar Erni
Meski sering disepelekan anak-anak muda, Erni percaya bahwa praktik seperti itu merupakan bentuk perjuangan perempuan untuk memberdayakan diri setelah proses persalinan yang menyakitkan. Dengan melakukan dan menciptakan obat sendiri alih-alih bergantung pada obat-obatan modern yang selama ini selalu dianggap lebih manjur membuktikan jika spektrum feminisme bisa dilihat tanpa menggunakan sudut pandang kolonial dengan modernitasnya.




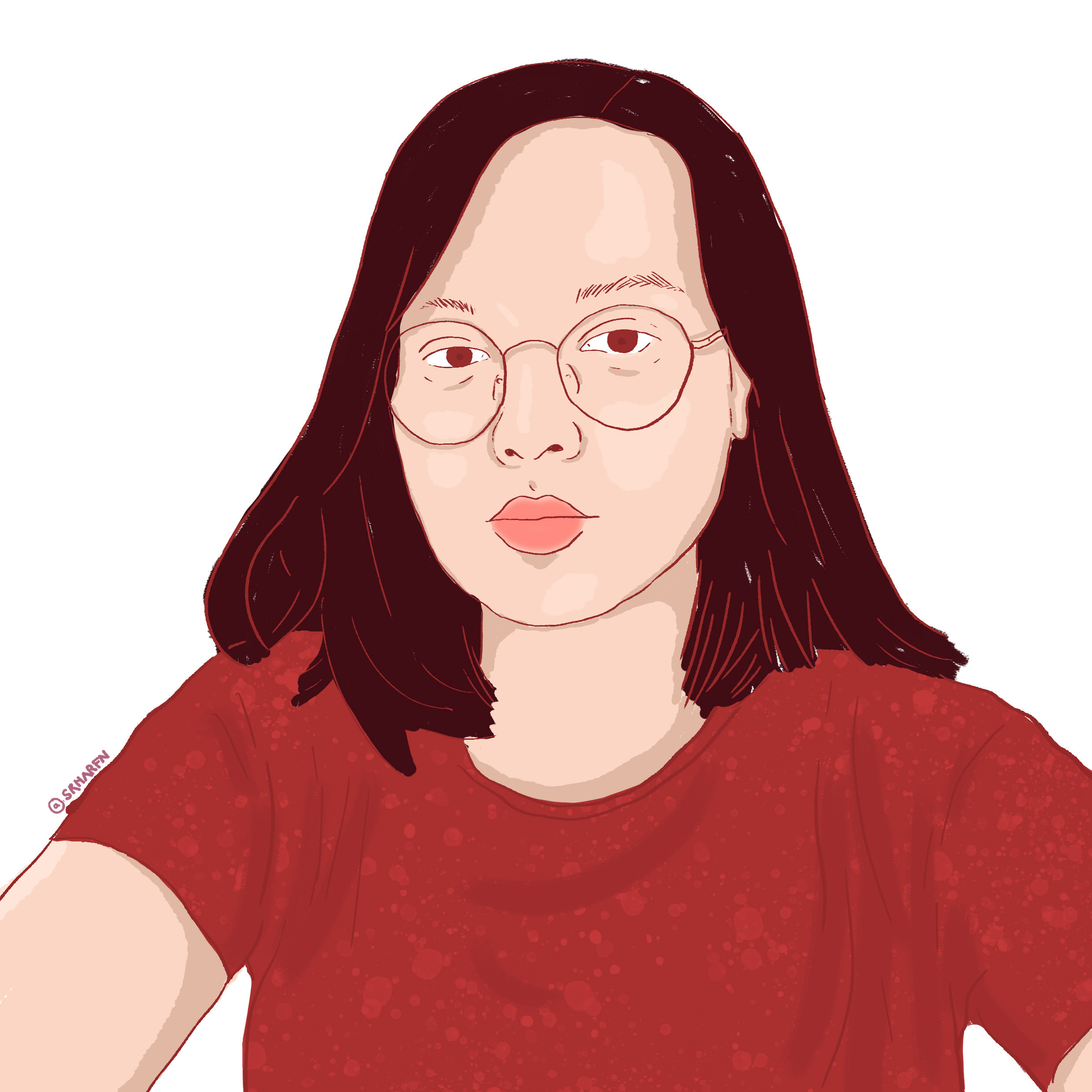



Comments