Salah satu trending topic di Twitter saat ini adalah nama seorang laki-laki, Gilang. Perbincangan ramai warganet diinisiasi oleh Fikri, pemilik akun Twitter @m_fikris yang menceritakan kronologi pelecehan seksual yang diterimanya dari Gilang.
Awalnya, pada tahun lalu, ketika Fikri masih menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di Surabaya, ia diajak berkenalan oleh Gilang (yang berkuliah di universitas negeri lain di kota yang sama) via media sosial dan komunikasi mereka berlanjut melalui WhatsApp. Gilang memperkenalkan diri sebagai mahasiswa angkatan 2015 yang sedang membuat riset dan mengajak Fikri untuk menjadi salah satu subjek risetnya.
Tidak seperti riset pada umumnya, Gilang meminta Fikri untuk membungkus seluruh tubuhnya dengan kain dan mengikatnya dengan lakban sehingga ia tidak bisa bergerak leluasa. Alasannya, dengan melakukan hal tersebut, diri seseorang yang sesungguhnya bisa terlihat, begitu juga dengan luapan-luapan emosinya.
Meskipun mulanya merasa takut karena diminta untuk melakukan hal yang menurutnya aneh, Fikri masih mengikuti instruksi Gilang. Ia merasa kasihan karena Gilang yang sudah duduk di semester 10 kuliahnya memohon-mohon Fikri untuk menjadi subjek risetnya, dan juga rasa tidak enak mengingat Gilang adalah seniornya.
Fikri meminta bantuan salah satu temannya untuk melakukan instruksi Gilang keesokan harinya. Setelah berjam-jam melakukan hal tersebut, Fikri mendapati perlakuan aneh dari Gilang berupa ucapan menggoda (“Sini peluk”), dengan ditambah “Canda, dek”. Tidak hanya itu, Gilang juga meminta teman Fikri yang membantu dia untuk juga membungkus diri.
Kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi setelah itu. Mulai dari ujaran menggoda lain, sikap memaksa dan mengancam Gilang terhadap Fikri bila ia tidak mau lanjut melakukan instruksinya (termasuk ancaman bunuh diri), menangis-nangis terus memohon Fikri membungkus diri, tuntutan untuk minta maaf, hingga Instastory Gilang yang menyatakan bahwa laki-laki itu sedang dalam kondisi parah sekali dan memohon doa untuknya (seolah bukan Gilang yang membuat story tersebut).
Baca juga: Survei: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Pindah ke Dunia Maya di Tengah Pandemi
Setelah kasus ini viral di media sosial, satu per satu orang yang mengenal Gilang dan sempat diminta membungkus diri atas nama riset mulai angkat suara. Ada juga yang menyertakan tangkapan layar berisi ucapan Gilang yang menggoda dan merasa jijik terhadapnya. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan merupakan mahasiswa baru atau di bawah tingkat kuliah Gilang.
Konsensus dilupakan
Kasus ini lagi-lagi mencerminkan betapa jamaknya pelecehan seksual, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga laki-laki. Yang saya soroti dari kasus Fikri adalah bahwa pelaku menggunakan statusnya sebagai mahasiswa senior, terlebih dari universitas ternama, untuk melakukan tindakan manipulatif. Ada (calon) korban yang memang telah curiga pada pelaku sehingga tidak melanjutkan komunikasi atau memenuhi permintaannya. Tetapi bagi sebagian lainnya, status Gilang tersebut bisa menimbulkan rasa enggan untuk menolak, apalagi diembel-embeli kata riset.
Hal lain yang saya perhatikan adalah dalam melakukan penelitian, siapa pun sudah sepatutnya bersikap fair dan menghormati subjek penelitian sepanjang proses berlangsung. Idealnya, penelitian menyertakan lampiran surat persetujuan (consent form) yang ditandatangani subjek.
Ketika ada hal yang tidak berkenan, tidak ada satu orang pun, baik dalam konteks riset maupun bukan, yang berhak untuk memaksa dan mengancam. Adalah hal ironis saat ada kejadian di mana subjek yang justru diperlukan partisipasinya dalam penelitian, malah menjadi korban dan diekori perasaan terintimidasi oleh peneliti. Bukankan ini tidak zaman lagi orang diteliti secara paksa?
Masalah konsensus mengemuka lagi di sini. Tapi akan sulit berbicara tentang konsensus apabila korban terlebih dahulu dimanipulasi oleh pelaku. Dalam kasus Fikri misalnya, ia sejak pertama tidak menduga akan menjadi korban pelecehan seksual sampai akhirnya ia mengetahui ada satu jenis fetish seksual yang melibatkan pembungkusan tubuh seseorang. Contoh macam Fikri ini banyak terjadi, entah pada laki-laki maupun perempuan, yang dulu pernah mengalami tindak pelecehan tetapi masih awam tentang hal itu sehingga baru menyadarinya ketika dewasa, atau setelah membaca informasi soal pelecehan seksual.
Baca juga: Pelecehan Seksual Dianggap Normal, Kecuali Dilakukan oleh Pria Gay
Di luar kasus ini, saya pernah mendengar ada modus pelecehan seksual meminta foto korban, padahal saat itu konteksnya korban ingin mengikuti suatu kursus bahasa. Lalu sebelum itu saya juga sering mendengar bagaimana sebagian teman laki-laki saya sering bercanda dengan melibatkan sentuhan, genggaman, atau gesekan ke selangkangan teman laki-lakinya yang lain saat kecil.
Itu semua saya rasa jamak, tapi masih segelintir saja yang menganggapnya pelecehan dan hal serius untuk disikapi tegas. Toh cuma bercanda, toh masih anak-anak, begitu barangkali pemikiran yang muncul di kepala mereka. Tapi kita tidak pernah tahu bukan, sejauh mana dampak yang dirasakan orang yang pernah dilecehkan itu sampai dewasa? Semakin kita melumrahkan candaan seksual, semakin mungkin anak-anak kecil bertumbuh tanpa mengetahui ada yang salah dari satu tindakan dan kemudian mewajarkan tindakan itu.
Jangan langsung dibawa ke orientasi seksual
Berikutnya dari kasus Fikri, saya mengapresiasi ketika dia mengatakan bahwa Gilang mengaku sebagai seorang biseksual dan Fikri tidak menghakimi hal itu. Dengan jelas ia menyatakan bahwa yang tidak disukainya adalah perilaku Gilang.
Kerap kali orang menempelkan orientasi seksual seseorang dengan perilakunya sehingga stigma terhadap kelompok tertentu seperti gay, transgender, atau lesbian misalnya, tumbuh subur. Padahal, perilaku melecehkan bisa ditemukan dalam diri siapa saja terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya. Penyampaian Fikri bisa menjadi pengingat untuk orang-orang mengerem penghakimannya terhadap seorang pelaku pelecehan seksual, memisahkan antara yang ada di tataran kepala dan perasaan (orientasi) dan tindakan atau perilaku yang kasat mata dari Gilang.
Selanjutnya yang saya amati adalah soal pembeberan fakta mengenai pelaku. Mungkin ada sebagian yang tidak sepakat dengan saya mengenai ini. Shaming atau doxxing pelaku di media sosial merupakan cara pemecahan masalah dengan masalah. Iya, di satu sisi thread viral di media sosial menjadi alat ampuh untuk memberi kesadaran akan tindak pelecehan seksual, termasuk yang tak lazim seperti Fikri alami. Melalui hal ini pulalah solidaritas sesama korban bisa terbentuk.
Baca juga: 2 Sisi Mata Pisau: ‘Penis Shaming’ Sebagai Balasan Kiriman ‘Dick Pic’
Selain itu, kita pun bisa memberi sanksi sosial atas perbuatan pelaku, bahkan mendorong munculnya sikap tegas institusi (dalam hal ini universitas tempat Gilang berkuliah) atau bahkan bisa sampai proses di jalur hukum. Ini sisi bagusnya.
Namun, omong-omong soal hukum, kita tahu di Indonesia ada aturan soal pencemaran nama baik yang justru bisa menjerat korban yang speak up. Di salah satu pernyataan Fikri sendiri, tersirat kekhawatiran bahwa dia akan “kenapa-kenapa” setelah membuat thread di Twitter soal fetish bungkus jarik. Ini tentu saja beralasan: Beberapa orang justru dilaporkan oleh si pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik.
Ingat kasus Deddy Susanto? Ancaman ingin memolisikan pelapor sempat dilakukan juga oleh Deddy setelah diberitakan melecehkan banyak perempuan dengan kedok memberi terapi psikologi. Ingat kasus Lalu, belum lupa dengan kasus Baiq Nuril, kan? Sekalipun ia yang jadi korban dan mestinya berhak menghirup udara bebas, ia yang malah dipidana dan menempuh proses panjang untuk menegakkan keadilan baginya. Ongkos yang besar toh?
Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi dan punya kekuatan sebesar apa untuk balik menyerang kita dengan hukum. Akan lebih strategis saya rasa kalau kasus semacam ini tidak hanya diramaikan di media sosial, tetapi juga diurus segera ke lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan seksual atau lembaga bantuan hukum agar kita dapat memilih langkah yang lebih efektif.



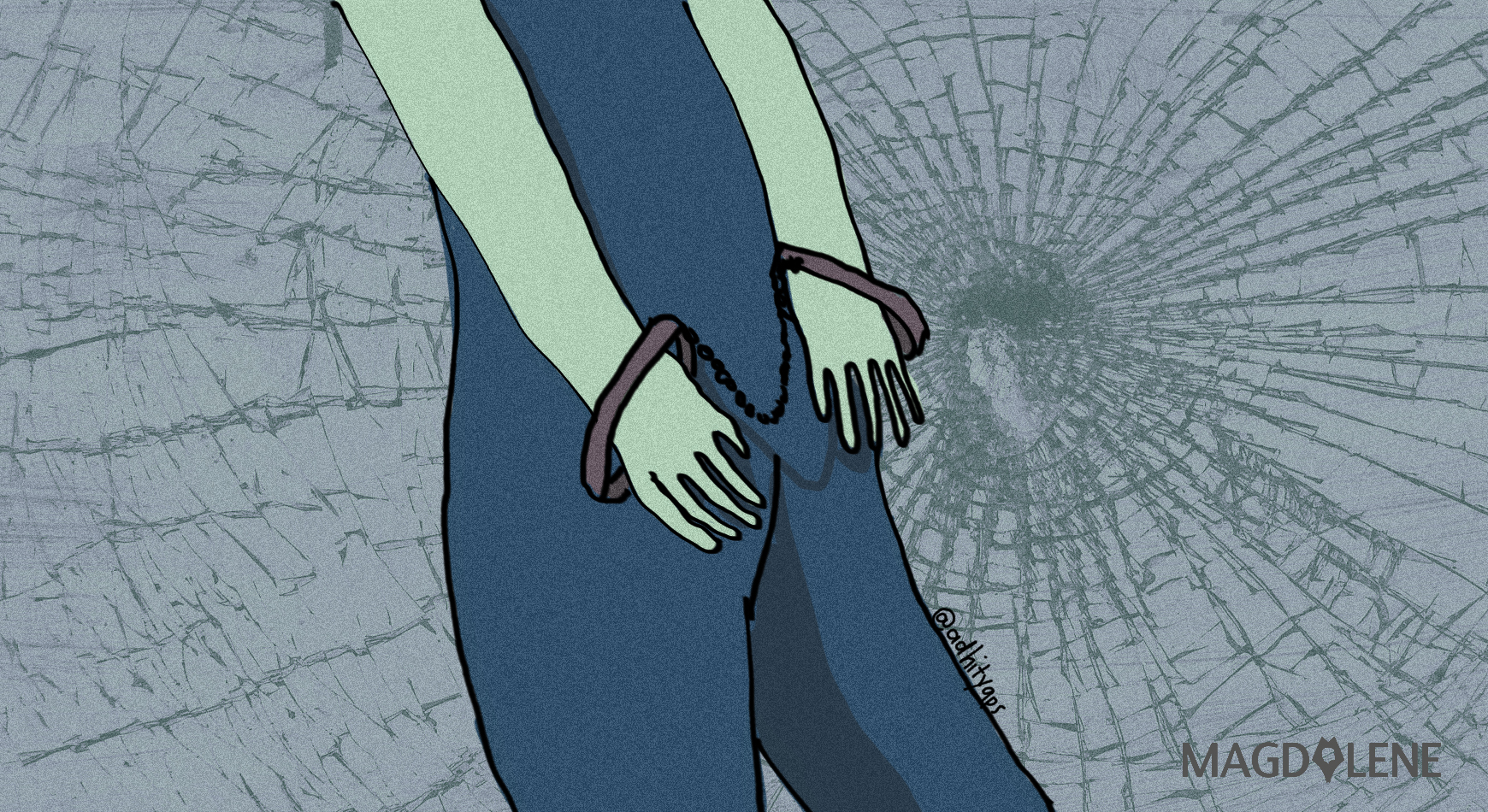




Comments