Susah emang ngomong sama SJW!
Ya gak heran bacaannya baru segitu.
Cek privilege lu sebelum berargumen.
Dasar feminis kafir/liberal/boomers/kiri/kanan...dst.
Jika sedang banyak waktu luang, terkadang saya suka iseng mengikuti perdebatan di jagat dunia maya, dan kalimat-kalimat semacam di atas sering berseliweran di lini masa. Kalau mau dipukul rata, gaya warganet dalam berdebat di media sosial bisa dikategorikan sebagai berikut:
- Tipe yang sekuat tenaga menampilkan data dan interpretasinya;
- Tipe yang penting “ngegas” dulu baru sadar atau paham konteks;
- Tipe yang ingin sekadar julid;
- Tipe ad hominem: “Perempuan kafir!” “Ngaco!” “Kurang piknik!”;
- Tipe yang merasa dirinya paling benar, dan tidak akan berhenti walaupun sadar argumennya salah, yang penting jatuhkan orang lain saja alias toxic people alert!
Dalam tulisannya di The Conversation, Collette Snowden, dosen Ilmu Komunikasi di University of South Australia mengatakan, media sosial merupakan medium yang baik karena kedekatan, jangkauan, dan intensitas, serta kemampuannya menyingkirkan keterbatasan waktu antara penyampaian infomasi dengan kejadian di lapangan. Namun di sisi lain, media sosial kurang kondusif dalam hal menyampaikan intonasi, nuansa, konteks dan kebenaran, sehingga tidak heran jika banyak orang yang berdebat tanpa argumen yang jelas.
Margianta Surahman, salah satu pendiri Emancipate Indonesia, organisasi pemuda yang berfokus pada isu buruh dan eksploitasi anak, merupakan salah satu contoh yang sering kali menggunakan media sosial untuk mengemukakan berbagai argumen dan data dari hasil risetnya. Baginya, berdebat di sosial media itu tidak selalu negatif selama kita tahu apa persoalan yang diperdebatkan. Bagaimana caranya?
Berikut ini enam tips berdebat di media sosial dari Margianta agar tidak terjebak dalam perdebatan hampa tanpa makna.
-
Cermat bukan cepat
Informasi yang berseliweran di media sosial tentunya amat beragam. Tak jarang saat ada informasi yang bikin emosi muncul di lini masa, tanpa aba-aba kita langsung membalas argumen tersebut dengan amarah yang meluap-luap. Untuk menciptakan perdebatan yang sehat, seharusnya kita lebih berpikir cermat bukan cepat, artinya tidak menjadi reaktif terhadap isu yang belum kita cek kredibilitasnya. Dalam hal ini, latar belakang yang empunya informasi juga penting untuk diperhatikan.
Baca juga: ‘Call-Out Culture’ di Media Sosial: Berfaedah atau Bikin Lelah?
“Misalnya ada isu yang muncul ke permukaan ,coba kita menahan diri untuk tidak mengetik apa pun di layar kita. Riset dulu ada beritanya atau enggak, ada referensinya atau enggak. Pastikan bahwa orang yang menyebarkan informasi ini kredibel, latar belakangnya seperti apa. Emang sudah ahli di situ atau enggak, tahan hasrat untuk merespons,” ujarnya.
-
Kenali platform yang digunakan untuk berargumen
Setiap media sosial memiliki pasar dan pengguna masing-masing, meskipun bisa juga ada lintasan. Tidak semua platform media sosial menyediakan ruang yang sama untuk berargumen. Twitter misalnya, hanya menyediakan maksimal 280 kata setiap kali mengunggah, sehingga kita harus memilah kata apa yang lebih efektif dan penting untuk disampaikan. Lain halnya dengan Facebook, di mana orang lebih leluasa untuk berargumen tanpa memikirkan keterbatasan kata, dan biasanya orang yang mau baca.
“Jadi kita harus lebih mengetahui karakter-karakter media sosial, dan bagaimana kita menyampaikan isunya. Cara saya berdebat di linkedin tentu berbeda dengan cara saya berdebat di twitter. Belajar dari quotenya Albert Einstein If you can not explain it simple enough, you don’t understand it well enough
-
Jangan berasumsi semua memiliki pemahaman yang sama
Menyamaratakan kapasitas orang dalam menangkap informasi merupakan asumsi yang harus dihindari ketika berdebat di sosial media. Ada banyak orang yang di tengah perdebatan seolah memaksakan apa yang dipahaminya kepada orang lain, karena media sosial dibuat tanpa mengenal latar belakang pendidikan, usia, ras, dan kepribadian. Margianta mengatakan, penting untuk melihat lebih dulu kepada siapa argumen itu kita tunjukkan dan untuk membuat arguman sesederhana mungkin.
“Ada yang pendidikannya lulusan SMA, S3, ada yang putus sekolah, dan ada yang berpendidikan tinggi tapi karakternya susah untuk menerima perbedaan. Jadi orang tuh beda-beda dan enggak semua mengerti konteks yang kita sampaikan. Jangan berasumsi mereka itu sepaham dengan kita, kalau bisa misalnya mau menyampaikan satu isu. Jangan pakai bahasa yang aneh-aneh yang rumit-rumit, harus yang semua orang bisa pahami,” ujar Margianta.
-
Jangan terpancing dengan akun anonim
Di tengah perdebatan tak jarang muncul akun-akun tanpa identitas atau anonim. Layaknya orang di belakang panggung, mereka bersembunyi dalam payung anonimitas, sehingga bisa berkomentar asbun alias asal bunyi tanpa menghiraukan argumen logis. Hal ini pula yang sering dialami Margianta.
Baca juga: Feminis Tak Melulu Marah-Marah, Rasa Humor Perlu untuk Hadapi Masalah
“Saya bergerak di isu pengendalian tembakau. Kalau berdebat biasanya saya pakai data. Nah, orang-orang yang pro-industri rokok, mereka pakai segala cacat logika, jadinya menyerang secara personal, memakai asumsi-asumsi yang enggak jelas, membelokkan alur pembicaraan. Jika sudah begitu, jangan terpancing. Yang penting kamu sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan, orang cukup pintar untuk melihat bahwa sebenarnya ini debat tentang apa sih,” ujarnya.
-
Prioritaskan kesehatan mental
Penting untuk digarisbawahi bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, dan tidak semua orang-orang yang berpendapat terhadap argumen yang kita sampaikan dengan niat mendapat pencerahan informasi, ujar Margianta. Banyak orang yang sejak awal berniat hanya ingin menjatuhkan mental kita, mencari segala macam cara untuk membuktikan argumen kita ini tidak valid, ketika kita sudah menyajikan data yang cukup kredibel.
Margianta menyarankan agar kita menghindari orang-orang semacam itu demi kesehatan mental kita.
“Ketika sudah di luar kontrol, ya break dulu. Memang betul harus direspons, tapi dalam takaran dan level apa, metodenya seperti apa, dan tidak harus selalu maksimal. Kita harus mikirin self-care. Kalau kita terlalu pusing dan tertekan itu juga bakal ngaruh ke pesan yang kita bawa. Kalau kita lagi down, nanti respons reaktif yang keluar, bukan argumen yang logis dan data,” ujarnya.
-
Jangan kasih ruang untuk buzzer politik
Media sosial sering dijadikan alat kampanye oleh para politisi, dan buzzer politik bayaran yang berkeliaran di media sosial memang dibayar untuk provokasi. Tugas mereka memainkan ketidaktahuan orang-orang di jagat maya dengan argumen tanpa data. Menurut Margianta, jangan pernah kasih mereka panggung untuk bersuara, karena itulah tujuan mereka.
“Report as spam, ajak teman-temen report. Kalau diladenin terus-terusan tidak ada habisnya. Jangan kasih mereka engagement. Harus hati-hati juga karena terkadang kita secara enggak sadar memberikan panggung untuk mereka. Kita ngasih retweet, kita ngereply itu kan bikin engagement mereka naik,” ujarnya.




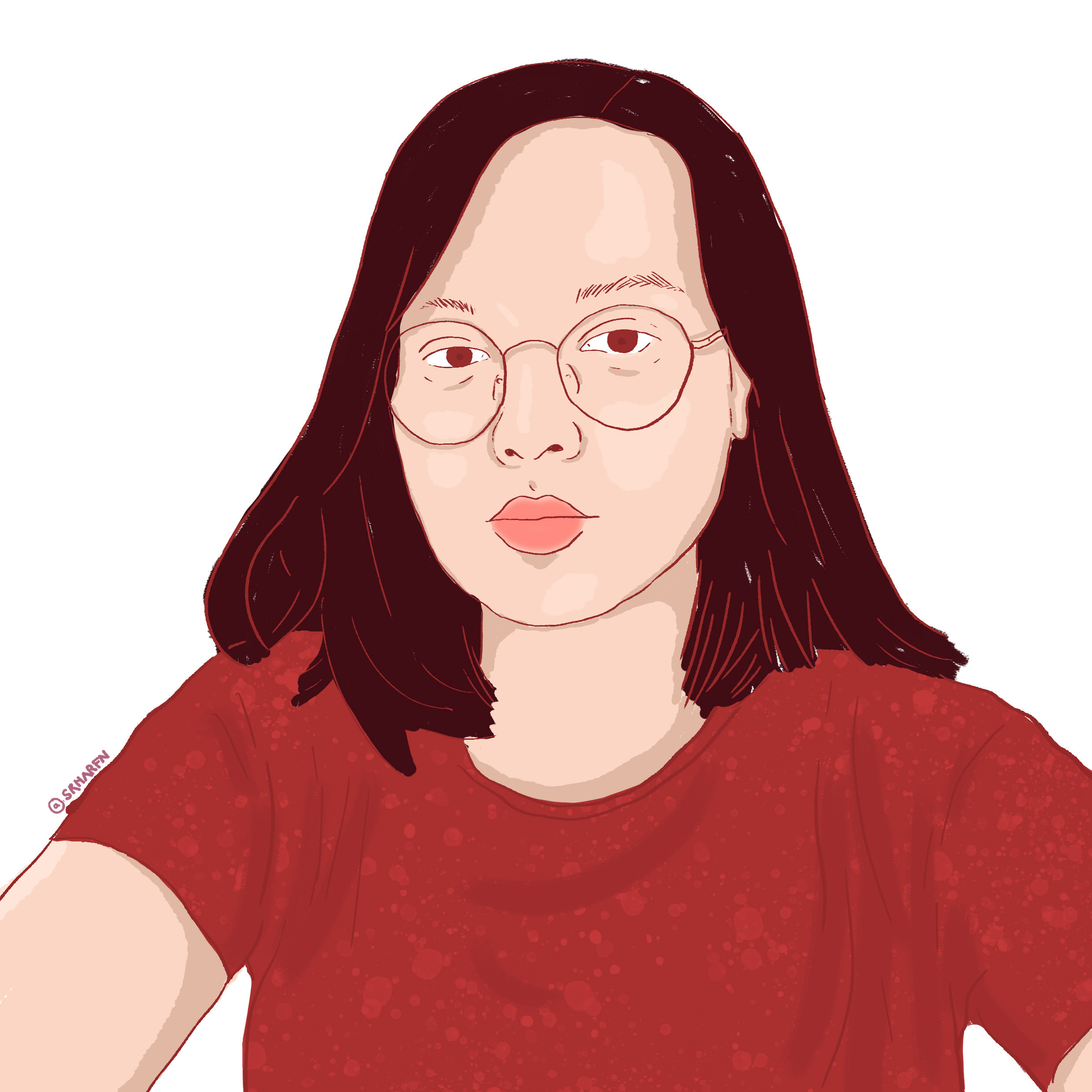



Comments