Ibu penjual baju, makanan, jadi suka ada kecemburuan dari Bapak ke Ibu. Kalau untuk Ibu ada yang nganterin barang, dia curiga itu pacar. Sampai Ibu kalau sambil dipukul ditelanjangi. Pakai celana dalam, pakai beha, diikat di kursi.. yang bikin sakit hatinya itu, dipukulin sampai dipotongin jarinya satu. Ibu waktu itu tidak boleh menangis, tidak boleh menjerit. Sedangkan Bapak hampir setiap hari bawa perempuan ke rumah di depan ibu saya, berselingkuh.
Demikian pengakuan “Pratiwi”, buruh perempuan yang menyaksikan kekejian ayahnya dalam menyiksa ibunya saat usianya masih tujuh tahun. Pratiwi, yang kini sudah berkeluarga, merupakan salah satu dari 26 responden sebuah penelitian mengenai maraknya kekerasan dalam rumah tangga di kalangan buruh perempuan, yang hasilnya diluncurkan baru-baru ini.
Dilakukan pada September-Desember 2019 oleh Perempuan Mahardhika, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu buruh perempuan, penelitian tersebut menjangkau para buruh perempuan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa setengah dari responden perempuan tersebut memiliki masa kecil yang kelam: Berkutat dalam kemiskinan, serta menjadi korban kekerasan fisik, verbal, dan seksual.
“Sejak kecil mereka menjadi korban kekerasan seksual dan harus menyaksikan ibunya disiksa. Karena alasan itu mereka mau memperbaiki nasib ketika sudah memenuhi syarat administrasi pabrik,” ujar peneliti Karolina L. Dalimunthe dalam diskusi bertajuk “Kekerasan Sistematis yang Melanggengkan Penaklukan Perempuan” di Jakarta (13/2).
Para buruh ini rata-rata bermigrasi dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak, ujar Karolina, sebagai buruh garmen di perusahaan tekstil. Terjun ke dunia kerja saat remaja bagi mereka adalah sebuah peluang untuk keluar dari pusaran keluarga mereka yang toksik.
“Kejadian tersebut tidak bisa mereka mengerti ketika kecil, tetapi kemudian ‘diterima’ sebagai nasib perempuan atau nilai yang kemudian diadopsi dalam perkawinan mereka kelak,” ujar Karolina.
Suami dianggap kepala keluarga, namun dalam praktiknya, karena mereka mempunyai pekerjaan sudah sejak lama, para buruh perempuan ini justru menjadi tulang punggung keluarga. Mayoritas dari suami mereka menganggur, sehingga beban yang mereka pikul menjadi berkali lipat.
Konsep pernikahan yang patriarkal
Pertengkaran hebat yang terjadi antara saya dan suami, membuat saya jadi sering menangis dan tidak tidur. Di tempat kerja saya pun jadi sakit kepala dan lemas. Saya pun mengonsumsi beberapa obat sakit kepala yang dosisnya lebih tinggi agar saya sanggup menyelesaikan pekerjaan sampai jam kerja berakhir.
Luapan beban kekerasan dalam rumah tangga dan pekerjaan itu diungkapkan oleh “Sari”, 38, penopang ekonomi keluarga. Setelah lelah bekerja seharian, ia masih harus menerima perlakuan ringan tangan suaminya saat bertengkar. Tuntutan pekerjaan membuatnya tak lagi menghiraukan luka batin karena perlakuan kasar sang suami, yang terpenting baginya pekerjaan bisa selesai tepat waktu.
Kejadian yang dialami Sari ini menjadi hal yang biasa terjadi pada 25 buruh perempuan lain. Setelah menikah, hampir semua responden ini menempatkan laki-laki sebagai hierarki paling tinggi.
“Secara umum, suami dianggap memiliki peran dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, dipandang sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam keluarga. Sedang istri lebih pada menjalankan tugas-tugas domestik seperti pengasuhan anak, dan pengelolaan rumah tangga,” ujar Karolina.
“Namun dalam praktiknya, karena mereka mempunyai pekerjaan sudah sejak lama, para buruh perempuan ini justru menjadi tulang punggung keluarga. Mayoritas dari suami mereka menganggur, sehingga beban yang mereka pikul menjadi berkali lipat karena mereka masih juga harus mengurus anak dan mencukupi kebutuhan sehari-hari suami,” tambahnya.
Neneng, 37, misalnya, rela untuk menjadi buruh kontrak ketimbang menjadi karyawan tetap, karena status kontrak memungkinkannya untuk mendapat uang pesangon saat perjanjian kerja disudahi setiap beberapa bulan sekali. Uang pesangon ini digunakan untuk melunasi utang suaminya ke rentenir, yang bunganya makin lama makin mencekik.
Baca juga: LSM Desak Adanya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pekerja Rumahan
“Saya tuh enggak mau ngambil program itu karena sayang, status karyawan tetap malah jadi kontrak. Saya tuh bingung, bimbang, kalau enggak diambil gimana itu ya,” ujar Neneng sambil menangis, seperti dikutip dalam laporan Perempuan Mahardhika.
Menurut Karolina, kasus semacam itu bukan hanya menimpa Neneng. Sebagian besar narasumbernya mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan, karena mengandalkan gaji saja tidak cukup. Mereka mencari uang tambahan untuk sewa rumah, kebutuhan makan sehari-hari, biaya sekolah anak, cicilan motor, utang di warung, termasuk membayar utang-utang suami atau keluarganya.
“Ada yang mencicil motor untuk membantu suami mereka yang katanya mau jadi tukang ojek online, tapi kenyataannya malah males-malesan. Para buruh perempuan ini merelakan waktu istirahatnya untuk terus bekerja. Jam tujuh pagi sampai empat sore kerja di pabrik, kemudian pulangnya dagang sampai tengah malam,” ujarnya.
Ketimpangan pembagian peran tersebut menjadi pintu masuk terjadinya KDRT, kata Karolina. Istri sibuk bekerja, sementara suami enggan melakukan pekerjaan domestik tapi kemudian merasa kehilangan kekuatannya karena melihat istri yang lebih independen secara finansial. Relasi hubungan suami istri yang semakin memburuk ini diperparah dengan kebiasaan suami mengonsumsi minuman keras dan berjudi.
Bertahan dalam rantai kekerasan
Kita itu kayak merasa terikat oleh rantai yang benar-benar kuat tapi rantainya itu gak kelihatan. Tapi itu nyata, kita itu diikat. “Kamu itu harus ikut apa kata suami. Kalau kamu enggak ikut kata suami, ya pergi tanpa izin suami itu dosa, dan dosa itu bukan hanya kamu yang menanggung, tapi saya sebagai suami juga menanggungnya”.
Karolina mengatakan ungkapan seperti itu banyak disampaikan oleh narasumber, yang secara terus menerus mengalami kekerasan fisik dan mental selama tinggal dengan suaminya.
Rumah dan tempat kerja merupakan dua lokasi kehidupan buruh perempuan, tempat sebagian besar kehidupan mereka dihabiskan. Kekerasan yang dialami di rumah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan yang terpisah dari tempat kerja.
Dalam penelitiannya, ia mengategorikan bentuk-bentuk kekerasan yang mereka alami menjadi enam kategori. Pertama, kekerasan fisik seperti menonjok, membentur-benturkan kepala, menginjak, maupun melempar benda keras seperti batu. Kedua, penganiayaan psikologis dan emosional seperti menghina, mengkritik, dan mempermalukan pasangan, atau poligami dan perselingkuhan. Ketiga, kekerasan verbal seperti berteriak dan memaki.
Keempat, penganiayaan secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual saat korban sedang sakit, atau mengancam akan menganiaya atau memperkosa orang terdekat (anak tiri) jika perempuan tidak mau berhubungan seksual. Kelima, penelantaran ekonomi. Keenam, pengekangan seperti pembatasan lingkup pertemanan maupun media sosial.
“Perlakuan kekerasan yang terus menerus dan berulang sebagai bagian dari keseharian membuat mereka selalu mengatakan keluhan yang sama: Capek, lelah, capek hati, nangis batin,” ujar Karolina.
Kekerasan yang mereka alami terus menerus juga menjadi sebuah trauma berat. Mereka gampang terpicu oleh sesuatu yang mirip dengan karakteristik pelaku sebagai lelaki superior.
“Saya semenjak itu paling enggak bisa dibentak, karena dia itu kalau sudah membentak pasti bareng sama tangan. Jadi saya kalau ada orang teriak atau ngomong kencang gitu kaget, langsung gimana sih, dredeg gitu,” ujar “Tata”.
Jika kekerasan sudah terjadi sedemikian parah, lalu mengapa mereka masih bertahan?
“Saya gimana ya, mbak, sakit tapi saya tidak berdaya. Mau pergi saya ada anak tiga, dia juga kerasnya kayak gitu, kayak orang kalap melewati batas,” ujar “Dina”.
Alasan Dina yang memikirkan masa depan anaknya menjadi faktor utama yang disampaikan hampir semua narasumber.
“Alasan lainnya, karena konsep pernikahan patriarki ini, mereka menunggu diceraikan, karena harusnya suami selaku imam yang menceraikan istri. Larangan orang tua menjadi alasan kedua. Selain itu, mereka takut dengan stigma janda. Terakhir, dan yang paling ironis adalah minimnya pengetahuan mereka tentang payung hukum kasus KDRT,” ujar Karolina.
Baca juga: 'Sekali Berstatus PRT Migran Selamanya PRT Migran'
Pembiaran oleh masyarakat
Vivi Widyawati, koordinator program penelitian Perempuan Mahardika mengatakan, KDRT terus berlangsung karena ada pembiaran oleh lingkungan sekitarnya. Masyarakat sering kali menganggap bahwa KDRT yang terjadi di ruang publik adalah urusan personal. Alih-alih menolong ketika terjadi kekerasan, masyarakat malah membiarkannya begitu saja dengan alasan tidak mau mencampuri urusan orang lain, katanya.
“Kalau mengadu ke ibunya, malah disuruh sabar dulu, mungkin berubah. Kemudian mengadu ke RT/RW, dibilang ini bukan wilayah saya tapi pribadi. Apalagi jika mengadu ke perusahaan yang tidak ada pertaliannya,” ujar Vivi.
Pada kenyataannya, KDRT sudah masuk ke dalam lingkungan kerja, karena selain memengaruhi performa kerja para buruh perempuan, tak jarang para suami yang sedang berkonflik dengan istrinya datang ke tempat kerja.
“Tidak ada keselamatan kerja jika pabrik tidak aman, dan tidak ada keselamatan tanpa keamanan di rumah,” ujar Karolina.
Minimnya pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menunjukkan hampir 71 persen kasus kekerasan dalam rumah tangga di dominasi oleh kasus KDRT, Karolina dan Vivi mendorong agar adanya sosialisasi tentang PKDRT di tingkat RT/RW serta desa/kelurahan.
Mereka juga merekomendasikan adanya ruang khusus di pabrik-pabrik yang bisa menjadi tempat mengadu ketika para buruh perempuan ini mengalami KDRT.
“UU PKDRT sudah seharusnya masuk menjadi jaminan keselamatan kerja para buruh perempuan. Mungkin bisa dibentuk seperti sekretariat informasi atau pertolongan di setiap pabrik,” ujar Vivi.
Karolina mengatakan bahwa rumah dan tempat kerja merupakan dua lokasi kehidupan buruh perempuan, tempat sebagian besar kehidupan mereka dihabiskan. Kekerasan yang dialami di rumah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan yang terpisah dari tempat kerja, demikian pula sebaliknya.
“Menangani persoalan KDRT tidak bisa dilihat dari perspektif rumah saja, melainkan tempat kerja agar buruh perempuan korban KDRT mendapat jaminan atas keberlanjutan kerja dan keselamatan dirinya,” ujar Karolina.




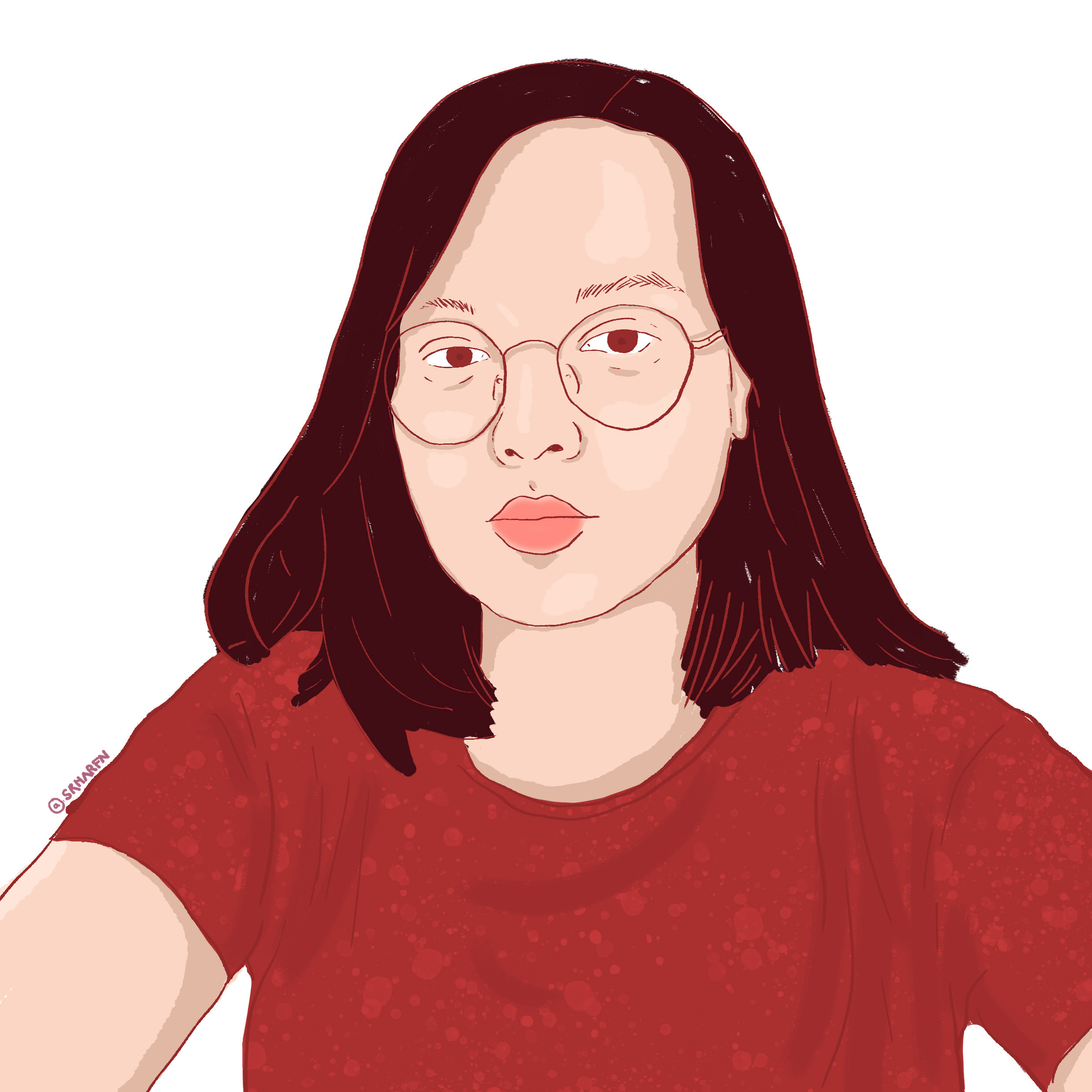



Comments