Baru-baru ini saya dan suami saya pergi ke sebuah klinik di dekat tempat tinggal kami untuk melakukan rapid test. Sebelum pergi ke klinik, saya telah mendaftar sekaligus membayar tes tersebut melalui sebuah aplikasi ponsel. Sesampainya di klinik, saya menunjukkan kode yang telah dikirimkan oleh aplikasi tersebut melalui surel kepada petugas klinik, untuk menunjukkan bahwa kami telah terdaftar dan melakukan pembayaran atas layanan rapid test.
Setelah sampel darah diambil, saya duduk di kursi yang disediakan tak jauh dari meja pendaftaran untuk menunggu hasilnya. Tak lama ada sepasang suami istri masuk ke dalam klinik. Sang istri sedang hamil, mungkin sekitar enam atau tujuh bulan. Tangan kirinya menggandeng seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun.
Di meja pendaftaran, perempuan itu berbicara pada petugas klinik bahwa dirinya ingin melakukan pemeriksaan USG. Petugas kemudian bertanya, apakah sang ibu telah melakukan pendaftaran secara daring, dan ibu itu menggeleng. Petugas klinik berusaha menjelaskan bahwa klinik mereka tidak lagi menerima kedatangan langsung untuk layanan USG kandungan, sehingga pasien harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui aplikasi atau nomor WhatsApp klinik tersebut.
Baca juga: Beban Timpang antara Ibu dan Ayah dalam Pendampingan Belajar dari Rumah
Raut muka sang ibu seketika berubah, seperti kebingungan. Ia berkali-kali memastikan apakah tidak mungkin untuk langsung melakukan USG tanpa mendaftar online. Petugas klinik menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebijakan klinik sejak pandemi untuk menghindari penumpukan pasien. Ibu itu kemudian memberi isyarat pada suaminya untuk berbicara kepada petugas klinik.
Setelah berbicara singkat, sang suami mengeluarkan ponselnya, mengikuti instruksi petugas klinik untuk memindai barcode, mengunduh aplikasi, lalu mendaftar jadwal USG keesokan harinya. Pasangan itu kemudian pulang dengan raut kecewa, terutama si Ibu. Mungkin ia bersedih karena tidak jadi melihat perkembangan bayi dalam kandungannya.
Saya tertegun, menyadari betapa kelirunya anggapan bahwa teknologi mempermudah banyak hal. Bagi mereka dengan tingkat pendidikan dan akses teknologi cukup, tentu saja hal tersebut membantu. Tetapi, saya lupa bahwa banyak juga pihak yang justru teralienasi dari kemajuan teknologi, terutama mereka yang terlambat memiliki akses untuk membangun kecerdasan digital.
Dalam tatanan masyarakat yang patriarkal, penggunaan, kepemilikan, maupun ruang yang diciptakan oleh perangkat digital tidaklah netral gender, ia dianggap sebagai domain laki-laki.
Bias Gender dalam Teknologi Digital
Saya ingat bagaimana sang ibu di klinik memberikan isyarat pada suaminya untuk berbicara kepada petugas, yang mulai menjelaskan perihal teknis pendaftaran daring. Teknologi, di balik segala kemudahannya, membawa konsekuensi kesenjangan gender yang curam. Dalam tatanan masyarakat yang patriarkal, penggunaan, kepemilikan, maupun ruang yang diciptakan oleh perangkat digital tidaklah netral gender, ia dianggap sebagai domain laki-laki. Hal ini membuat perempuan tidak mendapatkan manfaat yang sama atas kemudahan yang dihadirkan oleh transformasi digital.
Ada beberapa alasan terjadinya kesenjangan gender pada akses digital. Pertama, kemampuan untuk membeli perangkat. Ketika sebuah keluarga tidak mampu untuk membeli ponsel pintar untuk semua anggota keluarga, siapakah yang akan diutamakan? Ayah? Ibu? Atau anak?
Kedua, pendidikan dan kurangnya literasi digital bagi perempuan. Kesenjangan di bidang pendidikan tentu berpengaruh pada bagaimana perempuan menggunakan teknologi. Data dari ICT Watch pada 2017 menunjukkan, kurang dari 30 persen perempuan pengguna internet yang menggunakan internet untuk mencari informasi penting perihal hak dasar mereka seperti kesehatan, reproduksi, atau hukum. Literasi dibutuhkan untuk membangun kecerdasan digital. Kebanyakan perempuan kurang memiliki imajinasi mengenai hal-hal yang mungkin dilakukan di internet yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka.
Baca juga: ‘Invisible Women’: Data Laki-laki yang Utama, Perempuan Nanti Saja
Ketiga, norma sosio-kultural yang bias gender. Artikel yang ditulis Lestari dan Sunarto, yang bertajuk “Digital Gender Gap for Housewives” dan diterbitkan oleh jurnal The Messenger (2018), menggambarkan bahwa dalam masyarakat patriarkal, distribusi kuasa yang tidak setara dalam rumah tangga akan memengaruhi keputusan siapa yang dapat memiliki akses kepada teknologi.
Segala peraturan maupun sumber daya dibuat dan diputuskan oleh laki-laki, sehingga akan memarginalkan perempuan, menurut artikel tersebut. Dominasi patriarki di dalam keluarga mendefinisikan bentuk teknologi yang boleh dikuasai oleh perempuan adalah yang terkait dengan peran domestiknya, seperti rice cooker, mesin pencuci piring, ataupun microwave. Sementara ponsel pintar sebagai sumber informasi berbasis internet dianggap sebagai domain laki-laki.
Pandemi Perparah Kesenjangan Digital untuk Perempuan
Kesenjangan gender dalam akses digital ini diperparah oleh pandemi. Kebijakan pembatasan sosial membuat banyak sarana umum yang mengalihkan layanan secara daring. Dalam pengalihan ini, semua orang dianggap telah memiliki akses yang sama terhadap internet dan telah memiliki kecerdasan digital seketika. Cara pikir ini tentu merugikan perempuan.

Bagaimana tidak, kita mungkin ingat di pertengahan tahun lalu sempat terjadi anomali data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hampir seluruh laporan internasional memaparkan mengenai meningkatnya angka KDRT sebagai dampak dari karantina dan pembatasan sosial. Namun data KDRT dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2019 dan 2020, tidak menunjukkan perbedaan signifikan.
Setelah ditelusuri, hal ini terjadi karena banyak lembaga layanan kekerasan yang tutup di saat pandemi dan mengubah penerimaan pengaduan secara daring. Karena kurangnya literasi digital dan akses terhadap internet, korban KDRT yang sebagian besar adalah perempuan kemudian tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya.
Kesulitan lain yang dihadapi oleh perempuan dalam masa pandemi adalah pendampingan pembelajaran jarak jauh. Karena stereotip gender yang dilekatkan padanya, perempuan dianggap bertanggung jawab atas pendidikan anak. Penerapan kebijakan pembelajaran secara daring seolah mengasumsikan bahwa setiap ibu telah cakap mengoperasikan beragam aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan sebagainya. Sementara ayah, yang lebih mahir dalam pengoperasian internet, tidak banyak mendampingi anak dalam pembelajaran daring.
Baca juga: ‘Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith?’: Kebaikan yang Dinihilkan
Survei yang dilakukan oleh The Conversation menunjukkan bahwa lebih dari 66 persen pendamping pembelajaran jarak jauh adalah ibu. Hal ini memberikan beban tambahan yang harus ditanggung perempuan—mereka yang dengan tergagap membiasakan diri dengan perangkat digital untuk mendampingi anak bersekolah.
Jika kita kembali pada persoalan pasangan yang harus menunda pemeriksaan USG karena belum melakukan pendaftaran secara daring, kita juga akan melihat pengalaman yang berbeda yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Sang ayah mungkin merasa kecewa karena batal melihat perkembangan bayinya, dan harus mencari waktu untuk datang kembali ke klinik keesokan hari. Tetapi tentu saja kekecewaan yang dialaminya tidak termasuk kesulitan membawa perut buncit naik turun sepeda motor, menaiki satu persatu anak tangga klinik dengan nafas terengah dan sakit punggung, sambil menggandeng anak usia SD.




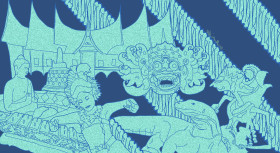


Comments