Pikiran saya yang terlampau imajinatif, ditambah depresi membuat saya sering memikirkan bunuh diri, hanya saja saya tidak menyangka akan benar-benar melakukannya. Alasan saya melakukan itu mungkin sepele, karena saya belum menyelesaikan skripsi. Namun hal itu menimbulkan stres berkepanjangan yang memicu gelombang depresi kembali datang.
Depresi sudah menjadi kawan saya sejak duduk di sekolah berasrama waktu SMA, meski saya tidak memahaminya saat itu. Depresi itu pergi setelah saya pindah ke sekolah reguler, tapi datang lagi di bangku kuliah, terutama saat mengerjakan skripsi pada 2015.
Di kampus, ibu dosen pembimbing saya sangat “menguji mental” saya. Saya kerap dihina di depan dosen lain atau orang banyak, dikatai, “Kamu sok tahu”, “Dasar wong gendeng”, atau “Yah, kalau begini ceritanya, sampai 2018 pun kamu enggak bakal lulus.” Ia juga menuduh saya melakukan plagiarisme, bahkan sampai diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai. Padahal tuduhan itu tidak terbukti sama sekali.
Dalam lingkungan keluarga, ayah saya termasuk mereka yang tidak memercayai kondisi mental saya ini, meskipun saya sudah mengalaminya sejak di bangku SMA. Teman-teman kampus yang tidak tahu dengan kondisi kejiwaan saya pun ikut menyalahkan saya.
Kekeruhan ini membuat saya memutuskan untuk pergi ke seorang psikolog di sebuah rumah sakit di Jakarta. Alih-alih mendapatkan perawatan, psikolog tersebut menganggap masalah saya ada karena saya “kurang beriman.” Ia berkali-kali menekankan bahwa saya mengalami depresi karena saya membuka jilbab, padahal depresi dan membuka jilbab adalah dua kondisi tidak terkait.
Segala kerunyaman itu memuncak dengan keputusan saya bahwa bunuh diri adalah pilihan yang baik. Semuanya terjadi sangat cepat dan saya melakukannya di kamar kos dengan cara mencekik leher sendiri. Anehnya, selama beberapa detik, kepala saya penuh dengan wajah orang-orang terkasih dan saya menangis sejadi-jadinya. Dalam beberapa detik pula, saya tidak melihat wajah Ayah, namun saya mendengar suara tangisan dia saat Nenek meninggal.
Beberapa menit setelahnya, saya yang masih menangis memutuskan untuk keluar kamar dan beruntung saya segera bertemu dengan dua teman kos yang menenangkan saya. Selama dua malam berikutnya, mereka melarang saya untuk tidur sendirian.
Saya kerap sekali dituduh kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, padahal saya sendiri sering mempertanyakan kondisi saya ini kepada Tuhan.
Di tengah kegamangan saya dan kekhawatiran teman-teman, saya memutuskan untuk pergi dan menonton film di bioskop sendirian, salah satu kegemaran saya yang sudah lama tidak saya lakukan. Teman-teman kos masih belum yakin saya bisa sendirian, namun saya mengatakan kepada mereka bahwa saya akan baik-baik saja. Saya memilih menonton film Logan, tentang salah satu tokoh superhero kesukaan saya, Wolverine, dari serial komik X-Men. Hari itu saya benar-benar mengaktifkan segala sensori saya dan berusaha mengucapkan syukur karena masih bisa merasakan kehidupan, serta berjanji untuk tidak melakukan ataupun memikirkan bunuh diri.
Saya merahasiakan kejadian tersebut dari keluarga saya selama beberapa hari karena saya tidak ingin membuat mereka khawatir. Ketika saya akhirnya memberitahukan mereka, Ayah saya menjadikan insiden itu sebagai bahan bercanda. Ia lalu sering berkomentar, “kenapa enggak sekalian (mati),” atau “ternyata takut mati”, yang tentunya membuat saya bersedih dan merasa sendiri.
Beberapa teman dekat yang mengetahui percobaan bunuh diri juga masih menyalahkan saya, meskipun tidak sedikit pula yang menunjukkan rasa simpati dan dukungan. Saya kerap sekali dituduh kurang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang akan saya balas dengan senyum miris karena mereka tidak tahu saya sendiri sering mempertanyakan kondisi saya ini kepada Tuhan. Salah satu bapak dosen yang mengetahui kondisi saya malah menjadikan saya bahan gurauan dan perlakuan dosen pembimbing pun tetap keras. Namun setelah usaha bunuh diri yang gagal itu, saya berjanji kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih kuat.
Menyalahkan diri atas aksi bunuh diri orang lain
Selang beberapa minggu kemudian, jagat maya dihebohkan oleh proses bunuh diri seorang laki-laki yang dengan sengaja menyiarkannya secara langsung lewat halaman Facebook pribadinya. Malang bagi pria itu, orang-orang yang menonton video tersebut justru lebih banyak yang menyuruhnya bunuh diri ketimbang menolong si pria itu. Almarhum serta keluarganya lalu dihakimi oleh masyarakat tanpa mau memahami latar belakangnya, sedangkan orang-orang yang memberi motivasi pria tersebut untuk bunuh diri, tidak terkena masalah hukum.
Saya iba pada pria itu. Seandainya dia memiliki orang-orang yang mendukungnya, tentu dia tidak akan memilih jalan tersebut. Anehnya, saya sedikit menyalahkan diri sendiri, dan berpikir bahwa jika saya membunuh diri saya malam itu, mungkin pria itu tidak bunuh diri.
Pada awal Juni lalu, T.O.P., salah satu anggota boyband besar asal Korea Selatan, Big Bang, mengalami overdosis. Big Bang adalah grup kesukaan saya, dan saat mengetahui T.O.P terkena kasus hukum akibat mariyuana, saya cukup sedih. Kesedihan saya bertambah saat dia meminum obat untuk kecemasannya secara berlebihan dan dalam keadaan koma selama beberapa hari. Anehnya, lagi-lagi perasaan bersalah kembali mendera saya. Saya berpikir, seandainya saja saya “sukses” bunuh diri, T.O.P mungkin tidak akan melakukan hal itu.
Pada saat yang bersamaan, saya sedang mempersiapkan diri untuk sidang skripsi. Di tengah perasaan yang masih kacau balau karena semuanya, saya mampu melakukan sidang skripsi dengan baik. Tapi tampaknya Tuhan masih memberikan saya ujian tambahan karena saya dimaki oleh dosen penguji saya. Teman-teman saya yang memahami situasi saya menenangkan saya. Saya juga sibuk mengingatkan diri agar tidak melakukan hal yang aneh.
Untungnya, saya bisa lulus dan menjaga pikiran saya untuk tetap positif sambil mengikuti perkembangan T.O.P yang kembali sadar dan menjalani persidangan. Saya terus mendoakan keselamatan T.O.P, melihat ketegarannya (meskipun saya masih sedih karena dia memilih obat-obatan terlarang untuk mengurangi kecemasannya) dalam menghadapi masalah, seolah-olah dia membantu mental saya untuk menjadi kuat.
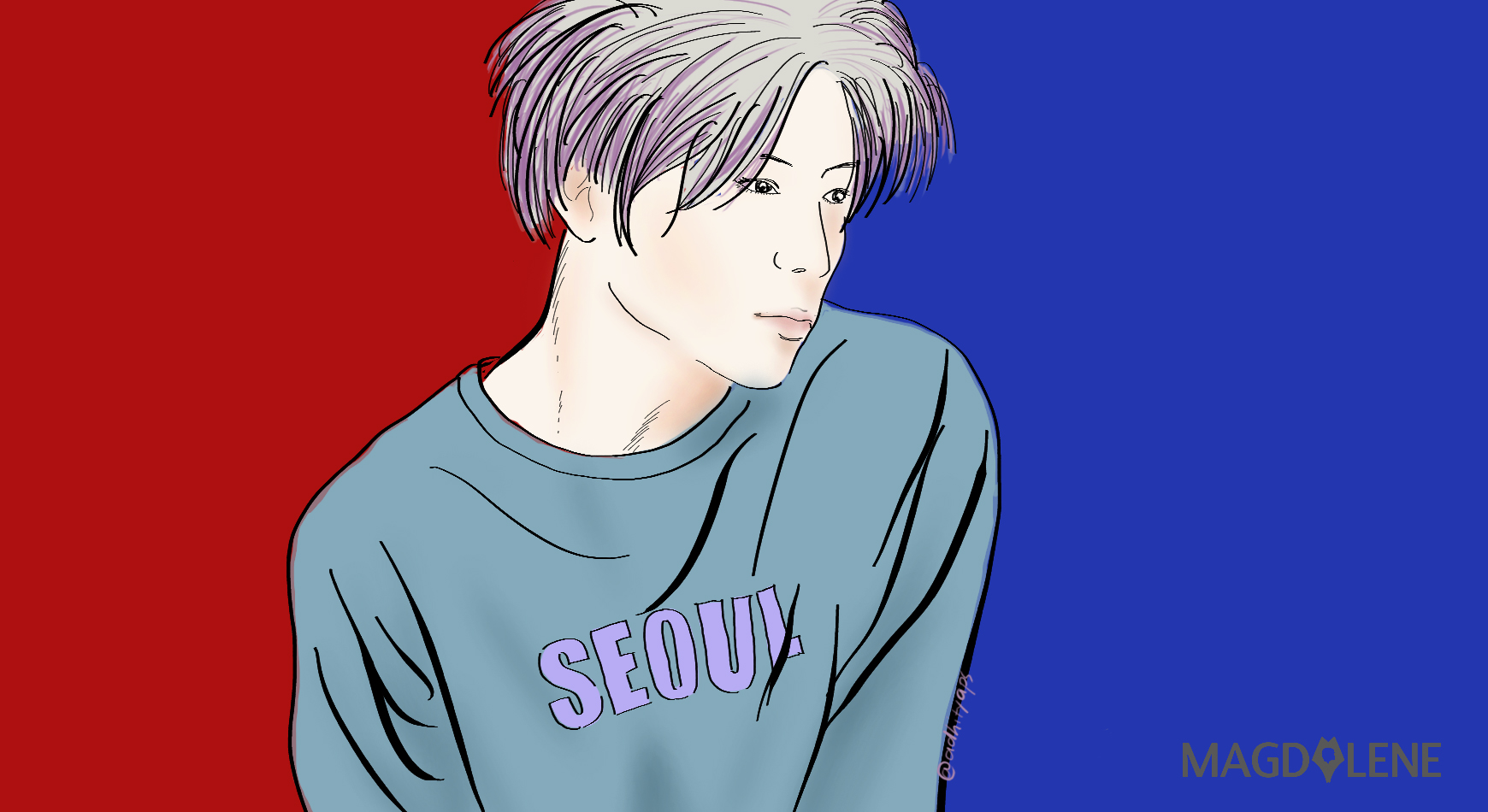
Kira-kira dua minggu menjelang wisuda, vokalis kesukaan saya dari band Linkin Park, Chester Bennington, meninggal karena bunuh diri. Akibatnya, pikiran, “seandainya saya yang mati….,” kembali menggelayuti benak saya. Chester yang sudah berjuang melewati depresi selama bertahun-tahun, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah sahabatnya juga melakukan bunuh diri dua bulan sebelumnya. Hal yang perlu dicatat adalah Chester memiliki keluarga yang bahagia dan tidak memiliki masalah di dalam bandnya, namun ternyata dirinya menyimpan kesedihan dan beban yang sangat berat, terutama setelah kematian sahabatnya.
Kematian Chester membuat saya patah hati. Saya merasakan ikatan batin dengannya karena sama-sama memiliki depresi dan bunuh diri. Perbedaannya adalah saya hidup dan dia tidak. Saya masih merasakan baju toga, sedangkan Chester tidak akan pernah menyelesaikan turnya.
Orang-orang terdekat saya mengatakan bahwa saya akan kembali sehat setelah wisuda. Namun depresi saya masih mengganggu di tempat saya magang, sebulan setelah wisuda. Saya masih terbayang dengan dosen pembimbing dan menjadi lebih mudah cemas, dan ada seseorang yang menggunakan kelemahan ini untuk menjatuhkan saya. Ketika masa magang usai Desember, perlahan-lahan saya kembali merasakan mimpi dan bahagia, yang sebelumnya tidak saya rasakan selama dua tahun.
Di saat saya berhasil meredakan depresi, salah satu bintang K-pop dari boyband Shinee, Kim Jong Hyun, memutuskan bunuh diri karena depresi yang dialaminya selama bertahun-tahun. Saya sangat menyesalkan kematiannya. Seandainya saja orang-orang sekelilingnya mengerti kondisinya, dan dia juga berani mengakui bahwa dirinya memiliki masalah kejiwaan, mungkin hal ini tidak akan terjadi.
Kematiannya menimbulkan pro dan kontra di Indonesia; tidak sedikit yang memakai agama untuk menganggap itu sebagai perbuatan tercela. Namun para penggemar membelanya mati-matian karena mengetahui alasan kematiannya. Selang sebulan kemudian, aktor Korea Selatan, Jeon Tae Soo, bunuh diri. Pria berusia 34 tahun itu juga memiliki depresi dan menyerah kepada penyakit mentalnya tersebut.
Meskipun kematian Jeon Tae Soo tidak menimbulkan perdebatan panas sepanas saat Jong Hyun meninggal, namun narasi menghakimi mereka yang bunuh diri masih sangat deras. Tuduhan keras ini tentu tidak membantu mereka yang memiliki kecenderungan ingin bunuh diri. Sudah cukup banyak lembaga swadaya masyarakat dan media massa yang berusaha ramah dengan mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental dan memberikan bantuan, namun stigma terhadap kondisi ini masih kuat. Hal ini membuat saya pesimistis. Saya hanya bisa berharap tahun ini masyarakat Indonesia lebih ramah terhadap penyakit mental. Saya percaya hubungan welas asih, ramah, dan penuh empati akan sangat membantu mereka yang memiliki masalah mental dan hasrat bunuh diri.
Ren adalah penulis lepas dan pencerita, dan telah berhasil menerbitkan beberapa tulisannya. Ia memiliki hubungan cinta dan benci dengan depresi, yang ia beri nama Orca karena berbentuk Paus Orca. Ren menganggap dirinya mirip Luna Lovegood.
Ilustrasi oleh Sarah Arifin dan Adhitya Pattisahusiwa.








Comments