Sebuah undangan pernikahan dari musisi/aktivis Kartika Jahja akhir bulan Juli lalu sukses membuat saya berkaca-kaca karena bahagia. Berita itu seperti pelipur lara di tengah derasnya kabar duka tentang meninggalnya kerabat, teman, dan kenalan akibat infeksi COVID-19. Tidak masalah jika kami hanya bisa menghadiri akad nikah secara daring, yang penting ada sesuatu yang berbeda dari berdiam di rumah dan mengucap “Innalillahi” atau “RIP” berulang kali setiap hari.
Pada hari H, saya sudah siap lima menit sebelum acara dimulai di depan laptop dengan memakai kebaya, yang sudah sekian lama menggantung di lemari. Senyum saya tak lepas melihat halaman rumah orang tua Tika yang cantik dengan dekorasi kain-kain Nusantara di sana sini, serta wajah tamu-tamu yang “hadir” dari berbagai tempat dan negara.
Senyum bertambah lebar saat pasangan pengantin muncul di layar beserta kedua orang tua mereka, tampil molek dengan pakaian adat daerah masing-masing. Sampai tiba saatnya pengucapan ijab kabul, tiba-tiba teman kami, Chika, mengirim pesan pribadi.
“Duh, gue deg-degan, takut khotbah nikahnya bias gender,” ujarnya. Saya mengamini, namanya juga sesama feminis SJW.
Kekhawatiran itu bukannya tidak beralasan. Sudah berapa banyak akad nikah yang saya hadiri dan sebagian besar khotbah nikah yang diberikan sungguh seksis. Isinya wejangan berat sebelah yang tak pernah jauh berkisar pada kewajiban istri untuk berbakti dan melayani suami, dan konsekuensinya bila melanggar.
Khotbah semacam ini sukses membuat saya cemberut saat melangsungkan akad nikah belasan tahun lalu. Kekesalan bertambah saat saya kemudian diminta mencium tangan suami. Saya diam mematung saat itu, menimbang-nimbang apakah saya harus menolak atau bagaimana. Desakan dari hadirin membuat saya menyerah dan mencium tangannya. Mengerti kekesalan saya, suami (yang sekarang sudah menjadi mantan) kemudian membalas mencium tangan saya.
Pengalaman yang sama soal khotbah nikah seksis ini dialami oleh beberapa teman, seperti Y, yang bahkan menghadapi double whammy karena ayahnya sendiri yang bersikeras memberikan khotbah nikah, alih-alih penghulu atau khatib.
“Bokap gue memang dominan banget. Inti isi khotbahnya adalah, apa-apa harus izin kepada suami dan kalau tidak diberi izin tidak boleh dilakukan,” ujarnya.
Teman yang lain, R, karena sering mendapati khotbah nikah yang seksis menjadi ekstra waspada saat ia menikah dengan melakukan penyaringan secara ketat.
“Soalnya gue trauma, sebelumnya waktu pernikahan sepupu, khatib nikahnya bilang, ‘Nah, sudah resmi, ini buku nikahnya sudah jadi SIM: Surat Izin Mengendarai Istri,” kata R dengan imbuhan sumpah serapah.
Meski berhasil menyaring khotbah nikah, R tidak dapat menghindari ceramah-ceramah yang diberikan saat pengajian sebelum pernikahan atau menjelang resepsi (“Banyak banget ceramahnya waktu gue kawin, sudah kayak ‘ceramahception’!”).
“Guru ngaji Nyokap bilang begini, ‘Jadilah perempuan baik-baik di luar rumah, tapi jadilah pelacur di rumah. Jaga nama suamimu di luar rumah, senangkan hatinya di dalam rumah,” ujar R, diikuti dengan sumpah serapah, kali ini dari saya.
Khotbah Nikah Tak Perlu Bias Gender
Ini sudah 2021, tapi kelihatannya khotbah nikah belum beranjak dari normatif (“suami istri harus rajin beribadah, ingat kepada Allah, menghasilkan keturunan yang baik”) dan seksis tadi. Padahal pernikahan, sebagai sebuah perjalanan yang tidak jarang memerlukan perjuangan dan pengorbanan, seharusnya diawali dengan nasihat yang relevan, bukan penekanan pada nilai-nilai patriarkal.
Baca juga: Tren Menikah Muda, Mencari Jalan Ke Surga
Cendekiawan Islam Nur Rofiah mengatakan, konsep pernikahan dalam Islam sebetulnya mengatur kesetaraan serta kebaikan bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan.
“Anggapan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga sehingga berhak berlaku semena-mena dan membuat istrinya tersiksa merupakan miskonsepsi dan cerminan sistem yang jahiliyah (bodoh),” ujar Nur, dosen pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta dan penggagas program Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI).
"Pernikahan dalam Islam itu mengedepankan ketenangan jiwa dan kemaslahatan (kebaikan) bersama, dalam artian, baik istri maupun suami harus sama-sama mendapatkan kemaslahatan itu. Jadi kalau pernikahan itu menjadikan perempuan propertinya laki-laki, itu berarti melanggar ajaran Islam," ia menambahkan, dalam sebuah webinar Magdalene.
Kenapa bukan konsep seperti ini yang ditekankan oleh para khatib nikah? Karena masyarakat patriarkal tentu saja.
Ada orang-orang seperti sepupu saya, yang beruntung karena mendapatkan khatib nikah yang paham kesetaraan. Dengan nada tenang tapi pasti, sang ustaz mengingatkan bahwa pernikahan bukan sesuatu yang mudah sehingga kedua belah pihak harus bekerja sama dan menjalin pengertian dan komunikasi.
“Ananda berdua memiliki latar belakang yang sama. Kalian pacaran sejak kuliah, di fakultas yang sama, lalu pekerjaan yang digeluti pun tidak jauh berbeda. Hal ini berpotensi memicu kebosanan, dan tanpa komunikasi yang baik akan menimbulkan masalah,” ujar khatib nan bijak dan kontekstual.
Satu lagi khotbah yang berkesan buat saya adalah saat menghadiri upacara pernikahan teman di sebuah gereja Katolik. Sang pastor mengatakan bagaimana kedua calon pengantin, yang berbeda agama, datang kepadanya untuk berkonsultasi.
“Mereka datang pada saya, katanya ingin menikah, namun ada suatu masalah. Saya bingung juga mau memberi nasihat apa, wong saya belum pernah menikah,” ujarnya, yang membuat hadirin tergelak dengan self deprecating joke-nya.
Saya lupa apa yang sang romo katakan persisnya setelah itu, tapi kata-katanya menghangatkan hati, apalagi karena pernikahan berbeda agama masih sulit dilakukan di negara ini. Yang saya ingat, tidak ada mata yang kering di gereja saat itu.
Baca juga: Argumen dari Ajaran Islam Mengapa Pemerkosaan dalam Perkawinan Dilarang
Kembali ke acara Tika, syukurlah khatibnya tidak bias gender, hanya terlalu sering melontarkan dad joke. Belakangan, Tika bilang, dia pun sedikit deg-degan, karena seminggu sebelum ia menikah, khotbah dalam acara pernikahan temannya sungguh membuat enek.
“Intinya, ikuti kata suami karena yang menanggung surga istri itu suami. Kalau suami bilang kerja, boleh kerja. Kalau suami bilang jangan kerja, percayalah bahwa Allah akan memberi rezeki melalui keringat suami,” ujar Tika.
Chika kemudian bertanya apakah pasangan yang menikah secara Islam boleh memilih penghulu dan khatib sendiri.
“Boleh, dong,” ujar saya.
“Waktu J nikah dulu, khatibnya Kyai Hussein,” kata Chika, menyebut seorang kenalan kami yang beruntung mendapatkan khotbah nikah dari seorang kyai feminis.
“Wow! Kalau begitu, buat yang berikutnya, gue mau Bu Musdah.”
“Yang berikutnya??” ia terhenyak, sebelum kami berdua terbahak-bahak.



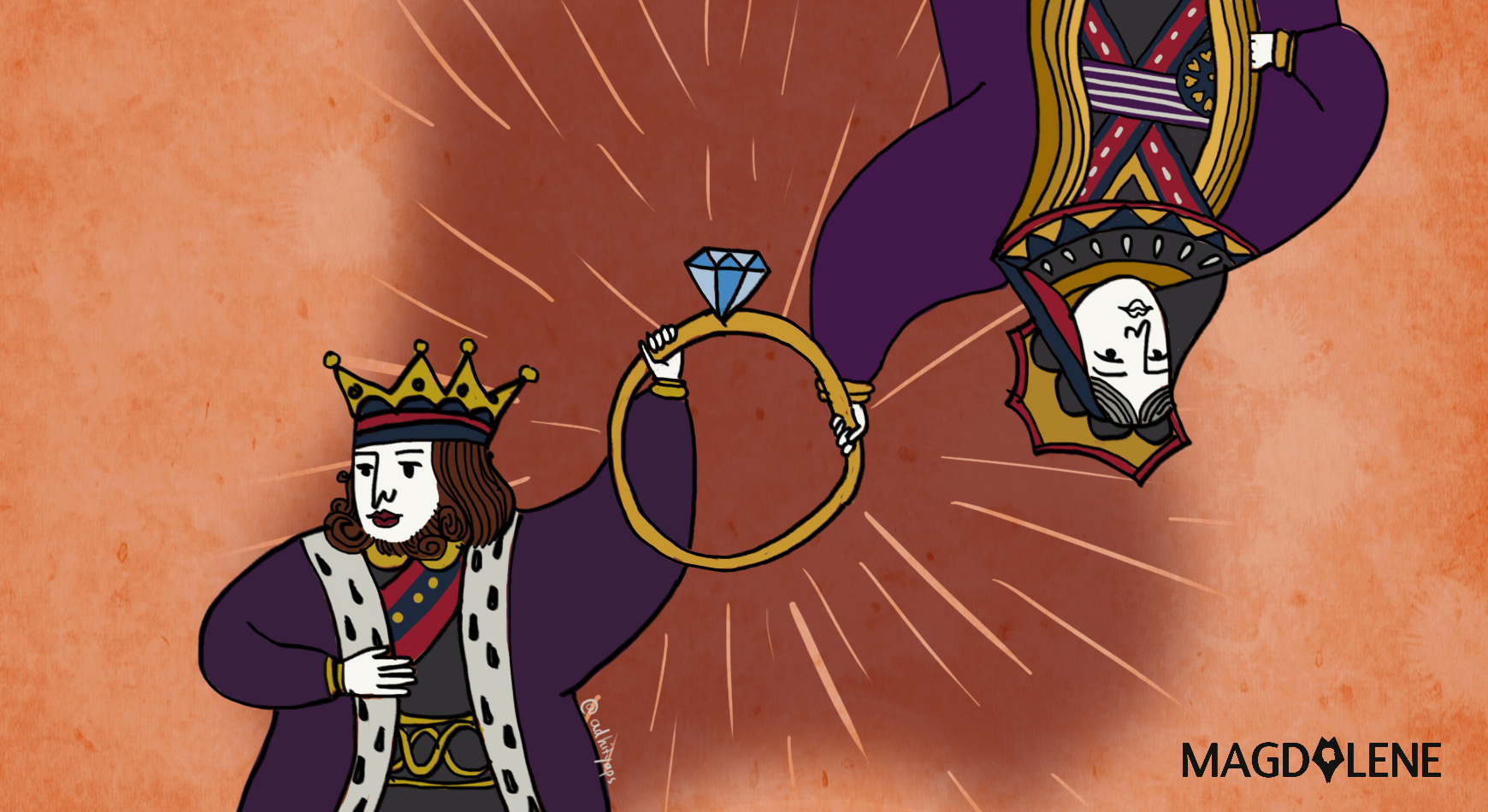
1.jpeg)



Comments