Saat dugaan pelecehan seksual terhadap kreator konten Gofar Hilman merebak di Twitter pekan ini, seketika itu juga pembelaan terhadapnya muncul dari teman-teman dan para penggemarnya.
Aktris Nikita Mirzani membela Gofar dengan mengatakan bahwa sahabatnya itu pria sopan yang tidak mungkin “grepe-grepe tanpa izin” dan ia menyebut perempuan penyintas lah yang mau dilecehkan. Komika Coki Pardede menyamakan Gofar dengan terpidana kekerasan seksual Hollywood Harvey Weinstein dan Bill Cosby “yang rata-rata bakatnya gokil” walaupun tersangkut kasus pelecehan seksual.
Sementara itu, komentar-komentar bernada victim blaming berhamburan di media massa, mulai dari menyalahkan pelapor, @quweenjojo, karena baru memunculkan kasus ini setelah tiga tahun, mempertanyakan mengapa dia diam saja saat peristiwa itu terjadi, hingga menudingnya tidak paham perilaku orang mabuk.
Di tengah-tengah tudingan dan komentar yang membuat ngilu dan triggering tersebut, ada langkah maju dari Lawless Jakarta, perusahaan makanan tempat Gofar menjadi salah satu pemegang saham. Pada Kamis (10/6) pihak Lawless mengunggah pernyataan berikut di akun Instagram mereka @lawless_jkt:
“Kami tahu dan memantau isu yang sedang beredar menyangkut nama Gofar Hilman. Kami dari Lawless Jakarta berdiri bersama korban. Mulai hari ini kami menyatakan bahwa Gofar Hilman sudah bukan bagian dari Lawless Jakarta.”
Baca juga: ‘Shaming’ Pelaku Kekerasan Seksual: Efektif Tapi Berisiko bagi Korban
Arian Arifin Wardiman, musisi dan salah satu pendiri Lawless, juga mengunggah pernyataan, “I stand with the victim” di akun Twitter pribadinya.
Banyak yang menuduh pernyataan Lawless sebagai gimmick atau branding, namun sikap seperti ini adalah sesuatu yang langka dari sebuah perusahaan sehingga patut diapresiasi. Entah lantaran desakan publik atau tidak, Lawless sadar bahwa urusan membela penyintas kekerasan seksual harus selalu jadi prioritas.
Budaya Pemerkosaan vs. Keberanian Penyintas
Dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Gofar Hilman dibongkar oleh akun Nyelaras, @quweenjojo, yang mengaku dilecehkan Gofar dalam sebuah acara di Malang tiga tahun silam. Kala itu, Nyelaras ditarik dan dirangkul Gofar dari belakang lalu disentuh di bagian sensitifnya hingga ia merasa trauma.
Yang lebih mengerikan, di antara rimba penonton, hanya satu yang berusaha menyelamatkan Nyelaras dengan menariknya dari pelukan Gofar. Selebihnya malah sibuk menyoraki, “Yaaahhh”, bahkan ada yang berteriak, “Dienakin kok enggak mau!”
Baca juga: Fetish Bungkus Kain dan Fenomena Pelecehan Seksual Berkedok Riset
Komentar-komentar seperti ini adalah bukti mengakarnya budaya pemerkosaan (rape culture) di Indonesia. Secara sederhana, budaya pemerkosaan adalah lingkungan di mana kekerasan seksual mengakar dan dinormalisasi dalam media, budaya pop dan masyarakat. Hal ini sering kali ada, kendati tidak secara eksklusif, dalam masyarakat yang sangat patriarkal di mana dinamika gender melenceng, dengan perempuan sebagai subordinasi laki-laki, dan kurangnya kesetaraan gender secara umum.
Budaya pemerkosaan diejawantahkan dalam regulasi yang tidak berpihak; media yang senang mengobjektifikasi perempuan dan memperhalus pemerkosaan dengan diksi yang kurang berperspektif korban, seperti menggagahi, hubungan intim, rudapaksa; serta budaya menyalahkan korban atau melakukan reviktimisasi.
Yang disebut terakhir ini adalah indikator paling mudah untuk menunjukkan, betapa pemerkosaan telah menjadi budaya. Komentar dari Nikita Mirzani, sesama perempuan, adalah tindakan menginvalidasi korban. Dia tidak sadar ada relasi kuasa yang timpang antara pelaku-penyintas, sehingga butuh keberanian untuk bicara di depan publik (spill the tea). Pernyataan komika Coki adalah cara lain dalam mewajarkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan orang dengan kuasa besar.
Keberanian Nyelaras diapresiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mengingat kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah lama menjadi puncak gunung es karena penyintas enggan berbicara.
Baca juga: Pelecehan Seksual Kian Marak Termasuk dalam Situasi WFH
Saya berulang kali meliput penyintas kekerasan seksual dan melihat betapa mereka semakin tak berdaya ketika bercerita kepada orang-orang terdekat. Alih-alih dikuatkan atau didukung untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual ini, mereka justru disalahkan dan tak dipercaya sebagai korban, lantaran gaya berpakaian mereka yang kurang tertutup, memancing perhatian lawan jenis, atau direndahkan dengan sebutan-sebutan seperti, “Menolak rezeki”, “Kamu juga menikmati, kan?”, dst.
Saya juga kerap mendengar cerita dari teman-teman jurnalis perempuan yang terpaksa diam meskipun dilecehkan secara verbal oleh rekan-rekan sesama jurnalis. Yang paling parah, kekerasan seksual ini dilanggengkan lewat ancaman-ancaman pemiskinan (baca: pemecatan). Misalnya tampak dari kasus teman-teman kontributor perempuan di daerah yang dipaksa untuk bertemu narasumber cum pemberi modal sekaligus merelakan dirinya dirayu atau dilecehkan. Jika menolak, konsekuensi yang dihadapi adalah pemecatan. Mereka tak punya pilihan.
Tak hanya dilanggengkan lewat orang-orang biasa, para elite juga ikut mereviktimisasi penyintas lewat ucapan maupun regulasi yang mereka bikin. Di level regulasi, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum kunjung disahkan, meski berkali-kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengatur tindak pidana Melanggar Kesusilaan (Pasal 281 ayat (1) dan Pencabulan (Pasal 290,292, 293, 294 dan 296).
Dari semua contoh ini, bisa ditarik kesimpulan, karakter asli dari banyak pembuat keputusan di Indonesia lebih banyak melihat kekerasan seksual sebagai masalah yang harus ditangani perempuan, bahwa pemerkosaan hanya dapat dicegah oleh perempuan. Para sosiolog percaya, budaya pemerkosaan mengaitkan hubungan seks yang tidak konsensual dengan struktur budaya masyarakat yang sangat patriarkal, menyebabkan pemerkosaan diterima luas secara sosial dan institusional.
Apa Pilihannya Sekarang?
Sebelum kasus kekerasan seksual Gofar mencuat, ada beberapa pihak yang berbicara di depan umum soal pengalaman dilecehkan, dan sebagian pihak yang berasosiasi dengan pelaku memutuskan untuk memberikan tindakan tegas.
Kasus kekerasan seksual Gilang ‘Bungkus’ berkedok riset membuat pihak kampusnya, Universitas Airlangga, mengeluarkan ia seketika. Pun, dalam kasus telepon dan percakapan mengajak berhubungan seks dari Ibrahim Malik, alumni Universitas Islam Indonesia, pihak kampus juga mencabut gelar mahasiswa berprestasi yang diraihnya pada 2015, menyusul pembentukan tim investigasi dan laporan-laporan yang masuk ke LBH Yogyakarta. Tak selesai di sana, Komunitas Peduli Perempuan berinisiatif memulai petisi di Change.org kepada Direktur Australia Awards untuk mencabut beasiswa S2 di University of Melbourne yang diberikan kepada Ibrahim.
Baca juga: Kekerasan Seksual di Rumah Sendiri, Mengerikan Tapi Didiamkan
Ada dua hal yang bisa saya catat dari beberapa contoh tersebut. Pertama, gerakan mengungkap kasus kekerasan seksual tak bisa diremehkan dan bisa berdampak serius bagi upaya memutus perbuatan jahat itu. Kedua, gerakan memutus kekerasan seksual tidak akan efektif jika tidak didukung oleh banyak elemen, termasuk oleh mereka yang punya kuasa. Untuk poin kedua ini saya kira butuh keberanian dan kesadaran untuk mengarusutamakan kesetaraan gender, demi mencapainya.
Kenapa? Sebab kita masih punya catatan buram karena terkendala faktor agama, budaya, dan regulasi yang tidak memberi tempat untuk bertumbuh suburnya gerakan itu. Di Indonesia, kebanyakan perempuan akan memilih diam atau terpaksa (baca: dipaksa) diam ketika mengalami kekerasan seksual.
Dalam kasus @quweenjojo misalnya, ia mulanya enggan spill the tea karena pengalaman bercerita dengan temannya membuat ia mengalami trauma kedua. Sudah jadi korban, ia juga masih disalahkan. “Lu terlalu hot sih,” “Bukannya dia punya alesan sampe bisa ngelakuin itu?” Jawaban-jawaban itu pula yang membuat ia memilih menahan diri sampai akhirnya berani membongkarnya di Twitter baru-baru ini.
Kita tentu masih ingat kasus Agni, mahasiswa UGM yang mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya. Meskipun ia berulang kali mengatakan tidak akan pernah menyerah memperjuangkan kasusnya, tapi sistem di kampus UGM telah memaksanya untuk diam. Ujung-ujungnya, kasus yang membetot perhatian media nasional itu pun menghilang dari peredaran. Agni mengendur saat diminta menyelesaikan lewat jalur kekeluargaan.
Pada akhirnya buat saya, semoga ada sistem yang lebih kondusif dan adil agar para penyintas lebih berani dan terbuka dalam mengungkapkan kasus mereka. Pun, semoga apa yang dilakukan Lawless bisa menjadi preseden baik agar bisnis, kolega, dan teman para pelaku kekerasan seksual bersikap tegas menghukum mereka, bukan malah membela atau tidak bersikap.
Ilustrasi oleh Karina Tungari




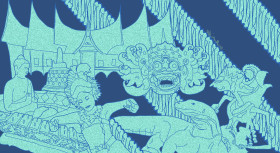


Comments