
“Kok sendirian? Agus mana?” tanya Ibu.
“Nanti nyusul, Bu. Masih ada kerjaan,” jawabku meraih tangan Ibu, salim.
“Lebaran gini kok ya masih kerja?”
“Namanya juga tentara, Bu. Ndak ada liburnya”.
Berkumpul di Kayu Manis pada hari pertama Lebaran adalah suatu kewajiban yang tidak bisa kami tinggalkan. Aku, Indri, dan Utari, seenggan apapun, kami tidak pernah bisa alpa dari keharusan yang satu ini. Bertemu dengan Bapak dan Ibu, menunggu keputusan siapa yang berhak menerima piala bergilir dengan titel ‘Anak yang Paling Mengecewakan’.
“Adik-adikmu itu lho, memang ndak pernah bisa dewasa,” bisik Ibu padaku, memandang kecewa pada Utari yang sedang menunduk diteriaki Bapak di teras belakang rumah.
“Perempuan itu ya di mana-mana harus bisa sabar. Harus nrimo. Kalau mbrontak terus, ndak bisa diatur, ya kayak gini ini kejadiannya. Laki-laki itu ya memang begitu kelakuannya. Kita yang harus bisa ngerti”.
Aku tidak bereaksi.
“Ibu sama Bapak itu sudah ndak punya muka lagi. Punya anak perempuan tiga, yang dua kok ya cerai,” Ibu berkata sambil mengelus-elus dadanya. Sesak karena kecewa. “Untung kamu sama Agus baik-baik, ya Rat. Dijaga suaminya. Jangan kebanyakan nuntut kayak adik-adikmu. Jadi istri itu harus manut. Nurut sama suamimu. Kuncinya itu”.
Aku mengangguk, memamerkan senyum palsu terlatihku.
“Dulu itu memang Ibu cuma sreg-nya sama Agus. Tentara, kerjanya jelas, kalau ngomong tegas, ndak plintat plintut, ganteng lagi,” kenang Ibu.
Terbersit di kepalaku bayangan Mas Agus muda, datang ke rumah dengan seragam prajuritnya. Menghabiskan waktu pelesirnya untuk menyeleksi kembang-kembang di Kayu Manis, berkedok mengunjungi Bude Karso, kerabat jauhnya.
“Untung dulu kamu nurut, dengerin Ibu pas dilamar Agus,” kata Ibu. “Ndak kayak si Indri yang ngotot minta kuliah dulu segala. Lah, sekolah tinggi-tinggi jadi Sarjana Hukum juga ujung-ujungnya suaminya selingkuh sama pembantu. Bikin malu aja”.
“Sekarang kamu tho yang enak. Punya suami Kolonel, bergaulnya sama ibu-ibu Jenderal, ibu-ibu pejabat,” sambung Ibu.
Aku tersenyum. Tidak menjawab. Tidak mengiyakan ataupun membantah.
Indri, adikku, si tengah, sudah dari enam tahun yang lalu bercerai dari suaminya. Konon ia terlalu sibuk bekerja, sering ke luar kota, sehingga suaminya sering main gila dengan pembantu rumah tangganya. Saat ia pulang ke rumah lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, terbongkarlah skandal perselingkuhan itu, dan Indri pun tanpa banyak pertimbangan langsung minta cerai. Sekarang ia hidup menjanda bersama dengan Indira, putri kesayangannya.
Aku ingat Bapak dan Ibu begitu terkejut ketika Indri pertama kali memberi tahu rencana perceraiannya. Sepertinya kata ‘perceraian’ tidak pernah sekalipun terbersit dan mampir di benak mereka.
“Pancene lanang gemblung!” dulu amarah Bapak masih lebih tertuju ke suami Indri.
“Kamu yakin, Ndri? Nanti kamu tinggal di mana? Siapa yang bakal menafkahi anakmu?” tanya ibu nelangsa, mungkin sedikit menahan tangis.
“Aku bisa, Bu, tinggal sendiri sama Indira. Aku sanggup membesarkan Indira sendirian!” jawab Indri tegas.
Indri bisa tegas karena dia memang mampu. Karirnya sebagai legal counsel di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar di ibukota cukup memberinya keyakinan dan rasa aman untuk bisa bertahan hidup tanpa sokongan laki-laki manapun. Beruntungnya dia.
“Eh, itu suamimu datang. Sana kamu sambut!” perintah ibu, yang tentunya langsung kuiyakan.
“Mas,” aku memberi salam, sambil mencium tangan suamiku.
Mas Agus memberikan tangannya untuk kucium, tapi tidak memberikan tanggapan sedikitpun. Memandangku saja pun dia sepertinya enggan.
“Ibu, bagaimana kabarnya?” tanya Mas Agus, meninggalkanku menjinjing tasnya, bergerak ke arah ibu, memberikan sungkem, wajah manis, dan perawakan gagahnya. “Maaf lahir batin, nggih, Bu. Sepurane sing katah.”
Ibu tersenyum menyambut menantu kesayangannya. Direngkuhnya tubuh suamiku, diberinya tepukan penuh kasih sayang, “Ibu sehat. Kamu juga harus jaga kesehatan, jangan kerja terus!”
Melihat Agus datang, Bapak yang dari tadi sibuk memberikan wejangan, lengkap dengan sindiran, keluhan, dan bentakan kepada Utari yang Lebaran tahun ini sepertinya sudah hampir pasti berhasil mencuri gelar bergilir ‘Anak yang Paling mengecewakan’, menghentikan aktivitasnya untuk menyambut suamiku.
“Baru datang, kamu Gus?” tanya Bapak sambil memberikan tangannya untuk disambut dan dicium, sebuah gestur penghormatan dari anak ke orang tuanya.
“Nyari apa, tho, kamu Gus? Memangnya uang bisa dibawa mati?” tanya Bapak, dengan celaan penuh kasihnya. Semua orang, termasuk Mas Agus, terutama Mas Agus, tahu betapa Bapak dan Ibu sangat menyayanginya.
“Tar, makanya dulu jangan ngeyel. Jangan pilih-pilih, jual mahal, eh dapetnya malah kayak suamimu,” Mas Agus menggoda Utari.
“Mas Agus ini ngomong apa sih?” balas Utari risih.
Dari dulu aku tahu, meski seluruh dunia telah berhasil diperdayanya, kalau sebenarnya kembang Kayu Manis yang ingin Mas Agus petik, bukanlah aku, melainkan Utari. Aku tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Kututup mataku rapat-rapat, meskipun ngilu di hati ini tidak bisa dibohongi.
Utari masih terlalu kecil ketika Mas Agus sering datang ke rumah dulu. Ia masih SMP. Bapak yang sudah terlalu gembira karena mengira Mas Agus tertarik padaku, anak perempuannya yang sudah siap dipanen, langsung sering menjodoh-jodohkan aku dan Mas Agus. “Sudah jangan lama-lama, langsung nikah saja!”
Entah karena tidak enak, tidak berani membantah bapak, tidak bisa menolak, atau alasan lain yang tidak kumengerti, Mas Agus pun kemudian benar-benar datang bersama keluarganya untuk meminangku. Tapi aku tahu pasti, hati dan cintanya tidak pernah untukku. Sebelum dan selama pernikahan kami berlangsung, hingga saat ini.
Meskipun rasa cemburuku pada Utari tidak pernah mati, tapi aku bersyukur bukan dia yang dulu dipinang Mas Agus. Bukan adik bungsuku yang harus merasakan apa yang aku rasakan. Cukup aku saja.
“Dodit itu kasar, suka membentak-bentak aku,” jawab Utari ketika Bapak kembali bertanya kenapa ia ingin menceraikan suaminya.
Dibentak katamu, Tar? Beruntungnya kamu. Kulirik memar di pergelangan bagian dalam tanganku. Kuping dan hatiku sudah kebal, mungkin sebentar lagi tubuhku juga mati rasa karena sudah terbiasa dengan semua siksa sakit ini.
“Nafkah dari Dodit untuk aku dan Dinda selalu tidak cukup. Uangnya selalu habis untuk hobi fotografinya yang tidak jelas itu,” jawab Utari.
Nafkah dari suamimu tidak cukup katamu, Tar? Beruntungnya kamu. Kuingat bagaimana pagi ini pembantuku memberiku uang ongkos untuk bisa pergi ke sini. Aku memang masih menggenggam titel istri, tapi itu hanya sebuah titel kosong, aku tidak punya sedikit pun kuasa di rumahku sendiri. Sudah lima tahun ini, aku hidup dari uang jatah. Suamiku lebih mempercayakan pengaturan pengeluaran rumah tangga kami kepada Mbok Nah, pembantu kami.
“Dodit tidak bisa apa-apa, semua urusan harus aku yang mengerjakan sendiri,” jawab Utari lagi.
Suamimu tidak bisa apa-apa katamu, Tar? Beruntungnya kamu. Kukutuk nasibku karena bersuamikan laki-laki yang serba bisa. Bisa memukul, bisa menjambak, bisa menampar, bisa mendorong, bisa menendang, bisa melempar barang-barang, bisa mengancam, bisa mengurung, bisa menjadikan hidupku seperti neraka. Hanya satu yang ia tidak bisa, menerima dan menghargaiku sebagai istrinya.
“Beri nasihat ke adik-adikmu ini Rat, bagaimana caranya jadi istri yang baik?” Pertanyaan Bapak membuatku yang sedari tadi diam tersorot.
Mau jawaban jujur? Diam saja. Pasrah. Jangan buat suamimu semakin marah. Tahan rasa sakitmu, nanti juga sembuh sendiri. Matikan indra-indramu, bunuh yang namanya perasaan dan emosi. Istri tidak butuh itu. Yang penting diam. Pasrah. Nurut. Kalau suamimu lelah menyiksamu, penderitaanmu juga akan selesai. Tapi jangan lupa siap-siap untuk siksaan esok hari.
Uang jatah dari pembantumu, harus kamu hemat, supaya tetap bisa beli make up dan baju yang layak. Supaya di depan ibu-ibu Jenderal, di depan tetangga, dan jika harus bertemu keluarga seperti sekarang ini, kamu tetap bisa terlihat cantik, sehat, dan berwibawa. Istri yang baik harus bisa menutupi aib dan menjaga nama baik suami.
Jika tidak tahan atau ingin kabur, ingat, kamu itu tidak bisa apa-apa. Cuma lulusan SMA, tidak sempat kuliah karena sudah keburu dilamar dan menikah, bisa kerja apa kalau minta cerai? Bisa menafkahi diri sendiri? Nggak malu jadi parasit keluarga? Mau jadi apa? Mimpi tidak punya, ijazah tidak ada, pengalaman kerja nihil. Istri yang baik itu istri yang setia dan bisa bertahan terhadap kesialannya.
“Yang penting saling pengertian aja,” jawabku singkat, ingin segera memindahkan lampu sorot yang menyilaukan dari arahku, mengarahkannya kepada siapa saja selain aku.
Hei, harusnya Lebaran tahun ini aku dapat kartu bebas sorotan. Harusnya aku dapat imunitas dari semua penghakiman ini. Aku sudah jadi istri yang baik, menerima semua perlakuan biadab suamiku, si menantu kesayangan ini.
Aku juga sudah jadi anak yang baik, satu-satunya anak perempuan yang menurut ketika disuruh menikah, setuju ketika diminta berhenti sekolah, dan bertahan dalam pernikahan sehingga tidak ada yang bisa menghakimi Bapak dan Ibu, “Itu kok anaknya cerai semua”.
“Nah ya gitu, kalian harus bisa kayak Mbakyu-mu,” ujar Bapak.
Aku tersenyum, merasa menang. Lebaran tahun ini, aku berhasil lolos dari label anak yang paling mengecewakan. Meskipun harus membayarnya dengan sangat mahal.
“Nah, sekarang Rat, Gus, kapan kalian mau punya anak? Masa kalah sama adik-adikmu? Sudah menikah lama kok ya nggak punya-punya anak?” tanya Bapak.
“Iya, Ibu dari dulu pengen nimang cucu dari kamu. Kok ya, nggak dikasih-kasih, tho?” sambung Ibu. “Cuma kamu anak Ibu yang belum ngasih Ibu cucu”.
Aku tercekat. Tak bisa menjawab.
Jadi, Lebaran tahun ini, siapa pemenang gelar ‘Anak yang Paling Mengecewakan’?
Aqmarina Andira adalah desainer konten dan presentasi di sebuah perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Ia gemar membaca dan menulis, ikut mendirikan pusat penulisan kreatif untuk anak muda, dan aktif terlibat dalam komunitas pencinta buku dan sastra.







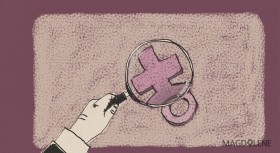
Comments