Drama Jenis Kelamin Lucinta Luna yang Buat Polisi Bingung: Dulu Muhammad Fatah, Kini Ayluna Putri
Pemuda Asal Blitar Gagal Perkosa Tante-tante Karena Ditarik Anunya
4 Potret Seksi Sulli eks f(x), Idola Korea yang Diduga Tewas Bunuh Diri
Judul-judul artikel misoginis semacam di atas adalah alasan mengapa Magdalene melakukan kampanye #WTFMedia lewat akun Instagram. Judul-judul berikut artikel semacam ini adalah cerminan dari pemberitaan media saat ini, yang pertumbuhannya meningkat seiring perkembangan teknologi, tapi tidak diikuti dengan perbaikan kualitas.
Pemilihan judul dan angle kebanyakan masih terlalu sensasional, dan dalam pemberitaan mengenai perempuan, masih banyak objektifikasi seksual sampai penyalahan pada korban kekerasan seksual. Ditambah lagi, arus informasi yang semakin tidak terkendali membuat masyarakat rentan terjerumus dalam berita hoaks, seperti informasi mengenai virus Corona.
Baca juga: Riset: Pemahaman Jurnalis Atas Isu Kekerasan Seksual Sangat Minim
Media bisa sangat cepat menayangkan berita, bahkan dalam jumlah banyak dalam satu waktu. Tapi tidak jarang ketika kita baca, berita satu dengan berita lainnya mengandung konten yang serupa, bahkan bisa persis sama.
Lalu, apa penyebab pemberitaan media ini begitu sensasional? Bagaimana cara kerja sebuah media dalam memproduksi berita? Bagaimana situasi pekerja dalam industri media? Dan apa yang dapat pembaca lakukan dalam menyikapi arus informasi yang deras ini?
Untuk membahas isu-isu ini, dan dalam rangka Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, Magdalene melakukan diskusi interaktif MadgeTalk di Twitter bersama Ignatius Haryanto (@ignharyanto), peneliti media dan salah seorang pendiri Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), serta pengajar jurnalistik. Berikut adalah hasilnya.
Magdalene: Sekarang ini, ada banyak sekali media daring, mungkin karena regulasi penerbitan media lebih longgar saat ini. Menurut Mas Hary, apa dampak positif dan negatif dari suburnya industri media daring sekarang?
Kemunculan media yang lebih banyak saat ini adalah bentuk dari demokratisasi media, di mana media tak lagi diatur dari sisi jumlahnya, seperti pada jaman Orde Baru dengan politik perizinannya. Namun, di sisi lain kuantitas yang besar ini tak sejalan dengan profesionalitas yang harusnya ditunjukkan media-media ini.
Positifnya, kita sekarang bisa memiliki pilihan yang sangat banyak media yang mau kita konsumsi. Hampir semua ada. Bahkan media feminis seperti Magdalene pun bisa tumbuh karena iklim ini. Namun, literasi media dari masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat sulit membedakan mana media yang kredibel dan mana yang tidak.
Dewan Pers menyebutkan bahwa ada 43 ribu media yang ada saat ini, tapi yang diverifikasi oleh Dewan Pers paling hanya 300-an. Tak sampai 1 persen. Jadi masih banyak masalah di sini. Banyak pihak yang mendirikan media dengan motif yang beragam, namun banyak dari media ini beroperasi secara tidak profesional.
Pemberitaan di media tidak membaik, kalau tidak bisa dibilang memburuk. Banyak berita yang sensasional, dilebih-lebihkan, di luar konteks pemberitaan, bahkan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Bagaimana pendapat Mas Hary soal hal ini?
Dalam situasi sekarang, di mana jadi sangat bebas, memang kita melihat media yang jadi sangat beragam. Mulai dari media yang serius, punya ideologi jelas, sampai media yang dipakai untuk melakukan pemerasan, atau media yang hanya dipakai untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
Inilah konsekuensi yang kita hadapi sekarang. Yang jadi masalah adalah ketika media itu melakukan pelanggaran kode etik, siapa yang mengawasi, mengingat Dewan Pers hanya menunggu pengaduan dari masyarakat dulu baru bergerak.
Dari sisi Dewan Pers, mereka mengupayakan untuk melakukan verifikasi perusahaan pers tersebut. Tapi ini juga bukan pekerjaan mudah apa lagi jika dilakukan secara manual.
Di sini menurut saya jadi penting untuk adanya program literasi media di sekolah-sekolah, kalau perlu masuk kurikulum. Program ini bukan cuma soal mengajarkan orang untuk menggunakan suatu media, tetapi juga terutama bagaimana menjadi bijak dalam konsumsi media dam bersikap kritis terhadap isi media.
Untuk media yang melakukan pelanggaran kode etik, bisa saja anggota masyarakat melakukan pengaduan kepada Dewan Pers. Misalnya Magdalene punya perhatian soal perempuan, silakan dikumpulkan berita-berita dan media-media yang merendahkan perempuan. Adukan hal tersebut secara reguler ke Dewan Pers. Magdalene juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain atau merekrut sukarelawan untuk melakukan ini.
Bagaimana dengan judul berita yang click-bait? Sejauh mana pemakaian judul click bait ini masih ok-ok saja?
Click bait itu menyebalkan karena sering kali menipu. Apa yang tertera dalam judul tidak selalu sama dengan isinya. Memang click bait itu strategi di tengah persaingan informasi yang overloaded ini, tetapi pembaca akan kesal dengan cara tampilan media online yang “menipu” ini. Mungkin lama kelamaan pembaca akan meninggalkan media seperti ini. Dilihat secara etik, judul seperti ini bisa dilihat sebagai berita bohong atau sensasional yang merugikan bagi pembaca.
Jadi click bait itu tidak oke-oke saja. Itu pekerjaan menipu... Memang saat ini media dihadapi dengan tantangan berhadapan dengan mesin pencari sehingga beritanya harus bisa ditemukan di awal pencarian. Ada rumusnya, tapi menurut saya ini praktik manipulatif.
Baca juga: Perempuan dan LGBT di Media Online: Direndahkan dan Dilecehkan Demi Konten
Sering kali berita persis sama muncul di sejumlah media. Sepertinya reporter yang meliput di lapangan saling menyalin isi berita/press release sehingga isi berita menjadi seragam. Bagaimana pendapat Mas Hary mengenai hal ini?
Puncak dari semua masalah ini adalah tuntutan dari media-media online dengan kuota penulisan berita yang mustahil kepada para reporter. Angka tertinggi yang saya pernah dengar adalah reporter diminta menulis 20 berita per hari di suatu media online. Ini eksploitasi dan manipulasi.
Eksploitasi di satu sisi atas jumlah berita yang dituntut. Dalam jam kerja, katakanlah 10 jam, itu artinya setiap 30 menit seorang reporter harus menulis berita. Mau dari laporan di lapangan, menyadur, dll. Kalau seperti itu tuntutannya, kapan reporter bisa istirahat, bisa makan.
Eksploitasi seperti ini tak pernah dibicarakan terbuka dan juga karena tak ada serikat kerja, serikat buruh yang menyoal masalah ini. Padahal buat saya ini eksploitasi. Nanti kalau lihat berapa honor yang didapat, saya sedih karena itu artinya satu berita bisa cuma dihargai Rp 10.000 saja.
Ini manipulasi karena praktik di lapangan yang terjadi adalah tukar menukar berita dari para reporter. Perusahaan mengakali mereka, sementara reporter di lapangan mengakali perusahaan. Sehingga kalau kita lihat beberapa berita dari sejumlah media bisa sama persis. Kembali lagi ke tuntutan kuantitas berita yang harus disetor.
Saya kira di sini ada salah kaprah kalau media online itu identik menghasilkan ratusan hingga ribuan berita per hari karena kalau dicek lebih jauh dari sekian ribu itu, keterbacaannya berapa persen?
Ada penelitian di Amerika Serikat yang menganjurkan menurunkan jumlah berita pendek-pendek lalu diganti dengan berita yang lebih dalam dengan jumlah narasumber yang banyak, analisis yang dalam, dan cara penulisan yang memikat. Model terakhir bisa jadi akan dibaca karena beritanya lebih lengkap. Bukan potongan-potongan yang tidak lengkap.
Baca juga: Media dan Pemerintah Lawan Hoaks Lewat Jurnalisme Data
Apa yang dapat kita lakukan dalam menyikapi berita yang sensasional?
Berita sensasional ya sudah tinggalkan saja. Kalau masyarakat Indonesia makin melek media dan makin kritis, kita hanya perlu melihat informasi yang relevan dengan hidup kita, dan kita yang menentukan apa yang mau kita baca.
Saya sendiri bergabung dalam puluhan grup WhatsApp, dan sebagian besar tak selalu saya baca karena saya tak merasa relevan. Kalau tak relevan, saya rajin clear chat WhatsApp Group tertentu.
Demikian halnya pada berita di media online. Saya lebih memilih dianggap kudet (kurang update) daripada saya harus memperhatikan semua informasi yang tidak relevan untuk saya. Saya lebih memilih menggunakan waktu saya untuk informasi yang memang saya butuhkan, dan itu saya yang menentukan.
Sekarang hoaks semakin sulit dideteksi. Bagaimana literasi informasi yang seharusnya kita gunakan dalam arus banjir informasi seperti ini?
Literasi media jadi makin mendesak. Tadinya saya pikir selesai Pemilu 2019, hoaks akan berkurang. Ternyata tidak. Beberapa minggu lalu, kasus Corona muncul. Kemenkominfo mengatakan menemukan 56 jenis hoaks untuk isu Corona ini. Gila ya?
Jadi memang banyak pihak harus bergerak untuk makin mencerdaskan masyarakat kita. Ada kelompok seperti MAFINDO yang bekerja mengklarifikasi macam-macam hoaks ini. Sejumlah media punya unit cek fakta dan lain-lain. Menurut saya, penyebar hoaks harus dihukum. Pemerintah sudah lakukan ini.
Literasi media di sekolah harus masuk ke kurikulum. Sementara itu, kepada masyarakat umum harus terus diingatkan untuk tidak cepat percaya dengan info-info yang sensasional. Masyarakat perlu diajarkan untuk bisa pilih media yang kredibel atau tidak, dan juga tidak buru-buru sharing atau komentar jika suatu informasi belum diverifikasi.
Terkait perspektif gender, sepertinya hal ini masih sangat kurang di media. Banyak sekali berita yang masih seksis, diskriminatif, misoginis, terutama kalau dalam kasus kekerasan seksual atau yang menyangkut kelompok minoritas seksual. Mengapa ini masih terus terjadi?
Saya sedih kalau membaca berita-berita yang merendahkan perempuan, kelompok minoritas, dan kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender). Terlalu sedikit media dan jurnalis yang punya pemahaman baik atas masalah-masalah ini. Kalaupun ada individu jurnalis yang paham dan sadar, ada struktur industri yang juga menghalanginya.
Berita-berita yang justru melecehkan dianggap viral. Misalnya sosok seperti Lucinta Luna yang di-bully habis dimana-mana, dan saat ia mengalami kasus hukum, itu pun masih diolok-olok. Memang perlu lebih banyak pihak yang speak up masalah ini. Eh, btw, udah nonton film Bombshell belom?
Film Bombshell diputar di Jakarta beberapa waktu lalu. Film ini menarik karena akhir dari kisah tersebut menggambarkan bahwa si peleceh perempuan (banyak korbannya) harus membayar mahal tindakan yang telah ia lakukan. Harusnya ini jadi pesan keras kepada pihak mana pun.
Banyak jurnalis, baik reporter dan redaktur perlu semakin sensitif atas isu-isu seperti ini. Dan jurnalis pria pun harus tahu perspektif gender. Jadi ini bukan cuma persoalan jurnalis perempuan saja loh.
Untuk kalangan minoritas lainnya, media harusnya juga memuat sisi-sisi dari mereka yang tak bisa bersuara. Saya pernah tanda tangan protes kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang orang-orang yang terkait LGBT tampil di layar kaca.
Saya dan kawan-kawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pernah memberi penghargaan Suardi Tasrif kepada kelompok LGBT dan kelompok ‘65. Saya pun dituding pro LGBT. So what? Mereka adalah manusia dan harus diperlakukan sebagaimana manusia lainnya, bukan didiskriminasi.
Media harus berani mengambil sikap untuk hal-hal seperti ini karena memang hal itu yang harus dilakukan atas kesadaran pada demokrasi dan penghargaan pada kemanusiaan.
Literasi media harus masuk ke kurikulum sekolah. Masyarakat umum harus terus diingatkan untuk tidak cepat percaya dengan info-info yang sensasional. Masyarakat perlu diajarkan untuk bisa memilih media yang kredibel atau tidak, dan juga tidak buru-buru sharing atau komentar.
Sudah ada inisiatif agar awak media/media melek isu gender, tapi beritanya masih belum membaik. Apa yang menjadi kendala dalam menerapkan kesadaran/sensitivitas gender di institusi-institusi media?
Seperti yang saya katakan di atas, kita perlu lebih banyak pihak yang terus mengangkat masalah ini. Jurnalis pribadi tidak cukup jika struktur medianya juga tidak peka. Harus ada makin banyak perempuan dalam media mengambil posisi-posisi menentukan sehingga policy redaksi bisa berubah.
Buat mereka yang berada di luar media, jangan bosan-bosan mencela media-media yang menunjukkan sikap tidak peka pada kelompok perempuan, kelompok minoritas, dan lain-lain. Dengan mempermalukan, atau mendekati sebagai teman, mudah-mudahan ini akan membantu media jadi berubah. Terus bersuara.
Bagaimana peran Dewan Pers sejauh ini dalam menangani media yang melanggar kode etik? Apakah penanganan yang dilakukan sudah cukup efektif? Lalu bagaimana jika ada masyarakat atau narasumber yang dirugikan?
Seperti saya sampaikan di atas, Dewan Pers hanya menunggu pengaduan dari masyarakat. Terkadang pers membuat imbauan, membuat pedoman pemberitaan, tapi kalau pengawasan tak dilakukan, lemah juga. Tidak efektif juga.
Dalam hal ini, bisa lakukan pengaduan tematik kepada Dewan Pers soal bias gender dan minoritas dari pers. Umumkan secara terbuka media-media yang tidak peka, buat diskusi yang melibatkan Dewan Pers. Di luar mekanisme Dewan Pers, ya permalukan saja media-media yang langgar itu. Sebut saja media yang sudah berkali-kali melanggar.
Jurnalis sepatutnya punya independensi dalam menulis berita, namun dalam praktiknya sulit dilakukan. Apa cara yang dapat dilakukan oleh para jurnalis agar tetap independen dan tidak takut memberitakan kebenaran atau cara pandang alternatif pada publik? Misalnya, di tengah situasi masyarakat yang banyak mengecam LGBT, bagaimana media yang membela hak-hak LGBT bisa terus bertahan dan memberi ruang bagi mereka bersuara?
Seperti saya katakan, jurnalis juga punya keterbatasan karena ada struktur media di atasnya yang membuat mereka tidak berdaya. Dengan memanfaatkan media sosial, isu soal LGBT bisa terus disuarakan. Bukan cuma oleh jurnalis, tapi juga pihak-pihak lain.
Intinya adalah penghormatan atas hak asasi seseorang, dan kita perlu tampilkan bahwa LGBT tidak melulu urusan seksualitas tapi juga ada banyak aspek sosial lain yang bisa dikedepankan. Mereka yang pandai menulis bisa bersuara lewat media sosial ataupun media yang sepaham.
Dari film Garin Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku, kita diingatkan bahwa budaya di Nusantara ada beberapa yang mengandung unsur LGBT dan selama ini hal itu tak dipersoalkan. Ada koeksistensi dengan budaya lokal dan modernisasi.




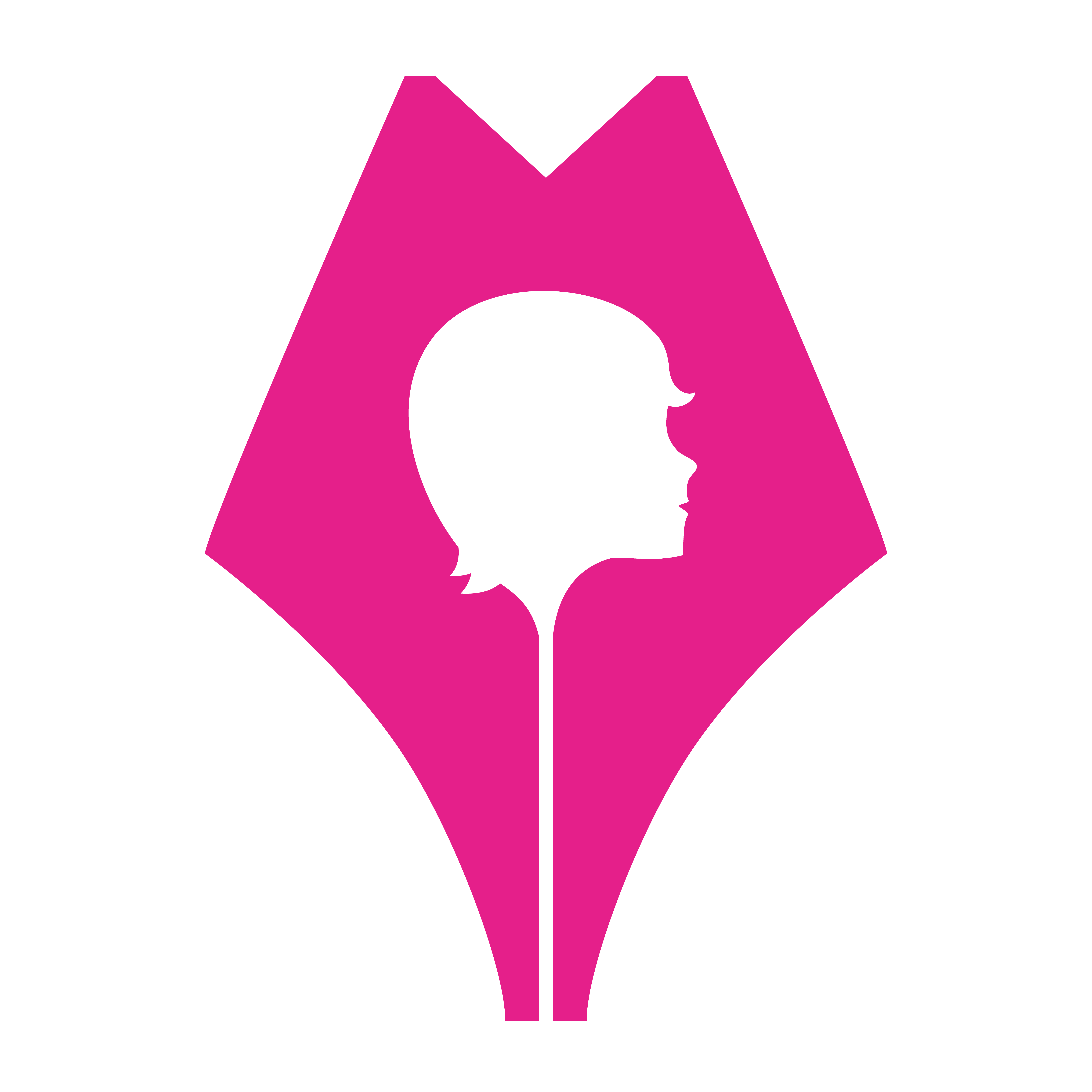



Comments