Mainkan newsgame selengkapnya di sini, dan selami langsung pengalaman menarik mereka yang nikah muda
Berapa usia terbaik untuk menikah? Tak ada standar jawaban yang sama. Journal of Social and Personal Relationship (2012) menyebut angka 25 adalah batas ideal. Pertimbangannya karena orang berusia 25 ke atas dinilai sudah memiliki kematangan mental yang cukup. Di Amerika Serikat (AS), menurut catatan Biro Sensus setempat pada 2013, usia 27 tahun jadi pilihan terbanyak perempuan, sedangkan laki-laki 29 tahun. Sementara, Pew Research Center pada 2011 menyebutkan, orang yang menikah sebelum berusia 23 tahun lebih mungkin untuk bercerai. Terakhir Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dengan dalih memperkecil risiko kehamilan, menyarankan perempuan untuk menikah hanya jika ia sudah berusia minimal 21 tahun.
Riset dan survei di atas mayoritas memang didasarkan atas sejumlah pertimbangan, mulai dari psikologis, keuangan, hingga kesiapan organ reproduksi. Namun, sebagian alasan jamak mengapa orang memilih menikah, lebih banyak didorong oleh motif yang berbeda. Alika, misalnya, memilih nikah di usia 22 tahun karena ingin memenuhi fantasi ala Disney-nya bahwa pernikahan adalah tentang bagaimana perempuan menunggu pangeran menyelamatkan ia dari nestapa dan membahagiakannya. Sementara, Dinda, memutuskan menikah karena mengalami kehamilan yang tak diinginkan (KTD). Untuk Viony, pernikahan adalah cara yang paling tepat dalam memantapkan jalan hijrahnya sekaligus menyempurnakan agama.
Baik Alika, Dinda, maupun Viony punya dua persamaan. Pertama, mereka mengesampingkan alasan penting soal kesiapan mental dan finansial—kedua alasan yang jadi faktor terbanyak penyebab perceraian, versi riset Shelby B. Scott, dkk. bertajuk “Reasons for Divorce and Recollections of Premarital Intervention: Implications for Improving Relationship Education” (2013). Kedua, mereka menikah di usia muda. Pernikahan muda sendiri jika mengacu pada pemilahan Badan Pusat Statistik adalah mereka yang memilih menikah di usia 19-24 tahun.
Ketiga perempuan ini cuma segelintir dari jutaan pelaku nikah muda di Indonesia. Kendati angka versi BPS menunjukkan angka pernikahan muda cenderung stagnan, sekitar 60% dari rentang 2015-2018, tapi realitasnya, pernikahan muda cenderung diglorifikasi oleh sebagian kalangan beberapa tahun belakangan ini. Gerakan nikah muda, seperti @indonesiatanpapacaranid, @hijrahdaripacaran, @beraninikahtakutpacaran dengan sengaja mempromosikan kampanye nikah muda. Alasannya nyaris seragam, yakni menghindari zina, menyempurnakan agama, atau mencari istri yang bisa melayani kebutuhan sehari-hari. Pacaran di sisi lain dianggap sebagai tindakan sia-sia, merusak kehormatan dan masa depan, sehingga pernikahan muda dianggap sebagai solusi tunggal.
Celakanya, kampanye nikah muda tak berhenti di sini, karena makin banyak pesohor yang membantu pesan-pesan itu teramplifikasi di ruang-ruang percakapan kita. Pernikahan artis Dinda Haw dan Rey Mbayang pada Juli 2020 misalnya, jadi buah bibir media, dibingkai sebagai fenomena yang layak ditiru, dan disebut-sebut sebagai relationship goal. Pernikahan influencer agama Taqy Malik, Muhammad Alvin Vaiz dipuji-puji sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya hidup anak muda yang suka gonta-ganti pacar, takut berkomitmen, dan tak siap bertanggung jawab.
Magdalene berupaya merekam keberagaman pandangan dan pengalaman terkait menikah muda. Kami mewawancarai belasan pelaku nikah muda, berusia 18-24 tahun. Rentang usia ini di samping mengacu pada batasan yang dibuat BPS, juga untuk membedakannya dari fokus ke pernikahan anak, yang punya dimensi isu berbeda.
Baca juga: Hamil di Luar Nikah, Pernikahan Muda Bukan Solusi Tunggal
Dari wawancara mendalam dengan para narasumber, kami menemukan ada perempuan yang hidup bahagia dengan pernikahan muda yang ia pilih, tapi ada yang berujung dengan konflik rumah tangga dan perceraian. Semua cerita ini sengaja kami suguhkan untuk memperlihatkan, pengalaman individu itu unik dan keberhasilan pernikahan muda sangat bergantung oleh sejumlah faktor, termasuk kualitas pendidikan, perspektif gender yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Kami sendiri berupaya senetral mungkin dalam mendengarkan dan menyebarkan cerita para perempuan ini. Tak ada niat menghakimi pilihan mereka, terlepas dari bagaimanapun kondisi rumah tangganya setelah memutuskan menikah muda.
Para sobat Magdalene bisa menyimak tujuh cerita pelaku nikah muda yang sengaja dikemas dalam format news game. Tujuannya agar pembaca bisa turut memahami motivasi dan menyelami pengalaman para perempuan yang menjalani pernikahan muda.
Motivasi Menikah Muda
Pernikahan kerap jadi salah satu indikator kedewasaan atau tujuan hidup. Di AS, menurut survei Pew Research 2011, memiliki pernikahan yang sukses adalah salah satu hal terpenting dalam hidup bagi 36% orang dewasa, 48% bilang itu penting tapi bukan paling penting. Menurut Brides, orang memilih cepat menikah demi alasan merayakan cinta, mencari rekan hidup agar tak kesepian, mendukung kesehatan finansial, hingga siap membangun keluarga baru.
Di Indonesia, menikah muda juga didorong oleh berbagai faktor. Dari pengalaman para perempuan yang dicatat oleh Magdalene, ada dua faktor yang memengaruhi pelaku nikah muda: Internal dan eksternal. Faktor internal umumnya berhubungan dengan keputusan yang dibuat sendiri dengan sadar, tanpa ada tekanan luar.
Masalahnya, keputusan ini tak pernah lahir dari ruang hampa, melainkan bergantung pada pendidikan, bacaan, keyakinan, pengalaman pribadi, dan lainnya. Mereka yang hidup di tengah ajaran agama konservatif, bisa saja melihat pernikahan muda sebagai jalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, trauma kanak-kanak, atau korban perisakan, punya kecenderungan untuk menjauh cepat-cepat dari keluarga, termasuk memilih nikah muda cuma agar bisa “kabur”.
Faktor eksternal adalah semua faktor dari luar dirinya yang mendorong seseorang untuk menikah muda. Contohnya, pengaruh influencer yang ajek mempromosikan soal nikah muda. Tekanan dari lingkungan yang rerata sudah menikah, sehingga ia merasa teralienasi jika tidak melakukan hal serupa. Tekanan sosial ini berlaku pula buat pelaku nikah muda yang mengalami KTD, distigmatisasi, lalu dianggap sebagai pendosa jika memilih opsi lain di luar pernikahan. Jika kamu mau tahu contoh yang lebih familier, faktor eksternal juga kerap mewujud dalam pertanyaan absurd dari keluarga tiap kumpul bersama: Kapan kawin, kapan punya anak, kapan nambah anak?
Baca juga: Keluar dari Pernikahan Toksik dan Menjadi Sugar Baby
Kehidupan Setelah Menikah Muda
Seperti disebutkan sebelumnya, artikel dan news game ini tak dimaksudkan untuk menghakimi pilihan-pilihan orang—jika ada situasi cukup ideal di mana pelaku bisa memilih sendiri tanpa paksaan—untuk menikah muda. Sebab faktanya, tak semua pelaku mengalami kehidupan yang buruk usai menikah muda. Ada orang-orang yang diberkahi privilese di mana mereka tak harus bercerai atau berkonflik karena terjerat problem finansial tapi sudah ngebet untuk menikah.
Ada pula yang memiliki pasangan suportif, sehingga ia masih bisa bertumbuh dan memiliki karier yang moncer. Kamila contohnya, tetap dapat mewujudkan salah satu mimpinya mengenyam pendidikan S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, meskipun dia menikah ketika masih kuliah pada usia 21 tahun. Hal itu karena mereka berdua sama-sama menekankan harus saling mendukung dan bernegosiasi, sehingga apapun yang dilakukan sudah jadi komitmen bersama dan tidak ada relasi yang timpang. Karenanya, mereka pun rela untuk berkorban untuk kebahagian mereka satu sama lain.
Namun, buat orang-orang yang tak punya privilese demikian, pernikahan muda adalah bumerang. Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia, Hasto Wardoyo dalam wawancara bersama Magdalene, (24/9) berpendapat, tidak hanya berpengaruh pada angka kematian ibu dan anak, pernikahan muda juga berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pasalnya, pasangan nikah umumnya masih harus bergelut dengan emosi yang belum stabil, besarnya ego mereka, hingga belum mengerti dengan baik tanggung jawab masing-masing sebagai orang tua. Karena hal inilah, sebagian pernikahan muda berakhir pada perceraian.
Baca juga: Nikah Muda karena Agama, Dua Kisah Perempuan
Klaim Hasto sejalan dengan pendapat Ann Gold Buscho Ph.D., penulis buku “The Parent's Guide to Birdnesting: A Child-Centered Solution to Co-Parenting During Separation and Divorce”, sebagaimana dilansir dari Psychology Today. Ia bilang, pelaku nikah muda yang ingin bercerai sering kali mengatakan, mereka tidak siap berkomitmen jangka panjang. Ada yang mengatakan mereka menikah karena "alasan yang salah", seperti ingin meninggalkan rumah atau tekanan orang tua mereka untuk menikah. Jika mengacu pada data dalam riset Shelby di atas, menikah terlalu muda menyumbang angka perceraian sebanyak 45% atau berada di peringkat kelima.
Memang tak semua pernikahan muda berakhir dengan perceraian. Ada juga yang bertahan tapi menghasilkan relasi toksik, yang diwarnai dengan kekerasan domestik, pemiskinan perempuan, hingga trauma anak. Namun, sekali lagi tetap ada pernikahan muda yang dalam beberapa hal, justru memberdayakan perempuan sebagai seorang istri, ibu, juga sebagai pribadi.
Pada akhirnya, pernikahan bagi mereka yang secara hukum sudah legal memang pilihan, tapi mesti dipastikan pilihan itu dibuat berdasarkan informasi yang memadai serta posisi yang berdaya dan setara.
Proyek jurnalistik ini didukung oleh International Media Support.



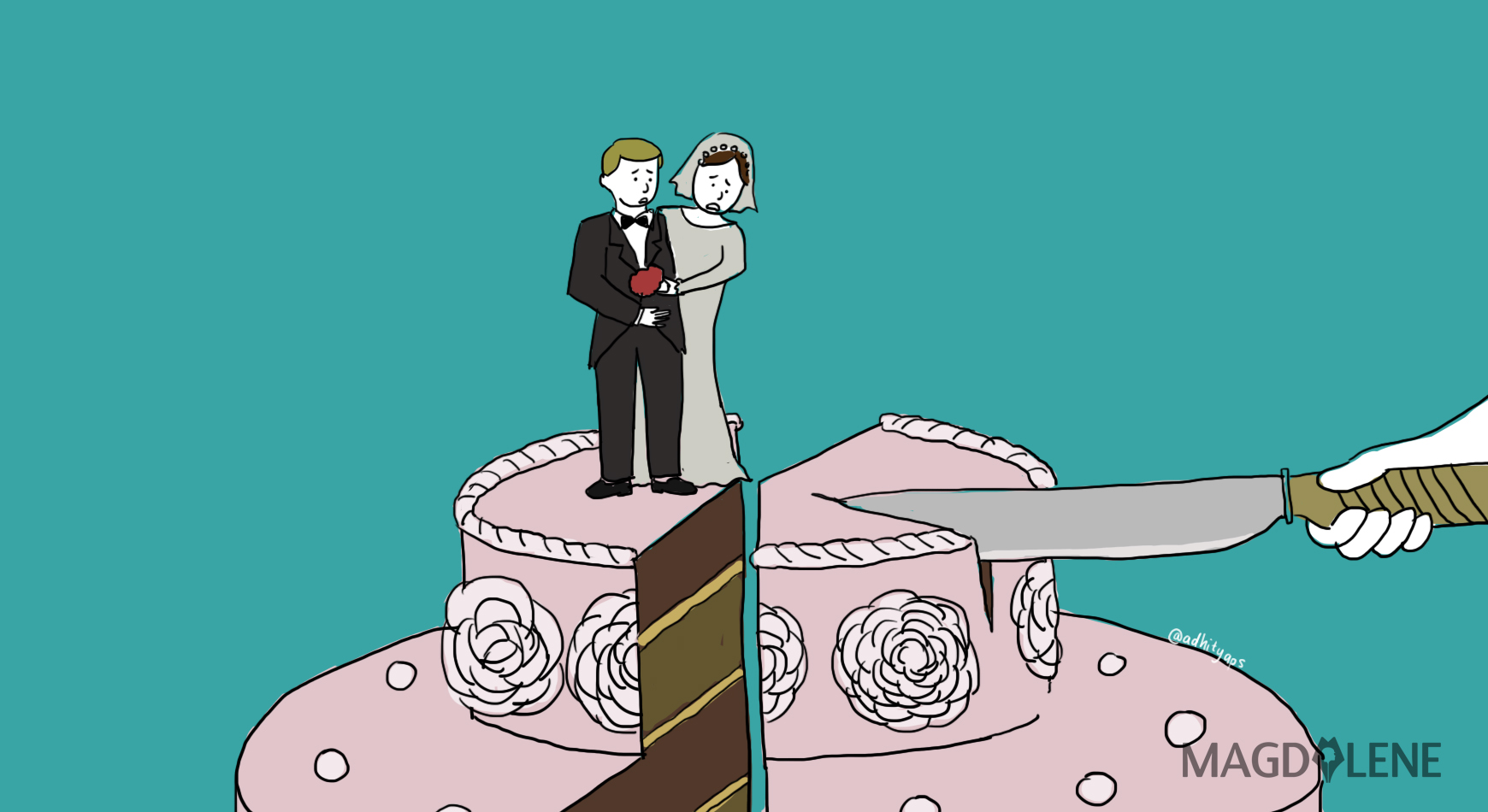
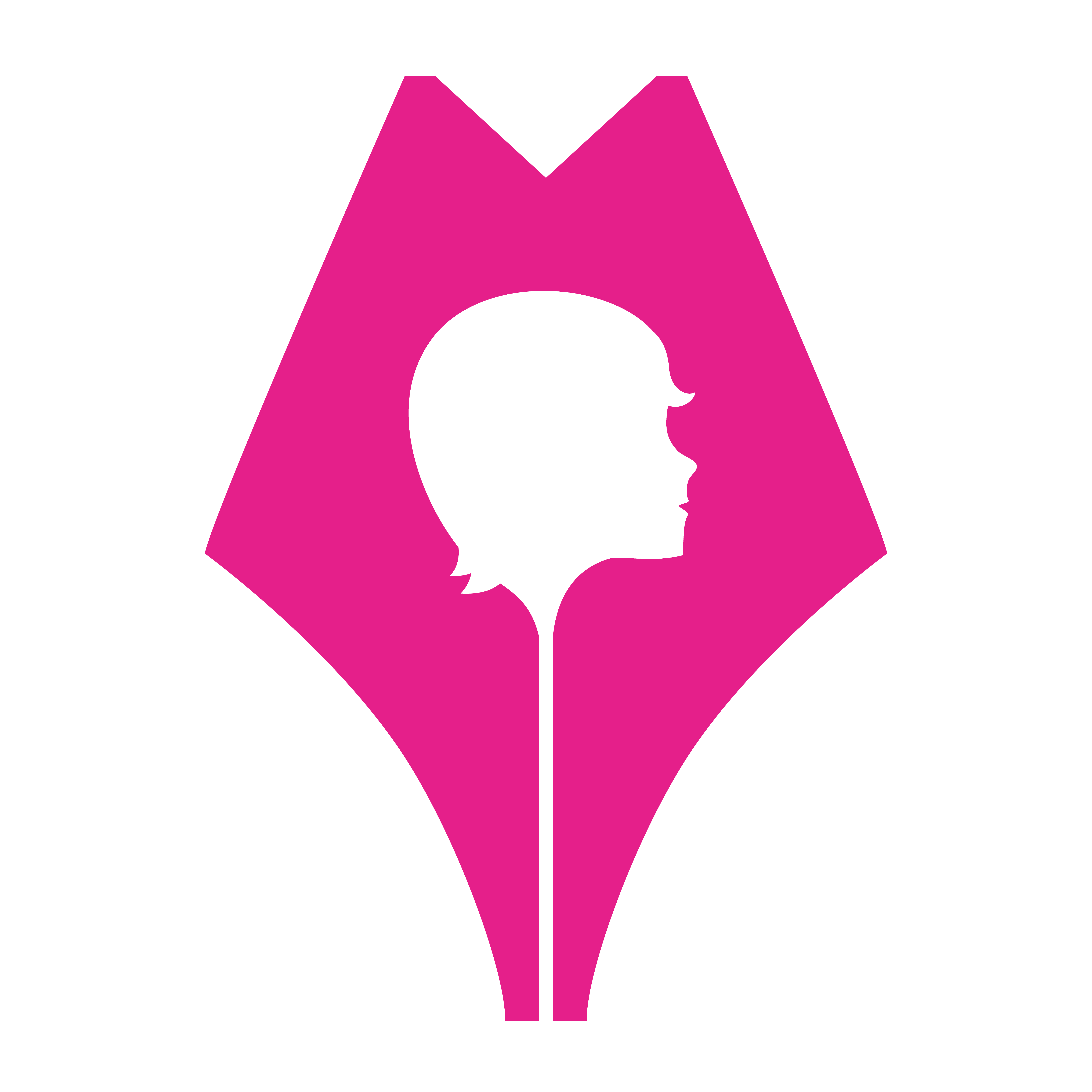



Comments