Baru-baru ini perhatian media internasional banyak terfokus pada pemilihan hakim agung di Amerika Serikat, terutama tuduhan-tuduhan pelecehan dan serangan seksual yang dilontarkan kepada calon hakim agung Brett Kavanaugh.
Salah seorang yang memberi kesaksian adalah Profesor Christine Blasey Ford, yang mengatakan bahwa Kavanaugh melakukan serangan seksual terhadapnya saat mereka di SMA. Atas kesaksian tersebut, Kavanaugh mengeluarkan berbagai ekspresi wajah dan gerak tubuh defensif – dari mulai merengut, bersuara keras, sampai menangis dan marah -- untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Berulang kali juga dia mengucapkan “demi nama baik diri saya dan keutuhan keluarga saya” ketika tuduhan tersebut dilayangkan kepadanya.
Hal yang menarik selanjutnya adalah bagaimana reaksi masyarakat seluruh dunia, khususnya kelompok liberal-progresif memaknai ekspresi-emosi yang hadir pada kesaksian tersebut. The Daily Show, acara komedi-kritik-politik yang dipandu Trevor Noah mengolok-olok naik turunnya emosi hakim agung yang kini terpilih itu seperti “sedang audisi untuk iklan (cokelat) Snickers”, yang biasanya memperlihatkan orang yang marah karena lapar.
Artikel ini tidak menjelaskan lagi bagaimana pelecehan dan serangan seksual dilakukan dengan kuasa dan jabatan. Tapi bahasan berikut berangkat dari perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berekspresi dan bertindak, yang memunculkan standar ganda yang selalu dituduhkan kepada feminis. Perbedaan berekspresi dan emosi menjadi pintu masuk untuk memahaminya. Ekspresi kemarahan Brett Kavanaugh adalah contoh yang tepat dan relevan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki persepsi yang berbeda soal ekspresi rasa malu.
Rasa Malu sebagai Kontrol Sosial
Mengapa banyak sekali produk pemutih kulit bagi perempuan Indonesia? Mengapa perempuan Indonesia terobsesi untuk mempunyai warna putih yang cerah? Pertanyaan tersebut dicoba dijawab oleh L. Ayu Saraswati, dosen Kajian Perempuan di Universitas Hawai’i, dalam bukunya Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional. Ayu berpendapat bahwa rasa malu mengontrol perempuan berkulit gelap untuk terus menggunakan produk pemutih yang dijual di pasaran. Rasa malu adalah kontrol sosial yang umum dalam masyarakat Asia. Khususnya di Asia Tenggara, ada banyak kata dari tradisi Nusantara tentang rasa malu dan supaya individu merasa bersalah atas tindakannya. Dengan kemunculan rasa malu, diharapkan seseorang bertindak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
Pada hari ini, masyarakat memiliki standar atas apa yang disebut perempuan dan lelaki, dan kita berusaha dikunci dalam dua identitas ini melalui perasaan malu. Kaidah keperempuanan dan kelelakian dibentuk dan diberikan prasyarat, dan semua orang berusaha masuk dalam kategori-kategori tersebut melalui serangkaian standar yang diberikan.
Kata “kemaluan” mendapat konteksnya ketika rasa malu berhubungan dengan identitas gender. Sayangnya, rasa malu sebagai kontrol sosial bekerja tidak persis sama terhadap gender laki-laki dan perempuan. Genital menjadi tolak ukur baik pada lelaki dan perempuan. Perempuan diharapkan merasa malu apabila tidak bisa menjaga “kesuciannya”. Selaput dara menjadi sumber kehormatan dari seorang perempuan dan seluruh keluarganya. Sedangkan pada laki-laki, perasaan malu ditumbuhkan apabila dia gagal dalam kelelakiannya, dan untuk itu banyak sekali alat bantu laki-laki untuk bisa ereksi, atau obat untuk memperbesar penis. Dari sini kita bisa lihat perbedaan antar apa yang disebut malu oleh lelaki dan perempuan.
Lebih lanjut, ekspresi terhadap rasa malu antara perempuan dan laki-laki juga berbeda. Karena kelaki-lakian dan keperempuanan adalah bentukan sosial maka masing-masing identitas gender diajarkan tindakan berbeda dalam mengekspresikan rasa malu. Perempuan diajarkan menarik diri dan menghindar ketika merasa malu, sedangkan laki-laki diminta untuk menyerang apabila dia merasa dipermalukan. Ini sebabnya mengapa butuh waktu lama bagi Profesor Ford untuk menceritakan pengalaman pelecehannya dan ada ledakan amarah Kavanaugh ketika membela “nama baik”-nya.
Perbedaan ekspresi ini terjadi bukan secara biologis tetapi hasil dari bentukan masyarakat untuk mendefinisikan gender feminin dan maskulin. Tidak semua perempuan akan menarik diri ketika merasa malu dan tidak semua laki-laki akan menyerang. Tetapi akibat pendidikan gender yang berlandaskan jenis kelamin, manusia bervagina belajar menjadi perempuan melalui kriteria feminin tersebut, dan sebaliknya untuk laki-laki.
Amuk dan Maskulinitas
Di dalam negeri, baru-baru ini terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh pendukung klub sepak bola Persib dari Bandung kepada pendukung Persija Jakarta. Peristiwa ini menewaskan Haringga Sirla, pendukung Persija berusia 23 tahun.
Pengeroyokan dan amuk massa hingga menyebabkan kematian bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya pada 2011, seorang penganut Ahmadiyah di Cikeusik juga tewas dikeroyok. Kesamaan dari peristiwa pengeroyokan ini adalah baik pelaku dan korban adalah laki-laki, kemudian alasan pengeroyokan tersebut adalah pembelaan “harga diri” dan “martabat”, baik itu martabat klub bola atau agama. Teori maskulinitas, sebuah kajian dari feminisme yang mempelajari tentang kelelakian dan menjadi lelaki berguna dalam analisa fenomena amarah dan penganiayaan berjamaah ini.
Profesor Antropologi Tom Boelstoff dari University of California menulis tentang budaya amuk dan maskulinitas di Indonesia terkait penyerangan kepada kelompok gay di Yogyakarta pada 2010. Sebagaimana feminitas dan maskulinitas yang merupakan bentukan budaya dan mempunyai variasi yang berbeda, amuk sebagai ekspresi destruktif diikat dalam batas-batas geografis dan kultural. Karena ruang lingkup maskulinitas bergantung pada komunitas, maka harkat dan martabat maskulinitas tersebut adalah hal yang harus dijaga supaya para anggota tidak merasa malu. Dan apabila martabat tercoreng dan anggota merasa malu, muncullah usaha-usaha destruktif untuk menyerang.
Amuk massa yang dilakukan kelompok muslim kepada kelompok minoritas seksual, menurut Boelstroff, adalah ekspresi rasa malu akibat martabat negara dan agama diserang. Dalam studi maskulinitas, kelelakian, atau pengakuan masyarakat sebagai lelaki, adalah sebuah martabat yang harus dipertahankan. Penyerangan terhadap kelaki-lakian membuat munculnya rasa malu, dan rasa malu direspons dengan serangan, amarah dan penghancuran.
Maskulinitas ada yang bersifat umum dan ada yang berupa ciri budaya seperti amuk. Amuk adalah tindakan marah yang dalam studi antropologi dilihat sebagai sindrom budaya terikat, yang merupakan kombinasi gejala psikiatri dan somatik yang dianggap sebagai penyakit yang dapat dikenali hanya di dalam masyarakat atau budaya tertentu, dan penyakit ini tidak dikenali dalam budaya lain.
Dalam perspektif feminis, amuk kebanyakan dilakukan oleh lelaki karena lelaki diharuskan marah ketika merasa malu oleh masyarakat. Selain itu, menyerang ketika merasa malu juga menjadi tindakan lelaki untuk mengembalikan kelelakiannya yang tercoreng. Tapi apakah perempuan bisa melakukan amuk? Beberapa literatur dan karya sastra menunjukkan perempuan mampu melakukan amuk tetapi dengan syarat melepaskan tubuhnya, alias sudah mati. Perempuan hanya bisa melakukan amuk ketika dia meninggalkan feminitasnya yakni tubuhnya. Apabila lelaki bisa melakukan amuk semasa hidup, amuk yang dilakukan perempuan direkam dalam film horor dalam bentuk teror hantu.
Kita tidak otomatis menjadi perempuan dan lelaki melalui sebab biologis. Keperempuanan dan kelelakian dipelajari dan dilatih setiap saat. Ukuran keberhasilan menjadi lelaki dan perempuan adalah bentukan masyarakat dan oleh sebab itu apa yang disebut dengan adil tidak bisa menggunakan standar yang sama bagi kedua belah pihak.
Apa yang selama ini diperjuangkan feminisme bukan kesamaan karena kesamaan jelas-jelas gagal menangkap perbedaan pengalaman antar gender seperti kasus ekspresi malu ini. Mengakui dan memahami perbedaan pengalaman adalah upaya kita menciptakan keadilan. Dan perjuangan feminisme tidak sekedar membela ketubuhan dan melawan kekerasan seksual tetapi revolusi kehidupan secara menyeluruh untuk memperjuangkan yang adil bagi seluruh gender berdasarkan pengalamannya.
Pelecehan seksual dan pemerkosaan adalah soal kekuasaan.




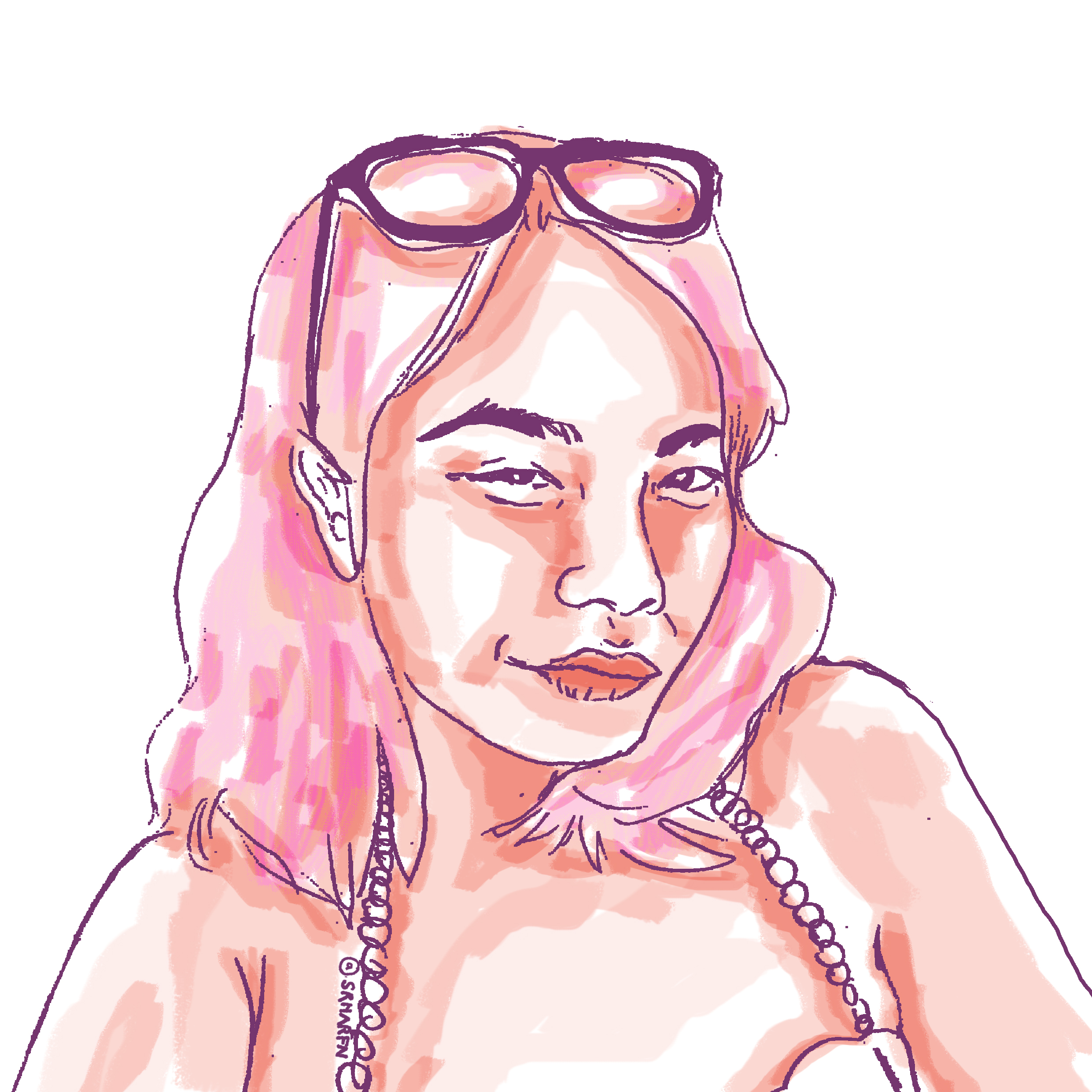



Comments