Masyarakat yang terliterasi kemudian berlomba-lomba mendorong perempuan untuk mengembangkan potensi sebesar-besarnya; bahwa perempuan bisa menjadi apa saja bila ia memang mau dan berusaha. Permasalahan muncul ketika tulisan-tulisan penyemangat yang menjunjung progresivitas perempuan melalui pengembangan potensi dalam bidang akademik dan karir ini di sisi lain seakan-akan mendiskreditkan perempuan-perempuan yang memilih untuk mengembangkan potensi di bidang domestik dan konservatif.
“Perempuan bukan hanya harus pintar masak, perempuan juga harus pintar sekolah, biar nanti karirnya bagus.”
Walaupun bernada motivatif dan apresiatif, kalimat ini memiliki standar ganda. Penggunaan kata ‘bukan hanya’ mengimplikasikan bahwa kemampuan memasak (dan kemampuan di bidang domestik lainnya) adalah sesuatu yang masih belum lengkap dan belum utuh jika tidak dibarengi dengan kemampuan akademik dan karir. Penggunaan kata ‘juga’ mengimplikasikan bahwa kemampuan akademik dan karir inilah yang berperan untuk melengkapi.
Ketika perempuan hanya menguasai bidang domestik semata, pengembangan potensinya dianggap belum utuh dan perlu disempurnakan. Perempuan-perempuan yang masih berkutat dalam bidang domestik dan gaya hidup konservatif dilabeli sebagai perempuan yang tak mampu meliberasi diri mereka sendiri, masih kurang wawasan dan pengetahuan, masih terkungkung budaya patriarki, dan oleh karenanya harus ‘ditolong’ supaya mereka bebas, baik melalui ajakan hingga cemoohan dan paksaan.
Di sisi lain, perempuan yang memberanikan diri mempertanyakan apalagi mendobrak batas-batas tersebut juga tak luput dari kubangan stigma yang akan diberikan oleh masyarakat luas, ketika mereka berjuang dalam proses panjang untuk merekonstruksi identitas mereka sebagai perempuan. Perempuan seakan tidak pernah tahu bagaimana cara menjadi perempuan utuh yang sebenar-benarnya. Bagi saya, tidak ada perempuan yang sempurna. Perempuan adalah manusia layaknya kalian semua, bukan metafor dengan gambaran ideal.
Bagaimana bila perempuan-perempuan itu sendiri yang memang memilih secara sadar untuk menggeluti bidang domestik dan menjalani gaya hidup konservatif? Apakah mereka bukan seorang feminis, paling tidak bagi dirinya sendiri?
Salah satu kelompok aktivis yang mengklaim diri mereka feminis adalah Femen, yang seringkali menyuarakan protes dan tuntutannya melalui aksi bertelanjang dada atau bertelanjang bulat di ruang-ruang publik. Tak terhitung sudah aksi-aksi kontroversial yang mereka lakukan, mulai dari aksi telanjang dada di acara konferensi Islam guna menolak keras penerapan syariah Islam, mencuri patung Yesus dengan menorehkan tulisan “God is woman” di dadanya saat misa Natal, dan lain sebagainya. Aksi-aksinya ini justru dikecam oleh banyak aktivis feminisme lainnya. Femen dianggap tidak menyuarakan hak-hak dan kesetaraan gender perempuan secara obyektif dan universal, namun hanya menyuarakan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka sendiri. Femen dianggap memperjuangkan kepercayaan dan idealisme yang sangat eksklusif.
Femen tak hanya menyuarakan apa yang mereka percaya, namun memaksa orang lain untuk turut mempercayai kepercayaan tersebut, yaitu perempuan haruslah bebas dari kekangan, yang mereka simbolisasikan dengan bertelanjang dada. Bukankah ini justru sebuah opresi pada perempuan-perempuan lain yang memiliki kepercayaan berbeda? Bagi aktivis Femen, memang agama dan atributnya adalah kekangan yang harus dilepaskan agar perempuan dapat terliberasikan secara hakiki, namun apakah demikian pula bagi perempuan-perempuan lainnya?
Nyatanya, banyak juga perempuan yang berhijab, misalnya, dan melakukan itu karena kesadaran penuhnya. Mereka tidak menganggap hijab dan agamanya sebagai suatu opresi, alih-alih, dengan hijab itulah mereka merasa terliberasi.
Ketika apa yang dipercayai sebagai suatu realitas dan kebenaran bagi satu individu atau kelompok kemudian ‘dipaksakan’ untuk harus dipercayai pula sebagai suatu realitas dan kebenaran bagi individu lain, maka di problematika muncul. Tiap-tiap individu memaknai realitas dengan cara dan kompleksitas masing-masing yang tak mungkin serupa. Tingkah laku yang sama saja bisa jadi merupakan derivasi dari buah pikiran yang berbeda, apalagi tingkah laku yang memang berbeda. Kebenaran adalah relatif dan subyektif milik individu itu sendiri.
Terjadi blunder ketika feminisme direduksi maknanya dan diabaikan kompleksitasnya dengan menyamaratakan semua kesadaran, realitas, dan kebenaran mengenai semua perempuan menggunakan definisi yang sama. Perempuan tak lagi dipandang dari sisi unit satuan analisis terkecilnya, yaitu individu yang unik dan berbeda antar satu dan lainnya. Saya yakin sebagai aktivis, kita memang memiliki tujuan mulia untuk memberdayakan perempuan dan menyadarkan perempuan dari ketertindasannya. Namun kita harus berhati-hati, karena ’ketertindasan’ bagi kita bisa jadi adalah sebuah definisi ‘kebebasan’ bagi mereka.
Aliran feminis liberal yang berangkat dari teori struktural fungsionalisme, muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan, nilai moral, dan kebebasan individu, akan tetapi pada saat bersamaan juga dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Asumsi dasar feminisme liberal adalah bahwa kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.
Dalam memperjuangkan persoalan masyarakat, menurut kerangka kerja feminis liberal, fokusnya adalah pada ‘kesempatan yang sama dan hak yang sama’ bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya, penekanan pada aliran ini adalah keadilan yang berasal dari sistem untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama. Lebih lanjut lagi, menurut aliran feminisme liberal, jika sistem sudah benar, namun perempuan masih dalam keadaan ‘terbelakang’ atau ‘tertinggal’, maka hal tesebut disebabkan oleh ‘kesalahan mereka sendiri’.
Di satu sisi, saya setuju dengan pemikiran aliran feminisme liberal, namun di sisi lain, ada juga poin-poin yang tak saya setujui. Saya sepakat bahwa dalam memperjuangkan persoalan masyarakat, harus dimulai dengan ‘kesempatan yang sama dan hak yang sama’ bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Keadilan sistem adalah hal yang mutlak saya setujui. Status-status dan peran-peran sosial harus didistribusikan secara merata pada laki-laki dan perempuan. Semua orang harus diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan berpartisipasi dalam ranah politik.
Namun, saya tidak setuju dengan anggapan feminisme liberal bahwa jika sistem sudah benar, namun perempuan masih dalam keadaan ‘terbelakang’ atau ‘tertinggal’, maka hal tesebut disebabkan oleh ‘kesalahan mereka sendiri’. Tidak ada istilah ‘terbelakang’ maupun ‘tertinggal’ dalam konteks peran dan status sosial, karena hal tersebut merupakan spektrum yang terdiri atas diferensiasi-diferensiasi yang berlaku horizontal.
Status-status dan peran-peran tersebut memang berbeda, namun bukan berarti satu lebih superior dan lainnya adalah inferior. Status dan peran bukanlah sebuah tingkatan vertikal. Kata ‘terbelakang’ mengimplikasikan ada yang ‘terdepan’. Pun kata ‘tertinggal’ mengimplikasikan ada yang ‘di depan’. Ketika sistem sudah benar, perempuan tersebut bukan masih dalam keadaan ‘terbelakang’ atau ‘tertinggal’. Menurut saya, perempuan tersebut telah memilih untuk menjadi apa yang ia inginkan.
Selain itu, saya juga tidak setuju dengan anggapan feminisme liberal bahwa hal tesebut disebabkan oleh ‘kesalahan mereka sendiri’. Memilih realitas yang hendak dijalani adalah suatu keharusan bagi tiap individu, dan individu yang dapat dengan teguh menekuni pilihan yang diambilnya secara sadar, terlepas dari apa komentar masyarakat adalah mereka yang patut diapresiasi.
Tidak ada kata salah dalam memilih. Tidak ada kata salah dalam menjadi berbeda. Karena bagi saya, ketika sudah ada kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi perempuan sebagai manusia, pada akhirnya perempuan memiliki hak, kebebasan dan otoritas atas dirinya, tubuhnya, hidupnya, dan masa depannya sendiri. Ia memiliki hak, kebebasan, dan otoritas untuk memilih apa yang mau dan tak mau ia lakukan. Sebagai feminis, mari melakukan refleksi dan introspeksi, mengenai sejauh apa pemahaman kita tentang feminisme, semangat apa yang seharusnya kita perjuangkan, dan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan.
Vita Kartika adalah mahasiswa tingkat akhir di Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga yang percaya pada konsep pendidikan seumur hidup dan kekuatan dari sebuah proses. Ia menulis dan mengkritik isu-isu terkini di semanticsatiation.blogspot.com. Ia dapat disapa melalui akun @vitdgaf di tiap media sosial.



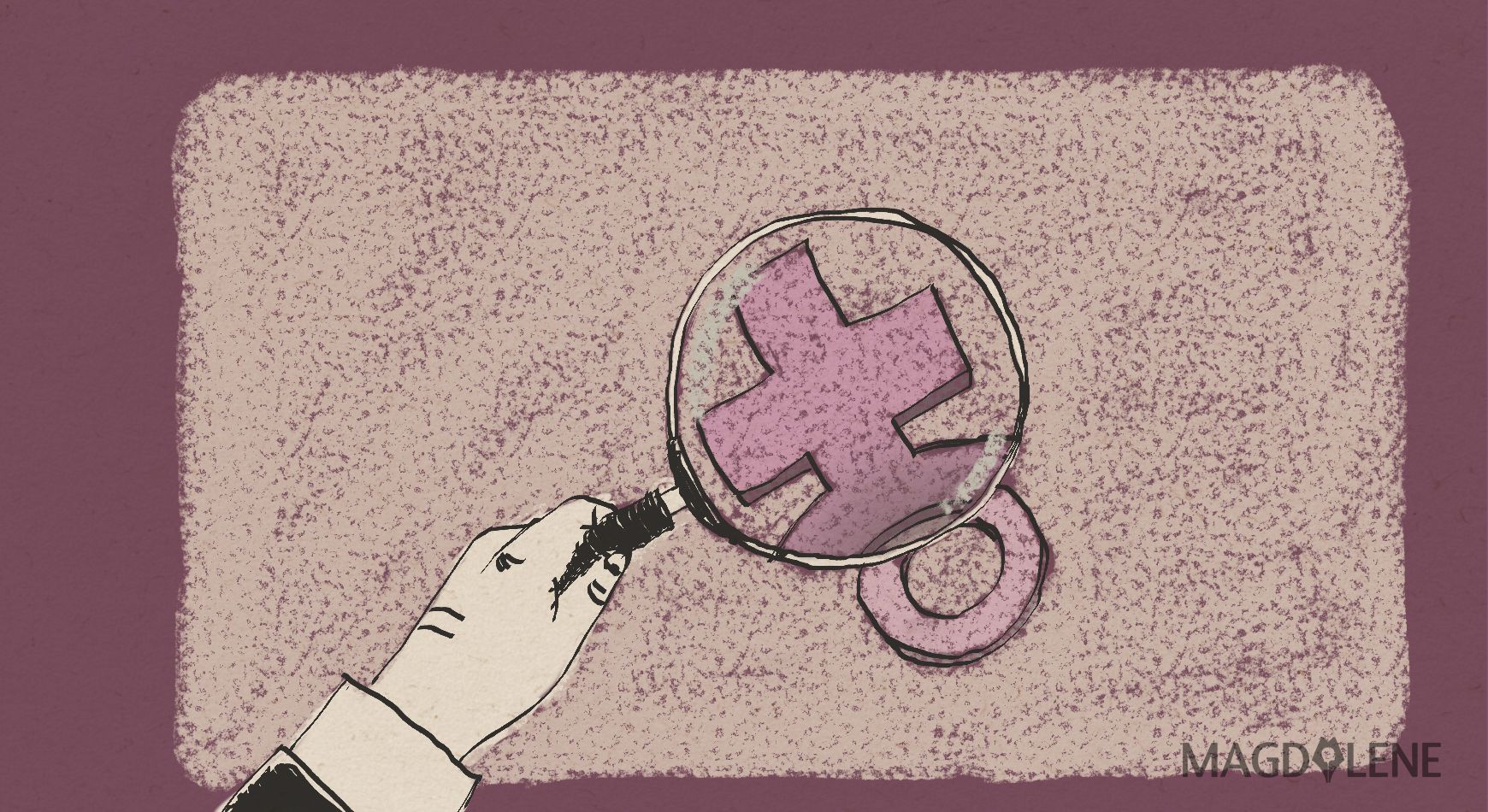


-thumb.jpg)

Comments