Belum lama ini anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bernama Amri Tanjung (21 tahun) ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan dan eksploitasi secara seksual seorang anak perempuan di bawah umur. Hal ini tentu menghebohkan masyarakat. Seiring dengan itu, kontroversi muncul setelah pelaku berniat menghapus kesalahannya dengan cara menikahi korban.
Kekerasan seksual menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, serta berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis. Korban juga terpapar risiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi penyakit menular seksual.
Dengan berbagai risiko berlapis dan berjangka panjang, korban dan keluarganya membutuhkan sistem penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang berkualitas.
Solusi menikahkan korban dengan pelaku tidak hanya merampas korban dari berbagai hak yang dimilikinya, tapi juga menunjukkan betapa sistem hukum di Indonesia belum memihak pada korban kekerasan seksual.
Menikahkan Korban Pemerkosaan dengan Pelaku Problematik
Dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia, menikahkan pelaku dan korban adalah hal yang sering terjadi. Berdasarkan rangkaian studi Barometer Kesetaraan Gender Tahun 2020 dari Indonesian Judicial Research Society (IJRS) yang salah satunya berbicara dengan 1.586 responden yang terlibat kasus kekerasan seksual, hanya terdapat 19,2 persen kasus di mana pelaku dipenjara.
Sebanyak 26,2 persen korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus–sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah dan pelaku hanya membayar sejumlah uang.
Hal ini dilakukan dengan dalih yang beragam, mulai dari menutup aib keluarga, agar anak yang dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana.
Padahal, menikahkan korban dengan pelaku berpotensi menimbulkan kekerasan yang berulang bagi korban, baik secara emosional, fisik, maupun seksual, serta merampas hak korban untuk memulihkan dirinya.
Alih-alih fokus pada pemulihan dan kebutuhan korban, solusi pernikahan justru mengerdilkan kekerasan dan trauma yang dialami korban.
Kesalahpahaman tentang Restorative Justice
Survei tahun 2016 yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) menemukan bahwa 51,6 persen dari sekitar 2000 responden menganggap pernikahan antara pelaku dan korban kekerasan seksual bisa menjadi alasan yang layak untuk meringankan hukuman pelaku.
MaPPI-FHUI juga menemukan bahwa banyak putusan hakim menggunakan alasan tersebut sebagai landasan untuk meringankan hukuman–seakan kerugian yang dialami korban sebagian terhapuskan dengan terjadinya pernikahan.
Di sini, masih ada anggapan yang keliru terkait restorative justice (keadilan restoratif), yakni konsep keadilan berbasis pemulihan hak yang sering digaungkan oleh aparat penegak hukum. Tampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.
Baca juga: Pentingnya Pendekatan ‘Restorative Justice’ dalam Penyelesaian Kasus AY
Padahal, menurut European Forum for Restorative Justice, keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana.
Artinya, menikahkan korban dengan pelaku justru bertentangan dengan konsep keadilan restoratif karena tidak menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang muncul melalui proses hukum. Bahkan, jalan pintas ini cenderung tidak memberi ruang dialog antara kedua pihak sehingga membungkam suara korban.
Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual harus fokus melakukan setidaknya tiga hal: Memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami, membuat pelaku menyadari dampak dari kesalahannya, untuk pelaku kemudian menjalani konsekuensinya secara hukum.
Di Indonesia, belum ada cetak biru yang jelas dari pemerintah terkait penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual. Namun, negara lain sudah menerapkannya dengan praktik yang berbeda-beda–ada yang dilakukan setelah pelaku dipidana ataupun bersamaan dengan proses pengadilan hukum pelaku.
Di Arizona, Amerika Serikat (AS), misalnya, ada sebuah program bernama RESTORE, yaitu praktik keadilan restoratif berbentuk konferensi (duduk bersama) yang ditujukan bagi kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa.
Dalam program ini, jaksa memberi rujukan, meminta persetujuan, dan akhirnya memfasilitasi korban dan pelaku agar bertemu dalam pertemuan yang aman dan konstruktif. Proses ini berjalan bersamaan dengan proses pengadilan secara terintegrasi sampai pelaku menyelesaikan masa tahanan.
Inti dari RESTORE adalah ganti rugi yang harus dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku dipastikan harus menaati perjanjian saat konferensi untuk membayar ganti rugi dan permintaan lain korban, misalnya untuk tidak mengontak korban atau tidak mengunjungi korban setelah keluar tahanan, mengikuti konseling, dan seterusnya.
Baca juga: Pedoman Baru bagi Jaksa Bantu Perempuan, Anak dalam Proses Hukum
Dalam studi yang sama dari IJRS sebelumnya, misalnya, lebih dari separuh masyarakat (56,8 persen) Indonesia berpendapat bahwa hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual bukan hanya penjara, tapi juga pembayaran ganti rugi terhadap korban.
Namun, kita harus ingat bahwa penerapan unsur keadilan restoratif seperti ini juga tidak selalu cukup untuk memulihkan hak korban, terutama jika agenda utamanya adalah perdamaian antara kedua belah pihak–suatu cara berpikir yang masih kental dalam masyarakat Indonesia.
Misalnya, konferensi rentan menimbulkan reviktimisasi–di mana korban kembali mengalami trauma dan kekerasan selama proses hukum–apalagi bila pelaku tidak kooperatif dan fasilitator tidak bijak dalam mengawasi pihak yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Ada juga risiko di mana korban justru mendapat beban psikologis untuk memaafkan pelaku sehingga tujuan pemulihan tidak lagi berperspektif kebutuhan korban.
Oleh karena itu, konferensi seperti ini pun harus difasilitasi oleh pekerja sosial, penegak hukum, dan konselor terlatih.
Negara Harus Utamakan Pemulihan Korban
Berbagai hal di atas menunjukkan sistem peradilan pidana belum memberi penanganan yang efektif dan mudah diakses bagi korban kekerasan seksual. Pada akhirnya, lebih dari 80 persen korban sama sekali tidak terlibat dalam sistem peradilan pidana.
Penanganan kasus kekerasan seksual seharusnya lebih berpihak pada korban, keluarga korban, dan saksi. Penanganan juga harusnya dibarengi dengan sistem perlindungan, pendampingan, dan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Di sini, negara lewat perangkat hukum dan aparat penegak hukum merupakan aktor yang sangat penting karena memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan bagi korban.
Kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pelaporan kekerasan seksual, misalnya, harus tegas dalam menindaklanjuti laporan kasus. Mereka mesti menghindari memberikan saran agar korban berdamai–bahkan menikah dengan pelaku. Sebaliknya, mereka harus merujuk korban mendapatkan layanan medis dan psikologis yang layak, dan memberikan hak-haknya agar akses keadilan bagi korban dapat terwujud.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.






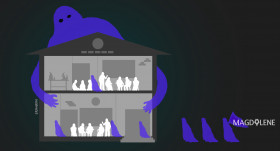
Comments