Pada April 2016, Istana Negara gempar karena di seberangnya ada sembilan perempuan yang menyemen kakinya sebagai aksi protes terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Pabrik semen tersebut berpotensi merusak Kawasan Cekungan Air (CAT), yang menjadi tumpuan hidup petani Kendeng. Mereka marah karena alam yang selama ini mereka jaga hendak dirusak korporasi dengan dukungan penguasa.
Istana Negara kemudian menjadi pilihan terakhir Sukinah dan delapan perempuan Kendeng lainnya, setelah aksi mereka mendirikan tenda di depan pintu pabrik semen sejak 2014 tak kunjung didengar. Para aktivis dan lembaga hukum kemudian membantu mengajukan gugatan izin pabrik ke Mahkamah Agung, yang pada November 2016 memenangkan gugatan peninjauan petani Kendeng.
Keberhasilan aksi Kartini Kendeng tersebut memantik banyak diskursus baru tentang gerakan ekofeminisme di Indonesia. Banyak orang menjadikan mereka sebagai contoh nyata bagaimana hubungan antara eksploitasi serta degradasi lingkungan hidup lekat kaitannya dengan subordinasi perempuan.

Sebagai perempuan di pedesaan yang masih patriarkal dan berkutat dengan ranah domestik, aksi petani Kendeng dan kelompok perempuan lainnya seolah menjadi simbol bahwa perempuan menjadi kelompok yang hadir di garda terdepan saat ada orang yang mengusik alam dan mengancam masa depan anak-anaknya dan rumah yang mereka tempati. Peran mereka di ranah domestik nyatanya bisa menjadi titik balik dari perlawanan desa. Ketika alam dirusak, perempuan menjadi yang paling berdampak karena mereka yang memastikan anak-anak bisa makan dengan layak.
“Ibu-ibu itu harus ada di garis depan memperjuangkan lingkungan ini, tidak harus bapak (laki-laki),” ujar Sukinah.
Bagi jurnalis Febriana Firdaus, peliputannya terhadap Sukinah dan teman-teman di Jakarta menginspirasinya untuk membuat film dokumenter Our Mothers’ Land atau Tanah Ibu Kami bersama dengan The Gecko Project dan Mongabay. Febriana menyoroti bagaimana kehidupan para perempuan di berbagai daerah Indonesia bertahan melawan korporasi yang ingin mengeruk sumber daya alam di Indonesia.
Baca juga: Peran Vital Ibu Rumah Tangga dan Petani Perempuan dalam Aktivisme Lingkungan
“Pertemuan saya dengan Sukinah di Jakarta dan pengalaman banyak meliput perempuan-perempuan yang memimpin gerakan untuk menjaga alam membuat saya berpikir sepertinya kita perlu mendokumentasikan mereka. Apalagi di Indonesia lebih suka visual dibanding membaca,” ujar Febriana setelah pemutaran Our Mothers’ Land di Ubud Writers Festival 2020 (29/10).
Berbekal pengalaman liputannya di berbagai wilayah Indonesia, Febriana mengajak penonton napak tilas menemui tokoh-tokoh perempuan hebat di Aceh, Jawa, sampai wilayah timur Indonesia. Tindakan mereka yang berani melawan aparat, preman, mengorbankan jiwa dan penghasilannya untuk melawan, bahkan sampai dipenjara, kemudian menjadi cerita yang menuntun jalannya film ini.

Perempuan melawan dengan tenun
Selain sembilan Kartini Kendeng, ada tiga tokoh lain yang diangkat dalam film ini: Aleta Baun yang dari Nusa Tenggara Timur, Eva Bande dari Sulawesi Tengah, dan Farwiza Farhan dari Aceh.
Mama Aleta, yang merupakan anak kepala suku, menginisiasi gerakan menenun melawan perusahaan tambang pada periode 1990-2000an, setelah melihat bagaimana alam di desa Mollo rusak oleh perusahaan tambang. Ia melakukan berbagai macam cara agar warga mau ikut berjuang melawan korporasi. Menenun dipilihnya sebagai simbol bahwa perempuan bisa tampil di depan untuk melawan bahkan dengan alat tenun yang melekat sebagai pekerjaan perempuan.
Baca juga: Tugas Mengelola Air Bebani Perempuan, Rugikan Mereka Secara Finansial
“Saya belajar dari alam daripada manusia yang membohongi saya. Pengetahuan unik dan mujarab, bukan buku. Kita enggak harus baca buku dulu untuk paham masalah lingkungan. Kita bisa belajar langsung dari alam. Manusia harusnya menjual apa yang mereka hasilkan bukan tanah atau gunung,” ujar Mama Aleta.
Atas perjuangan tersebut, Aleta mendapat penghargaan Goldman Environmental Prize 2013. Kontribusinya dalam melakukan perlawanan diakui dan diapresiasi dunia.
“Tantangan berhadapan dengan modal, mental harus kuat. Sendiri jadi bersama; mengusir ketakutan jadi kekuatan.” – Eva Bande
Salah satu nama penenun yang ikut dalam aksi itu, Lodia Oematan, menceritakan kembali betapa mencekamnya aksi yang mereka lakukan: Ia terus menenun tanpa henti meski aparat, preman dan alat berat perusahaan berada di depan matanya. Selama aksi, tidak hanya fisik yang terkuras berhadapan dengan aparat, Lodia juga mengatakan ada trauma secara psikologis yang menempel padanya. Ia juga harus rela berhenti menanam lahannya selama setahun karena ikut aksi.
“Lebih baik mama-mama menenun agar tetap punya hak milik. Menahan dengan tenun. Menolak, menolak, bor batu di samping kaki mama. Selama pendudukan diserang preman, dilindungi aparat,” ujar Lodia lirih.
Sementara itu, Eva Bande dari Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, sampai harus masuk bui karena mengorganisir para petani untuk melawan perkebunan sawit. Suaranya yang lantang untuk melawan itu berujung pada penjara, tempat yang nyatanya tidak membuatnya gentar sedikit pun. Eva dihukum empat tahun penjara, sedangkan beberapa orang yang terlibat gerakan dan dijemput paksa oleh aparat. Yu Patmi, yang anaknya, Nuril, menjadi korban memiliki trauma mendalam karena Nuril dijemput paksa. Nuril meninggal setelah dibebaskan dibebaskan dari penjara.
“Tolong jangan dikorek lagi, nanti kebuka lagi. Saya sampai sekarang enggak bisa dengar suara-suara,” ujar Yu Patmi.

Melihat itu, Eva tidak tinggal diam, setelah mendapat grasi dari Jokowi pada 2014, Ia mulai mengorganisir para ibu rumah tangga yang mengalami pahitnya ditinggal suami. Eva membentuk kelompok usaha atau koperasi sebagai wadah saling membahu satu sama lain untuk bisa bertahan hidup.
“Tantangan berhadapan dengan modal, mental harus kuat. Sendiri jadi bersama, mengusir ketakutan jadi kekuatan,” ujar Eva.
Baca juga: Masyarakat Adat Kian Rentan Akibat Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anak muda dan perlindungan lingkungan
Farwiza Farhan adalah salah satu pendiri organisasi nirlaba Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Haka), yang berfokus melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh. Perjuangan Farwiza tidak hanya sebatas menjaga hutan tapi juga berhadapan dengan para korporasi besar di meja sidang, ia tidak henti melakukan advokasi-advokasi untuk mencegah pengerukan hutan Sumatra.
“Inginnya bermain di hutan, tapi melindungi hutan sering kali lebih banyak dihabiskan di ruang sidang, ruang rapat, dan depan komputer,” ujar Farwiza, yang namanya sempat melejit setelah ia menemani aktor Leonardo DiCaprio menyusuri Taman Nasional Gunung Leuser.
Menurutnya, perempuan punya peran besar untuk melindungi lingkungan, bahkan bumi sendiri pun digambarkan sebagai sosok perempuan sehingga di banyak wilayah ada istilah Mother Earth atau Ibu Bumi.

Sebagai perempuan muda dan peneliti, Farwiza adalah perwakilan anak muda berpendidikan tinggi dan peduli lingkungan. Dalam narasinya, Febriana mengatakan bahwa Farwiza adalah contoh anak muda yang tidak harus pergi ke Jakarta terlebih dahulu untuk memulai perubahan. Farwiza seolah sengaja ditempatkan di bagian akhir film sebagai sebuah refleksi bagaimana baiknya anak muda kembali memahami permasalahan lingkungan.
“Perjuangan atas lingkungan ini tak akan berakhir, akan terus berlanjut sampai generasi berikutnya. Ketika kita punya pengetahuan akan alam, kita amplifikasi suara mereka, kita bagi cerita mereka,” ujarnya.
Our Mothers’ Land memberi bukti visual bahwa perempuan penjaga “Ibu Bumi” ini adalah tokoh-tokoh yang kuat dan punya pengaruh yang besar dalam menjaga ekosistem yang dinikmati manusia.
Our Mother’s Land dapat dilihat di YouTube.




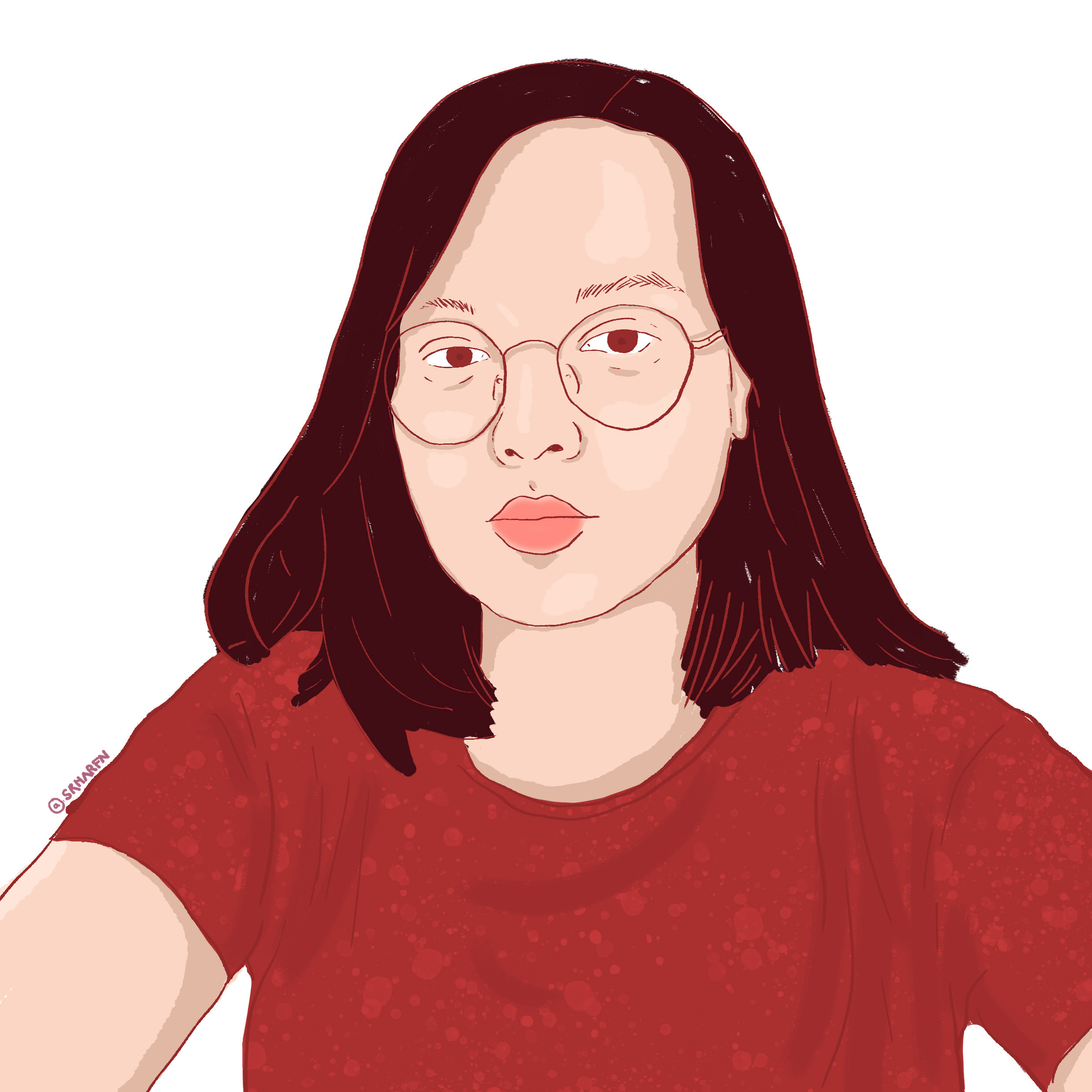



Comments