Dalam kritiknya terkait perkembangan pergerakan feminisme, penulis dan feminis Jessa Crispin mengatakan, “Saat ini, mandeknya feminisme disebabkan oleh pergerakan yang belum menyasar pada perubahan sistemik di tingkat negara.” Kalimat itu seketika muncul di kepala saya manakala berita pengesahan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (selanjutnya “Permendikbud 30/2021”) naik di media massa.
Peraturan menteri ini, jika boleh saya katakan, merupakan inovasi pejabat negara paling mutakhir (setidaknya sejauh ini) untuk melindungi perempuan. Inovasi yang saya maksud tecermin bahkan sejak mula kita menengok konsiderans peraturan ini. Nadiem berhasil memisahkan antara paradigma perlindungan penyintas dan pencegahan kekerasan seksual dari perspektif agama (yang biasanya selalu dibawa para penolak ide perlindungan perempuan).
Dalam teori hukum tata negara, konsiderans memiliki peran signifikan dalam memberikan gambaran politik hukum pembentukan suatu peraturan. Pada pertimbangan poin a, Permendikbud 30/2021 menyatakan “bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.”
Ini menjadi pengingat tegas bagi penyelenggara negara lain bahwa setiap warga negara berhak dilindungi oleh negara dari segala bentuk kekerasan—termasuk kekerasan yang berbasis pada gender dan relasi kuasa.
Kondisi di atas bertolak belakang dengan sejumlah tindakan pejabat negara lainnya. Contohnya dapat dilihat dari argumen penolakan beberapa fraksi di DPR atas Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai melegalkan zina. Atau, bisa juga kita tengok pendapat beberapa hakim konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-XIV/2016 yang berpandangan bahwa memberikan perlindungan atas persekusi berbasis gender bertentangan dengan agama dan oleh karenanya bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Seolah-olah, konstitusi adalah tafsiran agama dan tidak sejalan dengan upaya amplifikasi komitmen negara dalam memberikan perlindungan pada setiap warga negara atas penindasan yang didasarkan gender.
Perempuan Harus Bebas Trauma
Sebagai tempat yang menyediakan berbagai platform pengembangan diri, kampus idealnya meletakkan agensi perempuan sebagai komponen yang perlu dipertimbangkan untuk diberi perlindungan optimal. Ini mengingat budaya patriarki masih merasuki sebagian besar masyarakat kita, sehingga memungkinkan perempuan mendapatkan diskriminasi berbasis gender, dalam hal ini berbentuk kekerasan seksual.
Oleh karenanya, sebagai langkah afirmatif, perempuan harus dilindungi agar dapat berkiprah dalam kehidupan kampus. Trauma yang dihadirkan dari pengalaman kekerasan seksual berpotensi besar membatasi perempuan baik secara psikis maupun sosial untuk dapat mengaktualisasikan dirinya.
Ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan alienasi diri dari lingkungan sosial merupakan risiko umum bagi perempuan dewasa yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Acierano, dkk pada 1999 mengenai risiko perkosaan, dinyatakan bahwa beberapa perempuan penyintas kekerasan seksual mengalami gejala Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Depresi, gangguan tidur, dan penarikan diri dari lingkungan sosial ini menghambat manuver-manuver perempuan untuk meramu dan mengolah dirinya untuk menciptakan nilai yang dapat diperkenalkannya ke publik.
Berangkat dari pemahaman adanya risiko seperti ini, Permendikbud 30/2021 muncul sebagai upaya untuk memberikan perempuan hak konstitusionalnya, agar terbebas dari kekerasan yang mengobjektifikasi seksualitasnya.
Sebagai lingkungan yang mengklaim diri sebagai ruang akademik, perguruan tinggi merupakan pentas bagi para civitas akademika—termasuk perempuan. Budaya patriarki yang mengerdilkan perempuan sejak belia, seharusnya berhenti pada ruang akademik yang kerap menggaungkan kesetaraan gender sebagai pandangan filsafati.
Perubahan Sistemik dalam Perspektif Feminisme
Jessa Crispin memberikan gambaran umum bagaimana kondisi akademia yang kerap memperbicangkan feminisme dan membawa perbincangan ini pada ranah personal, membuat kita kerap kali terhalang untuk mengalamatkan ketidakadilan sistemik yang ada di depan mata. Pandangan utama Crispin pada permasalahan ketidakadilan ini berasal dari konsepsi bahwa serangan dan perubahan yang selama ini dilakukan tidak menyasar kepada sistem. Dengan demikian, Permendikbud 30/2021 ini harus dilihat sebagai upaya adanya perubahan sistemik untuk perlahan membunuh ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, setidaknya dimulai dari lingkungan kampus.
Perubahan sistemik dengan menggunakan lensa feminisme ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan akses terhadap pilihan-pilihan sebagaimana laki-laki. Dalam pandangan gender justice, keadilan hanya dapat datang dari sebuah sistem yang setara.
Filsuf Swami Vivekanand pernah berucap, “Sebagaimana burung yang tidak dapat terbang hanya dengan satu sayap, negara tidak akan maju ke depan jika perempuan tertinggal di belakang.” Penyebarluasan (mainstreaming) ide kesetaraan gender di kampus seharusnya tidak hanya jadi kecapan tanpa aktualisasi. Perempuan juga harus bisa nongkrong semalaman di kampus tanpa rasa takut. Nadiem Makarim menyadari betul bahwa ruang aman itu milik semua.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.






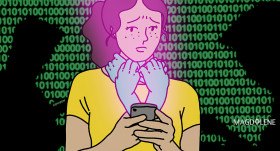
Comments