Dengan mata berbinar, Haniya, si gadis manis dari Iran menegaskan mimpi terbesarnya: untuk menikahi lelaki Korea Selatan. Berbagai kriteria lain yang umumnya dipertimbangkan untuk memilih pasangan hidup—kepribadian, sikap, pekerjaan, agama, dan lain-lain—tak ia gubris sama sekali. Jangankan aku, Eunhee yang berasal dari Korea sampai geleng-geleng kepala.
“Tapi kenapa? Aku bahkan ogah sama lelaki Korea,” tanya Eunhee. Menurutnya, mayoritas lelaki Korea terlalu sering mabuk. Tentu, terlalu berbahaya untuk terjebak dalam stereotip. Tetapi, menurut Eunhee, “Nanti kalau suamimu bekerja, pasti banyak acara yang mengharuskan dia untuk minum alkohol. Dan kau pikir hanya alkohol? Tentu tidak. Tetapi suamimu harus melakukannya demi menyenangkan atasan. Meski begitu kau tetap mau menikah dengan laki-laki Korea?”
Haniya tetap mengangguk.
“Haniya, bukankah kau tidak boleh minum alkohol dan makan babi?” giliran aku bertanya.
“Naneun mujogeon hanguk namjaya! (Pokoknya, aku hanya mau sama laki-laki Korea!)” Haniya tak bergeming, menegaskan bahwa tak ada lain untuknya selain laki-laki Korea. Aku dan Eunhee hanya bisa menggelengkan kepala.
Tidak hanya menikahi lelaki Korea, sepertinya Haniya memang berminat pindah kewarganegaraan. Haniya memang pernah mengeluhkan sebelumnya tentang peraturan ketat di negaranya terhadap perempuan. Salah satu contoh, kudengar perempuan Iran dibatasi dalam bekerja dan belajar. Mereka pun diwajibkan untuk memakai rusari, kain penutup kepala. Sering kali kulihat ia melepas rusari-nya saat ia di Seoul. Tertangkap mataku Haniya yang merasa bebas, di Korea.
Ia menyatakan keinginannya menjadi Hani Lee. Ia memuji setinggi langit budaya Korea, yang pertama kali ia ketahui melalui drama. Tidak hanya Haniya yang murah pujian. Delegasi dari India juga menyampaikan bahwa drama Korea sangat membantunya melewati masa-masa depresi. Sementara delegasi dari Jerman memuji keindahan huruf Korea, Hangeul, yang menurutnya sangat ‘estetis’.
Aku? Aku hanya penonton biasa. Aku, dan 82 delegasi lainnya dari seluruh belahan dunia, saat itu sedang mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Korea di Seoul. Kami terpilih setelah memenangi perlombaan pidato bahasa Korea di negara masing-masing, dan hadiahnya adalah pelatihan ini. Tidak hanya pelatihan, ada juga putaran final dari perlombaan pidato, yang diikuti oleh 14 delegasi terpilih. Hadiah utamanya menggiurkan: beasiswa di salah satu universitas di Seoul. Salah satu yang berjuang memperebutkan hadiah utama tersebut adalah Haniya.
Para delegasi ini bisa berkumpul seperti itu karena kami tertarik dengan Korea. Kami semua terpukau dengan apa yang kami lihat di drama-drama dan apa yang dilakukan para oppa (kakak laki-laki) dan onni (kakak perempuan) berwajah surgawi. Hanya saja, yang membuatku kaget adalah karena Haniya tak hanya satu—banyak peserta lain yang siap mengubah kewarganegaraan saat itu juga.
Tak habis pikir aku membayangkan bagaimana mereka begitu inginnya meninggalkan tanah kelahiran demi mengejar oppa. Tentu, jika oppa idamanku tiba-tiba melamar aku pun sepertinya akan langsung pingsan karena bahagia. Tapi aku tak pernah terpikir untuk benar-benar menjadi orang Korea. Entahlah, mungkin karena aku tak bisa hidup tanpa sambel tempe.
Apa mereka benar berpikir bahwa mereka adalah orang Korea?
Apa sebenarnya “orang Korea” itu?
Apa makna dari “warga negara”?
Pergulatan berkecamuk dalam kepalaku. Ya, adalah hak Haniya untuk memilih: tetap menjadi Haniya atau menjadi Hani-ya (“ya” adalah imbuhan di belakang nama yang lazim digunakan dalam percakapan antara teman dekat di bahasa Korea). Haniya tak pernah meminta untuk menjadi warga Iran. Bisa jadi ia merasa terkungkung atas batasan yang diterapkan negaranya pada perempuan. Bisa jadi ia memang tidak puas dengan negaranya.
Aku memang tak berhak untuk menghakimi. Toh, mungkin saja Haniya bisa bertemu dengan oppa impiannya, bahagia selamanya. Namun, aku khawatir jika yang terjadi sebaliknya. Belum lama aku dengar cerita tentang gadis Vietnam bernama Nguyen. Belum genap umur dua puluh, ia pergi meninggalkan kehangatan rumahnya untuk mengadu nasib dengan ara menikah dengan laki-laki Korea. Dengan berbekal secuil bahasa Korea, Nguyen mempercayakan tabungannya pada jasa perantara, yang berjanji akan mencarikan laki-laki baik, serupa yang Nguyen lihat di drama favoritnya.
Tak dipungkirinya, Nguyen merasa sedikit kecewa saat bertemu dengan suaminya, yang bekerja sebagai petani di pedesaan serta seusia dengan bapaknya di Vietnam. Tetapi, Nguyen masih optimistis, bahwa suatu hari ia bisa menjadi warga Korea dan membawa seluruh keluarganya keluar dari jurang kemiskinan.
Apa daya, pernikahan tersebut hanya seumur jagung. Nguyen sebenarnya tak masalah hidup di desa—tak beda jauh dengan desanya sendiri. Tak masalah pula dengan kendala bahasa, ia rajin belajar di pusat budaya setempat untuk memperlancar kemampuannya. Yang jadi masalah adalah saat suaminya mabuk dan menjadi ringan tangan. Tubuhnya lebam, meski wajahnya tak tersentuh—bahkan di saat mabuk pun suaminya berhati-hati agar tidak menjadi buah bibir.
Awalnya ia coba bertahan, demi bisa menjadi warga Korea. Satu kalimat dari ibu mertuanya memicu Nguyen untuk memberontak. Nguyen sudah cukup paham bahasa Korea untuk mengerti, saat ibu mertuanya menamparnya seraya mengatakan, “Kau itu sudah dibeli, tahu?”
Apa yang terjadi pada Nguyen tak menjamin Haniya akan bernasib sama. Namun, ada satu persamaan dari keduanya: rasa ketidakpuasan pada negaranya. Menikah dengan lelaki Korea dirasa menjadi jalan keluar.
Nguyen dan Haniya membuatku mempertanyakan kembali hubunganku dengan negaraku.
Aku hanya warga negara Indonesia biasa. Kulitku kuning langsat, sukuku Jawa. Agamaku Islam, tapi negara tidak memaksa aku memakai kerudung—meskipun ada tekanan sosial untuk itu. Aku bebas sekolah, bebas memilih jurusan yang aku mau (suatu kemewahan untuk perempuan Iran). Aku pun beruntung berada dari kelas ekonomi menengah, sehingga aku tidak harus menikahi laki-laki yang tidak kukenal untuk menyambung nasib keluarga. Aku, yang beruntung ini, tidak berhak menghakimi mereka. Aku tidak berhak menghakimi Haniya atau Nguyen sebagai orang yang naif, terjebak dalam fantasinya tentang oppa-oppa di drama yang ditontonnya.
Entahlah. Mungkin karena saat itu aku sedang keranjingan membaca Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer. Jiwa nasionalismeku sedang meluap; membuatku cenderung menghakimi mereka yang kuanggap kurang nasionalis. Tetapi, siapa aku untuk menilai derajat nasionalisme orang lain? Bagaimana dengan nasionalismeku sendiri?
Seberapa jauh aku mengenal Indonesia? Rasa-rasanya aku lebih hafal anggota boyband Korea dibandingkan nama kota-kota di Indonesia. Tak kunjung kukuasai bahasa Jawa, meskipun orang tuaku asli Sragen, Jawa Tengah. Nilai bahasa Indonesiaku di sekolah bahkan selalu lebih rendah daripada nilai bahasa Inggrisku.
Ya, aku memang menyukai budaya Korea. Tapi bukan berarti aku bisa serta merta menanggalkan identitas Indonesia-ku demi oppa. Di Indonesia inilah aku berakar, suatu hal yang tak bisa tergantikan tak peduli berapa lama pun aku diberi kesempatan tinggal di Korea. Ini benar kurasakan sendiri saat tinggal di sana selama sepuluh bulan untuk pertukaran pelajar. Menjelang akhir masa pertukaran, aku hampir rela menukar seluruh uang beasiswaku untuk segelas wedang jahe dan sepiring tempe mendoan.
Haniya akhirnya keluar sebagai juara dalam perlombaan pidato tersebut. Juri sepertinya tersentuh dengan niatnya untuk benar-benar menjadi orang Korea. Sementara Nguyen, setahuku ia telah bercerai dengan suaminya itu, dan bertahan hidup dengan bekerja serabutan di Seoul. Nguyen masih berharap untuk bisa menjadi warga Korea.
Aku pulang dari Seoul membawa pekerjaan rumah: mengenali tanah airku, Indonesia. Ingin kukenali lebih dalam keindahan dan kebutuhan bangsa yang menghidupiku ini. Ingin aku menjadi “anak semua bangsa dari segala jaman” yang “menulis dalam bahasa bangsanya, dan berbuat untuk manusia-manusia bangsanya”.
Amy Darajati Utomo baru lulus dari IR dan menemukan pekerjaan sebagai penerjemah bahasa Korea dalam industri minyak dan gas. Saat ini ia sedang membuat peta masa depannya, meski ia tahu betul bahwa hal itu mungkin sia-sia, sambil berharap titik-titik itu akan bersatu.



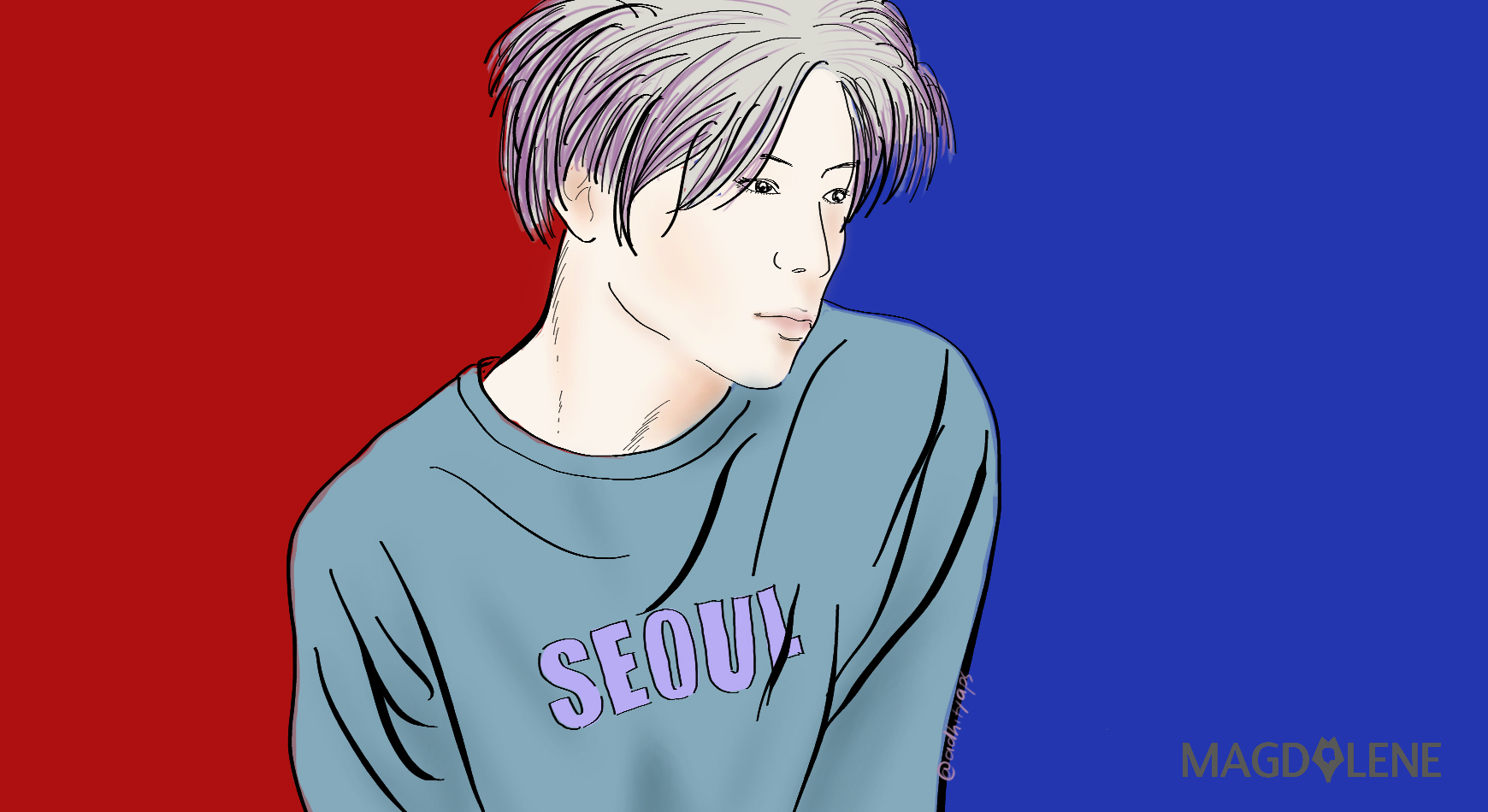



Comments