Budaya masyarakat yang masih sekadar “mengasihani” penyandang disabilitas, dan berbagai aturan yang menghalangi warga difabel untuk terlibat dalam ekosistem riset menyebabkan sangat sedikit penyandang disabilitas yang terlibat dalam penelitian di Indonesia, kata peneliti.
Ini menyebabkan minimnya riset di Indonesia yang melibatkan peneliti maupun perspektif disabilitas. Padahal, studi menunjukkan bahwa partisipasi kelompok difabel secara langsung dalam penelitian berujung pada kebijakan publik yang lebih inklusif dan tepat sasaran terhadap kebutuhan khusus penyandang disabiltas.
“Penelitian punya pengaruh untuk mendorong terciptanya kebijakan dengan memfasilitasi suara mereka terhadap apa yang menjadi halangan dalam keseharian mereka,” ujar Karen Fisher, profesor kebijakan sosial di University of New South Wales, Australia.
Ia menyampaikan hal ini pada webinar berjudul “Mengapa pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial penting dalam riset?” yang diadakan awal bulan September (2/9) oleh Knowledge Sector Initiative (KSI4DRI).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 10,8 juta penyandang disabilitas dengan usia kerja. Namun, hanya sekitar 5 persen yang memiliki gelar sarjana. Angka yang memiliki gelar doktor atau kualifikasi riset tinggi diperkirakan jauh lebih rendah lagi.
Berdasarkan data dari tim peneliti Universitas Airlangga, Jawa Timur misalnya, baru 7 persen dari total penelitian yang diterbitkan dari 2013 hingga 2017 menggunakan sudut pandang gender and minoritas secara umum. Riset yang khusus membahas hak penyandang disabilitas diperkirakan semakin sedikit.
Cara pandang yang ‘mengasihani’ warga difabel
Fajri Nursyamsi, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih memandang penyandang disabilitas dengan mentalitas belas kasihan, atau yang disebut sebagai “charity based approach”.
“(Orang lain) melihat disabilitas dari fisik dan mentalnya. Jadi, fokusnya hanya pada pribadi penyandang disabilitas, lihat kondisi tubuhnya, mentalnya, seperti itu,” kata Fajri.
Baca juga: ‘Aku Perempuan Unik’, Saat Perempuan Difabel Wujudkan Kesetaraan Lewat Seni
Bahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga mengategorikan difabel sebagai “anggota masyarakat bermasalah” yang punya “disfungsi sosial” dan dianggap seolah-olah “tak berdaya”.
Menurut Farjri, kelompok difabel dianggap harus menyesuaikan dengan lingkungan dan cara kerja masyarakat yang “normal”—mulai dari layanan umum, infrastruktur transportasi, hingga pendidikan. Bantuan sosial dianggap menjadi solusi utama untuk permasalahan warga difabel sehingga kebijakan pemerintah yang inklusif menjadi terbatas.
“Dampaknya, terdapat sedikit sekali motivasi bagi dunia akademik maupun pembuat kebijakan untuk melibatkan penyandang disabilitas secara inklusif,” katanya.
Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan “model sosial” di berbagai negara maju yang menempatkan pemenuhan hak warga difabel dalam berbagai kebijakan bukan sebagai “ketidakberuntungan”, tetapi sebagai bagian dari keberagaman di dalam masyarakat yang harus difasilitasi.
“Dengan pendekatan model sosial, isu disabilitas bukan sekadar menjadi isu ‘bantuan’, tetapi juga (dilihat) dalam sektor lain yang fokus (pada isu disabilitas), seperti pendidikan dan bencana alam,” tegas Fajri.
“Penelitian terkait penyandang disabilitas (saat ini) tidak jauh dari penelitian alat bantu, bantuan sosial, dan seterusnya. Padahal, penelitian harus dikaitkan pada lintas sektor.”
Banyak halangan institusional dari negara dan universitas
Minimnya sumber daya peneliti difabel juga disebabkan oleh adanya berbagai aturan yang meminta pendaftar jabatan peneliti untuk “sehat secara jasmani dan rohani”. Hal ini terlihat dari syarat untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mewajibkan calon dosen dan peneliti untuk “sehat secara jasmani dan rohani.”
“Teman-teman disabilitas mental misalnya, pasti akan tersisih dengan itu. Pilihannya bagi mereka adalah berbohong, atau sama sekali tidak punya NIDN, atau tersingkirkan untuk menjadi dosen dan peneliti di Perguruan Tinggi,” tutur Fajri.
Baca juga: UU Penyandang Disabilitas Sudah Ada, Tapi Pejabat Pemerintah Sendiri Belum Paham
Minimnya fasilitas pendukung di institusi riset juga memperparah akses penyandang disabilitas untuk terlibat dalam penelitian. Misalnya, hanya sekitar lima institusi pendidikan tinggi—di antaranya Universitas Brawijaya, Jawa Timur dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta—dari 4.500 universitas di Indonesia yang memiliki unit layanan bagi penyandang disabilitas.
Meskipun belum ada data secara nasional, Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) di salah satu kampus paling inklusif di Indonesia, Universitas Brawijaya, mencatat bahwa jumlah akademisi difabel di institusi mereka pun baru dua dosen.
“Padahal, untuk membuat suatu penelitian, harus dari lingkungan akademisi,” jelas Fajri.
Apa yang bisa dilakukan?
Para peneliti yang hadir dalam webinar tersebut mengusulkan adanya kolaborasi dengan komunitas difabel untuk memperbanyak penelitian yang melibatkan penyandang maupun perspektif disabilitas.
Karen menyarankan para peneliti untuk bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena LSM memiliki sumber data maupun pengalaman di lapangan yang lebih kaya terkait isu disabilitas.
“Misalnya, lewat komunitas atau organisasi beranggotakan disabilitas (bisa mendapatkan) data dan statistik yang berkaitan,” kata Karen.
“Pada akhirnya kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut untuk memahami berbagai penjelasan lebih mendalam dari data/laporan yang kita miliki.”
Karen juga mencontohkan suatu penelitian yang dilakukan dengan kolaborasi bersama Spinal Cord Injuries Australia, sebuah organisasi penyandang cedera saraf tulang belakang di Australia. Bersama dengan para peneliti, mereka duduk bersama membahas tujuan penelitian ini, membantu mengumpulkan berbagai data, hingga terlibat dalam melakukan wawancara dan survei. Hasil dari penelitian ini akan digunakan dalam proses revisi Undang-Undang Tahun 2014 tentang Inklusi Penyandang Disabilitas di New South Wales.
“Mereka jadi punya kredibilitas, mereka punya suara yang menggunakan bukti penelitian akademik,” kata Karen.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.





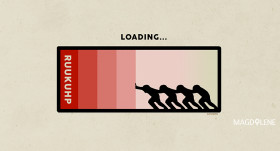

Comments