Oktober lalu, muncul kampanye #MeToo yang mengungkap pelecehan/aniaya seksual di Hollywood dan menjalar ke berbagai industri lain. Saya pun menulis status #MeToo tentang mengalami pelecehan di lingkungan sastra dan seni, terutama di Jakarta, tempat saya tinggal dan bekerja. Setelah itu, saya dihubungi oleh beberapa pihak untuk wawancara dan mengobrol, antara lain menyinggung soal apa yang dapat dilakukan oleh organisasi dan komunitas seni dan sastra untuk mengakhiri pelecehan dan aniaya seksual.
Oleh karena itu, saya ingin membagi beberapa gagasan yang pernah saya utarakan kepada seorang rekan di sebuah organisasi sastra yang bertanya kepada saya, apa yang dapat mereka lakukan. Mungkin gagasan-gagasan ini dapat digunakan sebagai pembuka percakapan tentang topik di atas, atau menyumbang kepada percakapan yang sudah terjadi di lingkungan masing-masing. Saya sadar saya bukan ahli dalam soal pendampingan korban maupun hukum yang relevan, tetapi gagasan-gagasan inilah yang masuk akal bagi saya. Saya harap kemudian kita dapat berkumpul dan merumuskan bersama apa yang sebaiknya kita lakukan, lalu bergerak bersama.
Pertama, merumuskan sebuah kode etik anti-pelecehan/aniaya seksual di lingkungan kerja, lengkap dengan prosedur standar untuk melaporkan kejadian pelecehan/aniaya seksual dan perlindungan korban. Ketika seseorang mengalami pelecehan/aniaya seksual, ia bisa jadi merasa sangat bingung, ketakutan, dan tidak tahu harus bagaimana, dan apakah ada yang mendukungnya. Adanya seseorang yang khusus bertugas untuk menerima dan menangani keluhan soal pelecehan/aniaya seksual dapat membantu. Tentunya seseorang itu adalah yang memahami masalah tersebut, kompeten dalam memberikan dukungan dan memberitahu korban segala pilihannya, serta dapat merujuknya ke berbagai pihak yang dapat menolong, entah itu dalam konseling, layanan kesehatan, layanan hukum, media, atau lainnya.
Orang itu sendiri mesti bebas dari tuduhan pelecehan/aniaya seksual, dan dipercaya oleh semua pihak, terutama mereka yang rentan terhadap pelecehan/aniaya. Harus pula ada jaminan kerahasiaan keluhan dan tidak akan ada resiko kerugian atau kehilangan kesempatan profesional bagi mereka yang berani melapor. Jangan sampai korban merasa takut tidak dipercaya atau justru dibungkam oleh orang yang bertugas menerima keluhan itu. Lebih baik lagi kalau dalam organisasi/komunitas dibentuk sebuah kelompok ally, atau kelompok dukungan (support group) yang dapat membantu korban bercerita, menghadapi pelaku, atau apa saja sesuai kebutuhannya, sehingga korban tidak merasa harus menjalani semuanya sendirian.
Selain itu, harus dirumuskan bersama proses penanganan keluhan. Jangan sampai melindungi nama baik organisasi/komunitas, apalagi nama baik pelaku, dijadikan prioritas di atas memberantas pelecehan/aniaya seksual dan memastikan perlindungan korban. Jangan juga menghalangi korban yang ingin menempuh jalur hukum atau melapor kepada media. Organisasi/komunitas dapat bekerja sama dengan lembaga yang memang berspesialisasi untuk membantu korban dalam hal itu. Organisasi/komunitas mesti siap memberikan sanksi profesional kepada pelaku. (Saya mendengar beberapa cerita tentang organisasi merasa kasihan kepada pelaku jika kehilangan pekerjaan, tanpa ada rasa kasihan kepada korban yang mesti mengalami trauma tiap kali bertemu pelaku di tempat kerja.) Kita pun dapat memberikan sanksi kepada organisasi/komunitas yang melindungi pelaku atau membiarkan pelecehan/aniaya seksual terjadi berulang kali. Mereka yang bertindak secara konsisten untuk memberantasnya dapat diberi pujian atau penghargaan.
Kita harus mengembangkan sebuah daftar pekerja media yang memahami isu pelecehan/aniaya seksual dan dapat melaporkan kasus-kasus seputar hal itu dengan sensitif. Daftar ini, berikut cara menghubungi para wartawan itu, dapat disebarkan ke berbagai organisasi/komunitas. Mereka dapat dihubungi apabila korban sepakat ingin bicara kepada media.
Komunitas/organisasi dapat memberitahu korban segala pilihannya, termasuk akses kepada hukum, konseling, dan pelayanan kesehatan. Kita dapat membuat pamflet berisi rujukan kepada berbagai organisasi konseling dan kesehatan. Pamflet ini pun disusun bersama lalu dibagikan kepada berbagai organisasi/komunitas seni dan sastra. Daftar ini mesti mudah diakses oleh anggota atau pekerja.
Banyak juga saya dengar cerita tentang penulis yang merasa ditempatkan dalam situasi tidak enak oleh senior yang mereka kagumi dan mereka harap dapat menjadi mentor—entah melalui ajakan kencan/berhubungan seksual, tatapan yang menelanjangi, atau lainnya. Walaupun hal ini belum tentu termasuk pelecehan, alangkah baiknya apabila organisasi atau komunitas sastra memperbanyak program mentoring resmi bagi penulis/seniman muda, agar mereka tidak usah merasa harus menahankan hal-hal yang tidak membuat nyaman tadi agar mendapat ilmu dari penulis/seniman senior, terutama mentoring sesama perempuan atau untuk mereka yang berasal dari kalangan minoritas atau yang kurang terwakilkan. Program ini menyertakan evaluasi tentang hubungan mentor dan muridnya, juga memiliki prosedur pengaduan jika terjadi pelecehan/aniaya pada suatu waktu.
Dalam kelas, seminar, atau forum yang menyasar penulis/seniman muda, terutama tentang berjejaring untuk penulis/pegiat seni muda, dapat diselipkan materi mengenai bagaimana menghadapi perhatian romantis atau seksual yang tidak diinginkan. Lalu apa yang dapat dilakukan jika mengalami ancaman atau tawaran tak senonoh (“kalau kamu tidur dengan saya, karya kamu akan saya terbitkan/kamu akan saya berikan pekerjaan/nilai bagus”)? Materi dapat pula menyertakan rujukan ke mana dapat mencari dukungan atau bantuan ketika mengalami perhatian yang tidak diinginkan.
Kita tidak bisa membicarakan soal mencegah atau menanggulangi pelecehan/aniaya seksual tanpa menciptakan masyarakat yang sadar soal perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab.
Kita pun mesti berkomitmen untuk memperbanyak perempuan dan minoritas di posisi kepemimpinan, orang-orang yang paham soal gender dan kekerasan berbasis gender di posisi kepemimpinan di penerbit, komunitas, dan organisasi seni dan sastra. Organisasi dan komunitas dapat bekerja sama dengan institusi yang berspesialisasi dalam bidang tersebut untuk mengadakan penataran seputar isu gender dan pelecehan/aniaya seksual.
Selain itu, promosikan ke mitra-mitra internasional tentang keberagaman organisasi seni dan sastra di Indonesia, sehingga tidak tercipta semacam monopoli yang dapat berakibat penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh.
Program-program di atas akan lebih bergigi apabila didukung oleh badan dan komunitas besar, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dewan kesenian di berbagai daerah, dan lainnya. Mereka dapat memimpin dengan memberi contoh, antara lain menerapkan langkah dan kegiatan yang disebut di atas.
Tampilnya logo mereka—tidak hanya logo lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau komunitas kecil—di program atau kegiatan seperti yang disebut di atas akan mengirim pesan kepada pelaku bahwa ini SERIUS. Kita bergerak ke masa depan di mana pelecehan/aniaya seksual tidak akan ditoleransi dan akan berpengaruh jelas pada karier pelaku.
Dan barangkali yang paling penting, kita tidak bisa membicarakan soal mencegah atau menanggulangi pelecehan/aniaya seksual tanpa menciptakan masyarakat yang sadar soal perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab, dan ini termasuk mendidik anak-anak muda kita tentang seks. Kita tidak bisa lagi membicarakan soal seks hanya dalam konteks dosa, pernikahan, atau reproduksi. Kita harus bicara tentang bagaimana memahami tubuh, gairah, kenikmatan, persetujuan, risiko serta tanggung jawab dalam perilaku seksual.
Satu hal lagi yang mesti saya tekankan adalah: kita harus melihat semua orang, tak peduli kelamin atau gender, sebagai setara. Kita baru akan melihat bahwa pemaksaan seksual itu salah apabila kita mengakui bahwa korban juga manusia seutuhnya dan setara. Perempuan bukanlah komoditi atau obyek pemuas gairah, juga tidak melulu korban atau calon korban. Perempuan mesti diakui juga sebagai subyek seksual yang berkehendak. Saya tidak ingin wacana pencegahan/aniaya seksual berujung membatasi kebebasan perempuan: dilarang keluar malam, dilarang berteman dengan laki-laki, dsb. Kita mesti memperbanyak percakapan dan wacana tentang apa artinya menjadi perempuan muda dewasa, apa artinya memilih untuk menjadi aktif secara seksual, bagaimana melindungi diri dan tetap menikmati dan memenuhi dorongan seksual.
Ketertarikan dan hubungan seksual adalah salah satu sisi hidup manusia yang paling kompleks. Soal seks tiap orang memiliki kesenangan berbeda-beda. Aku percaya tiap orang dewasa berkehendak bebas, walau banyak juga yang membuat keputusan berdasarkan ketidaktahuan. Oleh karena itu, kita dapat memperbanyak wacana dan percakapan soal berbagai bentuk hubungan, misalnya bagaimana hubungan yang mengandung relasi kuasa yang timpang bisa jadi lebih berisiko (walau menurutku belum tentu salah), dan sebagainya.
Terakhir, saya berbicara tentang lingkungan kerja yang aku merasa paling akrab, tanpa niat untuk membatasinya pada lingkungan itu saja. Saya sadar bahwa pelecehan/aniaya seksual terjadi di segala lingkungan, dan banyak rekan-rekan di luar sana yang jauh lebih rentan dan membutuhkan bantuan dan perhatian daripada aku sendiri.
Sekali lagi, gagasan-gagasan ini, dengan berbagai kekurangannya, saya tulis sebagai sumbangan kepada percakapan yang mesti kita lakukan bersama untuk kemudian bertindak bersama. Harapan saya, bersama-sama kita mewujudkan sebuah gerakan yang menjadikan suasana kerja kita lebih bebas dari rasa cemas akan pelecehan dan aniaya.
Eliza Vitri Handayani adalah penulis, kekasih, introvert, petualang, tidak religius, sering depresi dan kurang percaya diri, tapi pantang menyerah. Ia juga seorang penyintas dan banyak lagi. Sapa dia melalui Instagram dan Twitter: @elizavitri.
Ilustrasi oleh Florinda Pamungkasputri.



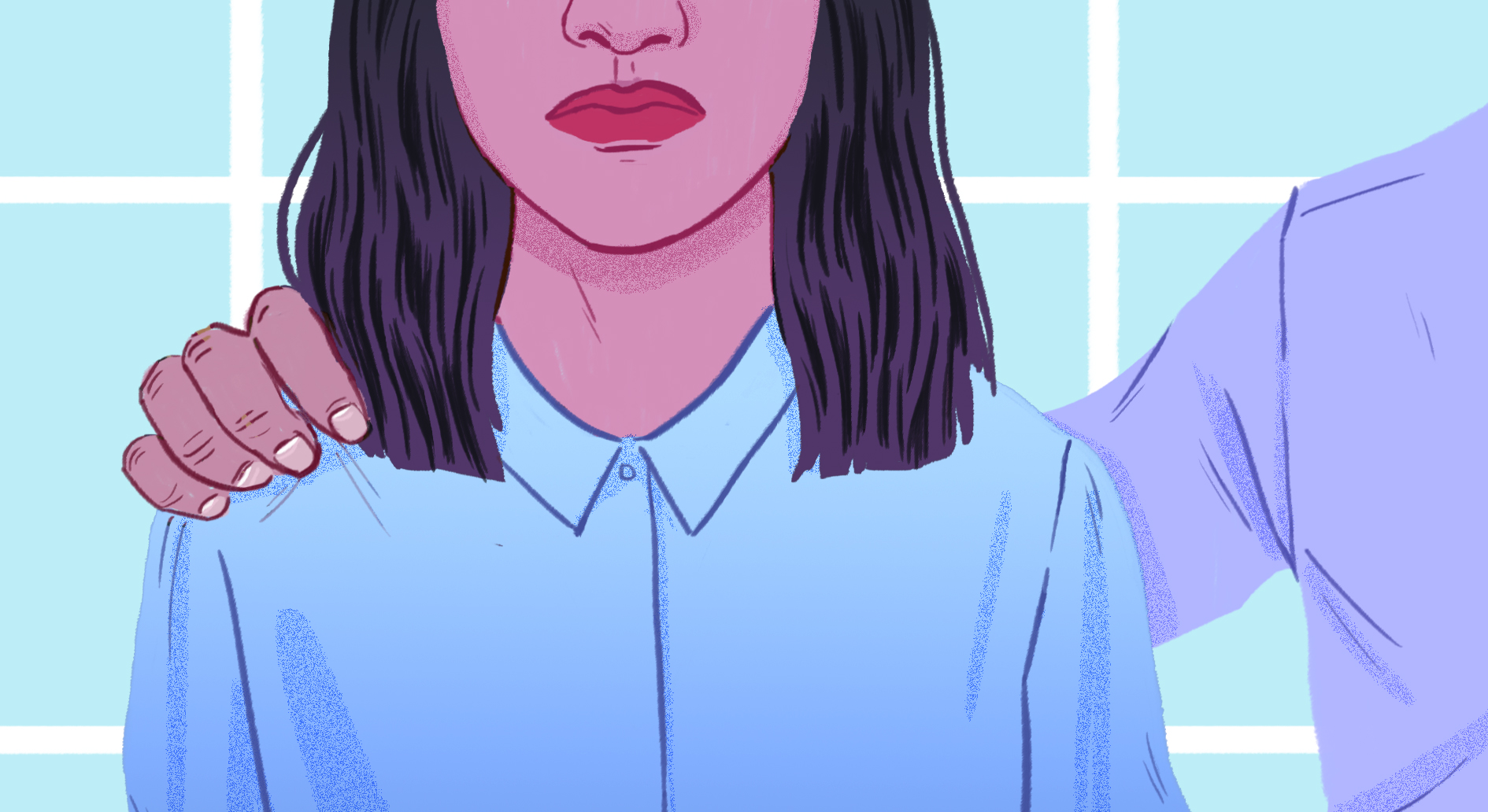




Comments