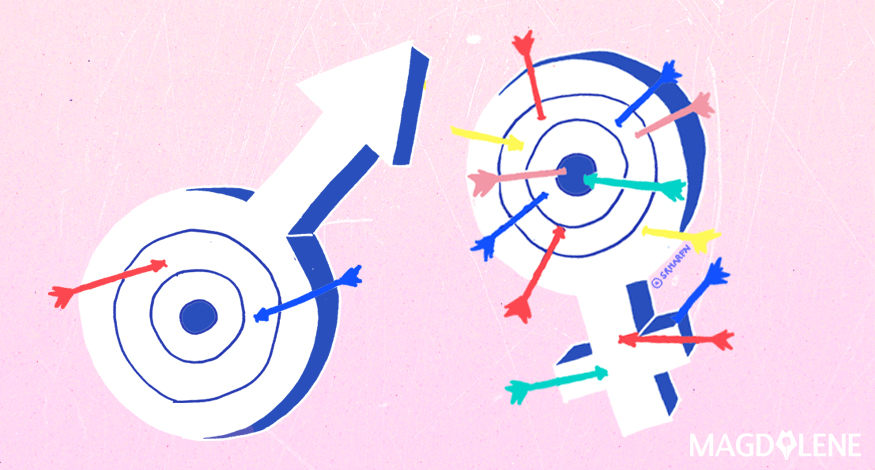
Para feminis sedang ketar-ketir dikuliti oleh publik. Baru-baru ini, salah satu tokoh pelopor #MeToo, Asia Argento, dituduh pernah memerkosa seorang aktor laki-laki yang saat itu berusia 17 tahun. Profesor Avital Ronnell di New York University (NYU) juga tengah menjalani penyelidikan karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang murid laki-lakinya di NYU. Yang kemudian menjadi sensasi adalah bahwa salah satu pemikir feminis, Judith Butler, menandatangani sebuah surat petisi yang meminta NYU untuk menghentikan penyelidikan kepada Ronell. Meski demikian, ia kemudian meluncurkan sebuah surat yang menyatakan kekhilafannya dalam menandatangani surat tersebut.
Di Indonesia, kasus terkait pelecehan seksual ini muncul bukan dari feminis lokal ternama, melainkan melibatkan Jonatan Christie, atlet bulu tangkis yang bertanding di Asian Games 2018. Jojo, begitu ia dipanggil, mendapat komentar-komentar yang “melecehkan” dari para penggemar perempuannya di akun Instagram pribadinya. Tanpa basa-basi, kasus ini pun dimanfaatkan oleh para anti-feminis untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap gerakan feminisme. Salah satu komentar yang sering muncul kurang lebih bunyinya seperti ini: “Ketika perempuan dilecehkan, para feminis marah. Tapi ketika laki-laki yang dilecehkan, ke mana para feminis? Ini adalah sebuah ketidakadilan gender!”
Komentar yang ada menunjukkan bahwa ketimbang menunjukkan simpati kepada Jojo, mereka mengambil lompatan logika bahwa kasus ini membuktikan feminisme tidaklah relevan, bahwa tidak ada penindasan secara struktural terhadap perempuan, dan bahwa perempuan layak dilecehkan karena laki-laki juga dilecehkan.
Terlepas dari kesalahan cara berpikir dalam pengambilan kesimpulan tersebut, sejumlah feminis mengambil posisi reaksioner dan membuat argumentasi dengan beban pembuktian yang sangat berat: bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban pelecehan seksual. Tulisan Nadya Karima Melati misalnya berupaya untuk membuktikan bahwa teori objektifikasi, budaya pemerkosaan, dan relasi kuasa membuat laki-laki imun dari pelecehan dan kekerasan seksual.
Dalam tulisan ini, kami berargumentasi bahwa pembenaran kasus pelecehan seksual terhadap Jojo bukan merupakan tindakan feminis dan bahkan berpotensi merusak arti gerakan feminisme yang sebenarnya.
Apa itu pelecehan seksual?
Yang patut disesali adalah akrobat logika dan argumentasi berbelit-belit dari para feminis ketika menjawab pertanyaan sederhana: “Apakah Jojo mengalami pelecehan seksual?” Konsep “relasi kuasa” kerap diulang ketika menjawab pertanyaan ini. Padahal, apabila kita melihat definisi resminya, “relasi kuasa” bukanlah sebuah kriteria untuk menentukan apakah suatu perilaku merupakan pelecehan seksual atau tidak.
Definisi dari Equal Employment Opportunity Commission menyatakan bahwa: “Pelecehan dapat mencakup ‘pelecehan seksual’ atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk kesenangan seksual, dan pelecehan verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual.”
Sementara itu, berdasarkan laman Sexual Assault Prevention and Awareness Center University of Michigan: “Pelecehan seksual didefinisikan oleh hukum sebagai permintaan untuk kesenangan seksual, pendekatan secara seksual atau perilaku seksual lainnya ketika (1) ketundukan/kepasrahan secara eksplisit atau implisit adalah suatu kondisi yang mempengaruhi keputusan akademis atau pekerjaan; (2) perilaku cukup parah atau mengakar untuk menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, tidak ramah, atau menjijikkan; atau (3) perilaku tersebut tetap ada meskipun ada pihak yang dikenakan perilaku berkeberatan.”
Zoe Williams dalam artikelnya di The Guardian mengutip Equality Act 2010 di UK bahwa pelecehan seksual adalah “perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang memiliki tujuan atau efek melanggar martabat seseorang, atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, menghina atau menyerang bagi mereka. Ini mencakup pernyataan tidak senonoh atau sugestif, sentuhan yang tidak diinginkan, permintaan untuk seks dan penyebaran pornografi.” Konsep relasi kuasa tidak menjadi bagian dari definisinya.
Narasi “relasi kuasa” juga berpotensi menjadi bumerang bagi gerakan feminisme sendiri karena dimensi relasi kuasa di masyarakat kompleks. Lihatlah misalnya kasus Argento atau Ronell yang sempat disebutkan di atas. Jika menggunakan logika “relasi kuasa” dalam artikel Nadya, Argento memang lebih inferior daripada korban laki-lakinya. Namun, Argento yang usianya lebih dewasa juga memiliki kekuasaan terhadap korbannya yang jauh lebih muda.
Ronell merupakan seorang perempuan dan korbannya adalah laki-laki. Tetapi, Ronell adalah seorang profesor dan memiliki kekuasaan atas keberhasilan karier akademis anak didiknya. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang menentukan bahwa apa yang dilakukan Argento dan Ronell merupakan pelecehan atau “ekspresi seksual sebagai perempuan yang terus digerus patriarki”? Mana relasi kuasa yang lebih penting atau lebih kuat di masyarakat? Apakah “relasi kuasa” dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan secara absolut hidup dalam sebuah vakum dan sepenuhnya terlepas dari faktor-faktor lain seperti usia, tingkat pendidikan, jabatan, bahkan kekayaan?
Sikap seorang feminis
Dalam menyikapi setiap kasus pelecehan seksual, sikap seorang feminis seharusnya mengarah kepada apa yang menjadi tujuan feminisme itu sendiri.
Feminis percaya bahwa perempuan ditindas oleh sistem penindasan paling tua di masyarakat, yaitu patriarki. Patriarki sebagai sebuah sistem dijalankan dengan gender yang membagi perempuan dan laki-laki menjadi kelas-kelas yang bersifat hierarkis. Dalam melanggengkan patriarki, laki-laki dicekoki nilai-nilai maskulin dan perempuan dengan nilai-nilai feminin untuk memastikan sistem penindasan tersebut berjalan dengan stabil di masyarakat.
Dalam kaitannya dengan kasus Jojo, pelecehan seksual dan objektifikasi adalah bagian dari belenggu peran gender maskulinitas yang perlu dihindari. Salah satu elemen penting hegemoni maskulinitas adalah keberadaan perempuan sebagai objek seksual laki-laki, seperti penelitian Mike Donaldson dari University of Wollongong yang dikutip dalam penelitian Nicolette Pacho dari San Jose State University tersebut. Objektifikasi seksual yang kerap dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan bisa dijelaskan dari wacana-wacana maskulinitas yang dominan, yaitu kompetisi antarlelaki, tidak emosional, dan menerima tekanan dari laki-laki lainnya. Bentuk maskulinitas ini merupakan salah satu produk patriarki yang berhasil dilakukan selama ribuan tahun.
Feminisme hadir dengan sebuah konsep masyarakat yang ideal, yakni masyarakat yang egalitarian dan bebas. Strategi utama feminisme adalah dengan membebaskan perempuan dari belenggu peran gender yang telah menindas perempuan. Untuk mencapai sebuah dunia sesuai yang diidealkan oleh feminis, kita menganalisis sifat dan peran manusia mana yang patut dipertahankan dan mana yang tidak. Tidak ada lagi yang namanya dikotomi peran gender maskulin dan feminin, sehingga manusia tidak lagi menggantungkan sifat dan peran mereka pada kedua hal tersebut. Jika maskulinitas membuat laki-laki mengobjektifikasi perempuan—yang kemudian menjadi alasan terjadinya pelecehan seksual—maka di dunia tanpa peran gender, maskulinitas juga akan hancur. Tidak akan ada lagi narasi bahwa manusia lain layak “dinikmati” hanya secara seksual.
Sikap feminis terhadap kekerasan seksual bukanlah dengan memperluas representasi pelaku untuk mengikutsertakan perempuan di dalamnya, melainkan menolak tegas dan menghancurkan tindakan-tindakan tersebut.
Dalam prosesnya, feminisme mendapat banyak penolakan bukan dari laki-laki saja, melainkan juga dari pihak perempuan yang tidak bisa membayangkan dunia tanpa kekangan. Tentu saja, 50 persen dari populasi dunia adalah perempuan, artinya banyak isi kepala dan ide yang bertentangan satu sama lainnya. Meski demikian, kaum anti feminis kerap menyamakan perempuan dengan feminis, tanpa memahami bahwa dalam tubuh feminisme sendiri banyak perempuan yang masih ingin bertahan di bawah patriarki.
Menjadi perempuan tidak otomatis membuat seseorang menjadi feminis. Mengimplikasikan bahwa semua perempuan adalah feminis sama saja seperti mengatakan bahwa setiap individu dari kelas pekerja pasti khatam Marx dan Engels sejak mereka lahir. Karena feminisme adalah sebuah paham yang dipelajari, maka salah satu cara feminis adalah mengedukasi untuk menyadarkan para perempuan (consciousness raising) mengenai opresi yang mereka alami.
Sama seperti perempuan bisa mendukung patriarki dan melawan feminisme, perempuan juga bisa mengadopsi nilai-nilai maskulinitas yang sudah ribuan tahun dipakai oleh laki-laki untuk menindas mereka. Namun, apakah yang dilakukan perempuan ini kemudian bisa dijustifikasi? Menurut kami justru perilaku ini menjauhkan kita dari masyarakat ideal yang feminis idam-idamkan.
Kami paham bahwa pendapat dari Nadya maupun teman-teman feminis lainnya berasal dari niat baik karena ingin mendukung feminisme. Sayangnya, pernyataan ini bukanlah taktik politik yang strategis karena tidak membawa kita ke masyarakat ideal yang seharusnya tidak memiliki perlakuan yang tidak merugikan kondisi material manusia lainnya.
Feminis sering jatuh ke dalam perangkap ini. Misalnya, ketika ditanya apakah perempuan sudi menjadi garda depan militer dalam perang, feminis reaksioner akan menjawab “Ya”, karena sejarahnya perempuan dianggap lemah sehingga menjadi garda depan militer akan memutarbalikkan stereotip tersebut. Jawaban ini bermasalah sebab tidak melakukan analisis mendalam bahwa perang merupakan kondisi di mana perempuan paling tertindas dan menderita, dan satu-satunya kesimpulan logis seorang feminis adalah perang seharusnya tidak ada, terlepas dari siapa pun yang berada di garda terdepannya.
Contoh lain adalah dalam banyak kasus penggusuran paksa di Indonesia, salah satunya di Surabaya, yang pemimpinnya adalah seorang perempuan. Lantas apakah karena pelakunya adalah perempuan maka penggusuran dapat dijustifikasi dengan feminisme? Pasti ada elemen kekerasan dalam penggusuran dan kekerasan sendiri merupakan sifat yang erat kaitannya dengan peran gender maskulin untuk menunjukkan dominasinya. Tentu saja sebagai feminis, penggusuran ini bukanlah sesuatu yang kita dukung dan justifikasi meskipun ada keterlibatan perempuan di dalamnya.
Sama seperti perang dan penggusuran, sikap feminis terhadap kekerasan seksual bukanlah dengan memperluas representasi pelaku untuk mengikutsertakan perempuan di dalamnya, melainkan menolak tegas dan menghancurkan tindakan-tindakan tersebut. Menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual yang telah merugikan perempuan secara material tentu jauh lebih penting daripada “memutarbalikkan stereotip” bahwa perempuan tidak memiliki ekspresi seksual. Sebuah gerakan politik yang komprehensif seharusnya membawa gerakan ke tujuannya, bukannya melawan stereotip belaka.
Priscilla Yovia adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum. Baginya, kesenangan yang sejati berarti dua hal: bisa shitposting di media sosial dan patriarki hancur lebur. Ia biasa menghabiskan waktu di akun Facebook, Twitter, atau Instagramnya: @priscyovia.
Anastasia Sijabat hanyalah warga biasa yang peduli tentang hak-hak perempuan. Eksistensi digitalnya yang sederhana biasanya berada di bawah nama @anasshrugged meskipun dia bukanlah penggemar Ayn Rand.
Ilustrasi oleh Sarah Arifin.



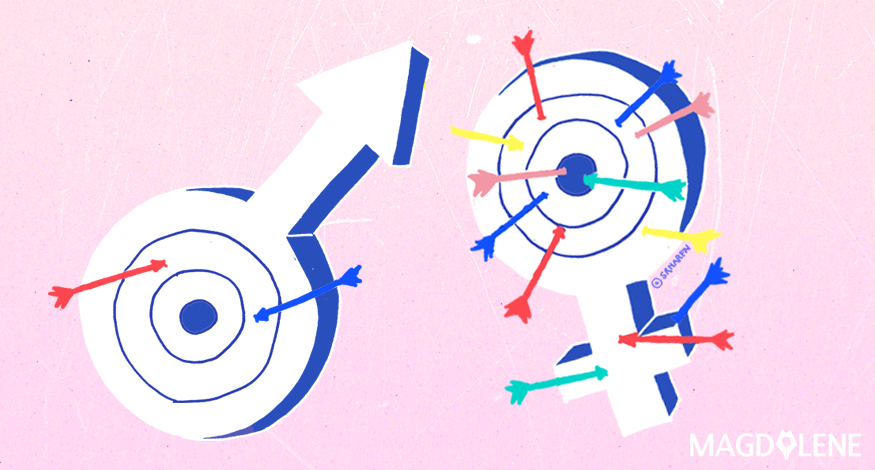




Comments