Baru tiga hari memakai krim pemutih, “Niki” terkejut mendapati kulit tangan dan kakinya gatal-gatal serta memerah. Namun ia tetap bersikukuh memakai krim yang ia beli dari toko daring itu karena berpikir masalah tersebut hanya gejala alergi minor. Beberapa hari kemudian, tak hanya gatal dan kemerahan, muncul juga garis-garis seperti stretchmark di bagian belakang pahanya.
Menyadari ada yang salah, ia segera menghentikan pemakaian krim dan pergi ke dokter kulit.
“Untung kulit saya masih bisa diselamatkan. Tapi jadi keluar uang banyak karena ada perawatan intensif sesudahnya. Lebih mahal dari krim itu,” ujar Niki, 23, kepada Magdalene baru-baru ini.
Saat itu baru pertama kalinya dia mencoba memakai krim pemutih. Sejak kecil dia memang suka diejek karena kulitnya yang sawo matang, namun baru setelah diputuskan pacarnya tahun lalu ia nekat membeli krim abal-abal dari internet.
“Aku diputusin pacarku karena kulitku katanya belang. Saat itu aku down banget. Sempat mikir kalau dunia ini hanya untuk orang-orang cantik dan putih,” ujar Niki.
Setelah itu, segala macam cara ia lakukan untuk membuat kulitnya lebih terang. Ia kemudian menemukan iklan-iklan lotion pemutih di online shop dengan beragam khasiat menggiurkan, yang ia pikir merupakan jalan pintas di tengah kebuntuannya. Setelah berpikir cukup panjang, Niki pun membeli salah satu krim tersebut, mengabaikan kekhawatiran di dalam benaknya karena melihat jumlah pengikut akun toko daring itu yang mencapai puluhan ribu, serta testimoni yang mereka bagikan.
Saat mengalami perawatan intensif, ia melihat unggahan di akun Instagram aktris Tara Basro, yang memperlihatkan kulit sejumlah perempuan yang penuh stretchmark akibat memakai krim sembarangan. Selain Tara, dokter spesialis kulit dan kelamin Listya Paramita juga membagikan soal kasus korban krim pemutih abal-abal di akun Instagramnya, @drmita.spkk.
“Aku bersyukur belum separah itu, masih bisa diselamatkan,” ujar Niki sambil bergidik.
Jika Niki resah karena warna kulitnya, “Nur” sering diejek karena pipinya yang tembam. Ketika melihat pesohor Barbie Kumalasari melakukan sulam lesung pipi, ia pun tergoda untuk mencoba. Berbekal berbagai bentuk testimoni yang ditawarkan sebuah klinik kecantikan, Nur pun rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah dengan harapan wajahnya akan terlihat lebih tirus dan manis.
Beberapa hari pasca pengerjaan sulam oleh staf klinik tersebut, pipi kanan Nur bengkak dan ada dua titik hitam di pipinya, selain titik dari benang yang ditanam di tempat bakal lesung pipi akan muncul. Kondisi ini menyulitkannya untuk berkomunikasi karena mulutnya sakit saat berbicara. Takut akan terjadi apa-apa jika dibiarkan lebih lama, Nur kembali ke klinik kecantikan untuk melepas benang yang sudah tertanam di pipinya.
“Soalnya pekerjaanku mengharuskan aku ngomong sama banyak orang, ” ujar perempuan berusia 27 tahun itu.
Baca juga: Butuh Belasan Tahun untuk Akhirnya Mencintai Kulit Gelapku
Ia merasa dirugikan karena dikenakan biaya tambahan meskipun benang yang ditanam susah payah itu tidak memberikan efek apa-apa, malah membuatnya sakit. Alih-alih menjadi tirus, wajahnya terlihat sama seperti sebelumnya.
Ketika ditanyai mengenai latar belakang dari sang penyulam, Nur menolak menjawabnya karena takut dituntut oleh klinik tersebut.
Standar kecantikan warisan kolonial
Dokter bedah plastik Teuku Adifitrian, yang lebih dikenal publik sebagai Tompi sang penyanyi, mengatakan banyak pasien di kliniknya adalah korban krim pemutih abal-abal.
“Ada yang dateng kulitnya udah pecah-pecah, kulitnya udah jadi stretchmark gitu, kasian banget. Dan itu enggak bisa diapa-apain. Sampai sekarang belum ada satu treatment yang terbukti efektif mengatasi stretchmark,” ujar Tompi, pemilik klinik kecantikan Beyoutiful Aesthetic, kepada Magdalene.
Ia juga banyak menerima pasien akibat komplikasi setelah melakukan sulam lipatan mata dan lesung pipi yang dilakukan serampangan oleh orang-orang tanpa latar belakang medis.
“Kasus lesung pipi sampai terjadi abses (bengkak bernanah) itu banyak bukan main. Memang ilmu ‘bengkel’-nya bisa dipelajari tapi dia kan enggak ngerti di anatomi di bawah jaringan matanya itu ada apa. Kalau ada apa-apa risikonya sampai terjadi kebutaan, jadi jangan sembarangan melakukan,” ujarnya.
Menurut Tompi, praktik sulam alis dan bibir masih bisa dilakukan salon-salon kecantikan karena tingkat komplikasinya masih sedikit. Namun untuk sulam lipatan mata dan sulam lesung pipi, seharusnya tidak dikerjakan oleh sembarang orang karena ada proses pembedahan kecil serta jahitan. Karena risiko komplikasi cukup tinggi, pengerjaan yang benar seharusnya oleh dokter bedah plastik, ujar Tompi.
“Namanya sulam lipatan mata, tapi pekerjaannya sudah benar-benar ngejait, membuat permukaan lubang kulit tembus ke bawah lalu diikat,” katanya.
“Sulam lesung pipi dan sulam lipatan mata itu pembodohan publik sih. Ini yang harus dihentikan, enggak boleh karena tingkat komplikasinya sangat tinggi,” ujar Tompi.
Pergulatan yang dialami Niki dan Nur bukan sesuatu hal yang baru. Definisi fisik perempuan ideal sebagai perempuan berkulit putih, berperawakan langsing, dan berwajah simetris merupakan standar kecantikan yang kadung menjadi sesuatu yang normatif.
Profesor Kajian Gender dari Universitas Padjadjaran Bandung, Aquarini Priyatna mengatakan, hal tersebut tidak terlepas dari warisan kolonial yang menempatkan ras kulit putih sebagai ras unggul, yang kemudian direduksi dan menjadi representasi cantik di banyak media.
“Dari dulu putih sebagai standar kecantikan enggak banyak berubah karena media tetap melanggengkan itu. Menyuplai kita dengan gagasan-gagasan itu kemudian kita memutarkannya, menekannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Aquarini, yang menulis buku Becoming White (2000).
“Saya percaya perempuan dan laki-laki itu berhak atas tubuhnya. Saya enggak bisa menyalahkan mereka karena peer pressurenya tinggi, medianya mengglorifikasi hal itu. Mereka akan berpikir everybody is doing the same thing so why can’t we?” ujarnya.
Baca juga: Kami Perempuan Melanesia, Kami Ada, dan Kami Cantik!
Pengawasan di mana?
Standar kecantikan kolonial semacam ini menciptakan pasar obat pemutih yang tidak pernah sepi pembeli, termasuk di dunia maya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mencatat transaksi produk mode di toko-toko daring mencapai Rp32,4 miliar sepanjang 2018, sedangkan pasar kosmetik sendiri mencapai Rp78,2 miliar di tahun yang sama. Angka transaksi bombastis tersebut juga dibarengi dengan peningkatan hampir 77 persen peredaran kosmetik dan obat pemutih tak berizin alias ilegal, menurut Mayagustina Andarini, Deputi Kepala BPOM Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
Perkembangan pasar kosmetik di dunia digital yang semakin bebas ini dinilai Tompi memerlukan mekanisme pengawasan khusus. Ia mengatakan perlu lembaga penyensoran barang-barang yang dijual secara daring, karena perlindungan konsumen itu harus diutamakan, apalagi produk yang dijual merupakan produk kesehatan.
“Bukan berarti melarang-larang orang berusaha, tapi diatur. Biar kalau ada apa-apa gampang dilacaknya,” kata Tompi.
Mayagustina mengatakan, pihak BPOM sudah melakukan pengawasan di semua bidang, termasuk di pasar digital. BPOM berperan dalam pengawasan pre-market dan post-market untuk menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk yang beredar.
“Kita awasi semua jalur peredaran kosmetik,” ujarnya.
Menurut Mayagustina, tren gaya hidup di media sosial serta makin banyaknya beauty influencer yang menerima endorsement tanpa memperhatikan legalitas produk yang mereka promosikan, mengakibatkan pelanggaran promosi kosmetik dan obat pemutih di media daring cenderung meningkat.
“Secara tidak langsung mereka turut andil dalam terciptanya ‘polusi’ pemutih ilegal,” tambahnya.
Meski BPOM mengklaim sudah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk mengontrol peredaran skincare abal-abal tersebut, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak obat-obat pemutih yang tidak berizin dijual secara bebas. Coba saja ketik “lotion kiloan” di berbagai sarana belanja daring, maka akan banyak muncul sederet krim dengan harga tidak masuk akal karena sangat murah. Satu kilogram lotion, misalnya, dihargai Rp200.000.
“Perlu ada lembaga penyensoran barang-barang yang dijual secara daring, karena perlindungan konsumen itu harus diutamakan, apalagi produk yang dijual merupakan produk kesehatan.”
Maraknya obat pemutih tanpa izin edar di pasaran ini diamini oleh Tompi.
“Obat pemutih yang beredar di pasaran itu setahu saya sebagian besar underground. Ini setahu saya ya, saya enggak bilang semuanya,” katanya.
Mayagustina mengatakan, di sinilah peran penting masyarakat dalam menjaga keamanan produk, dengan turut mengawasi dan melaporkan produk yang kadaluwarsa, ilegal, dan palsu ke BPOM.
“Untuk produk ilegal yang digunakan di skincare dilaporkan saja ke BPOM atau polisi agar ditindaklanjuti. Masyarakat harus berani melakukan ini supaya tidak llebih banyak jatuh korban,” ujar Maya.
Selain itu pihak BPOM mengaku terus melakukan inovasi agar bisa mengimbangi laju pasar digital dengan membuat aplikasi BPOM yang sudah bisa diunduh bebas. BPOM sudah mulai menerapkan ketentuan bahwa setiap produk yang beredar dan sudah berizin harus memiliki label 2D barcode yang nantinya bisa dicek melalui aplikasi tersebut.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, BPOM juga mengimbau mayarakat untuk lebih cerdas lagi memilih skincare maupun obat-obatan lain, dengan jalan cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluwarsa.
Baca juga: Iklan yang Merisak Perempuan: Tarung Bebas Penjaja Produk Kecantikan
Influencer dan representasi
Kehadiran media sosial, selain digunakan sebagai medium “pamer” diri dan gaya hidup juga merupakan ladang bisnis bagi influencer dengan pengikut ratusan ribu hingga jutaan tersebut. Mereka biasanya mengiklankan berbagai produk dari mulai mode, kosmetik, hingga skincare.
Para influencer yang umumnya sudah berkulit putih dan mulus dari lahir itu sadar atau tidak telah menciptakan standar kecantikan yang tidak kalah hiper realis. Namun sayangnya masih sedikit dari mereka yang paham dengan “pengaruh” yang mereka punya.
Kepada Magdalene, Mayagustina dari BPOM memperlihatkan data pengamatan berita media pihaknya yang menunjukkan banyaknya kasus para influencer yang didapati mengiklankan produk ilegal.
“Kami terus mengadvokasi influencer agar mereka tidak mempromosikan barang-barang ilegal. Kami juga sering berkolaborasi dengan mereka untuk membuat konten terkait hal itu,” ujarnya.
Menurut Tompi ada persepsi salah yang kadung tertanam oleh publik—banyak orang terbuai dengan apa yang sering ditonton mereka di televisi, film, maupun di media sosial.
“Mereka lihat orang kok kalau putih cantik ya, sehingga mereka tergoda ingin jadi seperti itu. Padahal banyak juga orang yang tidak putih tetap cantik,” ujar Tompi.
Ia menambahkan, masyarakat juga masih perlu diedukasi bahwa yang penting itu bukan warna kulit, tapi apakah kulitnya sehat atau tidak, dan memiliki tingkat kelembapan yang baik.
“Banyak pasien yang datang ke saya ingin putih, dan jawaban saya selalu sama dengan yang saya sampaikan tadi, untuk apa? Karena injeksi pemutih tuh bukan tanpa risiko. Ada risiko mulai dari batu ginjal dan segala macam,” kata Tompi.
Aquarini mendorong adanya keseimbangan representasi di media agar perempuan tidak melulu melihat model-model dengan jenis kulit dan wajah ideal yang hiper-realis.
“Media sosial itu mengafirmasi apa yang dianggap ideal apa yang bukan, jadi orang akan dituntut menampilkan diri ideal. Jadi kalau medianya seperti itu dan kita terlibat di dalam pelanggengan itu dalam praktik keseharian kita ya enggak akan berubah-ubah,” ujarnya.
“Semua punya bayangan normatif tentang apa yang ideal, mempraktikkannya sehari-hari, mengartikulasikannya menegaskannya dan mempercayainya. Kita tidak melihat representasi perempuan yang lain selain definisi yang sudah jadi normatif tadi. Kalau kita tidak punya media literasi, maka yang begitu akan terus berputar, perempuan dan laki-laki akan terpengaruh.”




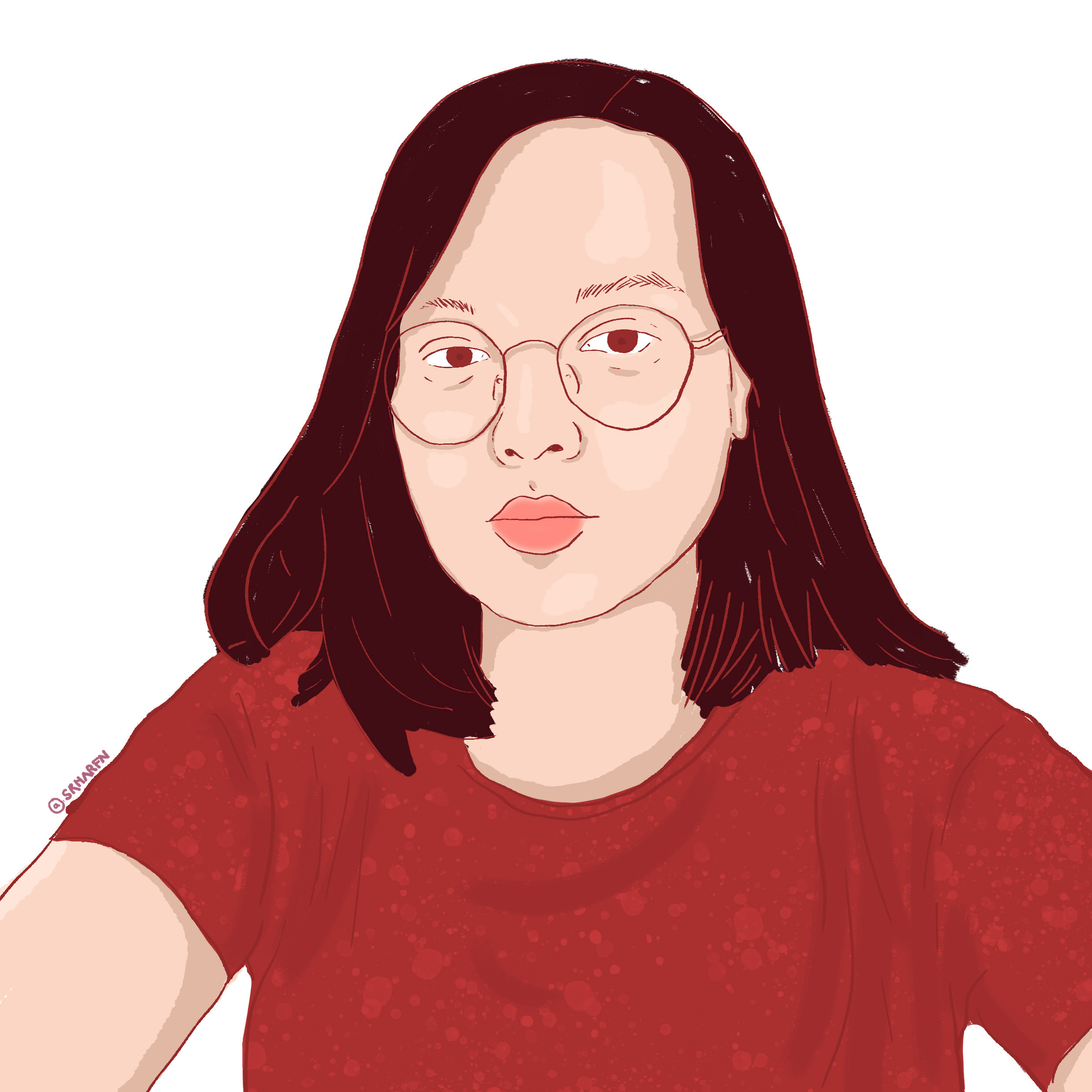
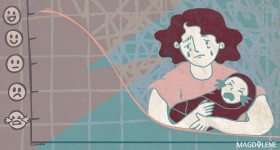


Comments