“Saya perempuan. Saya punya kelamin perempuan. Ya mandikan saya dengan pakaian perempuan. saya mau dimakamkan sebagai perempuan,” tegas Dorce Gamalama dalam wawancara di Youtube Denny Sumargo.
Nama Dorce belakangan jadi obrolan lagi, karena permintaannya dikebumikan sebagai perempuan. Pernyataan itu menuai polemik dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis yang mengutarakan pemakaman jenazah transgender harus dilaksanakan sesuai jenis kelamin ketika ia dilahirkan. Alasannya, tidak ada perubahan jenis kelamin dalam ajaran Islam, kecuali kelainan medis.
“Ikuti jenis kelamin awal, toh nanti yang mati enggak protes. Kalau diikuti wasiatnya, nanti jadi dosa,” katanya pada BBC Indonesia.
Respons senada datang dari ulama Buya Yahya. Ia mengatakan dalam kanal Youtube Al-Bahjah TV, Dorce tetap orang beriman. Namun, secara hakikat ia tetap seorang laki-laki, sehingga hak waris dan jenazahnya perlu diurus seperti laki-laki.
Menanggapi pertentangan ini, Dorce angkat bicara melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya. Ia berpesan, para pemuka agama tidak perlu terlibat dalam prosesi pemakamannya, dan menyerahkan urusan itu pada anggota keluarganya.
“Seharusnya Anda seorang kiai memberikan imbauan kepada siapa pun, karena saya juga manusia,” ujarnya, sekaligus meminta agar tidak ada komentar-komentar tidak baik terkait keinginannya itu. Dorce sendiri telah menyiapkan urusan pemakamannya bersama keluarga, sehingga tak perlu diurus orang lain.
Baca Juga: Lihat Lebih Dekat: Pengakuan Seorang Mantan Transfobia
Bukan Urusan Orang Lain
Peristiwa yang dialami Dorce tidak mengejutkan. Transpuan memang kelompok yang masih tertindas secara struktural.
Dina Listiorini mencatat, bentuk diskriminasi paling kelihatan itu ada dalam sistem layanan kesehatan. Ia mencontohkan, sejumlah masyarakat dan profesional yang belum inklusif masih menyematkan label “gangguan jiwa” terhadap komunitas LGBT.
Keterbelakangan ini juga hadir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia, yang masih mendefinisikan transgender sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Padahal, sejak 2019, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan identitas transgender bukan lagi “gangguan jiwa” melalui International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11).
Diskriminasi dalam institusi kesehatan itu berbuntut panjang. Penolakan identitas transgender diamini masyarakat juga turut dipengaruhi diskriminasi dalam institusi agama.
Meski Dorce telah dikenal lama dan cenderung diterima khalayak umum, dibanding kebanyakan individu transpuan lainnya, wasiat tentang pemakamannya kembali menyulut sikap transfobik banyak orang. Sepemantauan Magdalene, banyak komentar negatif yang tidak menghormati keputusan dan identitas gender Dorce di unggahan Instagramnya.
Amar Alfikar, teolog dan aktivis transpria, menyebut dua faktor besar yang mendorong tindakan diskriminatif yang dilakukan netizen pada Dorce. Yakni, pemberitaan media arus utama dan narasi agama.
“Seharusnya media menyajikan pemberitaan dengan penuh respect terhadap keragaman gender, bukan yang judulnya provokatif dan isinya enggak mengedukasi,” katanya pada Magdalene.
Sementara narasi agama yang disampaikan selama ini masih sangat biner dan heteronormatif (biner), menurut Amar. Sehingga, sebagian orang terjebak dalam perspektif yang tidak ramah keragaman gender dan seksualitas. Ia mengatakan, dalam hal ini tokoh agama berperan penting dalam memengaruhi tindakan umatnya.
“Ustaz-ustaz yang mengomentari kehidupan Bunda Dorce itu juga berperan membawa jemaahnya berpikir, atau bertindak tidak menghargai orang lain,” ucapnya.
Amar yang transpria, tak jarang juga mengalami hal serupa Dorce. Buatnya sendiri, diskriminasi berbentuk komentar negatif dari warganet adalah “makanan sehari-hari”. Alih-alih menanggapi, Amar memilih mengelola media sosial sebagai safe space. Ia sadar betul setiap pengguna memiliki kontrol penuh media sosialnya masing-masing.
Ia tak ragu memblokir pengguna atau komentar yang mengganggunya, jika dianggap melelahkan. Atau kembali ke support system-nya sendiri, ketika membutuhkan mereka.
Menurut Amar, ada peran pemerintah yang besar dalam permasalahan ini. Jelas bahwa fungsinya menjamin keamanan dan keadilan masyarakat, termasuk yang rentan, tidak berjalan. Kata Amar, pemerintah perlu memberikan edukasi menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat tentang memperlakukan kelompok minoritas.
Baca Juga: Bebaskan Diri dari Jebakan Kelamin
Pasalnya, diskriminasi yang diterima kelompok transgender bukan hanya tentang keributan cara pemakaman. Namun, terjadi di sekujur hidupnya.
Amar menceritakan, sejak pandemi ia sering mendengar dari teman-teman transpuan di beberapa daerah meninggal. Kadang tiga sampai lima transpuan meninggal dalam satu bulan.
“Waktu itu seorang transpuan asal Kebumen meninggal di Yogyakarta, dibawa teman-teman ke RT dan kelurahan setempat, tapi enggak ada yang mau ngurusin,” ungkap Amar.
Pada akhirnya, teman-teman transpuan bersolidaritas sendiri mengurus jenazah kawannya. Sesuatu yang tidak terjadi pada kelompok lain.
Pembedaan secara struktural ini juga perlu diselesaikan secara struktural. Untuk itu, Amar menegaskan perlunya kehadiran negara sampai ke akar rumput untuk mengikis penderitaan yang dirasa komunitas transgender.
“Sapalah perwakilan mereka di kampung dan desa-desa, ajak untuk menghormati tubuh orang lain, baik ketika hidup ataupun mati,” imbuhnya.
Islam yang Inklusif
Pendiri Hijrah Indonesia Gayatri Wedotami mengatakan, Islam harusnya adalah agama yang inklusif, sebab mengajarkan menghormati perbedaan di antara umat.
Ia menjelaskan, transgender sebetulnya bukan sesuatu yang tidak ada dalam fikih—ilmu yang mengatur kehidupan manusia dalam Islam. Istilah paling dekat dengan transpuan adalah mukhannats. Istilah itu digunakan untuk mendefinisikan perempuan dan laki-laki yang menyukai dan merasakan rangsangan seksual terhadap sesama jenisnya.
Aziz Anwar Fachrudin, dalam Khuntsa, Mukhannats, Transgender, menulis definisi “mukhannats” lebih tepat diterjemahkan sebagai “effeminate man”, lelaki yang perilakunya seperti wanita. Sehingga tidak tepat mendefinisikan transgender dengan makna hari ini: Orang yang identitas gendernya bukan seperti yang diberikan padanya saat lahir. Menurut Aziz, bahasa Arab modern untuk transgender adalah “al-mutahawwil jinsiyyan” atau kadang disebut singkat dengan “mughayir”.
Namun, terlepas dari mempeributkan makna, menurut Aziz, sudah waktunya bagi umat Islam untuk menambah pengetahuan tentang ilmu gender, yang memang lahir di zaman modern. Termasuk bagaimana fikih meresponnya.
“Bila anda bersetuju bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas ilmu, maka mari sama-sama belajar dulu sebelum marah-marah. Ujaran wahyu pertama adalah “bacalah”, bukan “emosilah”,” tulis Aziz.
Baca Juga: Asha bukan Oscar: Membongkar Miskonsepsi Soal Transgender
Buat Gayatri sendiri, faktor politik dan kolonialisme berperan penting dalam proses pemudaran identitas mukhannats dan pengembangan ilmunya dalam fikih. “Fikih tersebut memudar akibat dikomodifikasi dalam bentuk hukum tunggal, kemudian muncul hukum syariat,” ungkapnya.
Ia menyebutkan dalam ajaran Islam tidak terdapat kewajiban mengebumikan seseorang sesuai jenis kelamin sewaktu ia dilahirkan. Hanya terdapat perbedaan kecil, seperti jumlah lapisan kain kafan yang digunakan dan dhomir, kata ganti dalam pelafalan doa berdasarkan jenis kelamin jenazah.
Sebagai bentuk dukungannya, pada awal Februari lalu perempuan yang aktif sebagai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) itu menulis surat terbuka untuk Dorce, melalui laman Facebook Hijrah Indonesia.
Ia juga menyampaikan solusi, agar transpuan muslim mempelajari tata cara pemakaman. Dan nantinya, setiap transpuan, transpria, dan interseks—kelompok yang sering kali dikecualikan dari heteronormatif—dapat diperlakukan sebagaimana harapannya dengan identitas gender yang mereka pilih sendiri.
“Saya khawatir Dorce tidak menemukan sosok kiai atau guru yang dekat dengannya,” ujarnya, menjelaskan alasannya menulis surat tersebut.
“Saya berharap dengan surat itu, teman-teman trans(gender) dan interseks lain yang belum punya komunitas, mulai berpikir untuk bergabung dan menolong satu sama lain,” kata Gayatri.
Ilustrasi oleh Jeje Bahri



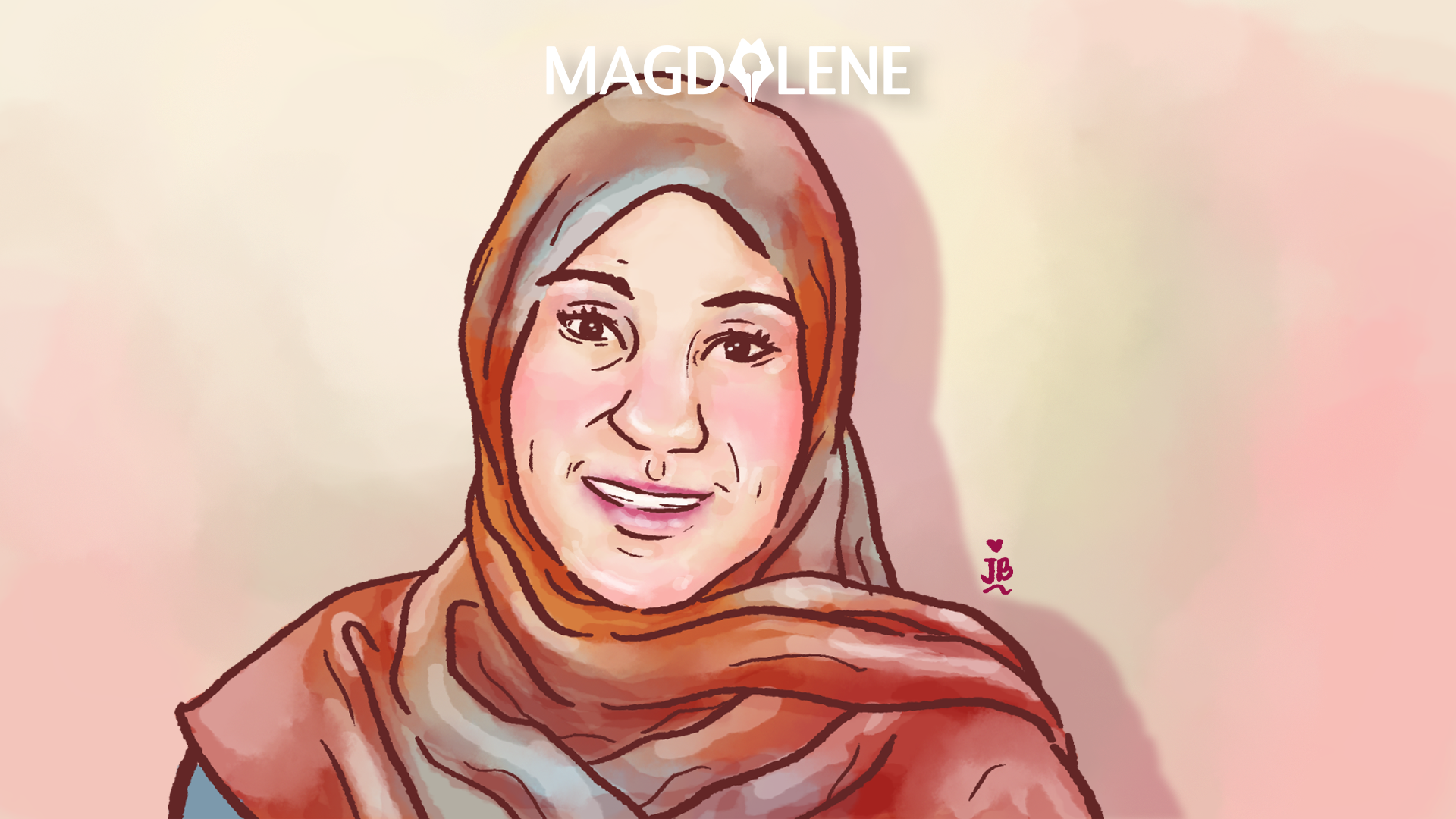




Comments