Kalimat ini masuk ke grup WhatsApp saya, menanggapi “malam pertama” yang akan dilewatkan teman saya. Ternyata, meski sudah 2017, dimana sebentar lagi (mungkin) akan ada yang bisa tinggal di Mars, pertanyaan seputar darah di malam pertama masih sering disemburkan. Saya jengah dengan pertanyaan tersebut dan dengan muka beku menatap layar ponsel yang terus berdenging memunculkan tawa dan komentar-komentar dari teman-teman yang lain.
Kemudian baru saya sadar kalau saya masih di Indonesia, dimana budaya patriarki masih mengikat erat sampai ke nadi. Dimana pertanyaan seputar keperawanan masih dianggap penting. Kesucian perempuan masih dinilai dari selaput tipis yang melekat di celah vaginanya. Kenapa masyarakat tempat saya lahir masih berpikiran kerdil seperti ini?
Pertanyaan-pertanyaan seputar keperempuanan masih sangat gencar diperdebatkan. Norma kemoralan masih ditekankan kepada perempuan. Perempuan harus bla, bla dan bla. Ada banyak catatan juga coretan tentang perempuan yang harus dituruti supaya jangan dicap tak bermoral. Yang sebenarnya kalau diurut-urut hanya lah demi pemenuhan pembuktian kepantasan untuk laki-laki.
Terkadang saya mempertanyakan kenapa kesetaraan seksual antara perempuan dan laki-laki belum tercapai, padahal dunia kesenian Indonesia sudah cukup menggebrak tembok-tembok hipokrit dan memberikan lahan yang luas untuk tema-tema gender terlebih perempuan untuk menuangkan karyanya. Film-film pendek karya seniman perempuan, misalnya, banyak yang mengangkat isu-isu gender yang dulu tabu secara terbuka dan gamblang.
Lantas, kenapa masih ada pertanyaan seputar darah di malam pernikahan? Sebenarnya saya tidak perlu merenung terlalu lama karena mereka yang di sekeliling saya membuka tabirnya sendiri. Kebetulan saya pernah dekat dengan beberapa penulis laki-laki yang lewat percakapan-percakapan ringan mengungkap betapa seksis pemikiran mereka.
Karya-karya (sebagian dari) mereka boleh saja menguarkan aroma keadilan, kesetaraan, kebebasan berpikir namun pada sebenarnya pikiran (sebagian) mereka masih terjebak dalam celana dalam yang menyempit saat birahinya menggelegak.
Saya masih perempuan (cukup) lugu saat menginjakkan kaki di ibukota yang menjanjikan mimpi dan kepuasan syahwat ini. Saya suka membaca dan (dulu) mengidolakan sejumlah penulis sebelum sadar kalau istilah masih banyak ikan di laut itu nyata adanya. Mengomentari kesenangan saya membaca, mantan pacar saya dulu bilang, “Suatu saat kamu akan duduk semeja dengan penulis (dia menyebut beberapa nama) dan mengobrol seperti teman.”
Akhirnya memang yang dibilang mantan saya benar, bukan cuma duduk semeja, kami bertukar cerita dan “membuat” kisah. Harga yang mahal untuk sebuah pengalaman bersastra? Dari kedekatan inilah saya menyadari kalau cerita-cerita (sebagian) mereka malah lebih menarik ketimbang cerita yang (sebagian) mereka tulis.
Jelas (sebagian) mereka bukan “setengah dewa”. Kebetulan saja (sebagian) mereka adalah laki-laki yang diberkahi kemampuan menulis namun (sebagian) mereka tetap laki-laki pada umumnya yang terkadang dikalahkan oleh keinginan syahwat. Berkata-kata manis untuk mencicipi kebodohan pembaca muda?
Saya pernah menanyakan ke salah satu dari mereka yang pernah dekat dengan saya, mengenai kebiasaan berhubungan seks dengan pembaca. Siapa saja? Dia menjawab, ada yang mahasiswi, pekerja kantor, pernah dengan istri orang yang belakangan dia tahu kemudian dia sesali (katanya). Kemudian satu yang saya ingat adalah dia mengatakan kalau tidak mau berhubungan dengan perempuan yang masih perawan. Alasannya? “Kasihan…” Kasihan karena dia tidak akan menikahi perempuan tersebut. Ini sama saja dengan mengatakan perempuan yang tidak perawan boleh ditiduri karena sudah bekas jadi tidak masalah, yang jadi masalah adalah perempuan yang “segelnya” masih utuh.
Ketika itu “agama” saya masih sastra dan menganggap jawabannya sebagai bentuk kemanusiaannya sebagai laki-laki. Percakapan melompat ketika kami membahas tentang seorang seniman yang diperkarakan karena katanya memperkosa seorang mahasiswi. Komentarnya adalah, “Kasihan padahal perempuan itu sudah nggak perawan lagi saat tidur dengannya (si seniman).” Ketika saya mendebatnya, dia menjawab, bukan itu maksudnya, “Dia (si seniman) dijebak,” tambahnya lagi, semakin absurd.
Betapa menyedihkannya menjadi tidak perawan di negeri ini, dicap barang bekas, dicap liar, sundal, kotor, apa lagi? Lebih menyedihkannya pemikiran ini datang dari (sebagian) mereka yang mengaku berbudaya dan gencar melontarkan keadilan baik secara verbal maupun tulisan di media, termasuk media sosial. Betapa menyedihkan hidup dalam dunia hipokrit, menjual tulisan dengan bungkus sosial untuk sejengkal perut dan masturbasi pujian.
Saya terbangun dari lamunan dengan tangan masih memegang ponsel yang layarnya sudah berwarna gelap. Ketika saya cek, tidak ada lagi komentar di grup WhatsApp yang membahas soal darah di malam pertama. Saya pikir, wajar kalau darah masih dibahas di malam pertama, keperawanan masih jadi bahan perdebatan, tolak ukur kesucian seorang perempuan. Bukannya mereka-mereka yang sejatinya corong untuk membawa isu gender ini ke ranah yang serius menjadikan ini sebagai hiburan, sensasi dan jualan? Dan ternyata bagaimanapun juga, apakah Kartu Jakarta Jomblo jadi dibuat atau tidak, tetap harus ada “darah” di antara laki-laki dan perempuan.
Ester Pandiangan berusia 31 tahun. Sejak 2008 sampai sekarang bekerja sebagai jurnalis. Saat ini sedang berdomisili di Medan dan ingin segera menetap di Yogya (kalau Tuhan mengizinkan).



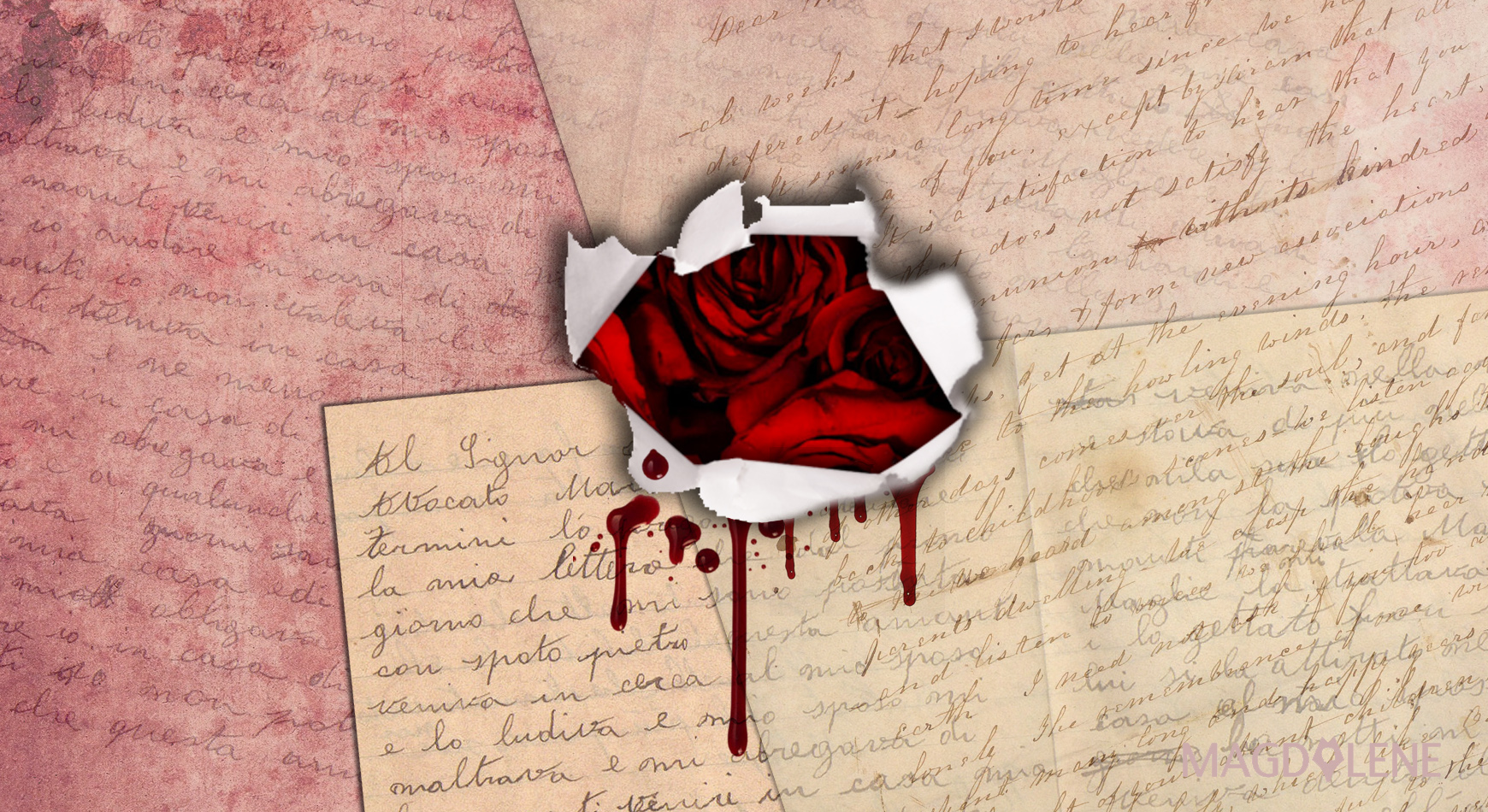




Comments