Ketika Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy mengumumkan adanya sertifikasi pernikahan pada 2020, muncul polemik mengenai kebijakan ini. Kelompok pro berkata ini sebuah ide bagus untuk mengetahui aspek psikologis dan finansial calon mempelai, serta memberikan informasi soal kesehatan reproduksi dan ke mana harus melapor dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kelompok kontra menilai praktik sertifikasi ini harus diawasi untuk mencegah materi yang generik dan memosisikan perempuan semata-mata sebagai pengemban tugas domestik serta penyedia layanan seks.
Saya sendiri memutuskan menikah tahun lalu ketika berusia 25 tahun. Untuk ukuran orang Indonesia, menikah pada usia 20an adalah hal yang umum dan mewah. Saya bisa menikah karena saya heteroseksual, cisgender, dan calon suami saya sudah mapan. Pernikahan bagi saya bukan akhir bahagia dari pacaran, tetapi level lebih tinggi dari relasi romansa: persahabatan seumur hidup.
Saya paham bahwa pernikahan adalah babak hidup yang rumit dan kompleks, sehingga sebelum memutuskan untuk menikah, saya dan pasangan perlu mempersiapkan diri lahir-batin. Selayaknya maju dalam pemilihan presiden, kami melakukan uji kepatutan dan kelayakan, mulai dari pemeriksaan kesehatan reproduksi dan membuat rencana terkait anak, sampai menghitung kemampuan finansial, melakukan pemeriksaan medis menyeluruh, serta liburan bersama untuk menguji sejauh mana kami bisa menghadapi konflik dan menyelesaikannya. Setelah itu, kami membuat agenda waktu untuk persiapan pernikahan secara administratif.
Kini, setelah satu tahun pernikahan berjalan, saya menyadari kunci dalam pernikahan adalah hubungan pernikahan yang setara.
Tentu bukan saya seorang yang menikah di usia 25 tahun; beberapa teman saya pun sudah menikah. Sebagai sesama pengantin baru, saya memperhatikan beberapa teman yang saling berbagi cerita tentang pernikahan barunya. Kita tidak bisa menghindari konflik dalam sebuah hubungan romansa dan tidak ada sebuah pernikahan yang adem-ayem saja. Setiap pernikahan pasti punya masalah dan sejauh mana kita bisa bernegosiasi dan mengelola masalah dalam pernikahan kita. Sebenarnya manajemen konflik dengan pasangan bisa dilakukan sebelum pernikahan dengan berlibur atau tinggal bersama. Sayangnya di Indonesia, tinggal dan liburan bersama pasangan bukan sesuatu yang umum dilakukan sebelum menikah.
Karenanya, saya menemukan banyak pasangan baru mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik dan berkomunikasi dengan pasangannya. Istri-istri sering melempar kode-kode media sosial untuk suaminya atau melakukan pola komunikasi pasif agresif ketika menginginkan sesuatu. Di permukaan, terlihat bahwa ini adalah masalah komunikasi karena istri sungkan bicara secara langsung sementara suami tidak mau mendengar. Namun masalah sesungguhnya lebih dalam daripada itu.
Perempuan makhluk yang sulit dimengerti?
Mengapa istri dan perempuan tidak bisa bicara langsung tentang apa yang dia mau kepada suaminya? Buang jauh-jauh hipotesis ala buku Why Women Can’t Read Maps and Men Don't Listen sebab feminisme melakukan analisis mengapa perempuan harus kode-kodean jika menginginkan sesuatu. Masalahnya adalah hubungan yang tidak setara yang berasal dari psike (jiwa) perempuan.
Perempuan terus menerus didoktrin untuk menjadi “pelayan suami” sehingga perempuan tidak mampu mengungkapkan pendapatnya secara langsung dan memutuskan sesuatu. Khususnya seorang istri, dia tahu apa yang dia mau tapi dia tidak mampu mengungkapkannya karena ia tahu ia berada di posisi yang inferior dalam rumah tangga. Istri bisa mengekspresikan "emosi" marah dan menangis ketika berpendapat, dan suami bingung dan berfokus pada ekspresi tersebut.
Baca juga: Nicky Astria dan Merebut Tafsir Soal Izin Suami
Suami bisa saja berdalih bahwa mereka melakukan tugas domestik bersama-sama dan dia mendengarkan apa yang istri inginkan, cuma apa yang diinginkan istri tidak jelas. Orang tua saya adalah salah satu contohnya. Mereka sudah menikah lebih dari 27 tahun dan bertahan karena diberkahi doktrin agama konservatif dan kestabilan finansial. Tetapi mereka mengulang masalah komunikasi yang selalu sama.
Ibu menuduh Ayah tidak mau mendengar, sementara Ayah bilang dia tidak tahu apa yang ibu mau. Walaupun Ibu memegang peran yang sentral dan dominan dalam keluarga, dia terlanjur memosisikan dirinya sendiri dalam keluarga sebagai konco wingking (teman di belakang suami) tidak bisa melihat dirinya sendiri mampu bertanggung jawab atas keputusannya. Ia memaksa ayah saya untuk tegas dan menjadi juru bicara dalam kehendak-kehendaknya.
Bagaimana posisi asimetris dalam romansa perkawinan ini bisa terbentuk? Dari mana banyak perempuan Indonesia belajar untuk menjadi seorang perempuan dan istri? Tentu dari apa yang dibaca, apa yang dilihat, dan apa yang didengar. Di Instagram, puluhan akun istri teladan/salehah berjamur mengajarkan bagaimana cara "menjadi istri": taat pada suami, tidak menolak hubungan badan, dan menyelesaikan tugas domestik.
Begitu juga dengan ceramah-ceramah di pengajian, petuah ibu dan mertua. Semua bicara bahwa istri harus menurut dan mengalah pada lelaki. Semua konstruksi sebagai “istri” dipelajari dan tertanam dalam psike perempuan yang baru menikah dan belum pernah menghadapi konflik nyata seperti tinggal serumah dengan pasangan. Semua materi menjadi istri itu tidak menyelesaikan masalah ketidaksetaraan dalam rumah tangga, hanya merepresi konflik dan mengalihkan rasa sakit dan penderitaan perempuan melalui aktivitas bersyukur dan bersabar. Akibatnya, pernikahan mungkin bisa bertahan tetapi suami-istri terlibat di dalamnya tidak bahagia.
Tanpa memahami akar masalahnya, kita akan melihat bahwa saling memberi kode adalah ciri adanya kasta antara perempuan dan lelaki dalam hubungan romansa. Misogini akan kembali menyalahkan perempuan karena bahasanya sulit dipahami. Patriarki akan meromantisasi hubungan heteroseksual asimetris ini dengan slogan "wanita ingin dimengerti", seperti dalam lagu Ada Band. Masalah dalam hubungan romansa bisa ditelaah dengan melihat sistem yang lebih besar turut andil membuat stereotip-stereotip dalam relasi lelaki-perempuan. Dan tanpa analisis feminisme, stereotip hanya akan dilanggengkan tanpa analisis struktur yang lebih dalam.
Restu agama dan negara dalam hubungan pernikahan asimetris
Ketika seorang teman dekat saya, sebut saja A, sedang mengurus keperluan administratifnya di Kantor Urusan Agama (KUA), ia rajin sekali menelepon saya untuk berbagi pengalamannya. Teman saya yang sudah memahami feminisme dan isu gender setuju bahwa ceramah pra-pernikahan dari penghulu sering kali bias gender.
Petuah pernikahan diberikan oleh penghulu yang notabene seorang lelaki yang menerima banyak kemewahan dalam pembagian peran gender dalam rumah tangga. Istri diwajibkan melayani suami tanpa ada informasi soal pemerkosaan dalam pernikahan. Tidak ada informasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Petuahnya pun sangat generik bahwa suami wajib menafkahi, sementara istri wajib melayani dan mengerjakan tugas domestik.
Baca juga: Diskresi Pemerintah untuk Batasi Poligami
Petuah penghulu konservatif ala KUA memiliki landasan. Pertama, tafsir agama Islam konservatif yang membagi peran domestik dan publik berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, jenis kelamin yang diakui cuma dua dan peran gender dibagi berdasarkan jenis kelamin. Selama Islam tidak memperhitungkan perspektif gender dalam kajiannya, selamanya dia akan jadi agama yang tidak bisa mengadaptasi hak asasi manusia.
Kini, kita telah memiliki banyak cendekiawan muslim yang bisa diikuti dakwahnya seperti Prof. Musdah Mulia atau teolog Lailatul Fitriyah. Kementerian Agama yang menjadi induk dari seluruh KUA di seluruh Indonesia wajib hukumnya mengadaptasi pemikiran para cendekiawan perempuan muslim ini ke dalam kajian keislaman Indonesia sekaligus menangkis teologi Islam yang konservatif/reaksioner yang konon bercokol pula di kementerian-kementerian di Indonesia.
Kedua, Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 1974 yang mensyaratkan peran gender dalam pembagian peran rumah tangga. UU Perkawinan ini sudah saatnya diamandemen karena sudah sangat usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan hari ini. Kehadiran organisasi seperti PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) yang didirikan Nani Zulminarni pada 2000, mematahkan pasal di UU Perkawinan bahwa hanya suami yang mampu menjadi kepala keluarga. Kehadiran UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2004 juga menyumbang paradigma keluarga baru tentang kekerasan dalam keluarga dan pemerkosaan yang juga terjadi dalam pernikahan.
Terakhir, paradigma bahwa pernikahan beda agama tidak bisa dilangsungkan di Indonesia. Dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia, pemerintah tidak bisa lagi melihat bahwa penduduk negara ini bisa diseragamkan. Selama ini masyarakat adat mengalami pemaksaan untuk masuk ke salah satu agama supaya pernikahannya diakui. Hal ini akibat tafsir dari Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan pernikahan negara harus disertai dengan restu lembaga agama. Sementara agama yang diakui hanya enam dan kepercayaan bukanlah bagian dari enam agama yang berlaku.
Untuk itu, diperlukan aturan yang baru untuk memisahkan pengesahan pernikahan negara dan agama. Kita harus merombak peraturan untuk tidak lagi menjadikan pernikahan agama sebagai syarat sah pernikahan sipil. Dengan tidak mensyaratkan pernikahan agama dan catatan sipil, pernikahan secara agama adalah pilihan tapi hak-hak pernikahan secara hukum tetap terjamin.
Negara Indonesia tidak bisa lagi menjalankan program tanpa ada riset tentang praktik pernikahan dan kebaruan-kebaruan dalam kehidupan berumah tangga pada hari ini. Tanpa adanya paradigma baru tentang pernikahan, kebijakan tersebut hanya akan menjadi program buang-buang anggaran sekaligus lahan basah untuk korupsi (misalnya seorang lelaki yang menyogok untuk mendapatkan sertifikat agar bisa poligami tanpa izin istri). Bayangkan jika sertifikasi pernikahan diwajibkan dengan landasan kedua hukum yang sudah usang dan belum ditingkatkan ini. Akan berapa banyak istri yang harus melempar kode dalam status supaya lebih diperhatikan oleh suaminya?




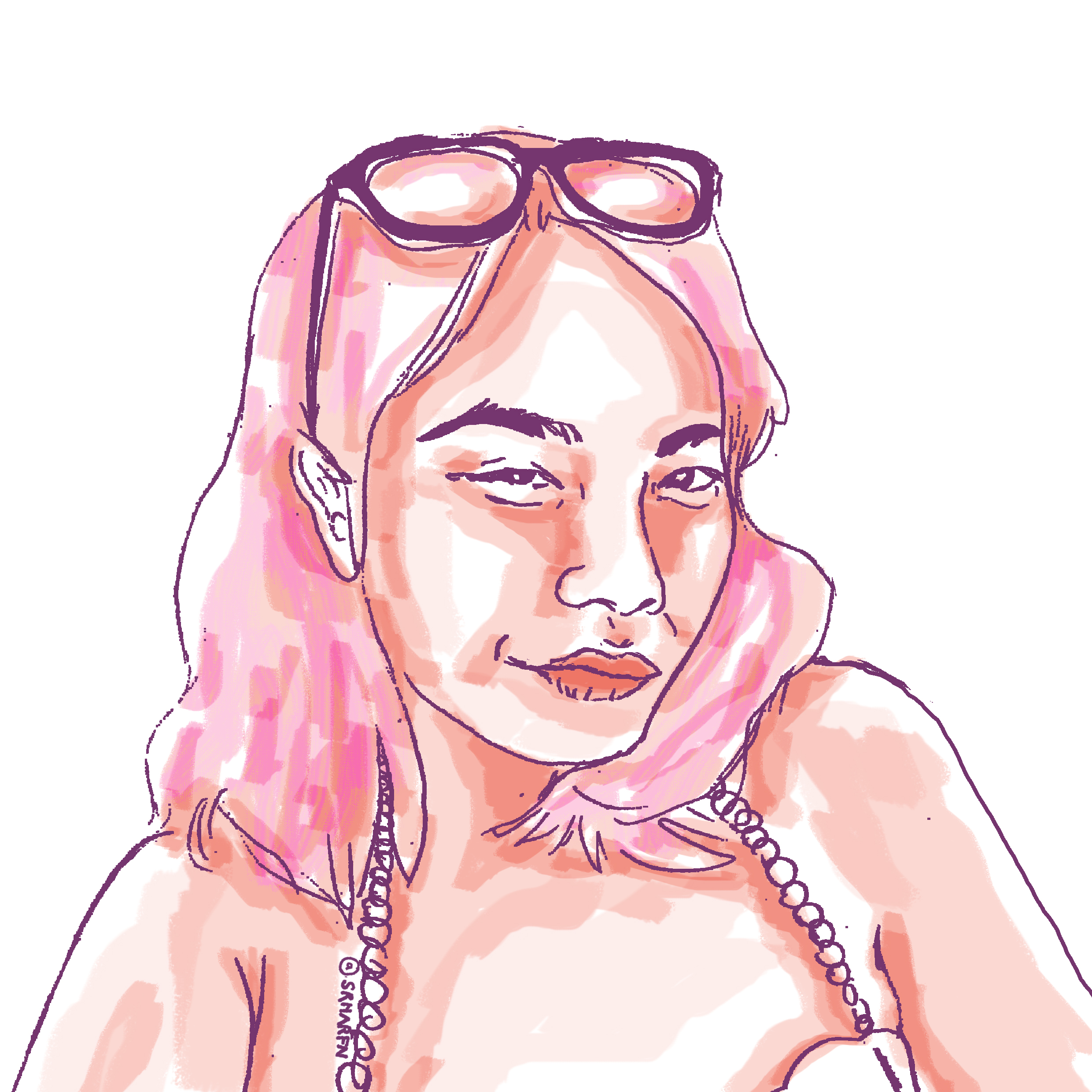



Comments