Beberapa waktu lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) memberhentikan salah satu pengurus dari jabatannya setelah ia mengunggah penolakannya atas diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas gender—Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)—di akun media sosial pribadinya. Unggahan tersebut bertepatan dengan momen Pride Month.
Yang bersangkutan disebutkan telah melanggar Peraturan Rektor IPB tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus dan menciptakan kegaduhan serta ketidakstabilan di media sosial.
Pekan kemarin, seorang mahasiswa yang mengaku non-biner diusir oleh dosennya dalam acara ospek Universitas Hasanuddin, Makassar.
Kejadian-kejadian tersebut tentu harus dipertanyakan dan dicermati secara kritis.
Pasalnya, mahasiswa kerap diasosiasikan sebagai agen perubahan yang progresif, terutama terhadap narasi politik, keadilan sosial ekonomi, ekologi, pendidikan, ras, dan gender.
Gerakan mahasiswa diyakini memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan. Sudah banyak catatan sejarah mengenai peran penting gerakan mahasiswa dalam melawan rezim yang represif di Indonesia, termasuk saat jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin Sukarno (1965-66) dan Orde Baru Suharto (1997-98).
Dalam beberapa tahun terakhir, mahasiswa juga kembali melakukan beberapa aksi demonstrasi untuk melawan rezim oligarki dan kebijakan-kebijakan yang dianggap mencederai demokrasi. Hasil riset pun menunjukkan bahwa mahasiswa masih peka terhadap isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Pemecatan pengurus BEM KM IPB dari jabatannya karena menyampaikan penolakan terhadap diskriminasi kelompok LGBT tersebut menunjukkan bahwa terlepas dari kesadaran para mahasiswa terhadap isu demokrasi dan HAM, masih ada politik homofobia yang mengakar dalam aktivisme mereka.
Baca juga: Gerakan Mahasiswa Kental Maskulinitas
Kampanye dan Insiden Anti-LGBT Sejak 2016
Titik balik mulai gencarnya aktivisme mahasiswa yang mengampanyekan sikap anti-LGBT ini berkembang sejak 2016, ketika terjadi serangkaian kampanye dan insiden anti-LGBT yang mengancam kelompok minoritas tersebut.
Semuanya berawal dari pernyataan Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) saat itu, yang meminta kampus-kampus untuk melarang aktivitas kelompok LGBT.
Setelah pernyataan tersebut, berbagai pernyataan sikap dan dorongan untuk menolak LGBT muncul, bahkan banyak yang dimobilisasi oleh pejabat negara, dari anggota parlemen hingga mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan beberapa kelompok Islam militan.
Pernyataan Menristekdikti itu juga mendorong munculnya aktivisme mahasiswa anti-LGBT, baik melalui organisasi intra kampus atau ekstra kampus di beberapa universitas di Indonesia. Petinggi kampus pun ikut mendukung penolakan tersebut.
Seringkali, mereka mengemas kampanye anti-LGBT sebagai “upaya untuk melindungi generasi bangsa dan keluarga Indonesia”.
Dalam konteks yang terjadi di IPB, unggahan media sosial pengurus tersebut sepertinya dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap norma maskulinitas dan ‘nama baik’ BEM KM IPB serta IPB sendiri sebagai institusi pendidikan. Rasa terancam tersebut adalah bagian dari emosi fobik—rasa amarah dan jijik—yang ditujukan kepada pengurus tersebut dan pemikirannya.
Pemecatannya sendiri, yang diumumkan di dunia maya, adalah contoh bentuk politik homofobia baru di era digital.
Baca juga: Aktivisme Mahasiswa Dekade Terakhir: Golput, Anti-Politik Praktis, Peka Isu HAM
Politik Homofobia di Indonesia
Diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual bukanlah fenomena baru di Indonesia. Tom Boellstorff, seorang profesor antropologi dari Amerika Serikat (AS), mencetuskan istilah “political homophobia” (politik homofobia) pada tahun 2004.
Konsep politik homofobia digunakan untuk memahami tragedi penyerbuan Wisma Hastorenggo di Kaliurang, Jawa Tengah, oleh Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) terhadap sekitar 350 orang kelompok LGBT yang tengah memperingati Hari Kesehatan Nasional pada 11 November 2000.
Berbeda dengan istilah heteroseksisme, yang merujuk pada norma yang hanya mengakui heteroseksualitas sebagai satu-satunya seksualitas yang alami dan benar, politik homofobia adalah sebuah logika budaya baru yang menghubungkan kehadiran kelompok gender dan seksual non-normatif di ruang publik dengan sebuah ancaman terhadap norma maskulinitas dan masa depan bangsa.
Logika ini menjadi justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok non-heteroseksual yang berusaha untuk mengklaim ruang-ruang publik.
Transformasi heteroseksisme menjadi politik homofobia ini dapat dilihat dari aksi pembatalan kegiatan yang diadakan oleh pegiat hak kelompok seksual minoritas, penutupan pesantren waria Al-Fatah, hingga upaya hukum untuk mengkriminalisasi LGBT.
Merujuk pada kasus pemecatan pengurus BEM KM IPB, politik homofobia kini tidak hanya ditujukan kepada kelompok non-heteroseksual saja, tetapi juga kepada orang yang memiliki pemikiran yang inklusif terhadap kelompok minoritas seksual.
Praktik ini bukan hanya bentuk represi terhadap keberagaman gender dan seksualitas, tetapi juga kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Baca juga: 20 Tahun Reformasi dan Narasi Gerakan Perempuan
Urgensi Merawat Demokrasi di Indonesia
Mengakarnya politik homofobia dalam aktivisme mahasiswa dalam beberapa tahun terakhir mengharuskan kita untuk melakukan refleksi kritis dalam merawat demokrasi di Indonesia.
Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita cermati:
Pertama, gerakan mahasiswa masa kini harus dipahami sebagai sebuah gerakan yang heterogen dan tidak bergerak secara kohesif.
Di satu sisi, ada gerakan mahasiswa yang berkolaborasi dengan aliansi rakyat yang lebih luas untuk mencapai perubahan progresif, termasuk untuk mencapai keadilan gender. Di sisi lain, ada pula gerakan mahasiswa yang justru beraliansi dengan organisasi masyarakat yang mengkampanyekan politik homofobia.
Kedua, di era digital ini, ruang siber menjadi tempat subur untuk berkembangnya politik homofobia. Konsep politik homofobia juga kini banyak dipraktikan dalam berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, bukan hanya kepada kelompok minoritas seksual secara langsung, tapi juga kepada mereka yang mendukung penghapusan diskriminasi terhadap kelompok ini.
Ketiga, politik homofobia yang mengakar dalam aktivisme mahasiswa perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai di tengah upaya mengawal pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), gerakan mahasiswa justru mereproduksi sistem yang represif terhadap keberagaman gender, seksualitas, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara Indonesia.![]()
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.






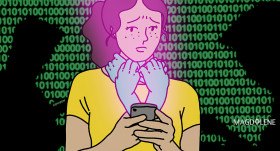
Comments