“Wah, enak ya punya anak perawan, bisa bantu masak dan beresin rumah.”
Kalimat itu terasa akrab di telinga saya ketika memasuki sebuah masa dimana masyarakat memberikan saya gelar ‘Perawan’. Perempuan yang telah memiliki alat reproduksi aktif dan belum kawin, mungkin itu yang menjadikan dasar dalam pemberian gelar ‘Perawan’.
Perawan merupakan sebuah fase baru bagi seorang perempuan. Ia harus berhadapan dengan sebuah realitas yang menghadirkan perempuan sebagai kaum kelas dua. Kalimat pada awal tulisan ini saya yakin salah satu kalimat yang rutin didengar perempuan muda. Selain itu ada banyak kalimat-kalimat lain, seperti:
“Sesukses-suksesnya seorang perempuan, ujung-ujungnya harus berurusan dengan dapur”
“Menjadi perawan tidak boleh malas. Nanti suaminya diambil orang.”
Dan masih banyak lagi yang menyiratkan seakan-akan seorang perempuan ditakdirkan untuk menyerahkan segala otoritas hidupnya di tangan lelaki. Seorang perawan dipaksa untuk menyetujui bahwa masa perawannya merupakan sebuah masa pembelajaran untuk persiapan legalisasi perbudakan oleh laki-laki melalui jalur pernikahan di masa depannya kelak.
Seorang perempuan mungkin tidak pernah menyadari bahwa penanaman paham yang menjunjung tinggi nilai patriarkis telah ada sejak kecil. Pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki telah diatur sedemikian rupa oleh keluarga. Perempuan bertugas di dalam rumah, dan laki-laki keluar rumah. Hal tersebut mungkin baru akan terasa saat seorang perempuan telah menginjak masa ‘Perawan’-nya
Sedari kecil, anak perempuan telah dicekoki nilai-nilai yang dianggap luhur, seperti harus berpakaian tertutup, harus banyak berada di dalam rumah, harus belajar berurusan dengan dapur, dan lain sebagainya, yang berbanding terbalik dengan laki-laki.
Hal-hal tersebut kemudian wajib diaplikasikan dalam kepribadian seorang perawan. Jalur kebudayaan yang telah dibangun sejak lama harus dilewati seorang perawan. Lurus tanpa boleh berbelok atau menoleh sedikitpun.
Menjadi perawan merupakan awal bagi seorang perempuan untuk menyadari bahwa dunia memandang sekitar melalui mata lelaki. Salah satu contoh paling konkret adalah saat seorang perempuan berjalan sendirian mengenakan pakaian minim di malam hari. Masyarakat memandangnya melalui pandangan birahi laki-laki sehingga perempuan yang keluar di malam hari dianggap akan membahayakan dirinya sendiri karena laki-laki senantiasa mengancam keamanannya.
Dari contoh tersebut, seorang perempuan, khususnya perawan, memiliki dua tugas penting. Pertama, bagaimana caranya untuk menyembunyikan tubuhnya dari cara pandang lelaki yang telah merasuk dalam diri manusia, yang kedua, bagaimana caranya agar tetap menjaga selaput daranya tidak dirobek oleh orang yang tidak diinginkan. Lagi-lagi seorang perawan baru menyadari, bahwa cara pandang publik seakan-akan menyalahkan atas terciptanya tubuh perempuan.
Sebagai seorang ‘Perawan’, saya paham benar bagaimana cara pandang masyarakat dan norma yang berlaku bagi seorang perempuan yang dianggap masih perawan. Dalam keluarga, saya dituntut untuk lebih mengerti pekerjaan rumah tangga dan banyak diam di rumah dibanding saudara laki-laki saya. Dalam masyarakat, saya harus menjaga diri saya dari cara pandang lelaki yang ada di tiap sudut jalan. Hal tersebut bertujuan untuk menyiapkan diri saya di masa depan sebagai seorang budak yang legal dengan selaput dara yang masih utuh.
Budaya patriarkis yang kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia memandang seorang ‘Perawan’ seolah-olah organisme yang ‘mudah rusak’ dan harus disimpan dalam etalase tanpa boleh bergerak bebas.




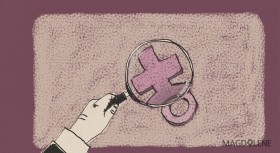


Comments