Ada kisah-kisah yang perlu diceritakan.
Dengan sangat berhati-hati, saya melangkah di atas batang pohon kelapa, tapi tetap saja saya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam genangan lumpur hitam. Tak jauh dari tempat saya jatuh tampak bangkai kerbau mengapung.
Saya angkat tangan kanan setinggi mungkin agak handycam yang saya genggam tidak ikut terjatuh.
Rekan seperjalanan saya, juru foto Beawiharta atau akrab disapa Bea, yang berada di depan saya berteriak menanyakan apakah saya baik-baik saja. Berjalan di genangan lumpur hitam setinggi pinggang manusia, dengan gaya ala patung Liberty membuat saya menyadari bahwa hanya dengan begitulah kami bisa mengamankan peralatan meliput yang kami bawa.
Kami berada di Leupung, daerah yang termasuk sangat parah terkena dampak bencana tsunami. Setelah 20 menit kami menyusuri daerah pesisir pantai ini, kami tidak bertemu seorang pun.
Berbekal biskuit dan air mineral, tujuan kami saat itu menuju wilayah yang belum tergapai bantuan. Kami menumpang motor, dilanjutkan dengan berjalan kaki. Gempa berkekuatan 9,1 Skala Richter telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah garis pantai yang membuatnya sulit untuk dilewati kendaraan bermotor.
Dalam kesunyian, yang terdengar hanyalah bunyi ombak yang membuat kami bergidik dalam suasana mencekam. Masker yang saya kenakan tidak mempu menangkal bau menyengat dari mayat manusia dan bangkai ternak yang bergelimpangan, beberapa dari mereka ada yang masih utuh.
Langit cerah saat itu ditambah dengan embusan angin laut yang sebenarnya sangat sempurna di terik matahari siang itu, tapi surga itu telah berubah jadi neraka, dengan sisa-sisa kehidupan yang berserakan.
Diantara gunungan puing-puing, sepatu, mainan anak-anak warna-warni dengan kaki serta tangan yang mencuat, saya melihat sebuah foto keluarga berbingkai yang diambil di studio.
Saat itu, Tahun Baru 2005 dan kami sudah berada di Aceh selama hampir satu minggu. Pagi itu, untuk pertama kalinya listrik kembali menyala dan saya ingat sekali itu televisi menyiarkan berita tentang konglomerat Adiguna Sutowo yang menembak mati seorang pelayan restoran. Saat itu yang ada hanya perasaan jijik terhadap tingkah sang konglomerat dan saya berteriak ke arah televisi. Tuan rumah tempat kami menginap, Nunuu Husein, orang Aceh asli yang kehilangan ayahnya saat tsunami melanda, hanya berdiri terdiam menyaksikan siaran televisi dari belakang saya.
Kami bertemu Nunuu saat kami mendarat di bandar udara Banda Aceh pada 27 Desember 2004, sehari setelah musibah tsunami melanda.
Sebenarnya drama telah dimulai bahkan sebelum kami mendarat di Aceh. Hampir semua penumpang pesawat Garuda yang kami tumpangi mengabaikan tanda sabuk pengaman dan berebut melihat ke jendela untuk menyaksikan pemandangan dari udara, air yang menenggelamkan rumah-rumah hingga ke atap. Kesedihan yang mendalam sangat terasa, mereka menangis dan meratap sambil mengucap “Allahu Akbar.”
Di bandara, teriakan dan isak tangis memenuhi ruang kedatangan penumpang dan kerabat penjembut bergegas menyambut penumbang dengan rangkulan.
"Bapak wartawan? Tolong bantu kami memberitahukan kepada dunia apa yang terjadi di Aceh. Ayo ikut saya!" ujar Nunuu kepada saya yang tengah berdiri kebingungan dan terpana, tidak tahu harus melakukan apa. Belum pernah dalam sejarah karir saya sebagai wartawan saya mendapat dorongan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu.
Pemberhentian pertama kami adalah bundaran Lambaro, tempat kami menyaksikan ratusan jenazah dibaringkan di depan kantor Palang Merah Indonesia.
Angka (seperti jumlah korban, jumlah kerugian, jumlah rumah yang hanyut, dll) dan gambaran situasi, adalah hal yang paling penting untuk para redaktur saya di Jakarta.
Almarhum Jerry Norton, salah satu redaktur saya, akan berkata dengan nada datar, "Kalau bisa dihitung, tolong kau hitung sendiri (jumlah mayat).”
Jadilah saya berjalan di tengah-tengah mayat untuk melihatnya langsung, sambil berkata "permisi" seakan mereka bisa mendengar. Hanya dengan begitulah saya merasa dapat tetap menghormati mereka. Saya cermati satu per satu wajah yang sudah tidak sempurna itu, beberapa mulut mereka tampak membesar melebihi ukuran normal.
Saya meringis tapi saya tetap bertahan karena saya harus menggambarkan keadaan yang saya lihat hingga ke hal-hal kecil sekalipun. Saat itu sempat terlintas di benak saya, haruskah dunia mengetahui hal-hal kecil yang penuh darah ini, haruskah hal-hal detil ini akan terus melekat di benak saya?
Gambaran itu adalah yang pertama dari yang tak terhitung kemudian, yang saya laporkan kepada para redaktur di Jakarta. Setiap jam saya hubungi mereka saya melalui telepon satelit, membacakan catatan yang saya tulis di buku, yang berisi kutipan, hal-hal menarik, fakta dan kerugian, kehilangan, keputusasaan dan kengerian.
Berkali-kali saya harus mencari tempat yang strategis, luas dan tidak terhalang apapun agar saya bisa menggunakan telepon satelit ini dan setiap kisah penyintas dilaporkan semata-mata sebagai fakta. Tak jarang, editor saya meminta saya berhenti sejenak saat saya sedang menggambarkan suasana kematian dan hal-hal yang mengerikan. Namun saya tetap mengingatkan mereka untuk terus menekan tombol 'on' karena bisa saja sambungan telepon satelit ini terputus. Jika diingat kembali, sepertinya saya terlalu sering menahan perasaan saya dan bersikap dingin.
Tetapi yang paling berkesan adalah kejadian di hari pertama.
Saya ingat sekali, saat meminjamkan telepon satelit saya kepada beberapa warga yang tidak tahu lagi bagaimana menyampakan kabar mereka kepada para sanak saudara. Seorang ibu menangis, jatuh terduduk saat menghubungi kerabatnya lewat telepon satelit kami, sementara seorang bapak berdiri di samping saya tidak sabar menunggu giliran. Beberapa kali saya harus menolak permintaan mereka yang ingin meminjam telepon satelit, karena kami harus lebih efisien menggunakannya mengingat listrik masih padam.
Kami berkeliling menumpang truk Brimob yang berpatroli menjemput korban luka dan para jenazah. Ternyata ada seorang yang tewas di atas truk ini, setelah ditemukan penduduk dalam keadaan masih bernyawa di antara puing reruntuhan pasar Aceh Raya.
Di sebuah rumah sakit militer, seorang ibu paruh baya dengan wajah penuh luka dan kaki dibalut terduduk di lantai mencoba menggapai saya sambil berkata "Tolonglah Nak." Saya bungkukkan badan untuk memegang tangannya tapi tak sepatah katapun keluar. Bahkan kata-kata yang menenangkan pun tidak mampu saya ucapkan karena saya merasa kami seperti sedang berada di neraka dan saya pun tak yakin apakah kita akan baik-baik saja. Lalu seorang dari polisi datang memanggil saya untuk melanjutkan patroli.
Malam pertama saya lalui di rumah Ibu Nunuu, yang disesaki sanak keluarganya yang selamat dari bencana, memikirkan kengerian yang saya saksikan yang membuat saya terjaga sepanjang malam. Tetapi yang paling mengganggu pikiran saya adalah ibu yang saya temui di rumah sakit. Saya tak hentinya menyalahkan diri saya sendiri, manusia seperti apa saya ini? Kenapa saya tidak memeluknya. menenangkannya atau melakukan hal-hal yang lebih manusiawi terhadapnya? Yang terjadi saya malah saya bergegas kembali ke truk untuk melanjutkan tugas liputan saya.
Kembali ke petualangan kecil kami ke Leupung, akhirnya kami bertemu dengan beberapa orang yang telah berjalan kaki berhari-hari dari kampung mereka di Calang. Mereka dapat bertahan hidup hanya dengan air kelapa. Bea dan saya memberi biskuit dan air bekal kami kepada mereka. Pemandangan yang paling tertanam di benak saya adalah saat seorang balita mengambil biskuit yang saya beri tanpa berkata sepatah pun. Tak terlihat apakah ia sedih atau gembira, saya tidak mengajaknya berbicara, bahkan tidak menanyakan namanya.
Seorang bapak yang menutup wajahnya dengan kaos sebagai masker memberitahu saya kalau bau mayat semakin menyengat pada malam hari.
Sepuluh tahun kemudian
Selama satu dekade saya belum pernah berkunjung ke Aceh lagi. Saya tidak pernah berkeinginan untuk mengisahkan pengalaman saya ini. Sebagai wartawan, kami diajarkan untuk melaporkan kisah orang lain, bukan cerita kami. Tetapi kunjungan saya beberapa waktu lalu telah mengubah apa yang saya yakini selama ini.
Aceh tidak memperlihatkan bekas-bekas kehancuran. Tenda-tenda darurat yang pernah muncul di tengah puing yang menggunung telah berganti menjadi gedung-gedung dan rumah-rumah. Kota Banda Aceh dipercantik oleh jalan-jalan yang luas dan mulus, jauh lebih bagus dibandingkan dengan jalanan berlubang di Jakarta yang bisa menjadi jebakan maut bagi pengendara motor.
Lalu ada masyarakatnya, terutama para penyintas.
Baru-baru ini saya bertemu dengan serombongan petani yang sudah kembali bercocok tanam setelah tsunami meratakan sawah mereka dengan tanah. Saya berbincang dengan beberapa pengusaha yang berbisnis daur ulang sampah setelah sebelumnya selama beberapa tahun mereka mendaur ulang baja dari limbah tsunami.
Kenangan saya pada perjalanan pertama tsunami masih melekat di tempat yang paling aman di benak saya. Saya bisa memutarnya kembali persis sama seperti yang pernah saya saksikan, dan detil yang paling mengerikan bisa kembali bermain di benak saya.
Pembicaraan saya dengan para penyintas bencana tsunami dan melihat apa yang terjadi di Aceh saat ini, sulit dipercaya bagaimana mimpi buruk itu bisa mengubah Aceh seperti saat ini.
Tak semua detil yang menjadi bahan laporan saya bisa dimuat. Mungkin saat itu saya terlalu terobsesi dengan hal-hal menarik di sekitar peliputan, mungkin saya seharusnya tidak berjalan diantara mayat di Lambaro. Mungkin saya tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang pernah saya wawancarai dan hingga kini saya masih bertanya-tanya bagaimana dengan nasib ibu yang saya temui di rumah sakit dan nasib balita yang saya beri biskuit.
Tetapi melihat pertumbuhan yang terjadi di Aceh saat ini, saya punya sedikit harapan, mungkin, mereka telah pulih kembali. Semoga.
*Diterjemahkan oleh Lenita Sulthani dari artikel "Horror and Hopes in the Tsunami Aftermath -- 10 Years On."





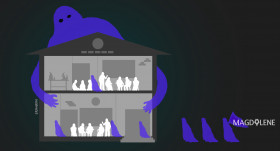


Comments