Ancaman pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Hukuman mati yang membayangi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang melindungi diri dari kekerasan dari majikan. Reviktimisasi dan penyalahan terhadap korban kekerasan seksual. Ini adalah contoh-contoh permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia saat mencari keadilan hukum. Bukannya mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan, banyak dari perempuan yang malah kembali menjadi korban akibat sistem hukum yang tidak berpihak pada perempuan korban, dan aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender.
Permasalahan ini menjadi fokus dari temu wicara “Saya dan Keadilan” yang diselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam (UE) dan Badan PBB untuk Program Pembangunan di Indonesia (UNDP Indonesia) melalui proyek EU-UNDP Support to the Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN), bekerja sama dengan Magdalene di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (29/11).
Penasihat Senior EU-UNDP SUSTAIN Gilles Blanchi mengatakan bahwa ia ingin fokus pada generasi milenial mengenai pentingnya keadilan gender melalui acara ini.
“Gender adalah masalah sehari-hari di Indonesia. Dengan berfokus pada isu gender ini, kami berharap bahwa secara bertahap kita bisa mengubah budaya yang ada serta ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki, dengan mengundang anak-anak muda untuk membuat perubahan,” ujar Gilles.
Salah satu panelis, aktivis hak pekerja migran Anis Hidayah dari lembaga Migrant Care, memaparkan situasi keadilan hukum yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, yang saat ini mencapai sekitar tujuh juta orang dengan 85 persennya adalah perempuan.
“Hingga hari ini, mereka masih sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi, selama mereka bekerja, karena mayoritas mereka bekerja di sektor yang sangat rentan, yaitu pekerja rumah tangga (PRT),” kata Anis.
Anis mengatakan banyak kasus di mana korban kekerasan fisik dan seksual justru ditahan dan dipenjara. Mayoritas pembantu rumah tangga (PRT) migran yang dieksekusi mati di Arab Saudi dan yang terancam hukuman mati adalah korban kekerasan seksual majikan, misalnya dalam kasus baru-baru ini terhadap Tuti Tursilawati, ujarnya.
“Permasalahannya, dari sekitar 179 negara penempatan, pemerintah Indonesia baru memiliki perjanjian dengan 14 negara. Artinya, jauh lebih besar jumlah ketiadaan kesepakatan bersama tentang jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja,” kata Anis.
Di dalam negeri, para buruh migran yang mencari keadilan hukum menemukan kebuntuan yang sama, ujarnya. Pada awal tahun ini, misalnya, ada kasus di mana saat buruh migran perempuan korban tindak pidana perdagangan orang menuntut perusahaan perekrutan, mereka mendapati hakim yang merendahkan, menyalahkan, serta mengintimidasi korban.
“Dalam agenda keterangan saksi korban, hakim malah mengatakan, ‘kalian sekolah tidak sebenarnya?’, ‘Saksi palsu, saudara bisa ditahan, jangan mlenca-mlence’, ‘Kenapa dari 150, hanya kalian berempat yang mengadu?’, dan lain sebagainya. Hakim kemudian memutus bebas terdakwa yang notabene istri seorang diplomat,” ujar Anis.
Lebih lanjut lagi, menurutnya, liputan media juga masih bias gender dan perspektif jurnalis masih tidak berpihak pada korban sehingga terjadi reviktimisasi dan kriminalisasi korban. Padahal menurutnya, media adalah salah satu informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Contohnya, ada satu pemberitaan terhadap kasus pekerja migran yang diperkosa berkali-kali, media memberi judul artikel ‘bagaimana mungkin diperkosa sampai lima kali?’ Media masih belum memiliki perspektif korban, bahkan media sering kali menyudutkan korban. Ini berpengaruh pada meningkatnya stigma dalam masyarakat yang melanggengkan budaya perkosaan,” ujar Anis.
Adanya pluralisme hukum, yakni hukum nasional, hukum adat dan hukum agama, sering menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Ratna Batara Munti mengatakan, korban kekerasan kerap kali tidak didukung dan sering disudutkan, bahkan dalam beberapa kasus korban dan keluarganya diusir dari rumahnya sendiri karena dianggap membawa aib di kampungnya.
Lebih lanjut lagi, ia mengatakan adanya pluralisme hukum, yakni hukum nasional, hukum adat dan hukum agama, sering menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan.
“Misalnya, korban KDRT yang harus mengurus laporan pidananya melalui jalur Pengadilan Negeri, dan perceraian melalui Pengadilan Agama, jadi prosesnya tidak mudah,” ujar Ratna.
Penerapan hukum adat juga masih banyak yang tidak sensitif dalam mempertimbangkan dampak yang dialami korban, misalnya penyelesaian kekerasan seksual secara mediasi, atau menikahkan korban dengan pelaku.
Albertina Ho, hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi (PT) Medan, mengakui bahwa aparat penegak hukum secara umum belum memiliki berperspektif gender.
Hakim Tinggi Albertina Ho
“Dalam persidangan korban kekerasan seksual sering disalahkan, diberi pertanyaan seperti ‘kenapa pakai rok pendek?’ Padahal itu hak perempuan, terserah dia ingin mengenakan apa,” ujarnya
Ia mengatakan, reviktimisasi korban dalam proses hukum masih sering terjadi. Korban harus bercerita pengalaman traumanya tiga kali: kepada penyidik, kejaksaan, dan di pengadilan.
“Norma hukum acara pidana juga masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa. Dalam UU acara pidana, sama sekali tidak ada disinggung mengenai hak korban. Tetapi hak tersangka dan terdakwa ada, yaitu hak didampingi penasihat hukum, dan sebagainya. Hak korban sama sekali tidak ada,” ujarnya.
Jurnalis dan aktris Marissa Anita mengatakan bahwa dengan situasi ini, tidak heran jika banyak perempuan korban enggan mencari keadilan hukum. Data dari Komisi Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa tiap 2 jam, ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Namun survei yang dilakukan lembaga kelompok dukungan penyintas kekerasan seksual, Lentera Sintas Indonesia, pada 2016 menunjukkan, 93 persen penyintas kekerasan seksual tidak melaporkan kekerasan yang dialami, dan 72 persen penyintas tidak pernah bercerita atau menceritakan kekerasan yang dialaminya kepada siapa pun.
Advokasi Kebijakan dan Revisi Legislasi
Ratna mengatakan bahwa LBH APIK sudah melakukan beberapa advokasi kebijakan, antara lain mendorong pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saat ini LBH APIK mendorong revisi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana LBH APIK mendorong revisi agar kesehatan reproduksi masuk di dalamnya yang mencakup aborsi aman bagi korban pemerkosaan.
“Seperti kasus WA di Jambi, korban pemerkosaan inses sampai hamil yang melakukan aborsi. Ia divonis bersalah dan menjadi pelaku tindak pidana. Padahal layanan kesehatan reproduksi merupakan hak perempuan apalagi korban kekerasan seksual, namun layanan dan informasi itu tidak diberikan sehingga korban menjadi tersangka,” kata Ratna.
LBH APIK juga mendorong segera dibahas dan disahkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), karena selama ini kekerasan seksual hanya dicakup dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak komprehensif dan ketinggalan zaman.
“Kita harus berpikir lebih strategis lagi untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Saat ini periode terakhir DPR, sebentar lagi pemilihan legislatif, sementara kalau RUU PKS yang sudah masuk Prolegnas sejak 2017 tetapi tetap tidak dibahas dan tidak segera disahkan, maka perjuangan kita semua akan mengulang lagi dari nol,” ujar Ratna.
Hakim harus mencegah dan menegur pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban.
Dalam kasus-kasus perempuan sebetulnya ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang merupakan bentuk kemajuan yang cukup signifikan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi perempuan korban kekerasan seksual yang kerap kali mendapat perlakuan buruk di pengadilan.
Dalam Perma tersebut sudah diatur bagaimana hakim harus bersikap di persidangan, seperti mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan status sosial, diskriminasi, dampak psikis, ketidakberdayaan fisik atau psikis, relasi kuasa dan riwayat kekerasan. Misalnya saja relasi kuasa atasan terhadap bawahan, buruh dengan bosnya, guru dengan murid, juga murid dengan dosen.
Namun kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai Perma ini menjadikan implementasinya tumpul. Dari sisi korban, Albertina mengatakan ada keterbatasan pengetahuan korban terkait hak-hak hukum, keterbatasan keuangan, ancaman dan stigma terhadap perempuan, keterbatasan akses ke penasihat hukum, akuntabilitas dan transparansi dalam pengadilan dan penyidikan, jarak dan transportasi, dan hambatan bahasa atau komunikasi.
“Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, kami memperluas Perma Nomor 3 Tahun 2017. Tidak hanya perempuan sebagai korban, tapi kami juga melihat perempuan sebagai pelaku, seperti Baiq Nuril di Makassar dan WA di Jambi yang harus dilindungi. Kami juga melindungi perempuan sebagai pihak, biasanya dalam perkara Perdata seperti perempuan menggugat perceraian,” jelas Albertina.
Selain itu, hakim juga harus mencegah dan menegur pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban, contohnya, korban adalah seorang pekerja seks. Hakim biasanya memberikan hukuman ringan terhadap tersangka.
“Kalau hakim bisa menerapkan peraturan terkait bagaimana dia bersikap di persidangan, maka ia akan menghasilkan putusan yang berperspektif gender dan korban mendapat hak dan keadilannya,” kata Albertina.
*Foto oleh Elma Adisya, Magdalene
Baca soal implementasi Peraturan MA untuk peradilan yang lebih berkeadilan gender.





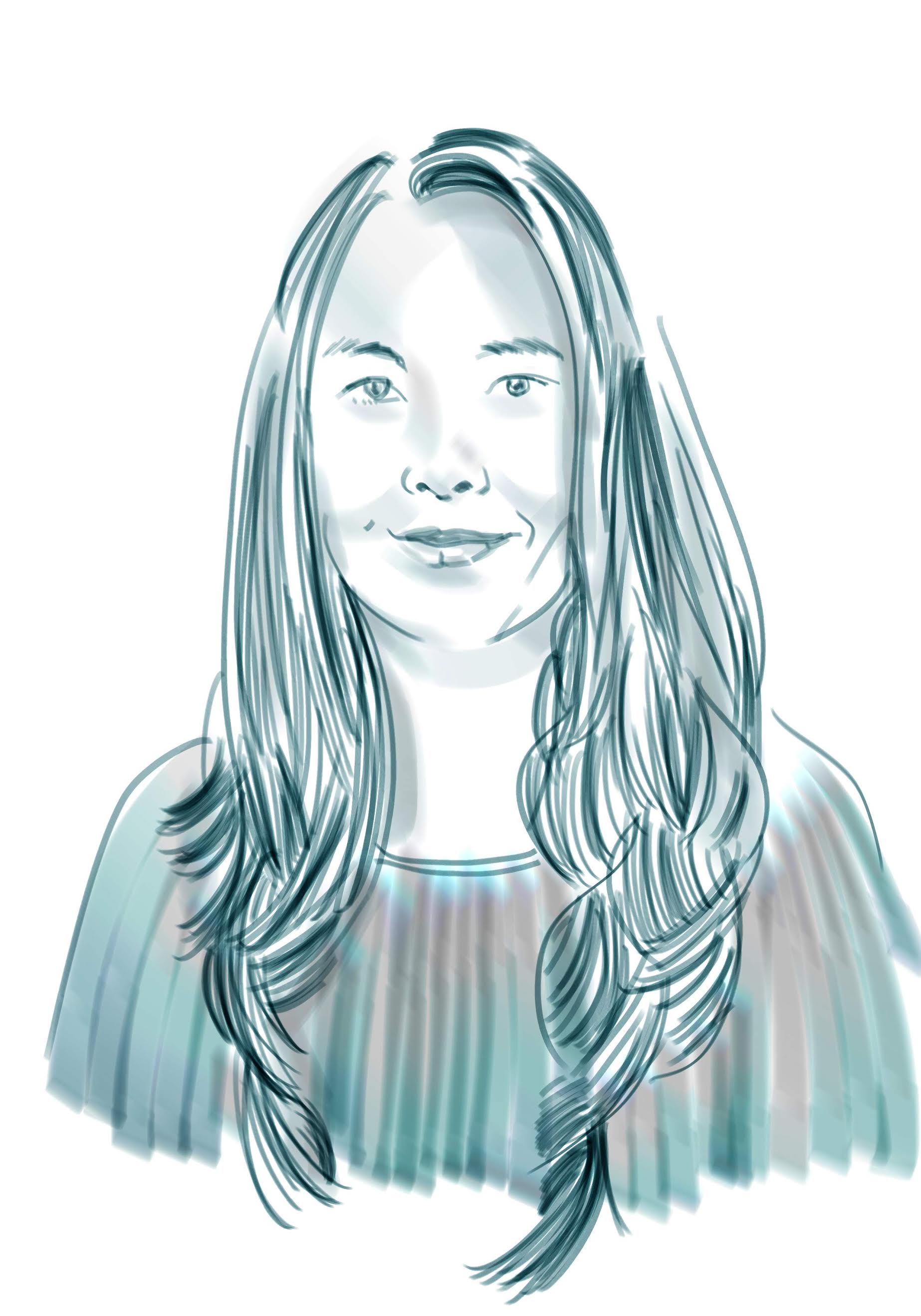



Comments