Perilaku bunuh diri dilakukan karena kurang iman, ibu tunggal adalah perempuan penggoda, hingga anggapan “orang luar” terhadap masyarakat Tionghoa-Indonesia, merupakan beberapa stigma sosial yang sering kita dengar atau pernah alami. Stigmatisasi yang dijelaskan sosiolog Prancis, Emile Durkheim pada 1895 ini nyatanya dapat memengaruhi status sosial, kesejahteraan psikologis, dan kesehatan fisik bagi penerimanya.
Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh psikolog asal Amerika Serikat, Brenda Major dan Laurie O’Brien berjudul The Social Psychology of Stigma (2005), stigma bahkan dapat menjadi ancaman identitas. Pasalnya, seseorang cenderung menafsirkan lingkungan sesuai dengan hal-hal yang relevan padanya, seperti emosi, keyakinan, perilaku, dan perlindungan harga diri. Sementara, orang-orang yang berada di luar identitasnya kerap jadi sasaran diskriminasi.
Konstruksi masyarakat yang bersifat “turun-temurun” ini terlanjur mengakar. Sebagai masyarakat yang menyadari adanya ketidakadilan, kita bisa saja mengambil peran dalam mendukung upaya komunitas yang berusaha meretas stigma berikut ini.
1. Into The Light Indonesia
Mengusung slogan “Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa”, Into The Light Indonesia merupakan komunitas yang berfokus pada edukasi, pusat advokasi, dan penelitian terkait kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri di Indonesia.
Baca Juga: Bagaimana Perempuan Indonesia dengan HIV/AIDS Berjuang dengan Stigma
Annisa Radyani, anggota divisi Task Force Crisis Intervention di Into The Light Indonesia menjelaskan, komunitas ini sekarang melakukan psikoedukasi pada masyarakat terkait pencegahan bunuh diri lewat pemaparan di media sosial, webinar, kerja sama dengan berbagai komunitas, dan support group di WhatsApp bagi penyintas kehilangan bunuh diri.
“Kami bukan pusat krisis, sehingga jika butuh bantuan cepat, kami mengarahkan mereka ke situs intothelightid.org. Di sana, siapapun dapat mengedukasi diri tentang perilaku bunuh diri, atau memahami apa yang perlu dilakukan apabila menemukan perilaku tersebut pada orang lain. Selain itu, terdapat banyak akses ke profesional dan informasi lokasi mereka.”
Into The Light Indonesia secara rutin melaksanakan berbagai workshop, support group, dan seminar berlandaskan riset yang dilakukan maupun isu yang hangat diperbincangkan. Beberapa di antaranya ialah Sharing Stories, Lingkar Studi Suicidologi, dan peringatani Hari Penyintas Kehilangan Bunuh Diri Sedunia.
Menurut Annisa, pada setiap acara yang diselenggarakan Into The Light Indonesia, banyak masyarakat yang ragu berkonsultasi ke psikolog atau psikiater karena terbebani stigma kesehatan mental selalu berkaitan dengan gangguan jiwa yang akan disampaikan oleh orang-orang di sekelilingnya.
Into The Light Indonesia mendorong dan memfasilitasi mereka yang membutuhkan bantuan untuk terlibat di komunitas sosial agar terbantu, terutama di kelompok marginal yang permasalahannya sulit diterima oleh masyarakat sekitarnya.
“Saat tidak mendapat dukungan dari lingkungan tempat tinggal, mereka berhak menerima dukungan sosial dari luar. Kami selalu mengatakan ‘kamu tidak sendiri’ karena perasaan sendiri dan tidak terkoneksi dengan orang lain merupakan salah satu faktor terbesar dari perilaku bunuh diri.”
Bersama Dewan Pers, Into The Light Indonesia menyusun suicide guideline news agar media menghindari pemberitaan sensasionalisme dalam kasus perilaku bunuh diri. Tujuannya agar ini tidak memicu perilaku serupa pada orang lain.
Baca Juga: Kalau Kamu Begini, Kamu Bukan Feminis: 7 Pandangan Saklek Soal Menjadi Feminis
2. Single Moms Indonesia
Berangkat dari trauma pribadi, Maureen Hitipeuw mendirikan komunitas Single Moms Indonesia (SMI) pada 2014 untuk menyediakan wadah bagi para ibu tunggal dalam mendukung satu sama lain. Bersama 5.900 anggota, mereka bergerak melawan stigma “bukan perempuan baik-baik” yang disampaikan masyarakat.
“Untuk mengubah stigma memerlukan banyak edukasi dan meningkatkan kesadaran dan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Jadi kami berusaha mematahkan stigma lewat unggahan di media sosial dan fokus memberdayakan para ibu tunggal, supaya mereka lebih kuat dalam menghadapi stigma,” ujar Maureen pada Magdalene, (27/7).
Pemberdayaan itu dilakukan dengan berbagai program mengasah kemampuan, seperti kelas membuat sosis, pemasaran di media sosial, dan menulis.
Public Relations & Partnership SMI, Sagita Ajeng Daniari menambahkan, komunitas ini juga mengadakan kelas soft skill, seperti healing. Ini diperlukan karena proses pemulihan menjadi ibu tunggal akibat perceraian dan ditinggal suami meninggal itu berbeda. Harapannya, kegiatan tersebut dapat membantu para ibu untuk bangkit, merasa aman, menerima masa lalu, dan punya harapan positif untuk masa depan.
Kemudian, terdapat program SMI Sisterhood, yakni mentorship dalam bentuk one on one dengan memasangkan ibu tunggal yang sudah berdamai dengan masa lalunya, untuk berperan sebagai “big sister” kepada anggota yang baru mengalami dan membutuhkan pendampingan.
SMI berusaha menciptakan ruang aman bagi para anggotanya. Secara ketat, mereka menyortir komentar di Facebook dan Instagram yang layak dipublikasikan sehingga tidak ada yang disudutkan atau dihakimi.
“Sudah terlalu banyak penghakiman dan perilaku kurang menyenangkan yang diterima ibu tunggal dari masyarakat. Oleh karena itu, di sini kami sangat menjaga supaya sesama anggota saling mendukung dan menguatkan,” tutur Maureen.
Untuk dapat menghargai ibu tunggal sebagaimana perempuan lainnya, Maureen menyampaikan, masyarakat perlu memiliki empati terhadap siapa pun agar dapat menghargai orang lain dengan latar belakang dan perjuangannya masing-masing.
Baca Juga: Saya Ibu dengan HIV, Mampu Lawan Stigma Masyarakat
3. Suara Peranakan
Menciptakan ruang inklusif melalui edukasi dan refleksi diri, Suara Peranakan lahir sebagai media untuk para Tionghoa-Indonesia dan warga minoritas lainnya guna memperoleh keadilan, perlakuan setara, dan manusiawi.
Di antara berbagai komunitas Tionghoa-Indonesia yang mempublikasikan konten sejarah dan budaya, Suara Peranakan memilih lebih progresif dan mengangkat isu politik dalam mengedukasi masyarakat, lewat konten di media sosial, tulisan pada situs suaraperanakan.wordpress.com, dan webinar.
“Selama ini kami melihat Tionghoa-Indonesia itu rentan dan banyak mendapatkan stigma. Kelompok ini jarang mendapatkan panggung, kalaupun ada pasti penguasa atau konglomerat, seperti pemilik Lippo Group dan MNC Group. Sementara banyak masyarakat biasa yang suaranya tidak terwakilkan oleh mereka maupun yang ada di media,” ujar Koordinator Editorial Suara Peranakan, Charlenne Kayla, (27/7).
Dalam mempublikasikan konten, peristiwa bersejarah yang masih membekas pada masyarakat Tionghoa-Indonesia menjadi perhatian mereka. Agar pesan tetap tersampaikan tanpa melibatkan testimoni penyintas, Suara Peranakan berusaha menyampaikan kebenaran peristiwa dengan menyertakan verifikasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Selama bergerak sejak Juli 2020, Charlenne menceritakan banyaknya respons positif yang diterima dari pembaca.
“Kami menciptakan safe space dengan membuka open call response di Instagram. Di sana teman-teman berbagi pengalaman sesuai pembahasan yang diangkat, misalnya Tionghoa-Indonesia di komunitas LGBTQ+, Tionghoa Muslim, dan standar kecantikan,” katanya.
Menurut Charlenne, sikap ketidakadilan terhadap masyarakat Tionghoa-Indonesia dapat diperoleh dengan mempelajari sejarah mereka.
“Sebenarnya masyarakat Tionghoa-Indonesia maupun non Tionghoa sama-sama perlu belajar mengenai identitas diri, budaya, dan peristiwa yang dialami. Dengan memperkaya diri, harapannya kita lebih berempati, baik terhadap komunitas sendiri maupun orang lain,” ucapnya.
Tulisan ini adalah bagian dari seri tulisan bertema “Usaha Menghapus Stigma”. Magdalene akan mewawancarai beberapa komunitas di Indonesia yang berdedikasi menghapus stigma di berbagai bidang, termasuk kesehatan mental, kelompok minoritas LGBT+, pekerja seks, dan lainnya. Simak terus tulisan lainnya ya.






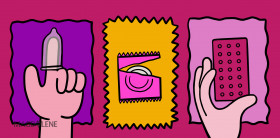

Comments