Urusan panjang pendek hijab atau jilbab sekarang ini bisa jadi standar baik buruknya seorang muslimah. Lebih jauh lagi, hal ini sering dijadikan indikasi pada jalur mana perempuan muslim akan menuju nantinya: Surga atau neraka.
Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Alimatul Qibtiyah, yang juga seorang peneliti, mengatakan sekarang ini banyak miskonsepsi tentang pakaian muslimah dibandingkan dengan masa lalu. Masyarakat dan kebanyakan ulama saat ini menafsirkan landasan normatif yang menjadi standar hijab, yakni Surat An-Nur ayat 30-31 dan Al-Ahzab ayat 59 dalam Al-Quran, secara tekstual tanpa konteks sejarah, ujarnya.
Surat An-Nur 30-31 pada intinya mengharuskan laki-laki menundukkan pandangannya, dan perempuan diharuskan menutupkan kain kerudung ke dadanya, kecuali pada suami, ayah, ayah suami, anak-anaknya, atau putra-putra suami mereka, saudara laki-laki, anak saudara perempuan, budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.
Sementara itu, Surat Al-Ahzab menyerukan perempuan agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh agar mudah dikenal, tidak diganggu.
“Mereka pun menyimpulkan bahwa pakaian syar’i (sesuai syariah) bagi muslimah adalah pakaian yang tidak berwarna cerah, berbentuk baju kurung (jubah), tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan, dan ditambah dengan jilbab yang menutup sampai pantat. Bahkan ada yang mengatakan wajah pun harus ditutup (cadar),” kata Alimatul, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pimpinan 'Aisyiyah, organisasi perempuan dalam Muhammadiyah.
Ia berbicara dalam webinar Kanal Moderasi Islam bertema Ragam Perspektif Pakaian Syar’i yang diadakan pada 23 April.
Perdebatan kemudian muncul dari sebagian ulama dan masyarakat Muslim reformis yang menggugat standar syar’i itu dengan mengkaji ayat-ayat tersebut tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Selain pendekatan teks, mereka juga menggunakan keruntutan logika, pendekatan dan pengalaman atas realitas spiritual keagamaan, serta kajian antropologi, historis, geografis, dan juga politik identitas serta otonomi tubuh perempuan.
Baca juga: Jilbab, Hijab, Cadar, dan Niqab: Memahami Kesejarahan Penutup Tubuh Perempuan
Kelompok ini menyimpulkan bahwa pakaian muslimah yang syar’i itu yang sopan sesuai dengan waktu dan tempat, aman, nyaman, sehat, dan tidak ada paksaan.
“Pakaian syar’i seharusnya tidak ditentukan oleh warna, bentuk, ukuran, dan juga bahannya. Syar’i menurut saya adalah yang sopan dan tidak menggoda sehingga mengakibatkan fitnah, nyaman, sehat, dan juga tidak terpaksa,” ujar Alimatul.
Tidak ada pakaian syar’i di Timur Tengah
Peneliti Islam dan anggota Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), Pradana Boy ZTF mengatakan, di tempat kelahiran Islam sendiri yaitu di Jazirah Arab, standar pakaian syar’i yang sering kali menjadi ukuran normatif beragama orang Indonesia, justru tidak berlaku, bahkan mungkin tidak ada.
Ia mengisahkan pengalamannya berdiskusi dengan tokoh agama Lebanon, Syaikh Hassan al-Amin, saat berada dalam sebuah acara dialog lintas agama di Austria. Pradana yang penasaran dengan pakaian syar’i akhirnya bertanya pada Syaikh Hassan terkait hal itu. Namun yang terjadi, si Syaikh mengernyitkan dahi.
“Dia balik bertanya kepada saya tentang apa yang saya maksudkan dengan jilbab atau hijab syar’i. Lalu, saya menjelaskan tentang tren pakaian Muslim di Indonesia. Dengan wajah kebingungan Hassan mengatakan sulit menentukan mana hijab syar’i dan bukan syar’i di negaranya,” ujarnya dalam webinar yang sama.
“Tiap-tiap daerah memiliki model hijabnya masing-masing tergantung pengaruh budayanya. Lalu mana yang syar’i di antara semuanya? Menurut Hassan, nilai syar’i atau tidak syar’i-nya jilbab atau hijab bukan pada model dan ukurannya, tetapi pada fungsi utamanya,” kata Pradana.
Di Iran, tambahnya, laki-laki yang menggunakan jubah dan turban harus melalui pendidikan agama minimal enam tahun. Sedangkan di Indonesia, siapa saja bisa memakai jubah. Ada identifikasi dengan tingkat kesalehan ketika seorang lelaki memakai jubah maupun pakaian syar’i.
Baca juga: Berhijab atau Tidak, Terserah Masing-masing
“Di Arab, petani dan peternak aja pakai jubah, kalau di Indonesia sudah pasti disebut religius,” ujar Pradana.
Contoh lainnya, menurutnya, adalah kopiah, yang di Indonesia identik dengan identitas seorang Muslim. Demikian pula dengan sarung atau baju koko. Namun identitas itu tentunya tidak dipakai oleh Muslim di seluruh dunia, karena kopiah dan baju koko adalah hasil bentukan budaya di Indonesia.
“Pertanyaannya adalah, ketika seorang muslim tidak memakai standar seperti itu, apakah ia menjadi kehilangan ke-muslim-annya? Dalam pemahaman inilah publik seharusnya bisa membedakan agama sebagai nilai dan pakaian sebagai kebudayaan,” ujar Pradana.
Dalam kaitan pakaian dengan religiositas, ia menganggap bahwa prinsip utama yang dipegang adalah nilai karena bersifat abadi dan lintas budaya, lokasi, serta batas zaman. Hijab yang dari waktu ke waktu berbeda model termasuk dalam hal-hal kultural yang bersifat sementara, terikat waktu, dan zaman, karena itu lalu bersifat relatif dari satu masa ke masa lainnya.
“Tentu tidak berarti harus dipertentangkan. Tetapi tidak juga harus dimutlakkan. Mutlak nilainya, tetapi nisbi perwujudannya,” katanya.
Sepanjang nilai-nilai yang berkaitan dengan pakaian tidak terabaikan, maka tidak ada keabsolutan bentuk atau model pakaian, atau bahkan tafsir absolut atas aurat.
“Dalam Islam, pakaian memiliki sejumlah fungsi di antaranya adalah sebagai penutup aurat, perhiasan, dan pelindung. Menutup aurat adalah nilai, tapi harus bagaimana, pakaiannya itu yang menyesuaikan,” ujar Pradana.
Sehingga prinsip yang berkaitan dengan pakaian itu terletak pada fungsinya, ujarnya. Sepanjang nilai-nilai yang berkaitan dengan pakaian tadi tidak terabaikan, maka tidak ada keabsolutan bentuk atau model pakaian, atau bahkan tafsir absolut atas aurat. Klaim bahwa satu model pakaian lebih Islami dibandingkan dengan pakaian lainnya adalah kurang tepat, kata Pradana.
“Kembali kepada Syaikh al-Ghazali, ia menyebut sorban sebagai contoh model pakaian yang disalahartikan sebagai pakaian Islami. Sorban bukanlah lambang keislaman melainkan budaya masyarakat Arab,” ujar Pradana.
Komoditas dagang
Tren mode kerudung syar’i yang sekarang ini jamak ditemukan di pasaran memiliki sejarah yang panjang, sepanjang kainnya yang bisa menjulur sampai mata kaki. Seperti yang disebut Pradana, tren jilbab syari’i dipengaruhi budaya dan kepentingan politik serta ekonomi sejak masa Orde Baru.
Carla Jones, profesor Antropologi Universitas Colorado, Amerika Serikat, yang penelitiannya berjudul Fashion and Faith in Urban Indonesia, mengatakan kekuatan Islam di ranah politik nasional pada 1980-1990 meningkat, membuat penguasa saat itu, Soeharto, merangkul kekuatan itu. Sejak saat itu, identitas muslim di kalangan anak muda meningkat.
Baca juga: Mengapa Saya Menolak Hari Hijab Sedunia
Pemakaian jilbab yang sebelumnya hanya dipakai oleh perempuan lanjut usia yang baru pulang naik haji, menurut Jones, mulai digandrungi anak muda yang mencoba hidup lebih Islami. Muncullah tren busana muslim menjadi komoditas di Indonesia, ditandai dengan munculnya penggambaran gaya hidup muslimah dalam majalah perempuan, baik yang arus utama seperti Femina, maupun yang ditujukan khusus untuk muslimah, yakni Ummi dan Noor.
Para pebisnis busana Muslim berlomba-lomba menggunakan peluang ini dengan menghubungkannya dengan penguatan iman. Standar busana Muslim yang “dijual” beserta embel-embel iman dan kesalehan dengan maksud keuntungan (capital) itulah yang Jones kategorikan sebagai commodity fetish, atau hubungan antara uang dan komoditas yang dipertukarkan di pasar.
“Jika kesalehan serta keimanan adalah ekspresi yang ditonjolkan atas nama fashion, maka konsep commodity fetish mungkin cukup menggambarkan transformasi tren hijab syar’i di Indonesia dari hal-hal religius menjadi fashion pakaian biasa,” tulis Jones.
Pradana juga mengatakan bahwa tren dengan label syariah sekarang ini lebih hanya sekedar untuk bagian dari pemasaran, tujuannya bukan lagi murni menjalankan fungsi agama tetapi lebih ke arah kapitalisme.
“Semakin panjang (pakaiannya) yang untung malah pabrik garmen,” ujarnya.




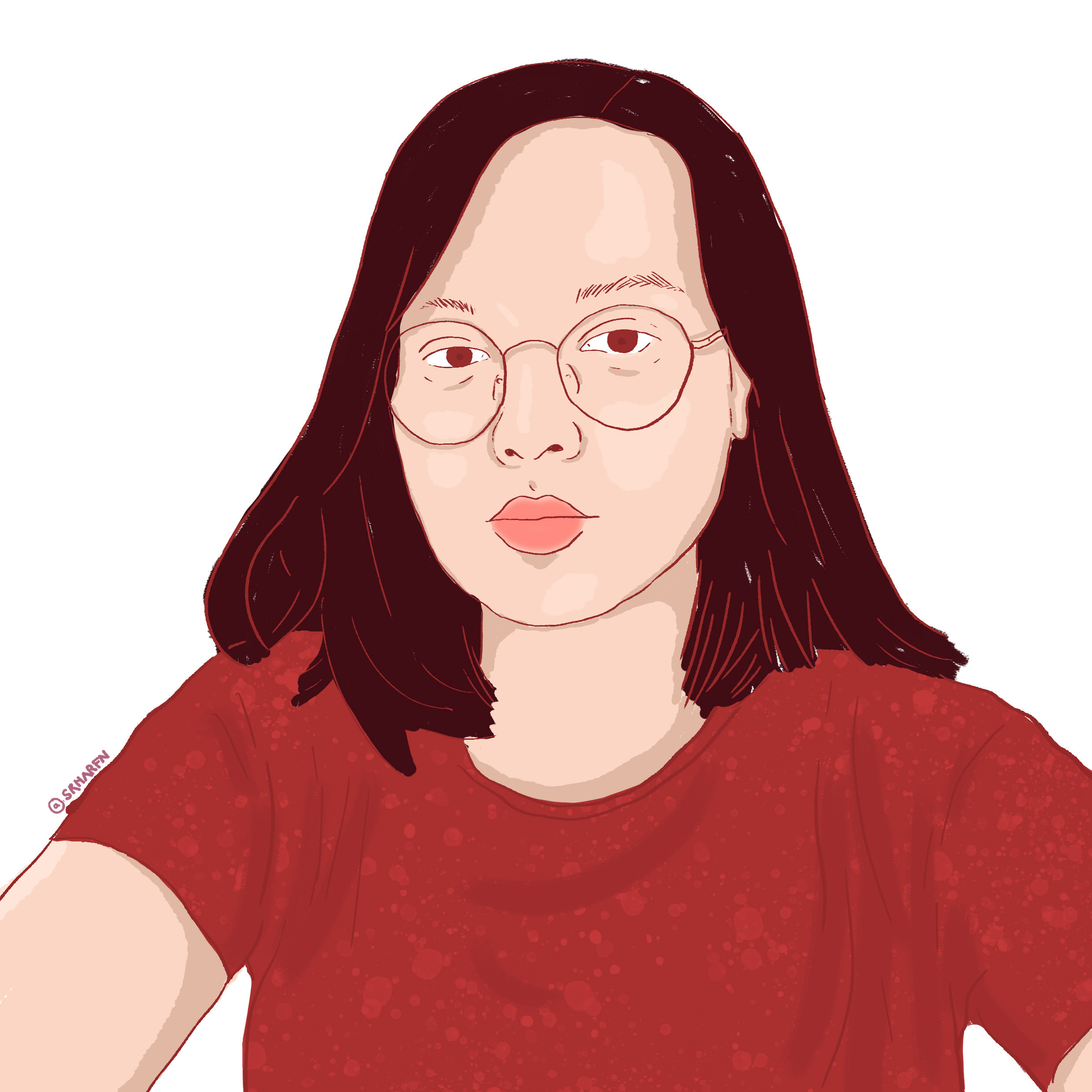



Comments