Tubuh perempuan dan anak perempuan selalu dijadikan perdebatan, khususnya dalam isu islamisasi di ruang publik, lebih spesifik lagi soal penggunaan jilbab pada anak perempuan. Ketika sebuah media asing mengeluarkan liputan pada 25 September 2020 lalu tentang penggunaan jilbab pada anak perempuan di keluarga muslim, liputan ini menjadi kontroversi. Situs media tersebut diserang dan editornya mendapat perisakan daring berupa ancaman doxing (penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan). Banyak orang menganggap liputan ini kontroversial karena media tersebut mengkritik pemakaian jilbab pada anak.
Dua selebritas Twitter alias selebtwit, sebut saja R dan F, menuduh video pendek liputan tersebut sebagai agenda imperialisme. Kedua lelaki ini mencurigai liputan yang, menurut mereka, seharusnya mempertanyakan juga kebiasaan orang tua memberikan pakaian lain seperti jin, sarung, hotpants atau kolor kepada anaknya. Pendapat dua selebtwit lelaki ini dicuit ulang hingga ratusan kali di Twitter dan sungguh membuat saya merasa patah hati.
Bagaimana tidak, para lelaki ini tidak lahir dan tumbuh sebagai perempuan dari keluarga muslim, tapi bisa-bisanya mereka menyamakan penggunaan jilbab dengan pakaian lain. Sebagai anak perempuan yang wajib memakai jilbab sejak dini, saya pikir anjuran menggunakan jilbab tidak bisa disamakan dengan penggunaan celana jin. Penggunaan celana jin tidak tertera di dalam Al-Quran sehingga bukan sebagai bagian dari kewajiban beragama. Ketika saya menolak memakai jin atau kolor, tentu orang tua muslim saya tidak akan berdebat tentang itu karena celana jin dan kolor bukan ajaran agama.

Jilbab punya legitimasi kitab suci, bukan sekadar pakaian yang bisa dicopot-pasang. Oleh karena itu sering kali perempuan yang melepas jilbab menerima hujatan dan persekusi. Pertanyaan seperti "jilbabnya mana?" adalah cibiran keras yang menggerus mental setiap hari. Ini tidak terjadi jika perempuan berhenti menggunakan celana jin atau kolor. Hal dasar ini sulit dimengerti lelaki yang tidak pernah diberi kewajiban menggunakan jilbab.
Benar bahwa perempuan muslim menggunakan jilbab di negara-negara seperti Perancis dan Amerika Serikat sebagai bentuk perlawanan dari opresi, sebab jilbab bukan norma masyarakat umum. Jilbab memberikan sebuah identitas sekaligus pernyataan menolak tubuh perempuan sebagai komoditas dan sentimen negatif terhadap komunitas muslim. Karena jilbab bukan norma utama, maka tidak akan ada yang menghardik kamu jika melepas jilbab. Hambatan justru ada ketika mengenakannya, karena sebaliknya, tidak berjilbab adalah norma utama.
Bagi saya, menyerang liputan nasib anak perempuan yang diwajibkan pakai jilbab sangat tidak bijak. Seharusnya sebagai selebtwit yang mengaku kritis, mereka tidak mendukung tren pola pengasuhan yang berdampak pada opresi masyarakat terhadap anak di masa depan.
Baca juga: Hijab dan Kita yang Tak Pernah Diberi Pilihan
Islam, kapitalisme, dan politik
Sebagaimana ajaran agama Islam di Indonesia yang beragam, begitu juga pengalaman berjilbab di Indonesia. Beberapa perempuan berjilbab karena pilihannya setelah dewasa, karena merasa nyaman, dan sebagai bagian dari kultur keluarga yang berjilbab dan menutup aurat. Ada pula yang memang dibiasakan sejak kecil. Pengalaman perempuan berjilbab adalah personal, dengan dampak yang juga personal. Oleh karena itu, yang harus dianalisis adalah bagaimana struktur dan kultur masyarakat yang menjadikan jilbab sebagai norma dan kontrol sosial perempuan. Masyarakat macam ini nyata adanya di Indonesia. Dalam ruang daring maupun luring.
Sebelum membela pemakaian jilbab di Indonesia, kita harus terlebih dahulu melihat kenyataan bahwa Islamisasi ruang publik di Indonesia adalah sebuah tren yang didukung oleh kekuasaan dan kapitalisme. Jonas Bens dan Timo Duile dalam artikelnya berjudul “Indonesia and the ‘Conflictual Consensus”: A Discursive Perspective on Indonesian Democracy" dalam jurnal Critical Asian Studies 49 (2017) memperlihatkan tren partai-partai nasionalis yang mencoba mencitrakan dirinya Islami, dan sebaliknya partai Islam berusaha mencitrakan dirinya nasionalis. Akibatnya, hanya ada dua ideologi bertarung dalam kekuasaan: nasionalis yang Islami. Tren nasionalis Islam dalam politik ditangkap oleh pemilik modal dan menghasilkan berbagai label dalam konsumsi sehari-hari makanan, pakaian, riasan, hingga lemari es.
Jika memang jilbab bukan opresi terhadap perempuan di Indonesia, mengapa perempuan muslim yang mau melepasnya atau transpuan yang mau memakainya justru dirisak dan dipersekusi?
Islamisasi ini juga hadir di media dalam wujud pencitraan perempuan dan pembentukan perempuan. Di media, kita bisa lihat bagaimana citra perempuan yang penurut, pasif, dan mengayomi dibungkus dengan ucapan Islami dalam Sinema Indosiar, Catatan Hati Seorang Istri (CHSI). Serial ini setali tiga uang dengan kisah melodrama Oh Mama Oh Papa yang pernah disiarkan oleh ANTV, namun dibungkus secara Islami karena CHSI diadaptasi dari buku laris dari penulis Islami, Asma Nadia. Islamisasi tersebut diwujudkan dalam pakaian para aktor dan aktris. Jilbab disematkan sebagai prasyarat tokoh protagonis.
Kita semua tahu bagaimana akhirnya politik dan media juga memengaruhi tren orang tua mendidik anak. Islamisasi pengasuhan atau Islamic parenting bukan hal yang asing dan diajarkan dengan mudah tersedia dalam layar gawai para orang tua.
Islamic parenting adalah tren yang merupakan bagian dari pembangunan keluarga muslim dan tren keislaman di Indonesia. Kamu bisa menemukan pelajaran pendidikan membangun keluarga muslim dengan mudah di YouTube, Instagram, dan sebagainya. Sehingga ketika seorang ibu berupaya membiasakan anak perempuannya pakai jilbab sejak dini, ia sedang menyesuaikan anaknya untuk bisa bertahan hidup dengan Islam sebagai arus utama masyarakat.
Islamisasi di ruang privat berupa pola pengasuhan ataupun di publik berupa “imbauan” berjilbab di sekolah negeri harus dilihat sebagai suatu kesinambungan, karena ruang privat dan publik tidak pernah terpisah seperti air dan minyak. Ketika ada kewajiban memakai jilbab di sekolah negeri, itu adalah insiatif pemerintahan nasionalis-islamis yang disokong oleh kehendak orang tua untuk Islamic parenting. Maka yang terjadi adalah pemaksaan jilbab kepada anak perempuan sejak dini. Tubuh perempuan memang disasar sebagai penanda kekuasaan oleh tren keislaman hari ini.
Baca juga: Rangkul Dia, Perempuan yang Membuka Jilbabnya
Suara yang hilang adalah bagaimana nasib anak-anak yang sudah dibiasakan berjilbab dan tumbuh-kembang dalam lingkungan Islami? Pilihan Islamic parenting atau secular parenting adalah hak tiap orang tua untuk mendidik anaknya, tapi bagaimanakah nasib anak-anak ini setelah dewasa?
Saya adalah anak yang dibiasakan untuk berjilbab sejak kecil. Ketika saya dewasa dan menemukan identitas diri saya tidak cocok dengan jilbab, hasilnya adalah nestapa. Ketika saya memilih melepas jilbab, saya mengalami perisakan oleh lingkungan terdekat, dituduh melacur, murtad, tidak dianggap bagian dari keluarga besar saya lagi, dan tidak diterima untuk mudik setiap Lebaran. Saya mengalami depresi hebat dan berkali-kali mencoba bunuh diri karena saya menyesuaikan identitas diri dengan apa yang telah dipaksakan keluarga.
Norma gender dalam pola pengasuhan
Feminisme sudah menyasar bahwa pola pengasuhan anak yang berbasis gender adalah basis dari opresi terhadap perempuan. Islamic parenting, sebagaimana yang tersedia dengan mudah di konten-konten media sosial atau YouTube, berisi tentang bagaimana mendidik anak sesuai ajaran Islam/Nabi yang membedakan pola pengasuhan anak dan pakaian untuk anak-anak. Tidak hanya pakaian, dibedakan juga apa yang wajib dilakukan anak perempuan dan lelaki melalui institusi selanjutnya, yakni sekolah.

Pertama-tama, pengasuhan dibedakan melalui identitas kelamin dan penentuan identitas gender anak oleh orang tua. Anak lelaki akan disunat dan dirayakan (diberi uang dan hadiah) bahwa ia laki-laki muslim. Sementara anak perempuan tidak mengalami hadiah dan uang sebab ia harus mengenakan jilbab. Kemudian orang tua akan memasukkan anak ke sekolah Islami, baik swasta maupun negeri.
Biasanya anak perempuan diberi kelas khusus bernama "keputrian", yang mengajarkan perempuan untuk menjadi perempuan, dengan menghindari seks bebas, berpakaian Islami, dan patuh pada suami. Pembedaan pola pengasuhan gender ini terus berlanjut dalam institusi keluarga dan pendidikan hingga saat anak akhirnya menemukan identitas diri, ia harus mengalami beberapa lapisan tekanan dari lingkungan Islami tempat ia dibesarkan hingga orang tua yang menjebaknya dalam ideologi agama.
Pola pengasuhan anak yang berlandas jenis kelamin yang biner, juga tidak memberi tempat bagi anak LGBTIQ+. Nabilah, 27, diusir dari rumah ketika memilih memakai jilbab untuk menegaskan identitasnya sebagai transpuan muslim. Nabilah juga berasal dari keluarga Islami yang membesarkan dan mengharapkan dia menjadi laki-laki. Ketika Nabilah ikut demonstrasi besar di Jakarta pada 2019, polisi menangkapnya dan melepas jilbabnya karena menganggap dia sebagai lelaki.
Baca juga: Sebenarnya Kita Berproses Jadi Lebih Baik atau Sekadar Mabuk Berhijab?
Jika memang jilbab bukan opresi terhadap perempuan di Indonesia, mengapa perempuan muslim yang mau melepasnya atau transpuan yang mau memakainya justru dirisak dan dipersekusi? Masyarakat dan lelaki harus memahami analisis lapisan opresi ini untuk melihat duduk perkara jilbab di Indonesia.
Keluarga Nabilah dan keluarga saya yang menerapkan Islamic parenting menjadi opresi pertama dan menjadi jalan bagi institusi masyarakat berikutnya untuk membeda-bedakan jenis kelamin. Jilbab menjadi alat untuk menindas perempuan karena keluarga dan masyarakat mengontrol dan (hanya) mengharuskan perempuan biologis untuk berjilbab.
Dua institusi ini bukan dikotomis privat/publik karena tidak pernah ada benar-benar pemisah antar kedua ruang tersebut. Islamic parenting, tren Nasionalis-Islam, dan komodifikasi Islam adalah hasil interaksi yang dirayakan masyarakat, dan dibela oleh selebtwit yang mengaku kritis. Dan perempuan beserta gender non-muslim lainnya harus menanggung perisakan sendiri-sendiri.




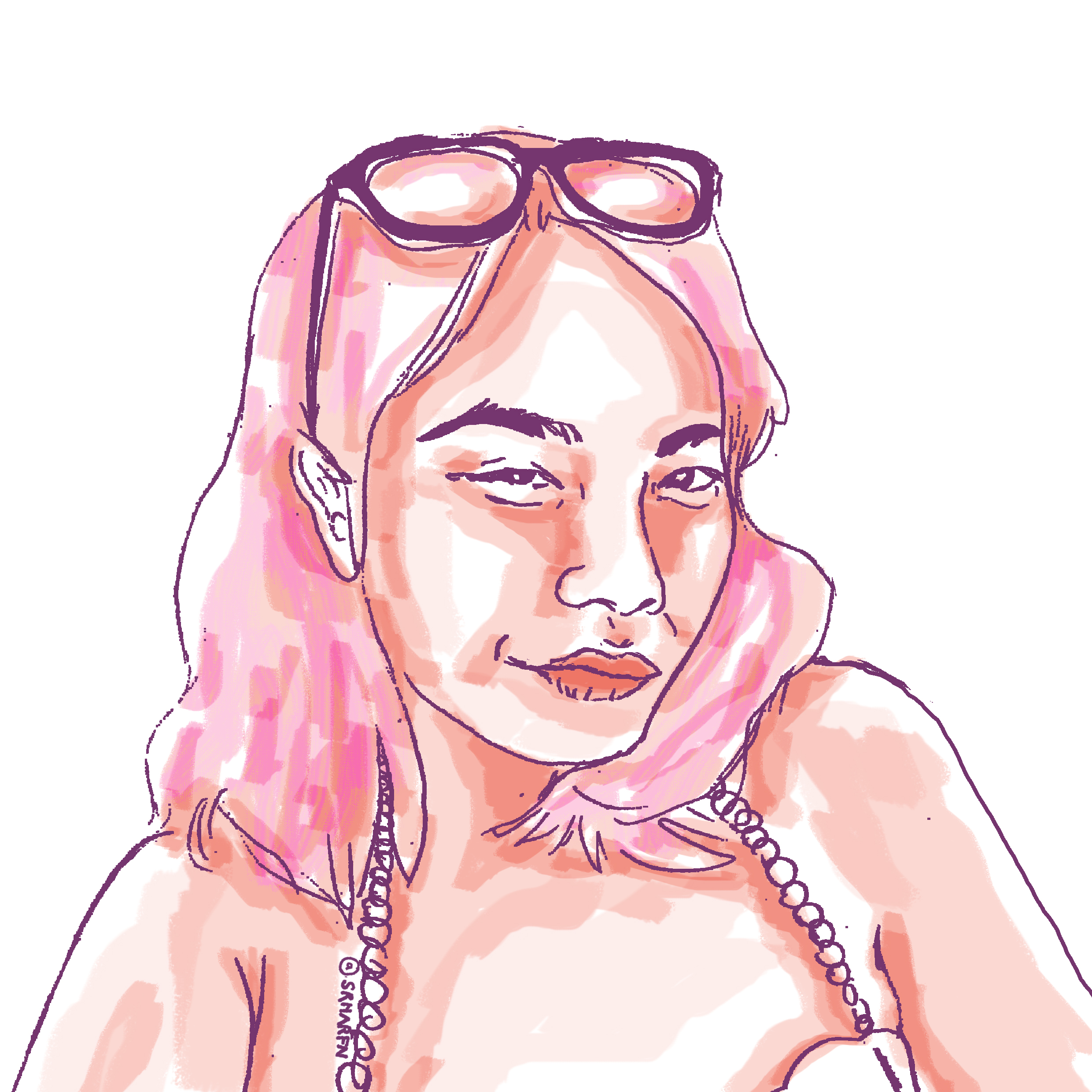

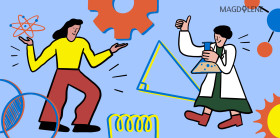

Comments