Usiaku sekarang hampir 20 tahun, aku tinggal di perkampungan kecil pinggir kota di mana usia rata-rata pernikahan di sini adalah 18-22 tahun. Banyak orang sepermainanku yang sudah menikah bahkan mempunyai anak. Itu bukan masalah bagiku.
Hal yang selalu mengganggu pikiranku adalah alasan mereka meninggalkan masa muda untuk berkomitmen seserius pernikahan. Orang-orang di sekitarku juga sudah menggodaku untuk segera menikah dan menyusul teman-temanku. Tapi, aku selalu ngotot untuk berkata tidak, bukan untuk menikah muda tapi untuk pernikahan itu sendiri.
Alasan terbesarku adalah aku tidak ingin hidup seperti kakak-kakakku. Kakak perempuanku yang pertama berusia 18 tahun ketika menikah. Ia mengandung anak pertamanya di masa akhir SMAnya. Ia ditinggalkan suaminya ketika usia anak pertamanya 1 tahun. Setelah itu, ia bekerja apa saja untuk menghidupi dirinya dan anaknya.
Di usia anaknya yang ke 3 tahun, ia pergi ke Malaysia untuk bekerja menjadi TKI. Di tahun kelimanya di Malaysia, ia mulai bisa menciptakan ekonomi yang stabil dan mampu membelikan anaknya kebutuhan-kebutuhan sekunder bahkan tersier. Tiga tahun yang lalu, ia menikah dengan warga negara Malaysia. Warga biasa yang hanya seorang pegawai. Ia bekerja sampai larut malam untuk mencukupi kebutuhannya dan suaminya, terkadang ia menomor-duakan anaknya.
Di mataku, pernikahan keduanya tidak kalah menakutkan dengan pernikahan yang pertama. Suaminya memang bertanggung jawab, tapi aku tidak melihat adanya kebahagian di pernikahannya kali ini. Apapun kebahagian yang ia dan suaminya tampilkan di depan keluarga kami adalah kebohongan.
Kakak perempuanku yang kedua menikah di tahun 2006. Suaminya tidak pernah menafkahinya. Segala aset yang mereka miliki, rumah, kendaraan, furniture, adalah hasil kerja kakakku. Bahkan, uang sekolah dan uang jajan anak keduanya semuanya berasal dari kakakku. Kakakku bukanlah wanita yang kaya, ia hanya buruh pabrik.
Pada tahun 2011 ia memutuskan berangkat ke Malaysia menyusul kakakku yang pertama. Ia meninggalkan anak-anak dan suaminya. Orang tuaku dan akulah yang mengambil tanggung jawab untuk menjaga anak-anaknya. Sedangkan, suaminya hanya pengangguran yang sekali-kali datang untuk menjenguk anak-anaknya. Tentu saja pernikahan kakakku ini menakutkan, mempunyai suami yang tidak bertanggung jawab dan harus menjadi kepala keluarga bahkan ketika masih mempunyai suami. Sebulan yang lalu, ia resmi bercerai dari suaminya.
Lagi-lagi perceraian di keluarga besarku. Bukan perceraian mereka yang membuatku takut, tapi, ketidakbahagian merekalah yangmembuatku takut. Bagaimana mereka mempertahankan rumah tangga, mendapatkan pasangan suami yang tidak bertanggung jawab, dan terpaksa menelantarkan anak-anak mereka.
Di usiaku yang hampir dua puluh ini, aku sekali lagi tidak percaya akan pernikahan. Pernikahan kakak-kakakku cukup mengajarkanku banyak, dan memberikan sedikit trauma kepadaku walaupun aku tidak pernah menikah. Aku tidak mau suatu saat aku menikah dan mengikuti jejak pernikahan kakak-kakakku. Menurutku, menjadi perempuan tidak harus menikah, walaupun di tempatku tinggal adalah aib bagi perempuan yang sudah di atas dua puluh lima yang masih melajang.
Sekarang, fokus utamaku adalah bagaimana menjadikan diriku sekuat mungkin. Karena di masa depan, hanya akulah yang akan mengatur finansial dan kebutuhanku yang lain, bukan seorang suami atau pasangan. Di jaman kesetaraan gender ini, sangat penting untuk semua perempuan menjadi independen.



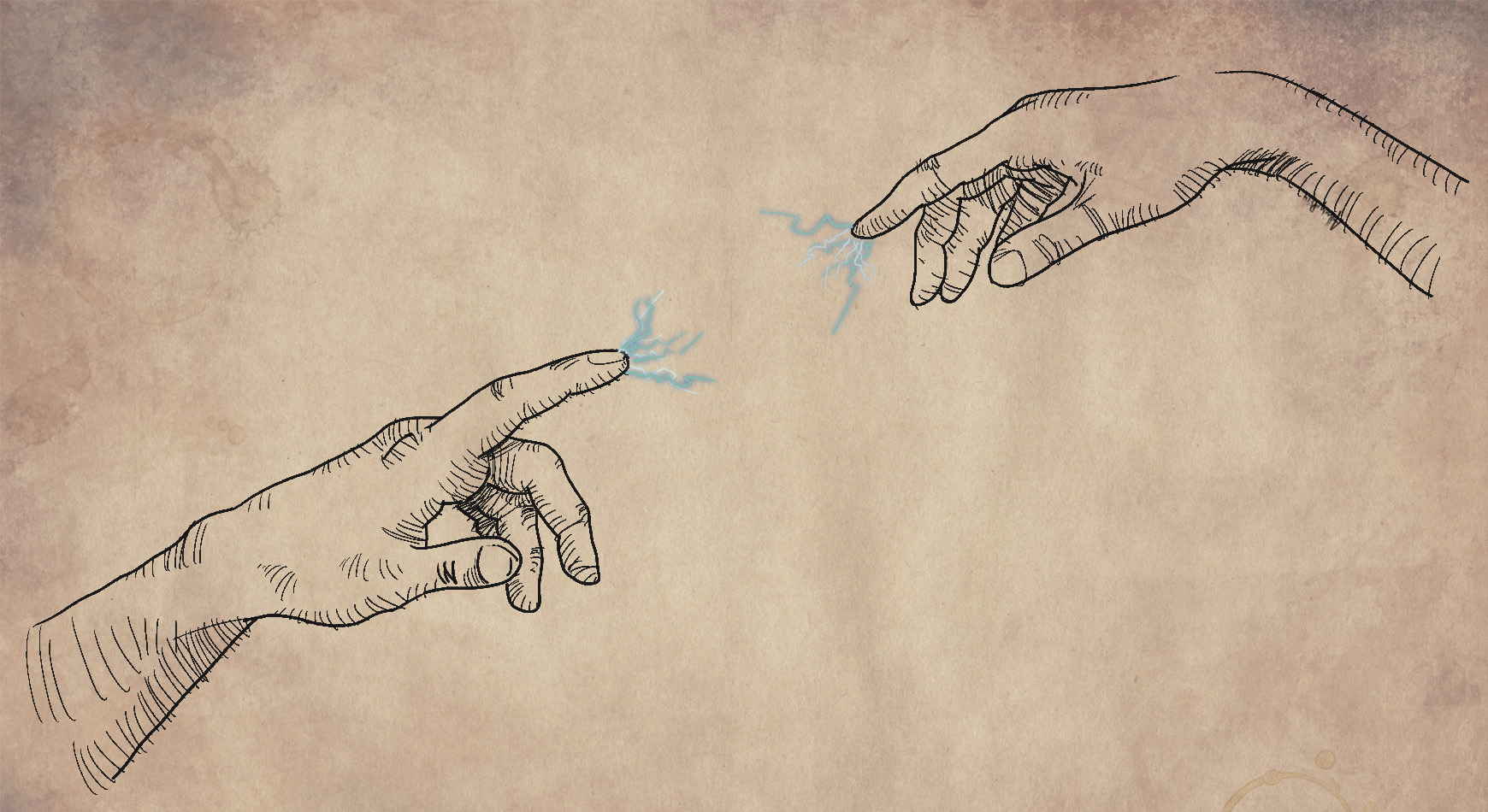




Comments