Penggunaan data digital sekarang ini sudah jamak ditemukan dalam berbagai industri dan birokrasi, seiring kondisi dunia yang sudah menjadi sangat terhubung. Negara, perbankan, sistem komunikasi, transportasi, teknologi, dan organisasi pembangunanan internasional telah mengadopsi berbagai bentuk identifikasi (ID) digital. Bahkan, saat ini banyak pihak menyerukan perlunya mempercepat proses pendaftaran untuk memastikan setiap orang di planet ini memiliki identitas digital mereka sendiri.
Kita tidak serta-merta sampai pada era baru manajemen data digital ini dengan begitu saja. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara aktif mendorong berbagai negara untuk memberikan jaminan hukum atas status kependudukan setiap warga. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memerangi kemiskinan struktural, status kewarganegaraan yang tidak jelas, serta pengucilan sosial.
Berbagai kebijakan sosial ini sengaja menyasar populasi miskin dan rentan – termasuk masyarakat adat, penduduk dari ras atau etnis minoritas, serta perempuan – untuk memastikan mereka mendapatkan kartu identitas sehingga bisa mengakses layanan umum. Dengan merangkul kelompok marginal, negara memberikan perhatian pada orang-orang yang secara historis mengalami pengucilan secara sistematis dan tidak diakui secara formal sebagai warga negara.
Namun, penelitian saya mengungkap bahwa negara di seluruh dunia dapat menyalahgunakan berbagai sistem identitas digital yang diakui secara internasional. Hasil studi ini juga diadaptasi menjadi buku berjudul ‘Legal Identity, Race, and Belonging in the Dominican Republic: From Citizen to Foreigner’ (Identitas Hukum, Ras, dan Rasa Memiliki di Republik Dominika: Dari Warga Negara Menjadi Orang Asing).
Buku itu menyoroti bagaimana pemerintah Republik Dominika menerapkan berbagai kebijakan yang secara sistematis menghalangi warga keturunan Haiti berkulit hitam untuk mengakses dan memperbarui identitas legal yang diperlukan di negara tersebut. Selama bertahun-tahun, orang-orang keturunan Haiti yang lahir di Republik Dominika berjuang mati-matian untuk (kembali) mendapatkan identitas mereka.
Namun, para pejabat berdalih bahwa selama lebih dari 80 tahun mereka telah keliru memberikan dokumen Dominika kepada anak-anak dari imigran Haiti, dan sekarang perlu memperbaiki kesalahan ini.
Di lain pihak, warga keturunan Haiti mengatakan bahwa mereka adalah warga Dominika, dan bahkan memiliki dokumen untuk membuktikannya – tapi negara justru menolak mereka.
Praktik-praktik ini berujung pada keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang mencabut status kewarganegaraan dari orang-orang keturunan Haiti yang lahir di Dominika, sehingga membuat mereka tidak memiliki negara. Sebuah kampanye berupaya melawan hal ini dengan menuntut lembaga catatan sipil di Dominika untuk kembali mengakui identitas kewarganegaraan semua warga keturunan Haiti.
Baca juga: Nasib Anak Luar Nikah Pekerja Migran dengan WNA
Dalam penelitian, saya menjelaskan bagaimana berbagai organisasi internasional pada waktu itu justru bersikap tak acuh saat Republik Dominika memburu dan menghalangi para warga keturunan Haiti untuk mendapatkan identitas kependudukan. Hasil studi ini sekaligus menjadi kritikan keras terhadap berbagai praktik politik identitas seperti ini di seluruh dunia.
Isu mengenai siapa yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi warga negara, serta siapa yang dikucilkan sebagai orang asing (yaitu keturunan Haiti), dianggap menjadi hak pemerintah Dominika sebagai bentuk kedaulatan mereka.
Akibatnya, puluhan ribu orang kini hidup di negara tersebut tanpa dokumentasi resmi. Ini membuat tidak bisa mengakses layanan sosial seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
Perlunya Mengatasi Kesenjangan Identitas Global
Saat ini, kita banyak melihat kasus-kasus serupa di seluruh dunia. Pada Juni 2021, saya menyelenggarakan konferensi di University of London, Inggris berjudul “(Re)Imagining Belonging in Latin America and Beyond: Access to Citizenship, Digital Identity and Rights” (Membayangkan Kembali Rasa Memiliki di Amerika Latin: Akses Hak Kewarganegaraan dan Identitas Digital).
Konferensi ini bekerja sama dengan Intitute on Statelessness and Inclusion di Belanda, dan membahas hubungan antara identitas dengan rasa memiliki, ID digital, dan hak kewarganegaraan.
Salah satu contohnya adalah makalah tentang nasib warga Prancis dalam skema BUMIDOM – gagasan dari pemerintah negara tersebut yang pada tahun 1960-an berupaya mendatangkan tenaga kerja dari daerah bekas jajahan Perancis – namun berujung diabaikan oleh negara.
Selain itu, ada juga akademisi yang membahas tantangan hukum yang dialami warga non-binary (seseorang yang tidak menganggap dirinya laki-laki maupun perempuan) di Peru, pengalaman warga Kuba di luar negeri yang tidak jelas kewarganegaraannya, serta perdebatan “bayi jangkar” tentang apakah anak-anak yang lahir dari migran tanpa dokumen secara otomatis mendapatkan akses menjadi warga negara Amerika Serikat (AS).
Konferensi tersebut diakhiri dengan acara meja bundar internasional yang mengkaji proses pendaftaran identitas digital di seluruh dunia yang kerap digunakan untuk tujuan diskriminatif. Meja bundar tersebut di antaranya membahas nasib dari populasi-populasi rentan seperti orang-orang Assam di India, Rohingya di Myanmar, dan orang Somalia di Kenya.
Perdebatan seperti ini akan semakin marak dalam 10 tahun ke depan. Bayangkan saja kejadian di mana seorang tunawisma tidak bisa lagi bepergian dengan transportasi umum karena perusahaan bus hanya menerima pembayaran dengan kartu, seorang perempuan tua berkulit hitam di AS tidak bisa mengikuti pemilu karena tidak punya identitas nasional, atau seorang perempuan yang dipecat dari pekerjaannya karena sistem mengidentifikasi dia sebagai imigran “ilegal”.
Bagi orang-orang yang berujung dikucilkan dari era digital baru ini, kehidupan sehari-hari akan terasa sangat sulit – bahkan mungkin mustahil untuk dijalani.
Baca juga: Dari Pembobolan Akun sampai ‘Sextortion’: Risiko Besar Kebocoran Data Pribadi
Meskipun kebutuhan untuk mempercepat pendaftaran identitas digital sangat mendesak, kita perlu berhenti sejenak dan merenung, terutama di dunia pasca-pandemi ini.
Tuntutan untuk membuat paspor digital COVID, kartu identitas biometrik, maupun sistem track-and-trace (uji dan lacak) memberikan ruang untuk pengawasan tidak hanya terhadap orang-orang yang keluar masuk suatu negara, tapi juga populasi rentan yang tinggal di negara tersebut.
Sudah saatnya kita berdiskusi serius tentang potensi buruk dari sistem ID digital, serta dampaknya yang sangat luas dan menentukan kehidupan banyak orang.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.



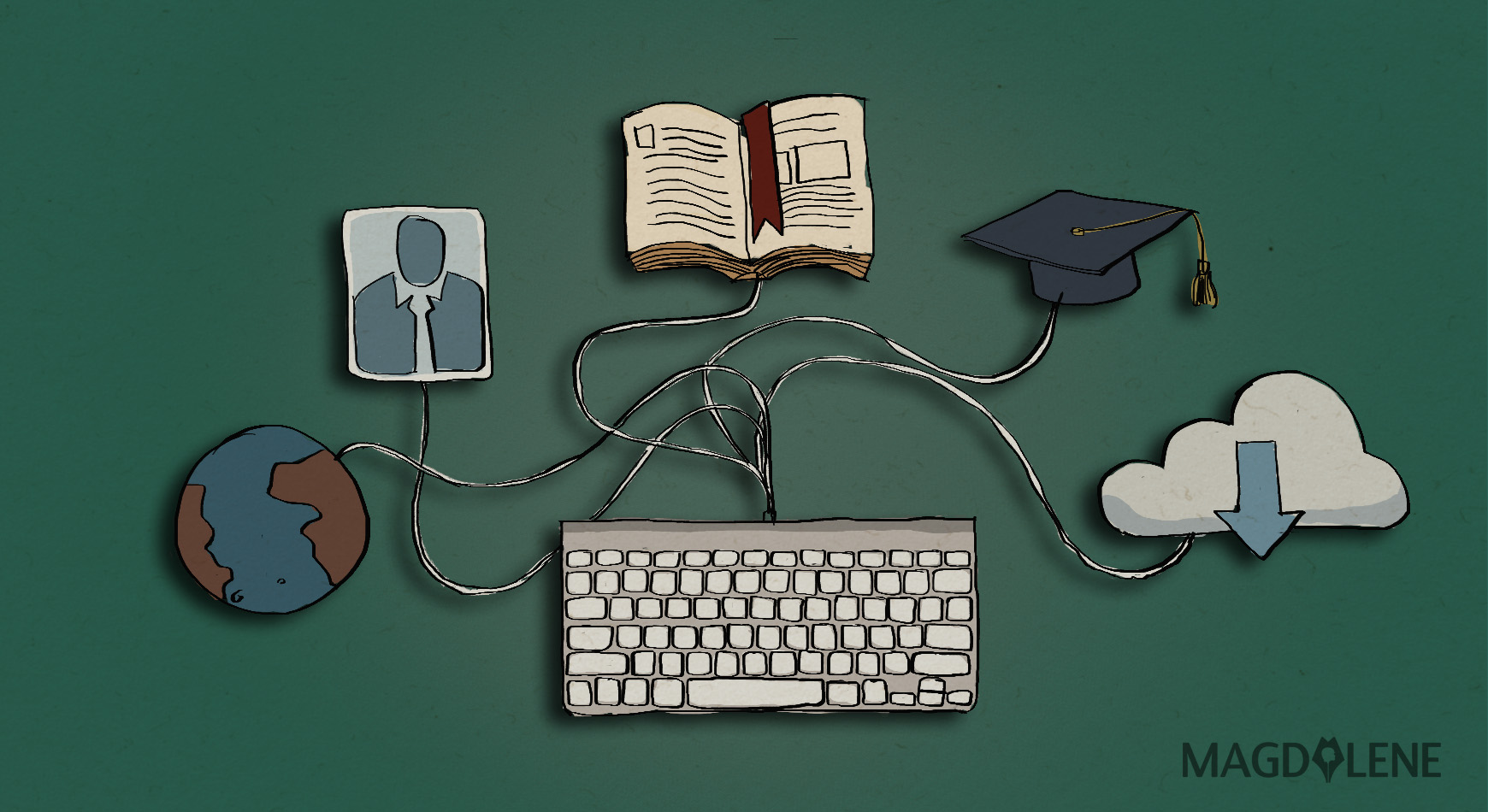



Comments