"I remember the day the police contacted me, it is a day I will never forget because it changed my life forever." (Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika polisi menghubungi saya, itu adalah hari yang mengubah hidup saya selamanya)
Pernyataan tersebut keluar dari salah seorang dari 195 korban yang dapat diidentifikasi atas pemerkosaan yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral asal Indonesia di Inggris, Reynhard Sinaga.
Nama tersebut sedang ramai sekali dibicarakan di kedua negara pada awal tahun 2020 ini. Kejahatan pemerkosaan yang dilakukan Reynhard bukan main-main; pengadilan Inggris menyatakan ini adalah kasus pemerkosaan oleh individual terbesar dalam sejarah dunia berdasarkan jumlah korbannya. Kronologi bagaimana pemerkosaan berlangsung dan tahapan pengadilan dipaparkan dengan detail oleh media Inggris, salah satunya BBC.
Sebagai warga negara Indonesia di Eropa, saya khawatir kasus Reynhard ini akan memperkuat sentimen anti-imigran yang sedang marak. Sementara itu di Indonesia, kebencian terhadap LGBTIQ akan semakin meningkat, menambah beban perjuangan para aktivis. Debat berlangsung antara mengapa predator seks bisa berkeliaran dan apa kondisi-kondisi yang membuat tindakan kriminal tersebut bisa berlangsung terus menerus. Dalam tulisan ini, saya ingin menyoroti bagaimana jika kasus pemerkosaan oleh Reynhard Sinaga terjadi di Indonesia.
Baca juga: Pelecehan dan Pemerkosaan adalah Soal Kekuasaan
Mengupas mitos pemerkosaan
Sinema, mitos, atau legenda banyak bicara tentang gang rape, atau pemerkosaan yang dilakukan oleh segerombolan laki-laki. Namun data kekerasan seksual yang dihimpun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya sejak 2005 menyatakan hal yang berbeda.
Pertama, negara bisa menjadi pelaku pemerkosa. Jika label "pemerkosa terbesar sepanjang sejarah dunia" disematkan karena jumlah korbannya, maka negara adalah pemerkosa terbesar. Khususnya dalam perang dan okupasi, kekerasan seksual dan pemerkosaan tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari okupasi atau penaklukan. Bagaimana Jepang merekrut perempuan-perempuan di wilayah jajahannya pada Perang Dunia II untuk dijadikan budak seks atau jugun ianfu adalah salah satu contohnya.
Dalam setiap perang atau penaklukan, pemerkosaan terjadi dan negara bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut. Contoh lain adalah pemerkosaan perempuan yang menyasar etnis Tionghoa pada 1998 di Jakarta dan di kota-kota besar sekitarnya. Jika kini tengah berlangsung perang yang berlokasi di wilayah Asia Barat mulai dari Suriah, Irak dan Iran, maka kita tidak bisa melupakan kemungkinan (atau sudah terjadi) pemerkosaan yang dilakukan atas nama negara.
Temuan kedua yang mematahkan mitos tentang pemerkosaan adalah individu pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban, bisa ayah, kakak, paman, tetangga, atau pemuka agama. Pada kasus pemerkosaan oleh orang dekat, korban bisa siapa saja dan banyak kasus terjadi selama bertahun-tahun dan sejak korban masih usia anak.
Kekerasan seksual ini dikenal dengan nama child molestation atau kekerasan seksual terhadap anak-anak. Child molestation sering dianggap sama dengan pedofilia. Sering kali pelaku memang menyasar anak-anak bukan karena berhasrat terhadap mereka, tapi anak-anak dilihat sebagai sasaran empuk karena dianggap belum memahami hubungan seksual, dan mudah dibujuk rayu apa pun jenis kelaminnya. Hal ini juga dilakukan oleh Reynhard yang dia menyasar calon korban lelaki yang sendirian, rapuh dan setengah mabuk untuk dipengaruhi dan dibujuk rayu.
Dan sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu korban Reynhard, pemerkosaan akan mengubah hidup korban selamanya. Banyak penyintas perkosaan mengalami post traumatic stress disorder (PTSD) atau kelainan stres pasca trauma yang mengganggu hidup mereka sehari-hari. Sulit tidur, mimpi buruk, sulit konsentrasi, depresi dan keinginan bunuh diri adalah gejala yang umum terjadi.
Kita tidak bisa membandingkan pengalaman diperkosa antara korban perempuan dan laki-laki karena rasa sakit dan penderitaan tidak untuk dibanding-bandingkan. Selama perangkat hukum terkait kekerasan seksual tidak diperbaiki, selamanya warga negara akan berada di bawah ancaman pemerkosaan.
Indonesia tidak mengakui pemerkosaan terhadap lelaki
Di Indonesia, banyak kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan lebih mudah dilaporkan dan diberitakan daripada terhadap anak laki-laki karena hukum tidak mengakui korban laki-laki. Selain itu, pemerkosaan di Indonesia masih dianggap tindakan asusila, bukan tindakan kriminal.
Untuk menentukan apakah sebuah kasus merupakan pemerkosaan atau bukan, berikut ini adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan aparat penegak hukum selama ini:
- Relasi korban-pelaku. Bukan relasi kuasa yang dicek oleh aparat penegak hukum Indonesia melainkan relasi hubungan. Pemerkosaan diakui apabila korbannya perempuan dan dalam hubungan rumah tangga resmi, sesuai Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) 2004, atau pelaku orang lain menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Alat penetrasi dan definisi perkosaan sangat sempit, yakni penetrasi penis dan vagina. Hal ini menyebabkan tidak diakuinya tindakan pemerkosaan jika penetrasi menggunakan jari, lidah, senapan, atau benda lain.
- Jenis kelamin korban. KUHP hanya mengakui jenis kelamin perempuan sebagai korban. Jika laki-laki mengalami perkosaan hanya disebut pencabulan dan hukumannya yang lebih ringan.
- Dampak kerugian. Sistem hukum di Inggris menghitung kerugian yang terjadi kepada korban sehingga jumlah korban akan memengaruhi masa hukuman. Hal ini tidak terjadi di Indonesia, berapa pun korbannya, karena perspektif korban tidak dimasukkan dalam pembuatan hukum.
- Pemulihan kepada korban. Kita lihat bagaimana seluruh pemberitaan kasus Reynhard mencantumkan informasi pengaduan bagi korban. Informasi pengaduan juga disertai dengan konseling dan pemulihan. Sebuah perspektif kemanusiaan yang tidak kita miliki dalam hukum Indonesia kita.
Baca juga: Pelecehan Seksual Dianggap Normal, Kecuali Dilakukan oleh Pria Gay
Dari perbandingan hukum tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa hukum di Indonesia sangat tidak manusiawi. Kita tidak bisa membandingkan pengalaman diperkosa antara korban perempuan dan laki-laki karena rasa sakit dan penderitaan tidak untuk dibanding-bandingkan. Selama perangkat hukum terkait kekerasan seksual tidak diperbaiki, selamanya warga negara akan berada di bawah ancaman pemerkosaan.
Jika kasus perkosaan berantai seperti Reynhard Sinaga terjadi di Indonesia, sudah pasti kasus ini tidak akan diusut sebab tidak ada landasan hukum bagi laki-laki dewasa korban perkosaan untuk mencari keadilan.
Bila fenomena pemerkosaan seperti gunung es, maka korban laki-laki akan berada di bagian paling dasar. Mereka tidak punya landasan hukum untuk mendapatkan keadilan ataupun keberanian untuk mengadu. Cibiran tentang homoseksual pasti menjadi hambatan apabila mereka mau bersuara. Persoalan pemerkosaan terhadap lelaki di Indonesia menjadi sangat kompleks karena baik hukum dan masyarakat kita sangat primitif dalam menyikapi hubungan seks.




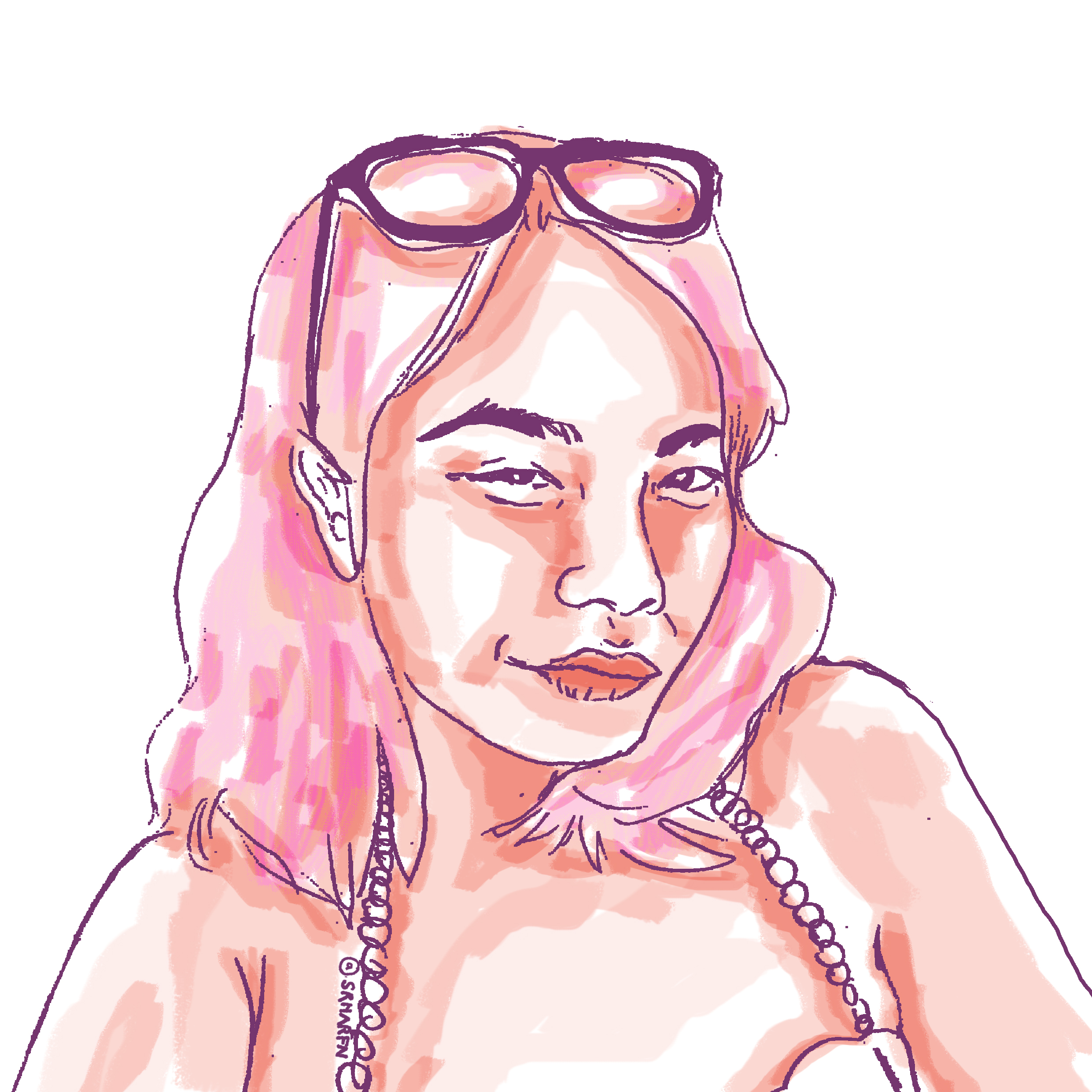



Comments